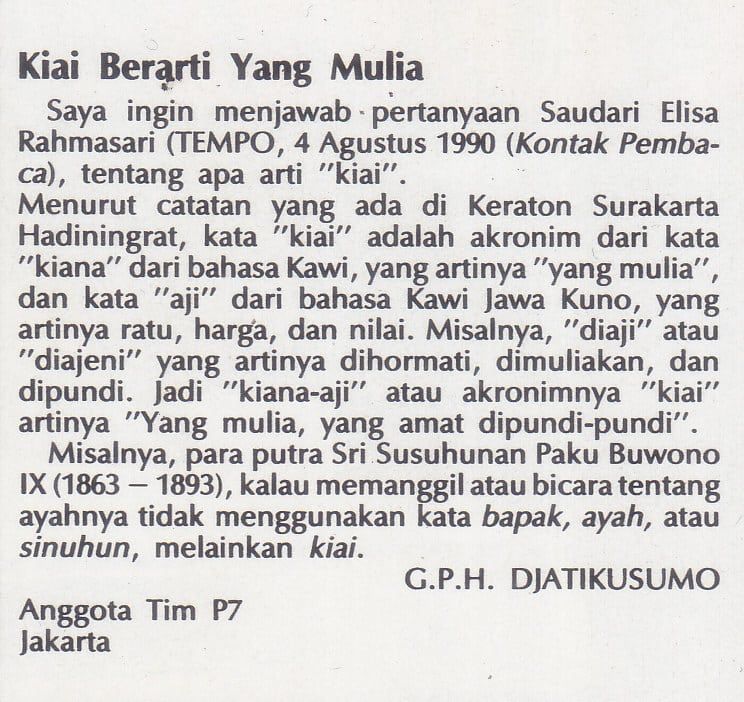
Arus sastra dan politik di Indonesia awal 2019 digegerkan oleh gubahan puisi cepat beredar ke pembaca. Puisi digubah politikus mengaku sudah menerbitkan sekian buku puisi. Puisi memicu seribu bantahan dan demonstrasi di kalangan kiai dan santri. Puisi mengenai doa dikaitkan kekuasaan.
Di situ, politikus itu mengesankan memberi diksi-diksi keras mengarah ke kiai. Para pembaca lekas memberi tafsir bahwa puisi memuat “hinaan” dan “serangan” pada kiai sepuh-terhormat di NU. Bermula dari puisi sulit dianggap cakep atau bermutu, kita disengat ke perbincangan politikus, puisi, doa, dan kiai.
Siapa politikus? Pada masa lalu, ada secuil jawaban mengandung sinis dan lelucon. “Bagi dia selalu ada kemungkinan bahwa seorang santo dalam kehidupannya dapat berubah (dan diubah) jadi penjahat, dan sang bromocorah berubah (dan diubah) jadi manusia teladan,” tulis Ignas Kleden di Tempo, 7 Juli 1984.
Konon, politikus memiliki kecenderungan mewujudkan kemungkinan kedua. Di Indonesia, orang mendapat julukan politikus sering merepotkan pengertian dan pengakuan berkaitan moral, kekuasaan, dan religiositas.
Ignas Kleden tak lupa memberi sepenggal renungan, “Politikus yang membaca dan menghayati puisi bagi saya tetaplah suatu mukjizat”. Kalimat bersumber dari kebiasaan para tokoh politik di Amerika Serikat masa lalu gandrung membaca buku-buku sastra. Ignas Kleden belum memberi sebutan ke kaum politik di Indonesia. Ia pun tak mau menggenapi pengakuan bahwa politikus menulis puisi tetaplah mukjizat.
Anggapan-anggapan itu sengaja terbantahkan melalui suara lain, “Dari penyair, orang-orang politik bisa belajar tentang licentia poetica, kebebasan para penyair memakai kemungkinan bahasa, mengolah kalimat setengah patah menjadi kejutan, menyulap sebuah kata hampa menjadi mutiara, atau suatu ungkapan jorok menjadi kristal”. Tulisan dari masa 1980-an teringat lagi bagi kita tekun membaca puisi, doa, dan politik berkaitan hajatan demokrasi, 17 April 2019.
Pada awal 2019, terbit buku puisi berjudul Surat Kopi. Puisi-puisi religius gubahan Joko Pinurbo termuat di halaman-halaman elok. Ia mengerti situasi politik dan keberagamaan di Indonesia.
Puisi diberikan untuk bacaan mengajak ke renungan, bukan pemicu sengketa, kecamuk, atau polemik. Puisi-puisi pantas terbaca oleh kaum politik atau “penonton” lakon demokrasi mutakhir. Di puisi berjudul “Doa Kecil”, Joko Pinurbo memberi pesan kedalaman:
Di halaman sajak ini/ aku sudah menjadi doa kecil/ yang tak terucapkan./ Berpendar-pendar di matamu/ bergetar-getar di bibirmu.
Puisi kecil tanpa pamrih-pamrih politis. Puisi justru mengembalikan kita ke doa mengandung kepasrahan dan ketakjuban.
Pada puisi berbeda dengan judul “Ketika Berdoa”, ia mengingatkan orang-orang jangan terlalu membenturkan perbedaan agama atau menggeret ke perkara-perkara politik. Joko Pinurbo menulis: Ketika aku berdoa,/ Tuhan tak pernah/ menanyakan agamaku.
Doa itu pengharapan tanpa harus dipaksa memamerkan “baju” agama minta sanjungan. Di hari-hari menjelang coblosan, orang-orang berdoa demi kebaikan, kerukunan, kedamaian, bukan berdoa atau menulis puisi tentang doa tapi berdampak heboh tak santun.
Bantahan atau demonstrasi pada politikus menggubah puisi mengenai doa, kekuasaan, dan kiai menjadi tanda zaman rawan kisruh. Kita tak perlu melulu berpikiran hal-hal mutakhir. Kita mundur ke masa lalu untuk mengingat kiai. Ingatan ke perkara sebutan dan pemaknaan.
Di Tempo, 4 Agustus 1990, seorang murid SMA bernama Eliza Rahma Sari mengirimkan surat pembaca ke Tempo. Surat berisi keinginan mendapat sejarah dan perkembangan arti kiai. Surat itu terbaca publik untuk lekas memberi jawaban-jawaban dengan pelbagai referensi dan kemungkinkan tafsir.
Jawaban-jawaban diberikan ke Eliza Rahma Sari dimuat berbarengan di Tempo, 18 Agustus 1990. Ibnu Chadjar (Jakarta) memberi usulan jawaban, “Bagaimana mulanya, kata ki dan nyi berubah menjadi kiai dan nyai? Dalam tradisi Jawa ada kecenderungan, untuk menghormati seseorang, kata yang bersangkutan diperpanjang dengan menambah awalan, sisipan, atau akhiran. Seperti kula menjadi kawula, yang artinya saya. Ki menjadi kiai.” Jawaban mengandung kemungkinan dengan pendasaran di bahasa dan sejarah Jawa itu bisa berterima meski tanpa ajuan daftar pustaka.
Jawaban lain diberikan Waluyo Basuki (Jakarta). Ia masih mengacu ke Jawa. Kita simak, “Dalam perkembangan selanjutnya gelar kiai juga diberikan kepada ulama Islam (termasuk pemimpin-pemimpinnya) yang telah memiliki kedudukan dan ketinggian ilmu di bidang keagamaan. Sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kata kiai merupakan istilah Islam yang berasal dari bahasa Arab”. Ia tetap mengakui sebutan kiai berasal dari bahasa Jawa.
Bermula dari surat pembaca, kiai jadi perhatian para pembaca di pelbagai kota. Keinginan memberikan informasi atau jawaban mengesankan ada kemauan memberi penghormatan pada kiai, bersumber masa lalu dan mengerti di situasi zaman telah berubah.
Tempo edisi 25 Agustus 1990 masih memuat jawaban mengenai kiai. Jawaban diberikan oleh GPH Djatikusumo. Tokoh nasional keturunan keraton memberi informasi penting bereferensi Jawa.
Jawaban menggoda pembaca melakukan lacak kepustakaan, “Menurut catatan yang ada di Keraton Surakarta Hadiningrat, kata kiai adalah akronim dari kata kiana dari bahasa Kawi, yang artinya yang mulia, dan kata aji dari bahasa Kawi Jawa Kuno, yang artinya ratu, harga, dan nilai.
Misalnya, diaji atau diajeni yang artinya dihormati, dimuliakan, dan dipundi. Jadi kiana-aji atau akronimnya kiai artinya yang mulia, yang amat dipundi-pundi. Misalnya, para putra Sri Susuhunan Pakubuwono IX (1863-1893), kalau memanggil atau bicara tentang ayahnya tidak menggunakan kata bapak, ayah, atau sinuhun, tapi kiai. Surat jawaban itu menantikan ada studi serius untuk jadi referensi bagi publik mengerti sebutan kiai berkaitan dengan bahasa, kekuasaan, dan agama. Begitu.




















