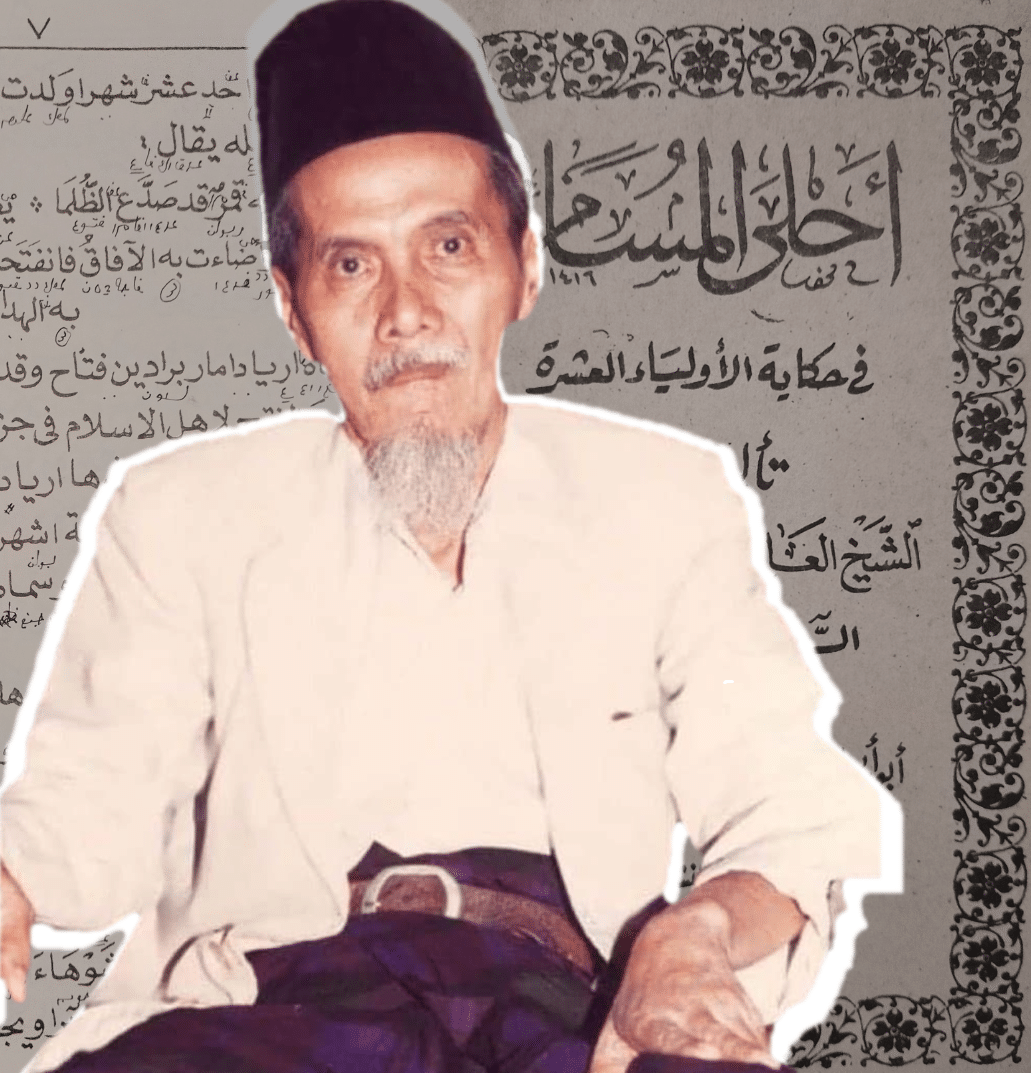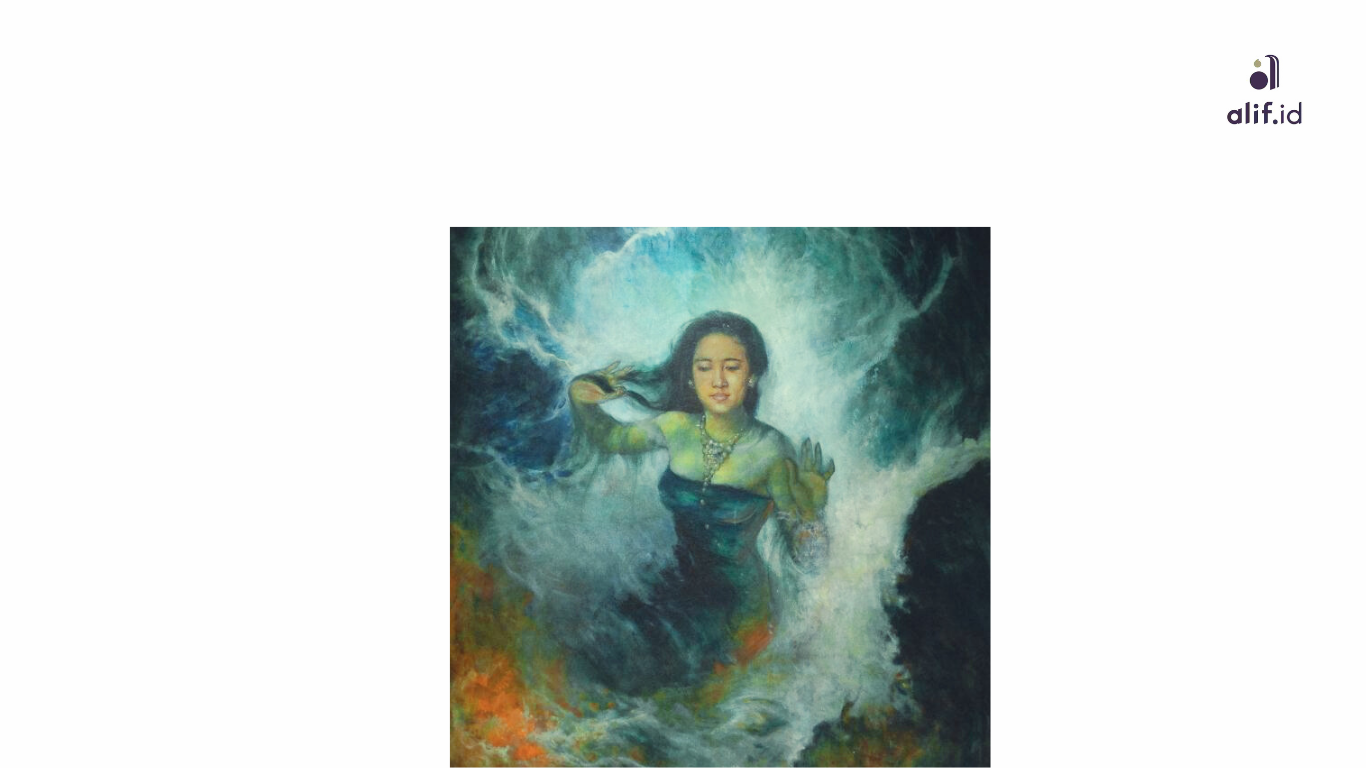Ketika poster film Siksa Kubur muncul, saya punya ketakutan Joko Anwar akan membuat film yang preaching. Apalagi salah satu karakter dalam poster tersebut adalah Sajaul Aqra, sosok ular yang dalam ajaran umat Islam ditugaskan untuk menyiksa si mayat di alam kubur. Lebih-lebih trailer-nya menggunakan lagu ‘Bila Waktu T’lah Berakhir’-nya Opick yang sangat akrab bagi penonton sinetron Hidayah. Namun setelah menonton film ini saya lega karena Joko Anwar mempertahankan wataknya sebagai sutradara yang mendewasakan penontonnya.
Sebelum menonton di bioskop, saya terpapar beberapa review dari YouTuber yang mengulas film ini. Secara umum, banyak yang menaruh kesan positif. Salah satu pengulas bahkan mengapresiasi sutradara Joko Anwar yang kembali ke ‘jati dirinya’ sebelum era Pengabdi Setan. Ada pula yang mewanti-wanti agar calon penonton menjaga espektasi karena meski bergenre horor, film Siksa Kubur ini cukup lambat.
Saya merasakan betul bagaimana film ini membangun ceritanya dengan begitu sabar. Sejak menit pertama, Siksa Kubur menuntut penonton untuk terus mengamati berbagai adegan dan dialog. Rasa-rasanya, satu detik saja ‘meleng’, ada jalur cerita yang akan sulit dipahami. Apalagi saat transisi dari Sita dan Adil kecil ke dewasa yang punya rentang 20 tahun. Joko Anwar sendiri pernah menyebut bahwa film ini berlatar 1997 dan 2017 namun tidak menyebut secara eksplisit di filmnya. Tidak adanya keterangan tahun membuat penonton rawan mengalami kebingungan.
Sebagai contoh, sebuah komentar di X mempertanyakan kenapa pada 1990-an sudah ada ponsel pintar layar sentuh? Komentar tersebut ditimpali akun lain dengan penjelasan bahwa ponsel tersebut berlatar Sita dan Adil dewasa di tahun 2017. Dari sini saja sudah terbukti betapa kehilangan sekian detik akan memporak-porandakan alur cerita yang memang dibangun sangat terstruktur, sistematis, dan masif ini.
Simbol agama
Premis film ini sederhana. Menceritakan perjalanan seorang Sita (diperankan Faradina Mufti dan Widuri Puteri) yang ingin membuktikan apakah siksa kubur itu benar-benar ada. Rasa penasarannya muncul akibat dendam terhadap sosok yang membuat kedua orang tuanya meninggal dunia secara tragis. Sebelum melakukan sebuah aksi, sosok tersebut memberikan sebuah kaset yang disebut sebagai rekaman siksa kubur kepada Adil (kakaknya, diperankan Reza Rahardian dan Muzakki Ramadhan).
Jika saya hanya berhenti menonton trailer, mungkin saya akan curiga Joko Anwar ikut-ikutan mengeksploitasi agama untuk menciptakan kesan seram yang instan. Namun sepanjang pertunjukan, kekhawatiran itu sama sekali tidak muncul. Simbol agama memang tak bisa dilepaskan dari film berdurasi hampir dua jam ini. Namun simbol-simbol tersebut digunakan untuk membangun cerita, bukan sebagai peledak yang membuat agama jadi bahan baku komoditas.
Salah satu plot penting adalah kisah Sita dan Adil saat di pesantren. Scene tersebut mengobok-obok imajinasi makna kebaikan. Diceritakan bagaimana pesantren tersebut memberikan pendidikan gratis kepada orang-orang yang kurang mampu. Pesantren adalah simbol harapan bagi orang-orang yang terpinggirkan. Seorang dermawan bernama Wahyu (diperankan Slamet Rahardjo) yang menyumbang banyak pesantren dan panti asuhan menjadi donaturnya. Dia dianggap sebagai juru selamat bagi banyak orang. Namun siapa sangka masa pelita yang dibawa justru merenggut masa depan puluhan santri yang tidak berdaya?
Setelah bersabar lebih dari separuh durasi, penonton akhirnya mendapatkan sensasi horornya. Ledakan-ledakan yang meneror penonton pada setengah jam terakhir merupakan dampak rentetan cerita di awal. Namun untuk mendapatkan sensasi itu, penonton perlu menyimak betul dialog-dialog dan berbagai adegan yang dibangun sepanjang film. Sekali lagi, jika meleng sedikit, bisa kehilangan konteks. Sebagai perumpamaan, jika film horor yang kaya jumpscare dibuat layaknya parade kembang api, film Siksa Kubur seperti bom nuklir yang diledakkan pada waktu dan tempat yang tepat.
Saya agak setuju dengan anggapan bahwa film Siksa Kubur ini bukan untuk semua orang, dalam arti tidak semua bisa langsung ngeh dengan apa yang ditampilkan. Film Siksa Kubur bukan jenis film horor religi yang menceritakan adanya orang jahat yang meninggal kemudian dipukuli malaikat di alam kubur. Sebaliknya, film ini begitu kompleks, dinamis, dan membutuhkan kejelian penonton. Saya bahkan menemukan beberapa hal baru setelah mendiskusikan film tersebut dengan istri dan menyimak berbagai pendapat di media sosial. “Oh, ternyata ini”. “Oh, iya juga, ya”.
Apakah itu sebuah kekurangan atau justru keunggulan film ini? Saya ingin menjawabnya dengan kalimat dari sang sutradara di akun X @jokoanwar miliknya. “Semuanya valid karena pengalaman menonton film adalah spiritual, nggak ada yang bisa dikte gimana hasilnya.”
Bagi saya, film ini 9/10.