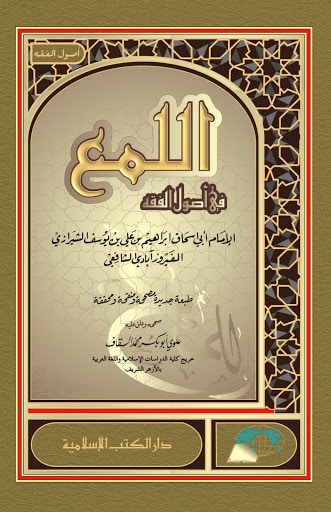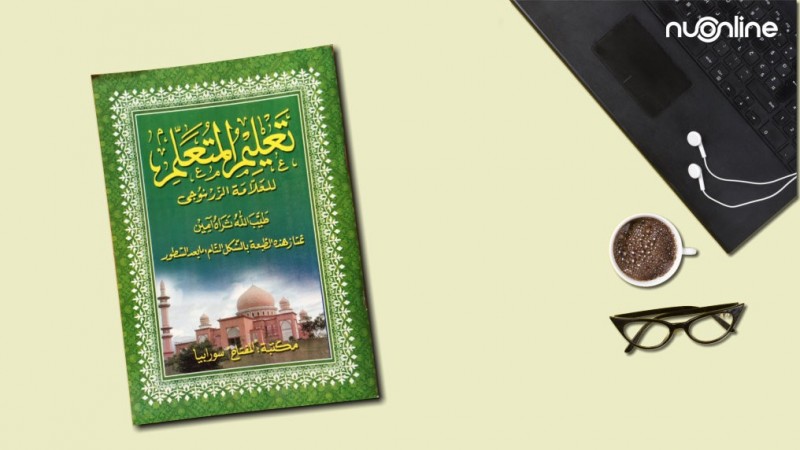Formulasi Radikalisme
Istilah ‘radikal’ sebenarnya memiliki makna yang cukup beragam, ia bisa dimaknai sebagai fundamental, esensial, mendasar, reformis dan terbuka. Radikal juga bisa dipahami sebagai ekstrem, militan, parsial dan sikap yang keras dalam memperjuangkan sesuatu. Isme yang dilekatkan pada istilah radikal lebih mengacu pada suatu paham yang ekstrem dan berlebih-lebihan sampai melampuai batas.
Keragaman makna ‘radikal’ ini pada dasarnya memiliki makna dua arah, yakni positif sekaligus negatif. Makna positif dari radikal biasanya mengacu pada suatu pandangan keterbukaan dan sikap moderat dalam memahami segala sesuatu, sikap ini bisa terjadi dan dilakukan dalam konteks pemahaman terhadap apa saja, karena ia merupakan sebuah sudut pandang.
Makna positif ‘radikal’ sering diarahkan pada kecenderungan terhadap kemajuan, merumuskan sebuah jawaban dari problem-problem yang dihadapi sampai pada akar-akarnya. Kelompok radikal yang positif lebih mengedepankan sikap jalan tengah dan juga mencari titik temu antara dua kecenderungan yang anggap sering berlawanan, misalnya antara posisi agama dan politik, sekular dan konservatif, atau modern dan tradisional. Mereka percaya bahwa setiap dua hal yang berbeda tidak selalu harus dipertentangkan.
Radikal dalam konteks negatif, biasanya mengarah pada satu pemahaman tentang sikap dan pandangan yang militan, kuat dan keras dalam memperjuangkan aspirasi pendapatnya. Makna negatif seringkali diarahkan dan dikonotasikan kepada satu istilah yang disebut radikalisme. Pemahaman yang paling umum tentang radikalisme mengarah pada suatu gerakan politik yang menjadikan agama sebagai basis ideologis. Kekuatan militansinya terletak pada satu kecenderungan untuk menetapkan doktrin agama sebagai sebuah prinsip universal dalam mengatur tatanan yang ada.
Itu artinya bahwa radikalisme dimaknai sebagai suatu paham atau aliran tertentu yang begitu militan dan ekstrem dalam berpolitik. Kelompok radikalisme menginginkan suatu perubahan yang besar dan pembaharuan sistem sosial dan politik berdasarkan prinsip-prinsip agama yang diyakininya, ia seringkali menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengubah secara drastis sistem yang selama ini dianggap sangat jauh dari nilai-nilai agama.
Sebagai gerakan politik yang berbasis agama, kelompok redikalisme seringkali menginginkan pembentukan negara berdasarkan prinsip syari’at. Mereka percaya bahwa hanya dengan sistem itu, keadilan dan kemerdekan akan mudah dijalankan di tengah kekacauan ketidaadilan, kesenjangan sosial dan korupsi yang merajalela. Mereka begitu yakin bahwa Khilafah merupakan satu-satunya jalan untuk sampai pada keadilan yang paripurna.
Sistem kepemimpinan ala Khilafah ini ingin menyatukan seluruh berbagai negara melalui satu kepemimpinan tunggal yang memiliki otoritas penuh atas kekuasaan politik dan agama. Padahal, jauh-jauh hari Ibn Taimiyah pernah mengatakan bahwa adalah tidak mungkin lagi untuk mendirikan negara Islam dalam satu kepemimpinan. Ibn Taimiyah di era itu sudah begitu menyadari tentang adanya sistem kenegaraan berbasis Republik.
Tidak hanya itu, hampir semua kelompok radikal tidak percaya dengan peradaban modernisme dan segala sesuatu yang menyertainya. Mereka mengira bahwa modernisme adalah ancaman bagi keutuhan sistem keagamaan mereka, dengan sekularisme dan liberalism sebagai ideologi yang mengiringi modernitas, keduanya sama-sama dianggap berbahaya dan harus segera dilawan dengan cara-cara apapun.
Posisi Kitab Kuning
Kitab kuning merupakan satu-satunya identitas pesantren (di samping Alquran dan Sunnah) dalam hal mempelajari dan mengkaji secara mendalam norma-norma Islam. Dengan kitab kuning pesantren terus menjaga dan mengembangkan khazanah keislaman yang begitu kaya.
Menurut saya, sebenarnya akar-akar radikalisme telah ada dalam penjelasan-penjelasan secara rinci dalam kitab kuning yang biasanya dikaji di lingkungan pesantren. Dalam kitab Fathul Mu’in dan Fathul Qorib misalnya, salah satu babnya, menjelaskan tentang suatu keharusan untuk mendirikan kekhilafahan Islam. Lebih tegas lagi, dalam kitab Ahkamul Sultoniah dikatakan tentang prinsip dan kewajiban dalam menegakkan negara Islam.
Yang menarik adalah, kitab-kitab ini juga dikaji dan justru menjadi bacaan wajib bagi pengikut organisasi Hizbut Tahrir yang begitu getol dalam mendirikan negara Islam. Pertanyaannya adalah jika kitab-kitab yang dikaji oleh para santri dan kelompok Hizbut Tahur adalah sama, tapi mengapa melahirkan suatu kesimpulan yang berbeda?
Dalam konteks inilah muncul apa yang disebut sebagai “problem epistemologis”. Kelompok garis radikal Hisbut Tahrir misalnya, memahami teks secara harfiah, parsial, dan hanya melihat apa yang nampak dipermukaan. Jadi dasar epistemologi yang mereka pakai hanyalah melalui prinsip epistemologi bayani, yakni suatu pandangan yang hanya berdasarkan pada teks semata dan hanya melalui teks sajalah segala sesuatu dapat dijelaskan.
Mereka tidak peduli betapa akal dan intuisi sangat berperan dalam memahami segala sesuatu. Justru landasan epistemologi yang berbasis pada akal dan intuisi, dianggap tidak orisinal dan dapat meracuni cara pandang yang murni terhadap teks keagamaan. Mereka lebih menggunakan standar epistemologi yang keliru dalam memahami agama.
Sementara para santri, lebih menggunakan pendekatan kontekstualis dalam memahami teks, apakah itu dari Alquran, Sunnah, atau dari kitab kuning, para santri mampu mendialogkan antara teks dan konteks, antara sisi historis dari teks dan bentuk kontekstualisasi dari penerapan teks tersebut di zaman yang lebih kekinian. Itu artinya bahwa kelompok radikal seringkali tidak mengerti tentang aspek-aspek historis dari kemunculan doktrin agama.
Misalnya, para santri lebih memaknai istilah jihad siyasah (politik) dalam konteks keindonesiaan. Karena memang penerakan sistem bernegara di Indonesia, sudah sangat dekat dengan cita rasa Islam. Seperti prinsip demokrasi dengan musyawarah, prinsip berketuhanan, berkeadilan, ataupun cita-cita kesejahteraan bersama, tidaklah menyalahi aturan Islam yang baku, justru memiliki makna yang searah. Tidak sebagaimana kaum radikal yang bahkan dalam memaknai sistem pemilu tak lebih sebagai al-Intiqaf fil Islam (pemilu yang haram).
Juga, para santri lebih dapat bersikap kritis terhadap pengkajian kitab kuning, mereka mencari titik temu antara teks dan konteks, dan tentu saja mencari kesesuaian yang mutlak antara prinsip teks dengan realitas yang berkembang.
Jika yang dicari adalah keadilan, maka tidak perlu membawa agama ke dalam sebuah sistem kenegaraan. Karena Indonesia telah menerapkan seluruh sistem berdasarkan nilai-nilai yang ada di Nusantara, tidak hanya dari agama, tetapi juga tradisi lokal, nilai-nilai filosofis yang luhur dan cita rasa bangsa Indonesia yang harmoni.
Peran Pesantren
Secara salah kaprah, banyak orang percaya bahwa pesantren adalah tempat yang subur dalam menanamkan paham radikalisme, karena pesantren adalah satu-satunya tempat yang paling identik dengan kajian keislaman secara ketat. Pandangan ini bukan hanya keliru, tetapi juga menunjukkan pemahaman yang sangat sempit tentang nilai-nilai Islam yang berkembang di Nusantara.
Bisa dikatakan bahwa pesantren sebenarnya lebih merupakan cagar budaya dan persemayaman kader ulama yang berkualitas. Di pesantren, para santri digembleng dengan kajian keagamaan yang begitu luas dan melalui pesantrenlah dasar-dasar moral mulai ditanamkan.
Sekarang ini, banyak ustaz karbitan yang sudah dianggap “ustaz” padahal ia tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren. Ini bukan hanya ironis, tetapi justru membahayakan bagi keberagamaan masyarakat yang sebenarnya lebih membutuhkan figur ulama yang lebih mumpuni dibidang ilmu-ilmu agama.
Pesantren juga bisa dipahami sebagai sebuah embrio Islam yang prinsip pengajarannya sudah diterapkan langsung oleh Nabi Muhammad Saw di Madinah pada waktu itu. pesantren juga melahirkan ulama yang memiliki pengetahuan yang luas tidak hanya tentang agama semata, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya.
Jika disebut sebagai cagar budaya dan tempat persemayamnya kader ulama, maka pesantren memiliki peranan yang penting dalam menanamkan nilai-nilai Islam yang damai dan sejuk. Islam ala santri sudah dikenal secara luas sangat bercirikan inklusif, yakni suatu sikap keagamaan yang terbuka dan moderat. Prinsipnya adalah selalu mengambil jalan tengah terhadap segala persoalan yang sendang dihadapi.
Pesantren juga merupakan lembaga pendidikan paling tua di negeri ini, sebelum ada Indonesia, pesantren sudah eksis sebagai media pendidikan keislaman yang dalam hal ini mempelopori lahirnya sistem pendidikan yang iklusif atau terbuka.
Fenomena radikalisme agama juga menjadi perhatian penting dari pesantren. Ini tentu saja tugas berat yang harus dihadapi para santri, seperti memberikan pelurusan terhadap pemahaman akan sejarah. Kaum radikal banyak tidak mengerti aspek kesejarahan dalam Islam, mereka seringkali bersikap a-historis dalam arti menganggap masa dulu dan sekarang adalah sama saja, yang dibutuhkan hanyalah bagaimana dapat menerapkan sistem Islam yang sudah baku tersebut.
Ini lagi-lagi, merupakan problem epistemologis. Dalam banyak hal, kelompok radikal ini keliru dalam memahami agama. Mereka menganggap kondisi dahulu dan sekarang tidak mengalami banyak perubahan, dengan begitu sistem syari’at dapat diterapkan dalam kondisi apa saja.
Kita semua telah sepakat bahwa Indonesia adalah negara Republik berasaskan Pancasila. Pesantren sebagai garda depan bagi penjangaan nilai-nilai keislaman yang mengedepankan nasionalisme, sudah sepatutnya memiliki peranan yang lebih penting dalam menangkal radikalisme agama. Jika pemahaman keagamaan kaum radikal ini keliru, maka pesantrenlah yang dapat meluruskan.
Di samping itu, sebagai lembaga keagamaan, pesantren justru lebih dekat dengan masyarakat ketimbang pendidikan formal, karena pesantren lebih mengedepankan kultur atau budaya. Itu artinya bahwa pesantren justru lebih dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dalam hal mensosialisasikan Islam yang terbuka dan selalu waspada terhadap bahaya radikalisme ini.
Pesantren sebenarnya memiliki jaringan para ulama yang begitu luas, komunikasi antar pesantren juga merupakan mediasi penting yang dapat menyatukan pandangan yang seragam kepada masyarakat. Melakukan dialog, juga merupakan media yang sangat penting.
Pesantren paling tidak, memiliki gerak pada dua arah, pertama mengembangkan kajian keislamaan yang begitu kaya dan selalu menanamkan sikap yang inklusif dalam memahami Islam. Jika keragaman aliran dalam Islam tidak bisa dihindari, maka dengan sikap inklusif inilah Islam dapat bersatu menjadi agama yang damai dan tidak menimbulkan konflik antar sesama.
Tidak ada yang lebih penting daripada dapat mengakui dan menghargai perbedaan sebagai sesuatu yang sama pentingnya dengan apa yang diyakini oleh setiap individu. Hak-hak asasi terhadap perbedaan pendapat haruslah dilindungi, betapapun berbedanya orang lain atau kelompok lain dengan kita, tidak ada alasan apapun yang dapat menjastifikasi atau menyalahkannya. Melalui pesantren, Islam dapat dihadirkan sebagai agama yang cinta damai, menghargai perbedaan, dan meletakkan perbedaan sebagai rahmat dari Tuhan yang Maha Esa.