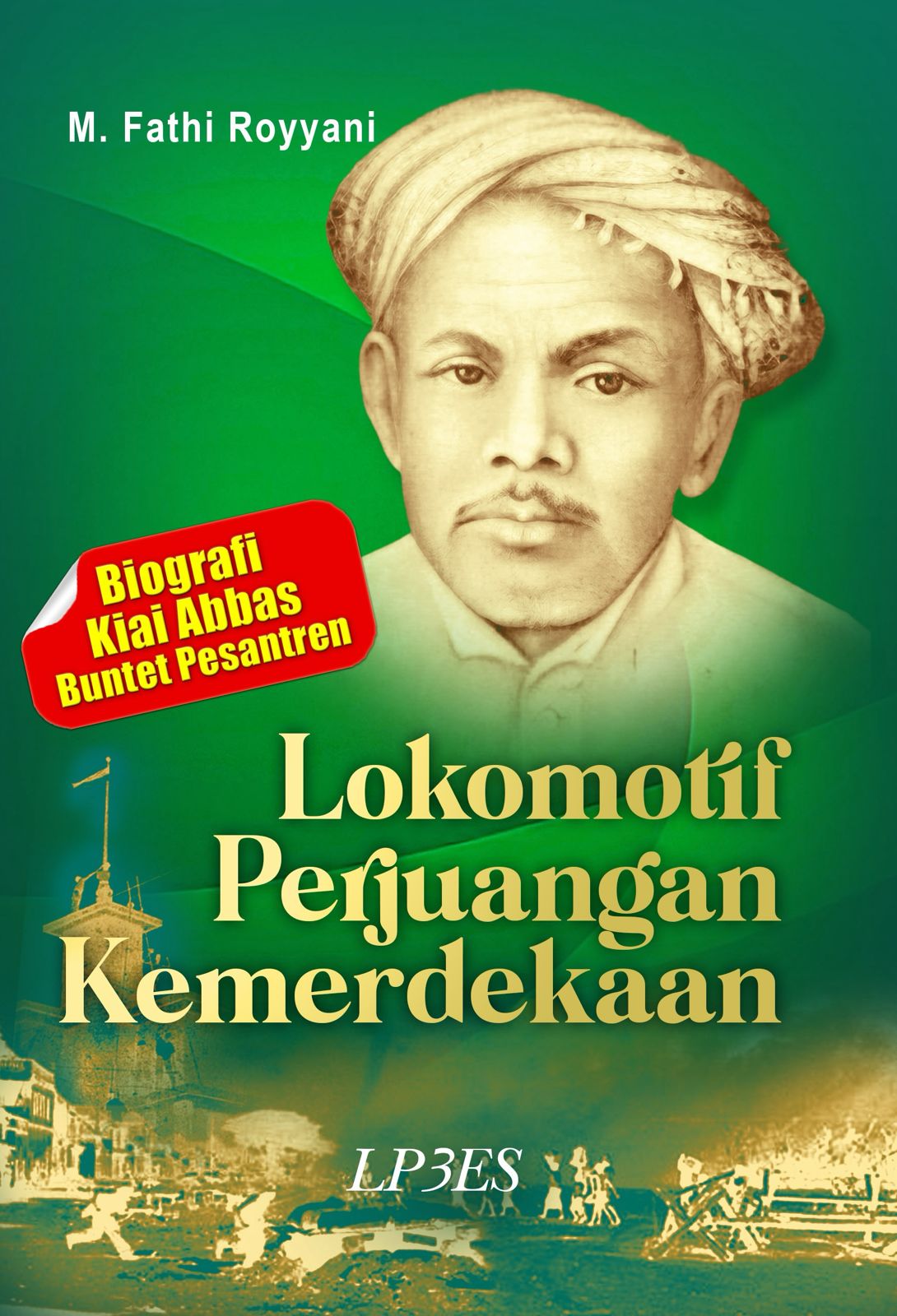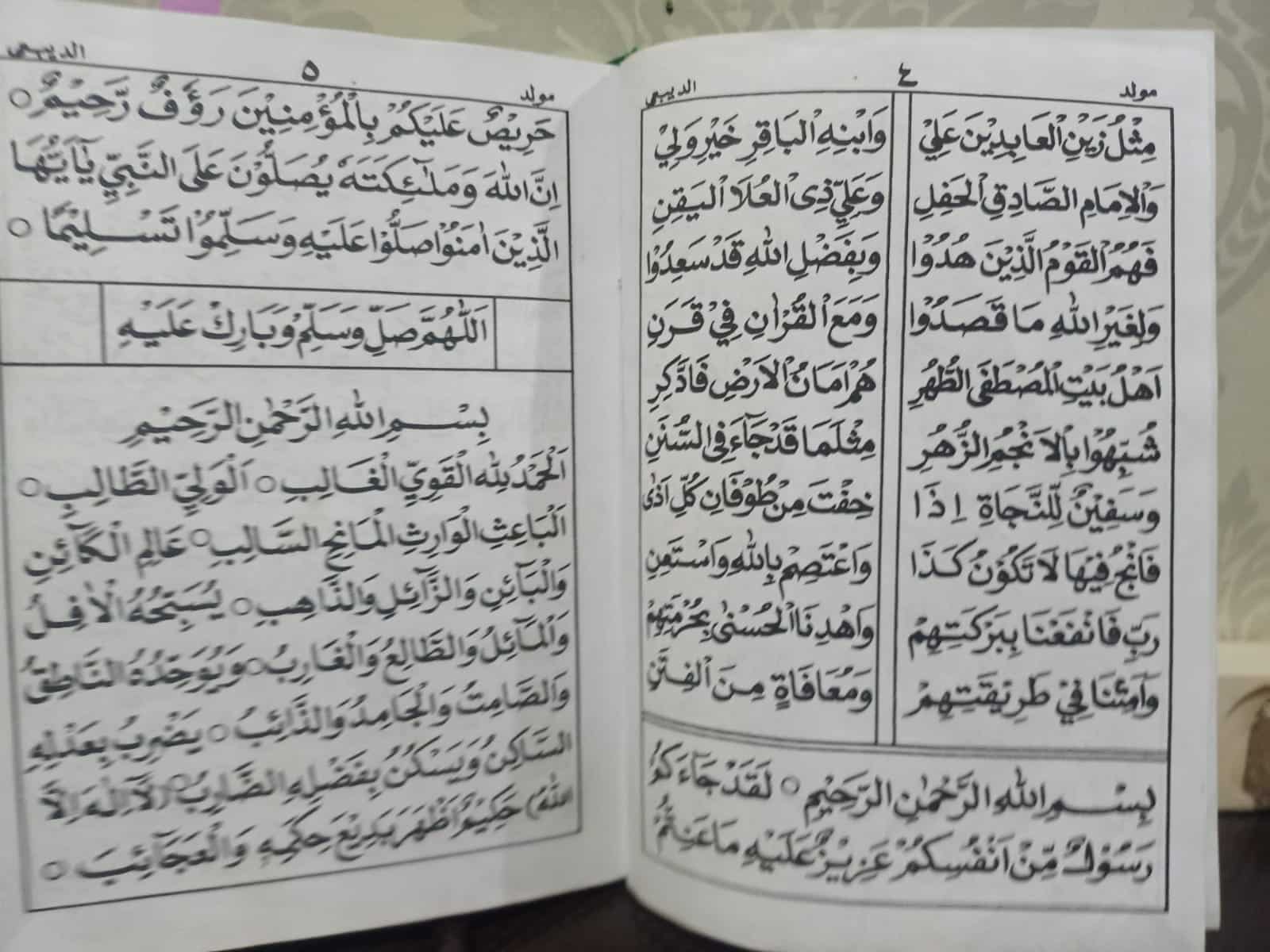Salah satu hal yang paling khas tentang kreativitas seorang Orhan Pamuk adalah bagaimana cara menyenangkan dan menggoda para pembacanya, dengan terus-menerus mengaburkan batas antara kebenaran dan fiksi.
Sang perawi utamanya–individu yang mencakup banyak aspek yang terkenal dari kehidupan novelis sendiri dalam cerita mereka–dia membuat kita penasaran untuk menebak-nebak, bagian mana dari cerita yang sebenarnya terjadi dan yang imajiner.
Ketika Pamuk menerbitkan beberapa novel pertamanya, hanya orang-orang yang secara pribadi berkenalan dengan sang penulis atau keluarganyalah yang bisa berpartisipasi dalam permainan tebak-tebakan ini.
Saat dia telah menjadi semakin masyhur–dan terutama karena penerbitan memoarnya, Istanbul: Memories of a City–banyak pembaca setianya (termasuk saya sendiri) telah ditarik ke dalam pusaran keintiman emosional, seperti orang tuanya, saudaranya, neneknya, dan bahkan pelayan keluarganya, menjadi tokoh-tokoh yang akrab.
The Museum of Innocence berkisah mengenai seorang pengusaha yang mencoba merebut kembali cinta sejatinya, dan menghibur diri dengan mengumpulkan benda-benda yang berhubungan dengan Fusun, si gadis sepupu yang dicintainya itu. The Museum of Innocence adalah seolah-olah kisah cinta, namun bukanlah sekadar roman picisan.
Inilah kelebihan Pamuk: sementara dia mendongengkan penantian panjang seorang lelaki, melalui benda-benda yang dikumpulkannya, dia tak hanya mengingatkan kembali Kemal kepada Fusun, tetapi juga menjelajahi Istanbul, Turki di satu waktu dan sebagai sebuah tempat: ketegangan (atau perbauran elok) antara Barat dan Timur.
Melalui benda-benda itulah kita melihat ketegangan mengenai “keperawanan”, misalnya. Sementara Sibel, mantan tunangan Kemal, merasa cuek kehilangan keperawanan karena ia sudah “ter-Paris-kan”, di sisi lain ia juga merasa malu karena pertunangan mereka berantakan (padahal orang sudah tahu ia pernah tidur dan tinggal serumah sebelum menikah dengan Kemal). Demikian juga melalui sehelai bikini: bagaimana Fusun, si bekas kontestan kecantikan Turki, masih merasa canggung harus berjemur di pantai.
Penderitaan ekstrim Kemal bertahan sebagai hasil perpisahannya dari Fusun, dan tentu saja, karena rasa bersalah. Dia merasa hancur karena tidak dihargai, dia peka akan nasib perempuan di Turki, yang menjadi salah satu tingkat tertinggi di dunia dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.
Sebelum Kemal jatuh cinta dengan Fusun, Kemal dan teman-teman kayanya, sering menghabiskan malam mereka dengan berkeliaran di kota Istanbul, untuk “membebaskan” para perempuan yang akan memenuhi fantasi seksual mereka. Akan tetapi, pada kesempatan langka ketika mereka benar-benar bertemu perempuan seperti itu, mereka membenci dan membuatnya seperti masuk ke dalam neraka. Sementara pada saat yang sama, mereka bersikap munafik dengan menuntut standar patriarkis, seperti konsep “keperawanan” dari istri dan anak-anak perempuan mereka.
“Gila” oleh cinta, Kemal sekarang menyadari bahwa itu adalah semacam perilaku yang diterima sebagai hal yang normal dalam masyarakat (yang benar-benar gila!). Ibu Kemal meringkas situasi sangat akurat ketika ia mengkritik Kemal bahwa, “di sebuah negara yang laki-laki dan perempuannya tidak bisa bersama-sama secara sosial, di mana mereka tidak bisa melihat satu sama lain atau bahkan memiliki percakapan, tidak ada hal ihwal seperti cinta … Apa kamu tahu itu? Aku akan memberitahumu: karena lelaki saat melihat perempuan seperti menunjukkan beberapa bunga, mereka tidak merepot-repotkan diri dengan apakah ia baik atau jahat, cantik atau jelek –mereka hanya menerkam perempuan laiknya hewan kelaparan. Kondisinya seperti itu. Dan berpikir bahwa mereka sedang jatuh cinta! Apa ada cinta di tempat seperti ini?” (450).
Museum of Innocence merupakan museumnya orang-orang biasa. Kisah cinta yang bisa terjadi pada siapa saja. Tempat garam yang mungkin sama dengan yang ada di rumah kita. Gaun yang sama yang dikenakan nenek kita. Dasi yang sama yang dikenakan kakek kita. “Museum sesungguhnya adalah museum yang bisa mengubah waktu menjadi tempat,” ujar Pamuk.
Yang paling membuat saya ngakak, tentu saja ketika di salah satu halaman, saya menemukan frasa “the first Islamic porn films”. Seperti apa film porno Islami ini? Adegan-adegan cintanya merupakan gabungan antara seks dan slapstick, dengan segala adegan percintaan yang ditiru dari film-film porno Eropa, tapi dengan aktor yang tak pernah menanggalkan celana dalam. Tentu saja orang akan bertanya-tanya, di mana pornonya, dan lebih lanjut: di mana Islaminya?
Dan kita tak perlu bersusah-payah untuk mencari film semacam itu di Turki. Mengetahui bahwa seseorang pernah menuliskan perihal ini sudah cukup untuk merasakan ketegangan Barat-Timur. Banyak orang ingin mengadopsi hal-hal hebat dari Barat, tapi ingin membalutnya dengan Timur atau dengan Islam. Apakah hal itu malah tidak menjadi Barat atau tidak menjadi Islam/Timur sama sekali, itu urusan nanti, barangkali.
Novel ini, dengan caranya sendiri menjadi sejenis katalog untuk museum benda-benda yang dikumpulkan oleh Kemal, yang kelak dinamakannya sebagai “The Museum of Innocence”. Hingga bisa juga disebut, buku ini merupakan penjelmaan apa yang dikatakan Aristoteles mengenai waktu.
Dalam Physic, Aristoteles membedakan antara “waktu” dan “momen” (yang diterangkannya sebagai “saat ini”). momen, seperti atom, bersifat mandiri dan tak terbagi-bagi. Sementara waktu merupakan alur yang mengaitkan momen satu dengan lainnya. (Ya, Pamuk menulis soal ini di salah satu bab). Jika The Museum of Innocence merupakan “waktu yang menjelma dalam ruang”, maka benda-benda di dalamnya merupakan “momen-momen”.
Tapi bukankah momen-momen itu, terlepas dari kemandiriannya, juga mengundang tafsir dan sudut pandang yang berbeda-beda? Demikianlah. Meskipun bagi Kemal, sebatang puntung rokok Samson akan mengingatkannya kepada momen, ketika Fusun menempelkan rokok tersebut ke bibirnya, benda itu juga bisa berarti catatan penting perihal penyelundupan rokok, ihwal usaha Marlboro berpenetrasi ke pasar Istanbul, dan akhirnya bisa juga menjadi sejenis kisah antropologis yang lebih kaya dari itu.
Jikalau cerita merupakan rangkaian kejadian, yang ditandai oleh deretan waktu, maka kumpulan benda-benda itu bisa kita sebut sebagai “waktu yang menjelma ruang”. Bukankah demikian hakikat sebuah museum? Di salah satu halaman novel ini, kalimat itu secara eksplisit disebutkan. Bahkan melalui karakter utama Kemal, novel ini menyajikan sejenis esai (sebenarnya novel ini secara keseluruhan bisa dibilang merupakan sejenis esai) tentang waktu.
Apa yang luar biasa dari Museum of Innocence adalah keberhasilan seorang Pamuk dalam menggabungkan antara perspektif huzun (kemurungan) perihal Turki dan patologi seksual dengan sangat mesra. Kerinduan ala Proustian untuk mengambil setiap detail menit per menit dari apa yang hidup seperti di dalam Istanbul-nya si pemuda Orhan Pamuk yang begitu sederhana. Tinimbang dengan kompleksitas dari realitas kehidupan di sana hari ini, tentu saja, Istanbul dalam novel ini memang nampak begitu bersahaja.