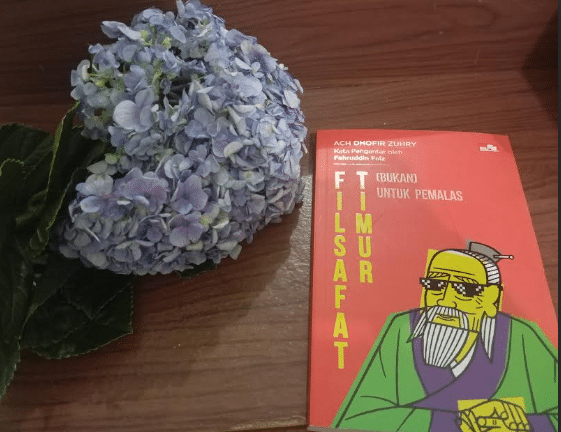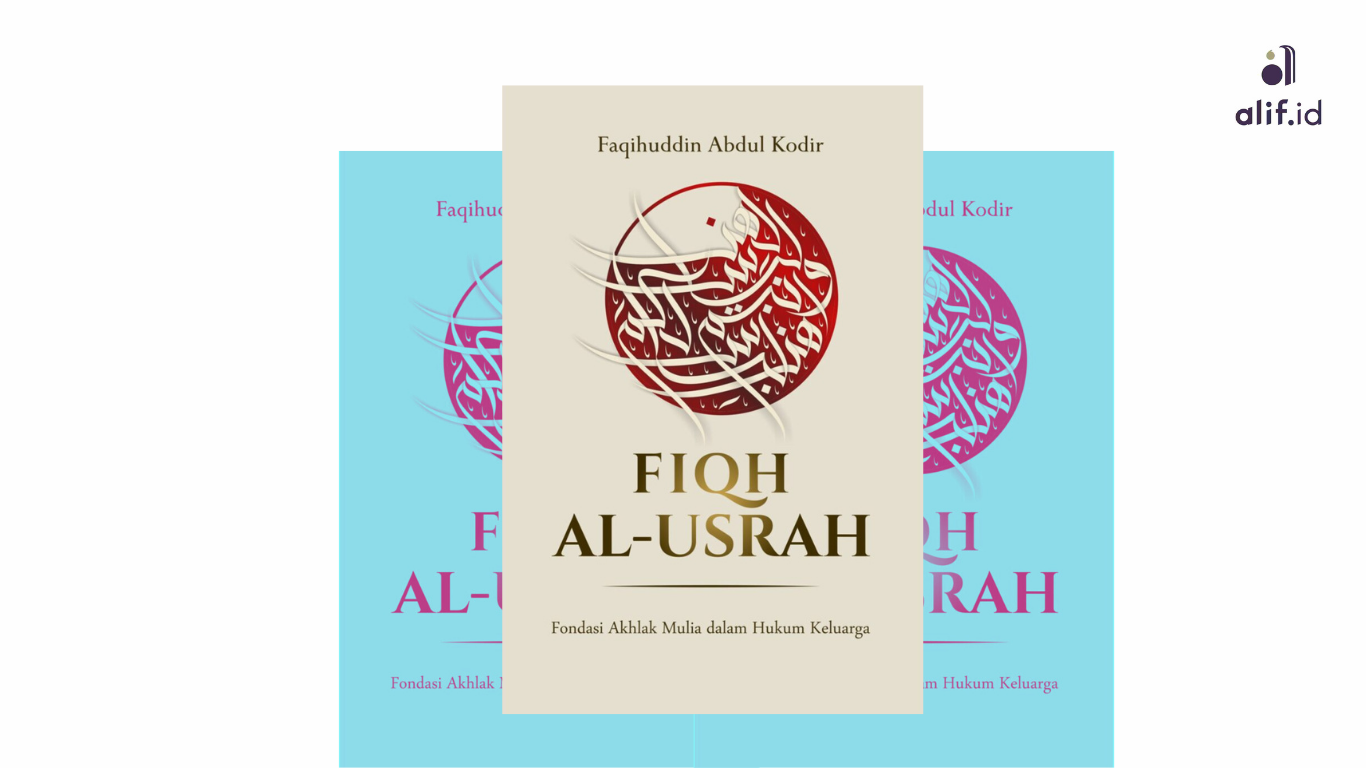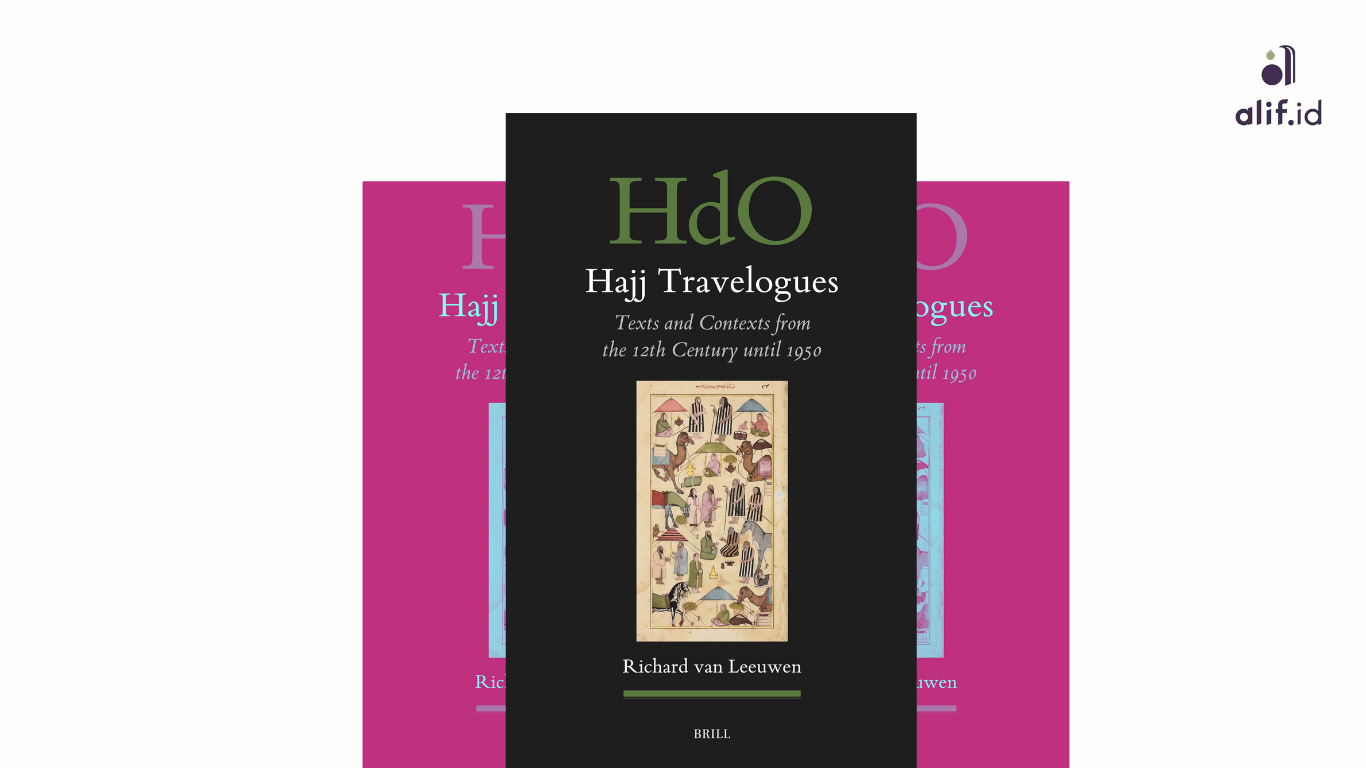“Sebelum revolusi, dia calon rahib. Selama revolusi, dia komandan kompi. Di akhir revolusi, dia algojo pemancung kepala pengkhianat-pengkhianat tertangkap. Sesudah revolusi, dia masuk rumah sakit jiwa.” Merahnya Merah (Iwan Simatupang)
Ini kalimat pembuka novel yang klasik dalam sejarah sastra kita. Membuka salah satu novel Indonesia terbaik sepanjang masa. Saya dulu terpana oleh efektivitas kalimat itu menggeplak rasa ingin tahu di kepala. Dan Iwan Simatupang memang mahir mencipta kalimat yang ringkas, padat, menggebrak, sekaligus mencucuk perhatian pembaca mengikuti aliran cerita di novel-novel dan cerpen-cerpennya yang absurd.
Tapi, kali ini, saya tertarik benar pada kata “revolusi” di situ. Saya teringat, mendapat kesan dari bacaan-bacaan masa silam, pernah ada masa kata “revolusi” ini begitu menggugah dan menggigit rakyat Indonesia. Hingga ke titik nadir, rupanya, ketika kata “revolusi” terlalu banyak dikoarkan dan terlalu bermuatan politik partai dan kekuasaan, pada masa 1960-an hingga pertengahannya. Sesudah peristiwa 30 September 1965, hingga 1966, kata “revolusi” masih digunakan, a.l., oleh Soeharto, untuk merebut diskursus itu dari PKI dan Bung Karno. PKI dinarasikan sebagai “pengkhianat Revolusi”.
Kata “Revolusi” di sini, kita tahu, mengacu pada Revolusi Kemerdekaan RI 1945. Dan memang, kelahiran serta kemerdekaan Indonesia adalah sesuatu yang revolusioner: sebuah perubahan sosial-politik-budaya menyeluruh hingga ke sendi-sendi suatu masyarakat, yang terjadi dalam waktu cepat. Sebuah perubahan sistemik. Yang diubah adalah sistem pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Dan bentuk revolusi itu adalah menciptakan sebuah bangsa baru, sekaligus sebuah negara-bangsa yang menyatakan diri lebih dulu dari pengakuan internasional terhadapnya (yang baru tiba pada 1949).
Tapi, dalam pidato Bung Karno di sidang BPUPKI, tampak jelas di masa genting itu, “revolusi” adalah pertama-tama, revolusi alam pikir: kemampuan berdiri di kaki sendiri. Kemerdekaan, dalam pidato itu, ditempatkan sebagai “jembatan”, dengan janji kemajuan dan kemakmuran modern di seberang jembatan itu.
Iwan Simatupang malah memotret kata “revolusi” yang sekian lama gilang-gemilang itu sebagai sebuah kata penuh kekerasan dalam novel ini. Di awal novel, dengan segera ia menggambarkan sebuah dunia pasca-Revolusi yang penuh darah dan nanah.
“Kini, revolusi telah selesai. Telah lama, kara sebagian orang. Ah! Barangkali juga tak selesai-selesai. Dia tak tahu. Rumah sakit jiwa telah lama pula ditinggalkannya.”
Dan segera saja dalam paragraf demi paragraf sesudah paragraf di atas, Iwan mengisi dunia sesudah revolusi kemerdekaan itu dengan gelandangan, kaki korengan bernanah, remaja yang diperkosa ramai-ramai setelah ayahnya digorok dan ibunya diperkosa ramai-ramai oleh gerombolan begal, desa yang musnah dalam semalam, penduduknya ke kota jadi gelandangan dan pelacur, rumah-rumah gubuk kecil, dan seterusnya. Revolusi dalam dunia novel ini tak memenuhi janjinya. Dan itu baru di bab pertama.
Tentu saja, orang bisa curiga, novel Iwan ini tak lebih dari bagian “kekerasan budaya” Orba. Terbit 1968, dan tampak seiring dengan upaya depolitisasi istilah “revolusi” rezim Soeharto. Di masa Orba, “revolusi” jadi kata dekoratif belaka setiap upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Film-film perjuangan versi Orba dibikin dan menggeser makna “revolusi kemerdekaan” jadi hanya “revolusi bersenjata” pada suatu masa lampau melawan Belanda dan Jepang.
Bahkan, ketika terjadi revolusi politik pada 1998, kata yang dipilih sebagai bendera adalah “reformasi”. Padahal, ia juga sebuah perubahan sistemik yang berjalan cepat: penerapan otonomi daerah, kebebasan pers, peluruhan dwifungsi ABRI, perubahan lembaga legislatif (DPR) yang jadi lebih terbuka pada partai2, pilpres langsung, dsb. Sampai kemudian kata itu diangkat lagi oleh Jokowi, dengan istilah “Revolusi Mental”.
Saya sempat membatin, istilah “revolusi mental” adalah sebuah oksimoron. Revolusi semestinya bersifat sistemik dan struktural, tapi “revolusi mental” bermain di wilayah yang aman-aman saja, saya pikir, yakni wilayah “mental”. Dalam konstruksi ide Jokowi, pengertian “mental” ini lebih ke soal cara berpikir, sikap, dan psikologi individu untuk membangun bangsa. Sebuah konstruksi yang sering kita jumpai di kalangan pebisnis “sukses”.
Tapi, ada juga yang menganggap serius jargon Jokowi ini, dan itu menarik. Saat menanti arak-arakan Jokowi seusai dilantik sebagai presiden RI di gedung MPR pada 2014, di bundaran HI, kawan saya Krisnadi Yuliawan, ngobrol dengan Sarwono Kusumaatmaja.
Sarwono, yang tampak menikmati suasana pesta rakyat saat di bawah terik matahari itu, tiba-tiba berucap dengan nada reflektif: “Yang paling sulit bagi Jokowi nanti itu adalah soal revolusi mental. Sulit mengubah perilaku orang-orang di dalam sistem yang telah lama nyaman dengan perilaku selama ini.”
Saya jadi kepikiran sesudah itu. Apakah berarti “revolusi mental” memang sebuah persoalan nyata? Sarwono adalah politisi yang menarik, politisi Golkar yang turut mengubah persepsi masyarakat agar berani berpikir mengganti Soeharto semasa saat-saat genting Reformasi 1998 dulu lewat wawancara “sakit gigi” dengan Ira Kusno di sebuah televisi swasta.
Setelah lima tahun pertama masa kepresidenan Jokowi, kata “revolusi mental” jadi bahan ledekan kaum oposisi dan mereka yang kecewa pada Jokowi-JK. Pada periode kedua ini, Jokowi sendiri agaknya sudah jarang menyebut istilah ini. Di dalam kancah politik warga, kata “revolusi” sesekali masih melenting di kalangan kaum anarko muda. Mereka ini kebanyakan bukan kaum proletar beneran, tapi anak-anak kelas menengah kota yang memproletar-proletarkan diri. Apakah karena itu, kata “revolusi” di kalangan mereka yang sering bocor ke linimasa medsos saya, sering terasa kopong?
Dengan kalimat pembuka novelnya, Iwan Simatupang menunjukkan betapa pernah ada masa kata “revolusi” menjadi sebuah kata yang prominen, bahkan seakan sebuah “mother of reality”, bunda kenyataan: hidup Tokoh Kita, sosok tak bernama yang jadi tokoh utama novel Merahnya Merah, terpacak dalam kata “revolusi”. Di sekujur novel tersebut, Iwan Simatupang seakan hendak mengabarkan bahwa dunia kenyataan yang lahir dari rahim revolusi itu telah tak ada lagi.
Benarkah memang sudah tak ada, atau tak perlu, revolusi di Indonesia?
Selamat Hari Merdeka!