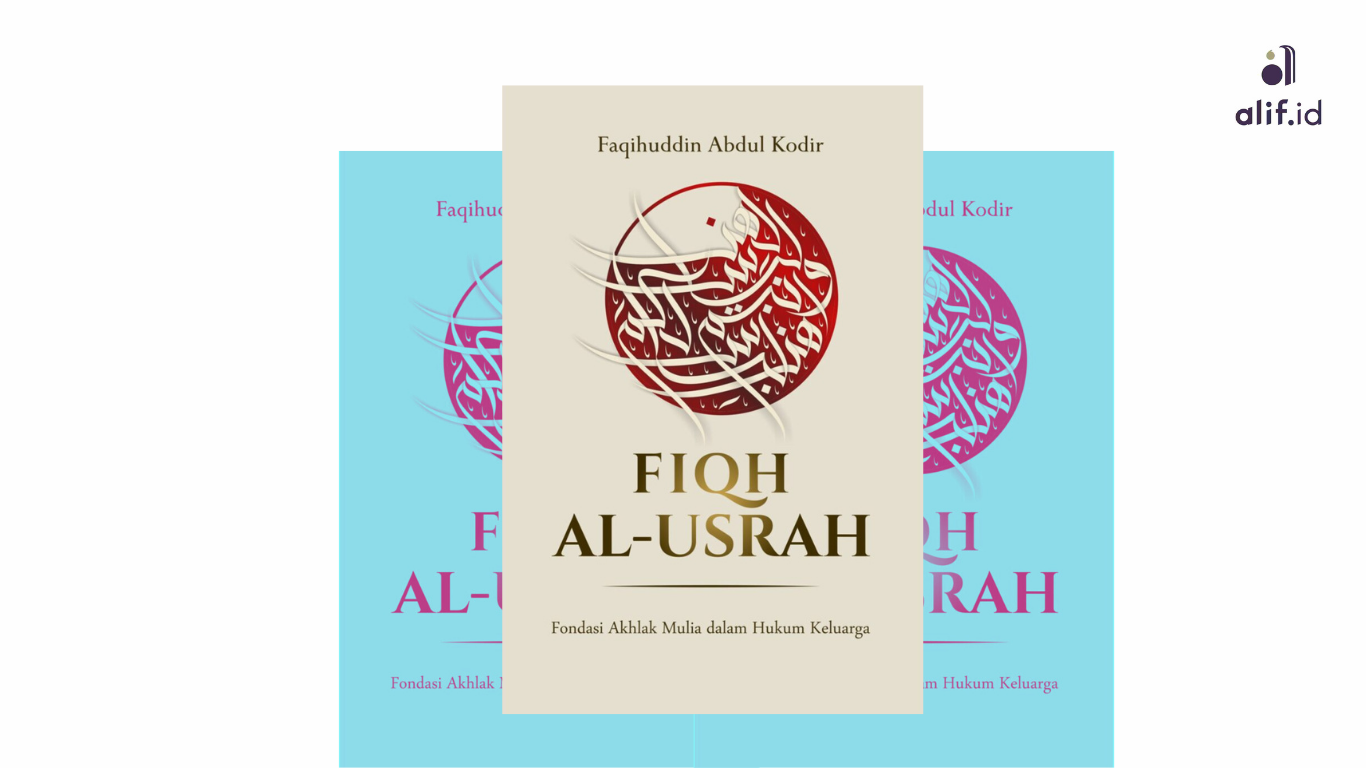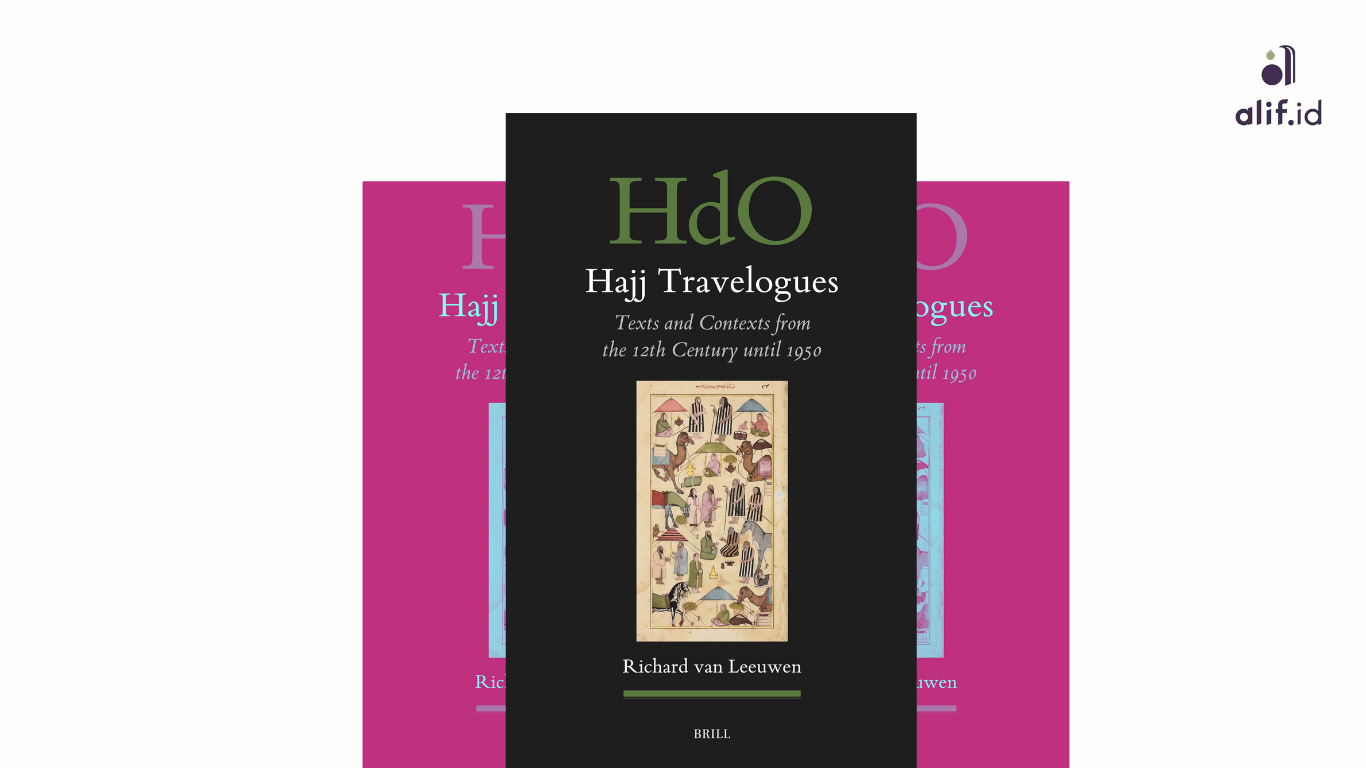Novel dari Negeri Terbelah
Novel-novel Mustaghanami lebih banyak menggambarkan kegelisahan negeri asalnya. Betapapun Aljazair adalah negeri yang terbelah. Selepas masa kemerdekaan di tahun 1962, Aljazair mengalami semacam kegamangan identitas. Di satu sisi, Aljazair adalah negara Arab Afrika Utara yang mendapatkan kemerdekaannya dari Prancis—setelah dijajah sejak 1803, tetapi di sisi yang lain, tradisi dan budaya Prancis justru tak enyah dan semakin mengakar urat saja.
Aljazair perlahan-lahan mengkhianati dirinya sendiri dengan meninggalkan tradisi dan ”identitasnya” sebagai negara Arab, dan lebih memilih untuk meniru tradisi dan identitas penjajah Prancis. Arab seakan dipandang sebagai keterbelakangan, sementara Prancis dipandang sebagai kemodernan dan masa depan yang menjanjikan.
Inilah sejatinya titik nadir kegamangan Aljazair; ketika kebencian dan ketergantungan, bahkan pemujaan kepada penjajahnya bertaut menajdi satu. Ada sesuatu yang seakan menjadi kebenaran: sejarah Aljazair modern harus dibangun di atas jejak kolonialisme Prancis, yang justru telah membantai puluhan ribu rakyat Aljzair.
Dalam hal ini, membaca novel-novel Mustaghanami akan mengingatkan kita pada sosok Orhan Pamuk, novelis Turki peraih nobel sastra 2006. Dalam karya-karyanya, Pamuk menggambarkan negerinya yang tengah mengalami kegamangan identitas; sebagai bagian Barat-Eropa di satu sisi, dan sebagai bagian Timur-Islam di sisi yang lain. Tentu saja, antara Barat-Eropa dan Timur-Islam merupakan dua entitas tradisi, identitas, dan peradaban yang silih berbeda—sekalipun tak mesti berseberangan.
Kegamangan identitas Aljazair dapat dilihat dari fenomena keseharian yang sederhana dan kasat mata. Betapapun di Aljazair, bahasa Prancis lebih dominan dan ”bergengsi” dari bahasa Arab. Sangat mengherankan memang, ketika sesama warga Arab di Aljazair—utamanya yang tinggal di kota-kota besar, lebih terbiasa berbicara menggunakan bahasa Prancis daripada bahasa Arab. Warga Aljazair pun seolah memiliki identitas ganda, yakni, secara tradisi dan identitas mereka adalah Arab, tetapi budaya dan bahasa mereka adalah Prancis.
Sindrom budaya dan bahasa Prancis demikian kuat dan bahkan dominan, menggerus budaya dan bahasa Arab. Fenomenafrancophone, atau ”Prancisasi” budaya dan bahasa ini demikian mendemam, sehingga menjadikan budaya dan bahasa Arab terpuruk dalam kubangan keterasingan. Sayangnya, keterasingan bahasa ini juga merambah dunia susastra Aljazair. Kebanyakan sastrawan Aljazair, semisal Hamid Grine, Anwar Benmalek, Yasmina Khoudra, Mirna Shaab, dan Ghazai Proue, lebih banyak yang menulis karya-karya mereka dengan bahasa Prancis.
Di tengah keterasingan bahasa Arab akibat merebaknya sindrom Fenomenafrancophone di negerinya, Mustaghanami justru berusaha untuk melawan semua keterasingan itu, yaitu dengan menulis novel-novelnya dalam bahasa Arab. Jerih usaha Mustaghanami ini lantas menobatkan dirinya sebagai perempuan novelis Aljazair pertama yang menulis karya-karyanya dalam bahasa Arab. Dewan juri dari Naguib Mahfouz Medal memuji usaha Mustaghanami tersebut. Ia didaku sebagai sosok sastrawan Aljazair yang dengan gigih berjuang melestarikan bahasa Arab di tengah pelapukan, keterasingan, dan kepunahannya akibat sindrom Prancis yang merebak di negeri itu.