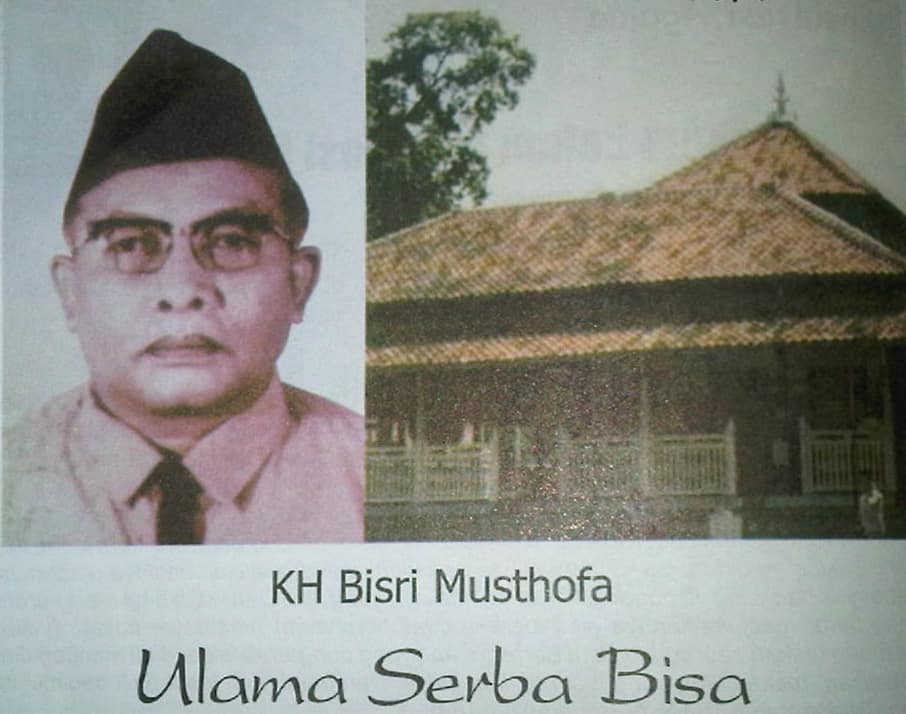Kisah ini dikutip dari karya sufistik klasik Rumi, yakni Matsnawi. Suatu hari, ketika Nabi Musa a.s. turun dari Gunung Sinai, seseorang bertanya, "Apakah kau bisa mengundang Tuhan untuk datang dan makan malam bersama kita?"
Nabi Musa a.s. menjawab dengan marah, "Kita tidak bisa mengundang Tuhan untuk datang makan malam. Tuhan tidak makan malam. Tuhan tidak terbatas. Tuhan melampaui batasan kebutuhan akan makanan. Selain itu, Tuhan tidak memiliki mulut. Tuhan jauh melampaui bentuk ragawi manusia! Tuhan tidak seperti kau dan aku. Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan adalah segalanya."
"Apa kau yakin kita tidak bisa mengundang Tuhan untuk makan malam bersama kita?"
"Ya!"
Ketika Nabi Musa a.s. kembali ke Gunung Sinai, Tuhan bertanya tentang undangan tersebut. Nabi Musa a.s. berkata, "Aku bilang bahwa Kau tidak dapat makan."
Tuhan berkata, "Tidak, Musa. Kembalilah dan katakan kepada mereka untuk menyiapkan pesta besok sore dan Aku akan datang."
Bisakah kita bayangkan bagaimana perasaan Nabi Musa a.s.? Dia harus kembali dan mengatakan kepada kaumnya bahwa ia salah, bahwa Tuhan akan datang untuk makan malam bersama mereka. Ia harus lakukan itu setelah sebelumnya mengatakan dengan tegas bahwa Tuhan tidak punya mulut, Tuhan tidak makan atau minum, dan Tuhan mestinya tidak dianggap sama seperti manusia. Tentu saja, itu sangat berat baginya. Namun, perintah Tuhan harus dijalankan. Pesan-Nya harus disampaikan.
Semua orang sangat senang mendengar kabar itu. Mereka menyiapkan sebuah pesta besar keesokan harinya. Para juru masak membuat hidangan terbaik. Semua orang sibuk ikut mempersiapkan pesta tersebut.
Di tengah-tengah kesibukan persiapan pesta, seorang lelaki tua datang. Dia bertanya apakah ia bisa mendapatkan makanan dan minuman? Nabi Musa a.s. menjawab, "Tuhan akan datang untuk makan malam. Tunggu sampai Tuhan datang. Tidak seorang pun boleh makan sebelum Tuhan datang!"
Para juru masak menyuruh orang tua itu bekerja mengambil air.
Waktunya makan malam tiba dan berlalu, tetapi Tuhan tidak muncul juga. Malam semakin larut. Makanan mulai menjadi dingin. Tentu saja orang-orang mengeluh kepada Nabi Musa a.s. "Pertama kau mengatakan bahwa Tuhan tidak makan, lalu kau bilang Tuhan akan datang untuk makan malam bersama kita dan sampai sekarang Tuhan belum juga muncul. Nabi macam apa kau?" Nabi Musa a.s. yang malang tidak tahu harus berbuat apa.
Keesokan harinya, Nabi Musa a.s. kembali naik ke Gunung Sinai dan mengeluh, "Wahai Tuhan, aku sudah bilang kepada kaumku bahwa Engkau tidak makan. Kemudian Engkau mengatakan akan datang makan malam, tetapi Engkau tidak muncul."
"Aku sudah datang. Aku kehausan dan kelaparan, tetapi tidak seorang pun memberiku sesuatu untuk dimakan dan diminum. Lelaki tua yang datang dari gurun pasir adalah salah satu hamba-Ku dan ketika kalian memberi makan hamba-Ku, kalian memberi-Ku makan; sewaktu kalian melayani hamba-Ku, kalian melayani-Ku."
***
Kisah di atas dikutip dari buku berjudul “Obrolan Sufi”, yang merupakan terjemahan dari buku Sufi Talks : Teachings of an American Sufi Sheikh karya Prof. Robert Frager Ph. D. Tempo hari ketika saya membagikan cuplikan kisah tersebut di akun media sosial pribadi, ternyata banyak orang yang menyukainya. Bahkan beberapa di antaranya mengaku sampai merinding membaca kisah ini karena hikmah yang disampaikan sangat dalam.
Selama ini, beberapa orang mungkin salah kaprah dalam memahami konsep melayani Sang Ilahi. Saya katakan mungkin, yang artinya tidak semuanya. Mereka cenderung menafsirkan wujud pengabdian dan pelayanan itu hanyalah dalam bentuk ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ini berarti menjalin hubungan vertikal ke atas – hablunminallah. Padahal sebenarnya, menjalin hubungan dalam arah horizontal – hablunminannaas pun adalah hal yang tidak kalah pentingnya.
Sesuai dengan kisah yang disampaikan di atas, ketika kita melayani orang lain itu sama halnya dengan kita melayani-Nya. Ketika ada seseorang yang datang menemui kita untuk meminta pertolongan, maka selayaknyalah kita ulurkan tangan. Dan ini tidak terbatas pada iman atau agama, derajat sosial atau kedudukan orang tersebut dalam masyarakat. Siapapun dia, wajib kita bantu selama kita mampu.
Apabila hal ini diterapkan dengan benar, niscaya tidak akan ada tindakan diskriminasi atas dasar ras, agama, gender dan sebagainya.
Pernah ada juga kisah yang beredar, tentang akhlak seorang kiai kampung. Dikisahkan pak kiai yang juga adalah kepala pesantren di kampung tersebut adalah orang yang gemar berpuasa Sunnah Senin – Kamis. Suatu hari ada seorang tamu yang datang berkunjung ke rumah pak kiai. Sebagaimana adab melayani tamu, pak kiai menghidangkan jamuan untuk tamunya tersebut. Ternyata si tamu malah meminta pak kiai untuk menemaninya makan. Tamu tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa pada hari tersebut, pak kiai sedang berpuasa Sunnah.
Lalu apa yang dilakukan pak Kiai? Ia membatalkan puasanya dan ikut menyantap hidangan yang telah disediakan. Tak ayal hal ini menimbulkan keheranan pada para murid yang menyaksikan kejadian tersebut, karena biasanya pak Kiai sangat tertib dan disiplin dalam menjalankan ibadah puasa sunnahnya. Selidik punya selidik, ternyata tamu tersebut sebenarnya ‘hanyalah’ seorang sales penjaja sebuah produk. Pak kiai kampung itu telah menunjukkan bagaimana seharusnya seorang hamba Allah melayani hamba-Nya yang lain dengan ikhlas, tanpa pamrih atau pilih-pilih.
Lebih jauh lagi, dalam ilmu tasawuf, konsep melayani hamba-Nya ini adalah salah satu implementasi dalam menerima segala macam hal yang dihadirkan oleh-Nya. Apapun itu, entah orang yang bertamu, entah tetangga yang meminta bantuan, sekedar seekor kucing yang meminta makanan, atau bahkan peristiwa kemalangan dan musibah yang menimpa, semuanya adalah hal yang sudah ditentukan oleh-Nya untuk hadir menemui kita. Tinggal bagaimana respon kita terhadap kehadiran hal-hal tersebut.
Pada level tertentu, buat para sufi, ungkapan alhamdulillah tidak hanya berlaku ketika memperoleh sebuah kenikmatan atau rezeki, namun juga termasuk ketika mendapatkan penyakit atau musibah. Wallahualam []