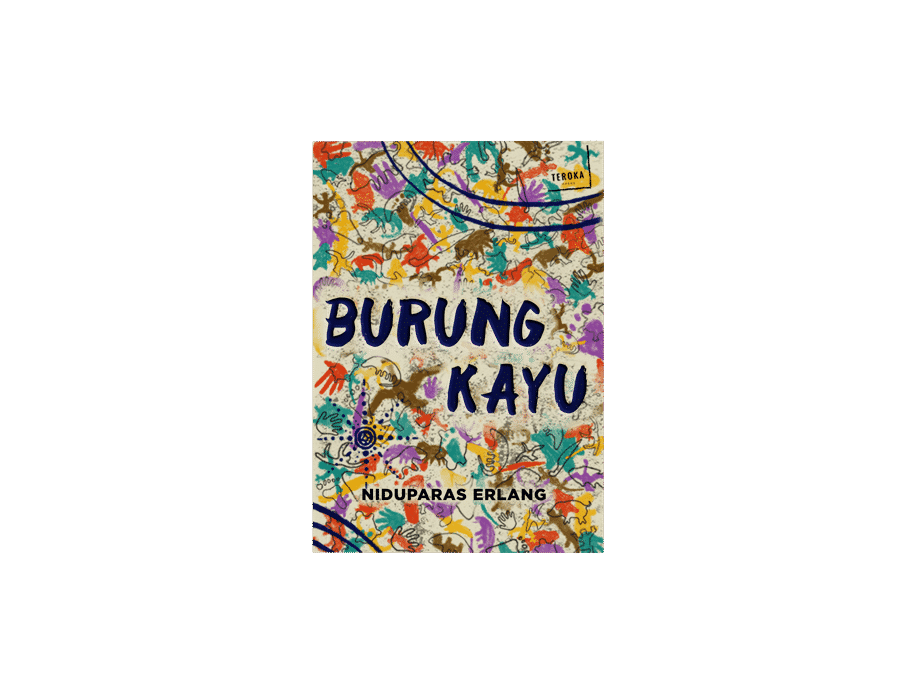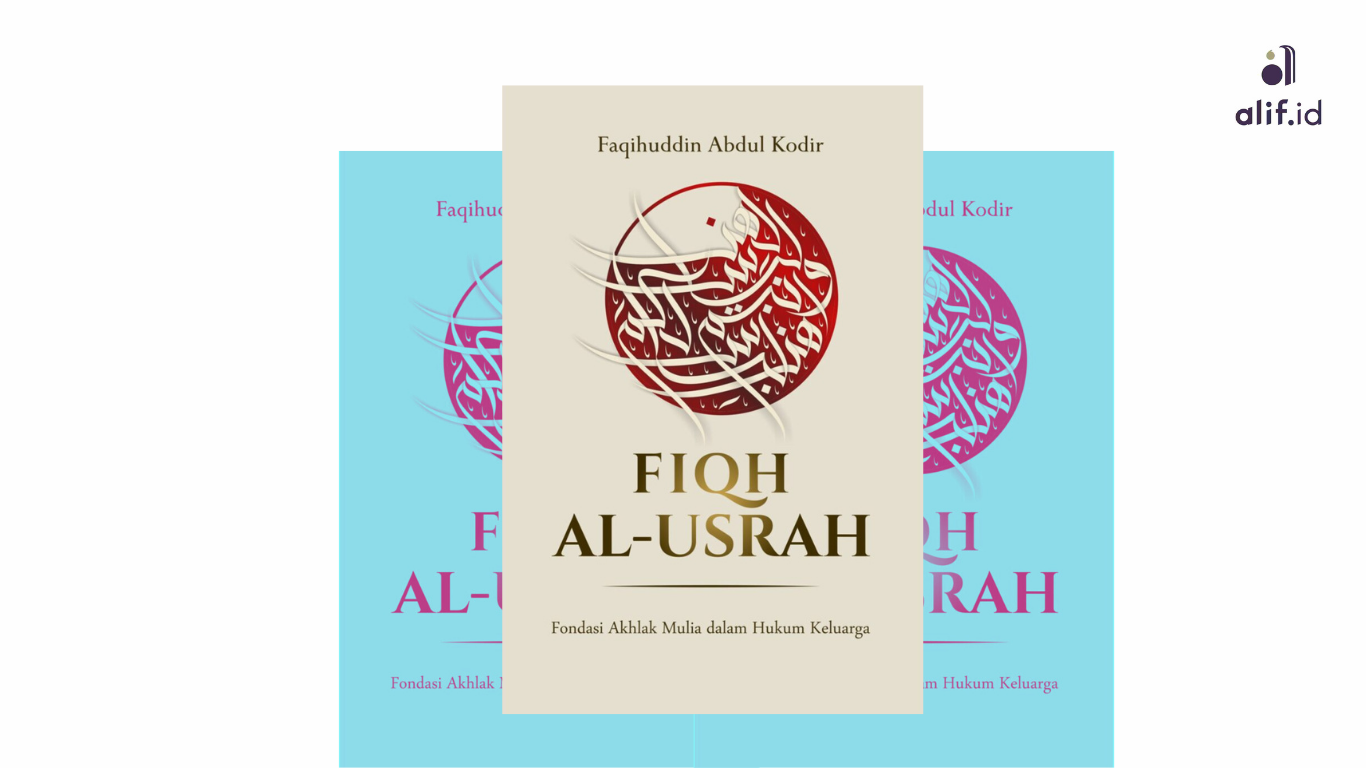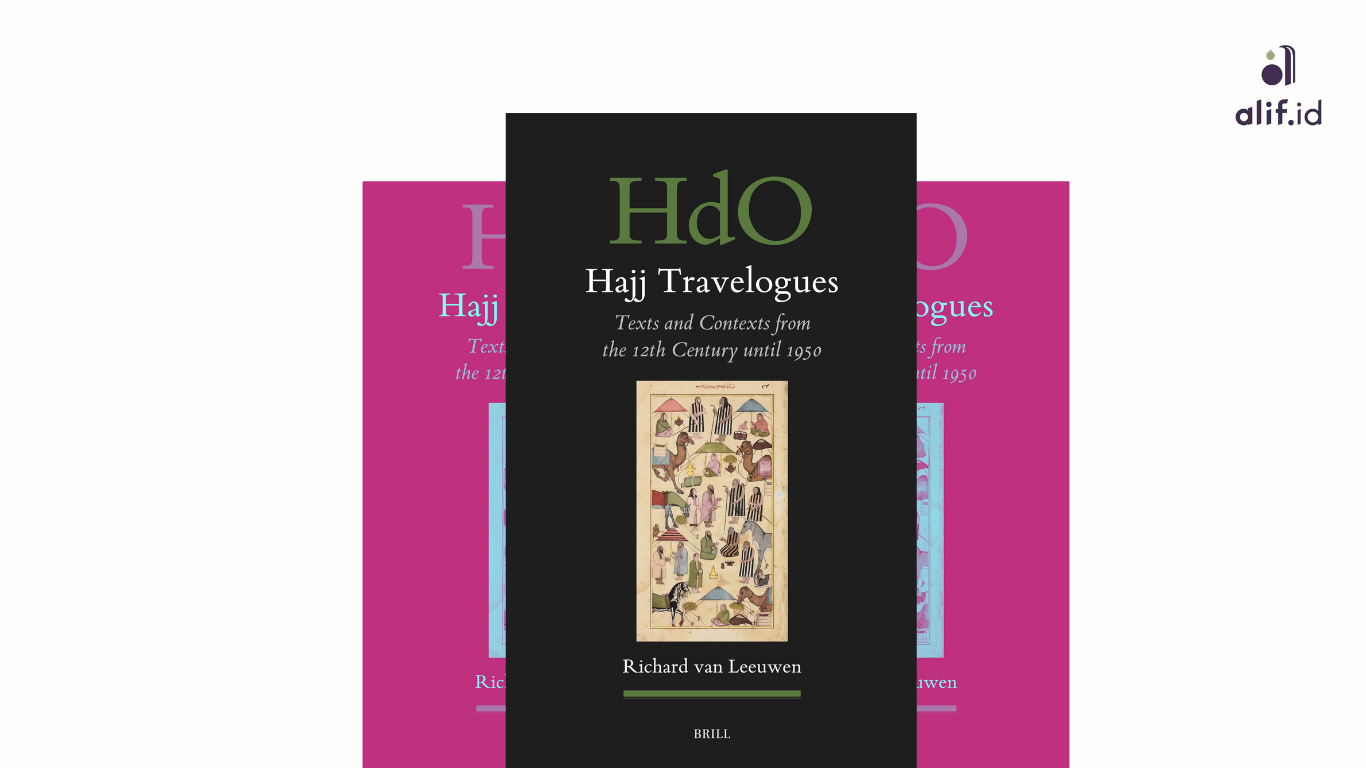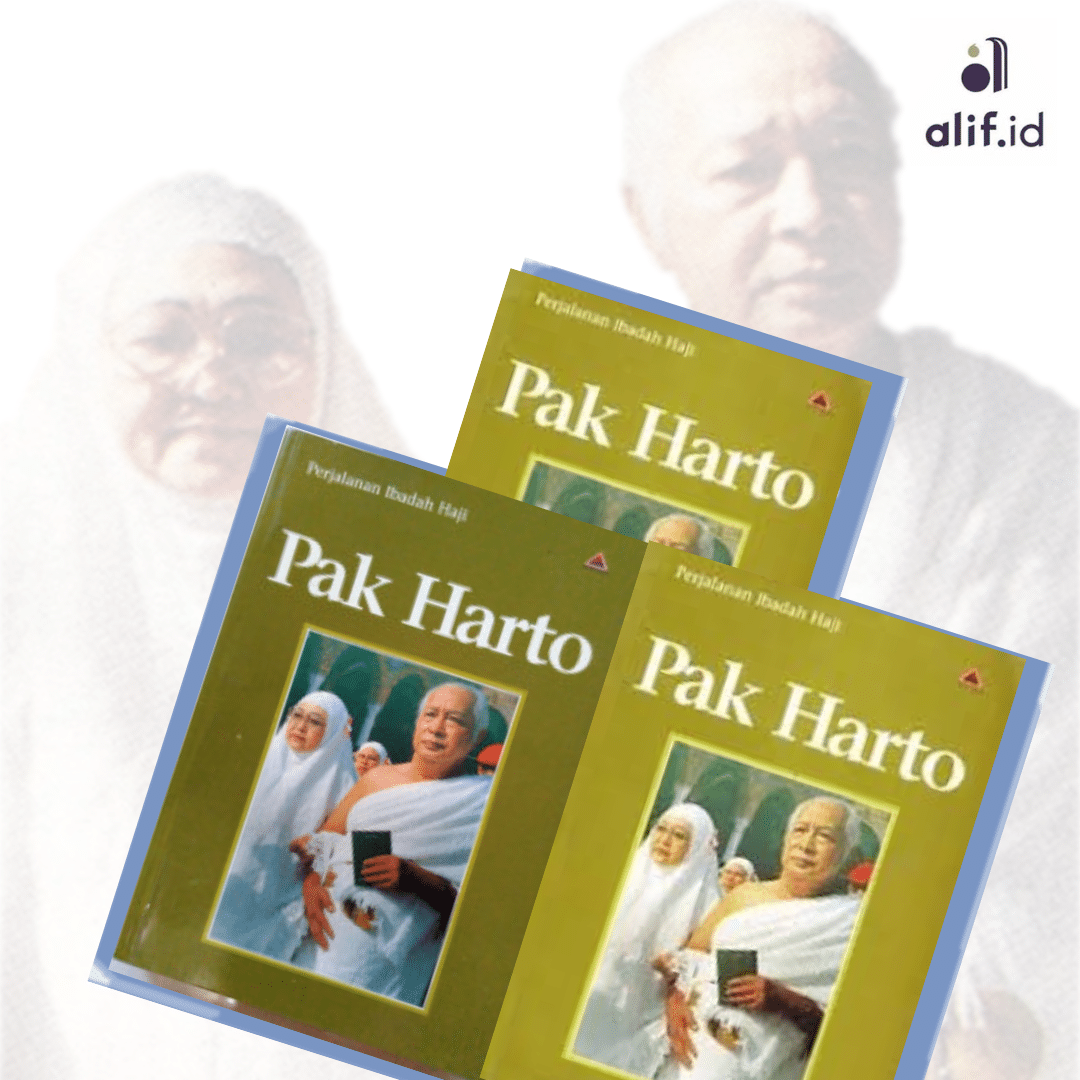Alkisah, Harihar Roy bermukim di sebuah desa bernama Nischindipur. Dia tinggal bersama isterinya, Sarbajaya; puterinya, Durga; dan puteranya, Apu. Seorang kakak sepupu bernama Indir Thakrun tinggal bersamanya pula, tetapi meninggal dunia tatkala Apu dan Durga masih kecil.
Sebagai Brahmana, Harihar hidup dengan bekerja sebagai pendeta keluarga bagi banyak orang. Pekerjaan itu menyebabkannya sering meninggalkan keluarga untuk waktu yang lama, tetapi pendapatannya kecil dan tidak menentu.
Saat dia pergi, isterinya Sarbajaya harus dapat menjaga dirinya dan kedua anaknya, berjuang mengatasi kemiskinan dan kesombongan para tetangganya yang kaya. Akan tetapi, Apu kecil dan kakak perempuannya, Durga, sama sekali tidak terganggu oleh popokan kemiskinan itu.
Kecintaan mereka terhadap alam melindungi mereka dari gangguan itu; keriangan karena dapat menjelajahi hutan atau tepian sungai dengan langgas menghapus segala kekecewaan dan kemelaratan hidup yang melanda.
Kemudian bencana menimpa. Durga mati ketika baru berumur 13 tahun. Sejak itu, Harihar dan Sarbajaya insaf, bahwa tidak ada yang bisa mereka peroleh dengan tetap tinggal di Nischindipur. Mereka harus menemukan kehidupan yang baru, di tempat nan anyar. Dengan pikiran begitu, mereka jual barang-barang mereka yang hanya sedikit, lalu pindah ke Kashi (Benares). Apu baru berumur 10 tahun ketika itu.
Untuk beberapa waktu lamanya keadaan tampak membaik. Harihar hidup dari membacakan Kitab Suci dan menceritakan kisah dari mitologi Hindu di Dashashwamedh Ghat. Ada beberapa pesaingnya yang juga melakukan pekerjaan itu, namun penghasilannya mulai lebih baik tinimbang ketika mereka masih tinggal di desa. Kamar sewaan yang mereka tinggali gelap dan lembab, tetapi di sinilah Sarbajaya merasa senang. Apu mulai bersekolah, dan segalanya berjalan geladir.
Tetapi hanya dalam waktu sekitar setahun keluarga itu sudah pecah kembali. Kali ini jauh lebih buruk keadaannya. Harihar, satu-satunya pencari nafkah, meninggal dunia setelah sakit sebentar. Sarbajaya terpaksa harus menjaga dirinya sendiri dan puteranya, di tempat yang gabir, tanpa teman, dan tiada uang sepeser pun.
Beberapa tetangga yang baik hati memang menolongnya, tetapi tentu saja tak dapat berlangsung selamanya. Harga diri membuatnya tidak mungkin kembali ke Nischindipur. Kalaupun ia terpaksa kembali ke sana, Sarbajaya tahu, tidak akan bisa ia tinggal di rumahnya nan tua dan bobrok itu.
Pasca berjuang sengit selama sebulan, datang tawaran pekerjaan. Sebuah keluarga dari Burdwan (di Bengala) yang sedang berkunjung ke Kashi membutuhkan seorang perempuan Brahmin untuk membantu memasak. Mereka ingin membawa juru masak yang baru itu saat mereka kembali ke Burdwan. Sekali lagi Sarbajaya dan Apu harus pindah dari rumahnya, tetapi hanya itulah yang bisa mereka lakukan agar tidak mati kelaparan. Mereka pindah ke Burdwan dengan gembira.
Tempat tinggal mereka yang baru ternyata sebuah lingkungan rumah tangga yang besar dan kaya raya, penuh dengan pelayan dan pembantu. Sarbajaya bergabung dengan kelompok dapur sebagai pembantu juru masak. Ia dan Apu mendapat sebuah kamar kecil dekat kandang. Keadaan itu jauh dari menyedang, tetapi paling tidak, ibu dan anak mendapat lagi tempat berteduh.
Selagi Sarbajaya menghabiskan sebagian besar waktunya di dapur, Apu menjelajahi rumah besar itu, sambil mengamati para penghuninya dari jauh. Pada mulanya dia terlalu jengah dan takut mendekati siapa pun di antara mereka.
Namun ketika berlangsung pesta pernikahan di tengah keluarga itu, dan banyak kerabat datang dari kota-kota dan desa-desa lain, dia berkenalan dengan seorang gadis bernama Leela. Ia beberapa tahun lebih muda dari Apu. Ayahnya adalah salah seorang pemilik rumah besar itu, tetapi tinggal di Calcutta.
Meskipun Leela tinggal di situ hanya beberapa hari, persahabatan sempat tumbuh di antara kedua anak itu, terutama karena Leela dan ibunya (yang dikenal oleh para pegawai sebagai Mejo Bourani) baik hati, penuh kasih sayang, dan sama sekali tidak angkuh.
Bahwa Apu adalah anak seorang juru masak, sepertinya mereka tidak peduli. Leela tidak ragu-ragu mengajak Apu masuk ke kamar belajarnya, memperlihatkan buku-bukunya, dan bahkan menjenguk Apu di kamarnya yang sempit dan bau.
Leela memberikan pulpennya, meskipun Apu menolaknya, semata-mata karena Apu belum pernah melihat pena yang tidak perlu dicelupkan ke dalam tinta. Ketika Leela kembali ke Calcutta, baik Leela maupun Apu tidak menyadari bahwa persahabatan mereka adalah persahabatan yang akan berlangsung sepanjang hidup mereka.
Pasca kepergian Leela, Apu mencoba berteman dengan anak-anak lain di rumah besar itu. Namun, tak lama kemudian, dia pun tahu bahwa mereka tidak semanis dan sebaik hari Leela. Suatu hari, Apu dituduh melukai seorang anak, padahal tidak, dan dia dihukum berat. Apu berusaha keras untuk menyembunyikan hal ihwal ini dari ibunya, tetapi patah pucuk. Keduanya pun merasa terhina, tapi tak bisa berbuat apa-apa.
Pada waktunya, mereka pun dapat menerima situasi itu. Apu merindukan hari-hari bahagia masa kecilnya di tepian sungai Ichhamoti; dan terutama dia merindukan kakaknya dan teman-teman mainnya yang lain, khususnya seorang gadis bernama Ranu.
Tetapi di dalam hati dia mengerti bahwa hidup bukanlah untuk melihat ke belakang dan tenggelam dalam kesedihan. Optimisme yang melekat pada sikap dan pendekatan Apu terhadap kehidupan, menghapus semua kemasygulan. Apu sadar masa depan akan menjadi miliknya, asalkan dia mampu memandang ke depan.
Arkian, imbauan nyata dalam novel Pater Pancali: Tembang Sepanjang Jalan karya Bibhutibhushan Banerji –yang tak lekang oleh waktu –ini, pada pokoknya disebabkan oleh dua faktor. Pertama, pelukisan yang betul-betul otentik, menggetarkan dan indah, perihal orang-orang desa dan kehidupannya sehari-hari. Kedua, hal-hal itu dipanggungkan melalui nalar, mata, dan lidah seorang anak lelaki beserta kakak perempuannya, Durga.
Apu dan Durga ialah anak-anak yang nyata, yang hidup, yang alami. Mereka berpikir, berwatak, dan berwicara galib selaiknya anak-anak. Sedikit sekali penulis dalam kesusastraan mana pun yang dapat menyaingi Banerji dalam memafhumi dan menyatakan empati kepada tingkah polah anak, dan dia menulis tanpa sesuatu kesan keramahan orang dewasa.
Selain itu, dalam Pater Pancali, desa tidaklah diidealkan. Ia tidak didedahkan ataupun dikomentari. Ia disajikan sebagaimana adanya, kadang-kadang secara objektif, tapi lebih sering secara subjektif, oleh orang-orang yang hidup di situ –terutama oleh kedua anak itu.