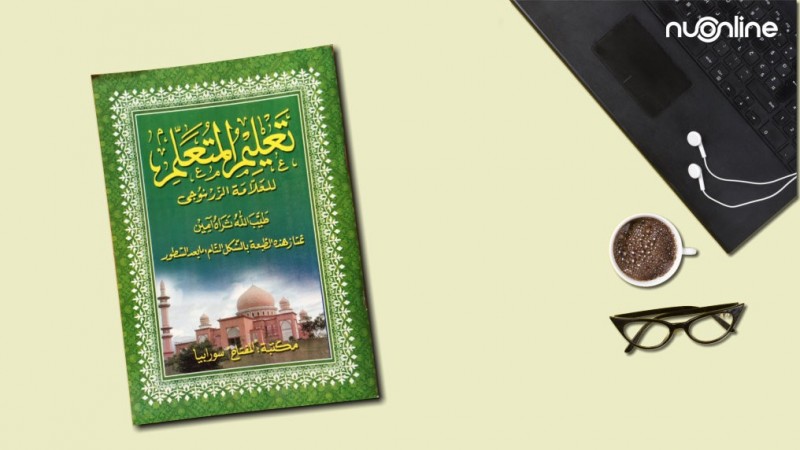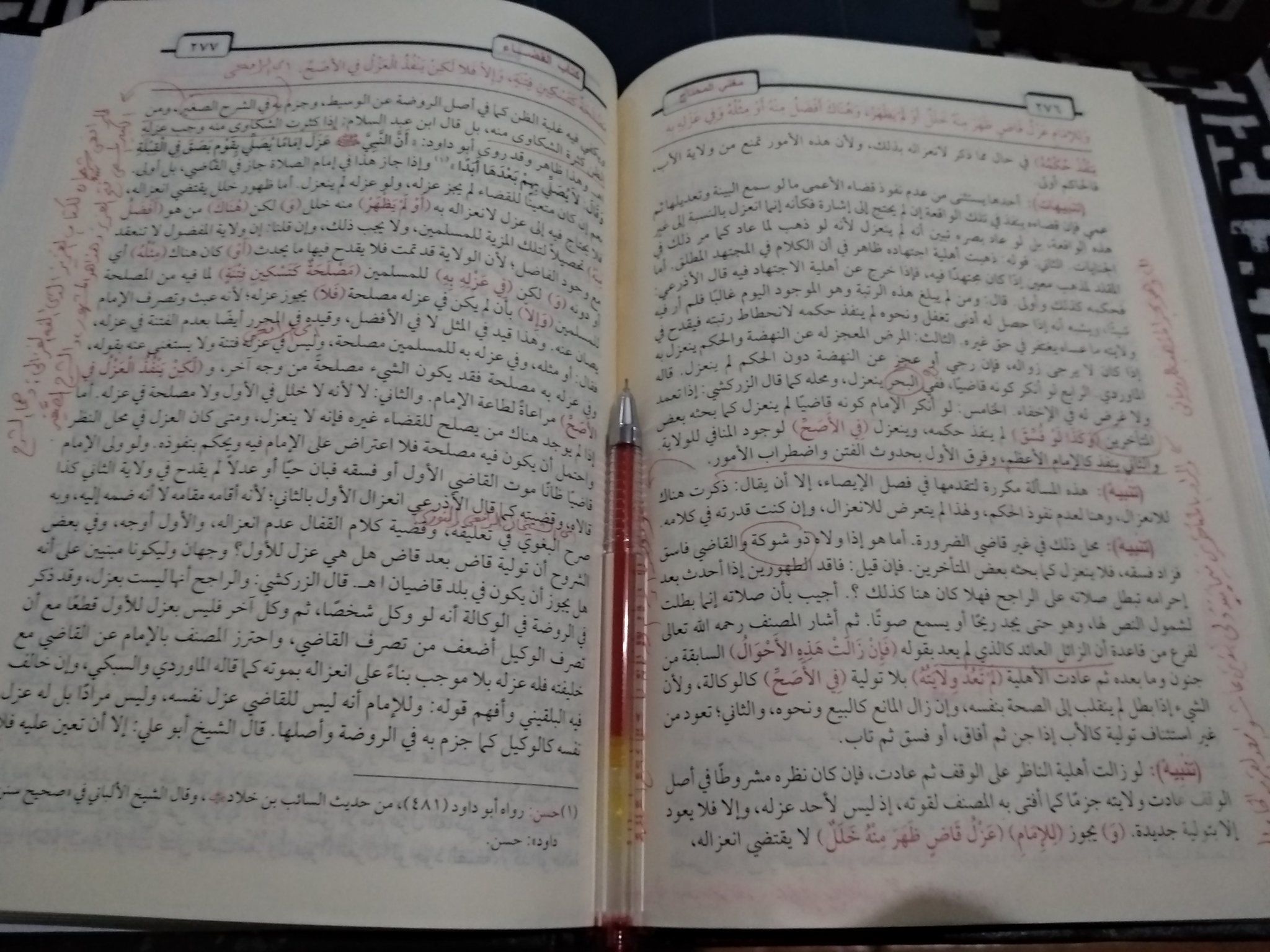Tentang tiga hal tulisan ini dibuat. Pertama, ‘panasnya’ perdebatan religiusitas di seputar kontestasi politik sebagai dampak dari politik identitas dan politisasi agama.
Kedua, serentetan ‘bencana’—sebagaimana sebagian besar dari kita menamainya—di sepanjang 2018 mulai dari gempa beruntun di Lombok pada bulan Juli yang menewaskan 348 jiwa, tsunami Palu dan Donggala yang menewaskan 2113 jiwa, serta yang terbaru tsunami Selat Sunda yang menewaskan 437 jiwa. Belum termasuk cuaca ekstrim dengan intensitas hujan deras dan angin (super) kencang di beberapa lokasi termasuk Bogor dan Cianjur serta penampakan awan mirip gelombang ombak tsunami di Makassar.
Ketiga, fenomena sinetron religi bertema ‘azab’ baik yang berjudul ‘Azab’ maupun ‘Zalim’ yang menampilkan segala sesuatu serba hitam putih dan simplifistik, dengan judul serba ‘provokatif’ sekaligus jenaka sehingga urusan ‘hukuman’ Tuhan lebih terasa seperti olok-olok.
Pada 24 Oktober 2018 Kumparan melansir 194 judul FTV bertema seperti ini dengan contoh judul sebagai berikut: Durhaka Kepa Suami, Jenazah Istri Membusuk Berhari-hari, Penipu Investasi Bodong yang Kakinya Membengkak Tewas di Dalam Mobil yang Jatuh ke Jurang dan Terbakar, atau Pasangan Pengoplos BBM Mati Terbakar Bensin, Jenazahnya Tertimpa Tiang Listrik dan Liang Lahatnya Tersambar Petir Berkali-kali.
Apa irisan yang dapat kita bedah dari ketiga fenomena tersebut kaitannya dengan judul tulisan yang saya tawarkan?
Pertama-tama, saya harus mengapresiasi kadar generosity atau kedermawanan dan solidaritas masyarakat Indonesia yang senantiasa sigap bahu-membahu menolong sesama yang terdampak bencana. Tidak hanya hari ini, bahkan ketika tsunami 2004 menerjang Aceh.
Jika boleh membangga-banggakan kesalehan kolektif kita, kedermawanan dan solidaritas yang demikian bagi saya sudah merupakan outcome nyata dari ketakwaan dan keislaman kita.
Walau kadar kebanggaan diri itu terciderai oleh ulah oknum yang memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi—dengan motif apapun, mulai dari yang mengkorupsi dana bantuan, yang swafoto berlatar lokasi terdampak demi eksistensi di sosial media, serta yang memanfaatkan rasa takut dengan menyebarluaskan hoaks.
Sering kali, oleh sebab perpolitikan kita dihiasi oleh perdebatan superfisialistik terkait kesalehan, disertai cara pandang serba hitam putih ala FTV Azab dan Zalim, banyak kemudian yang mengaitkan dan/atau menuduh pihak-pihak tertentu sebagai penyebab terjadinya bencana.
Mula-mula bencana didefinisikan dan diyakini sebagai wujud azab dari Allah, dan karena ia adalah azab, maka harus ada objek/sasaran tembak dari azab tersebut. Ketika Lombok didera gempa, tanpa kesadaran berempati kepada korban, muncul tuduhan bahwa gempa tersebut diakibatkan oleh perubahan kiblat politik Tuan Guru Bajang Zainal Majdi. Padahal tuduhan tersebut belum tentu benar dan tidak selalu dapat dikonfirmasi kepada Gusti Allah selaku Maha Berkehendak.
Singkat madah, bahkan ‘bencana’ pun dipolitisasi dan dikaitkan dengan sentimen religiusitas-politis yang dipaksakan sesuai dengan syahwat politiknya masing-masing. Korban-korban yang berjatuhan dalam tragedi yang memilukan itu tidak lagi dilihat sebagai manusia-utuh tetapi juga sebagai angka dalam statitik dan berikutnya sebagai petunjuk ihwal apakah 2019 harus ganti presiden ataukah tidak.
Padahal, adalah benar kata Sudjiwotedjo, boleh jadi sesungguhnya yang selamat adalah mereka yang syahid ‘akibat’ tsunami dan gempa, sedangkan justru kitalah yang sebetulnya merugi karena masih harus ‘gedebugan’ di muka Bumi. Termasuk di dalamnya, gedebugan menghadapi jebakan sikap mencari-cari kambing hitam seolah-olah azab Tuhan sebercanda itu. Lagipula, apa yang kita sebut ‘bencana’ ‘kan tidak selalu harus merupakan azab.
Jika kita melihat konstruk geografis Indonesia, lokasi kita memang adalah daerah yang rawan terhadap apa yang hari ini kita sebut bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Jika dilihat dari sudut pandang ini, fenomena-fenomena alam tersebut sejatinya adalah cara alam menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri sebagian bagian alamiahnya untuk mencapai keseimbangan kembali dan senantiasa, atau juga menyesuaikan diri sebagai cara ‘menyembuhkan diri’ akibat kerusakan-kerusakan yang kita lakukan. Jika yang kedua yang terjadi, maka ‘bencana’ yang terjadi layak disebut azab.
Alasan kedua, bahwa azab tidak selalu berupa sesuatu yang sifatnya ‘destruktif’ dan ‘menakutkan’ seperti si ‘bencana’ tadi. Dalam Islam ada istilah istidraj yaitu kesenangan yang Allah sempalkan ke mulut, hati, perut, dan jiwa seseorang sebagai bentuk ‘hukuman’ bukan sebagai ‘kasih sayang’. Semata-mata agar hati orang tersebut semakin tertutup dan dia semakin jauh dari-Nya.
Dalam hal ini, azab dapat berupa kesenangan, kekayaan, kesuksesan, atau umur panjang dengan kesia-siaan.
Maka bisa jadi korban ‘bencana’ sebetulnya bukanlah objek azab—mereka justru terdampak. Martir yang Allah panggil lebih cepat agar tidak terjebak pada fitnah yang makin masif. Hanya, kadang kita kadung merasa lebih baik daripada orang lain; atau kadung dibutakan ambisi pribadi kita; dilenakan oleh kesenangan-kesenangan duniawi yang kita rasakan; sehingga secara tidak tahu diri kita merasa Allah Beserta Kita dan azab-azab ini pastilah karena orang lain, pastilah karena Jokowi, atau Prabowo, atau para kampret, atau para cebong, artis yang kerjaannya hedonis, para pelaku penyimpangan seksual, dan seterusnya.
Semua kemungkinan itu ada, bahwa ‘bencana’ ini boleh jadi memang tidak hanya bagian dari cara alam menyeimbangkan diri kembali tetapi juga cara Allah menegur kita—baik itu karena sangat sayang atau sangat marah. Tetapi sepertinya Allah tidak menghendaki ‘teguran-teguran’-Nya ini dijadikan olok-olokan, dijadikan alasan untuk setiap dari kita semakin mempertontonkan syahwat kebencian dan rasa-diri-paling-benar. Allah tentu ingin kita melakukan perbaikan dan perbaikan sesungguhnya mesti dimulai dengan keberanian otokritik dan kemawas-dirian untuk tidak menganggap orang lain lebih jauh dan lebih rendah derajatnya di sisi Allah.