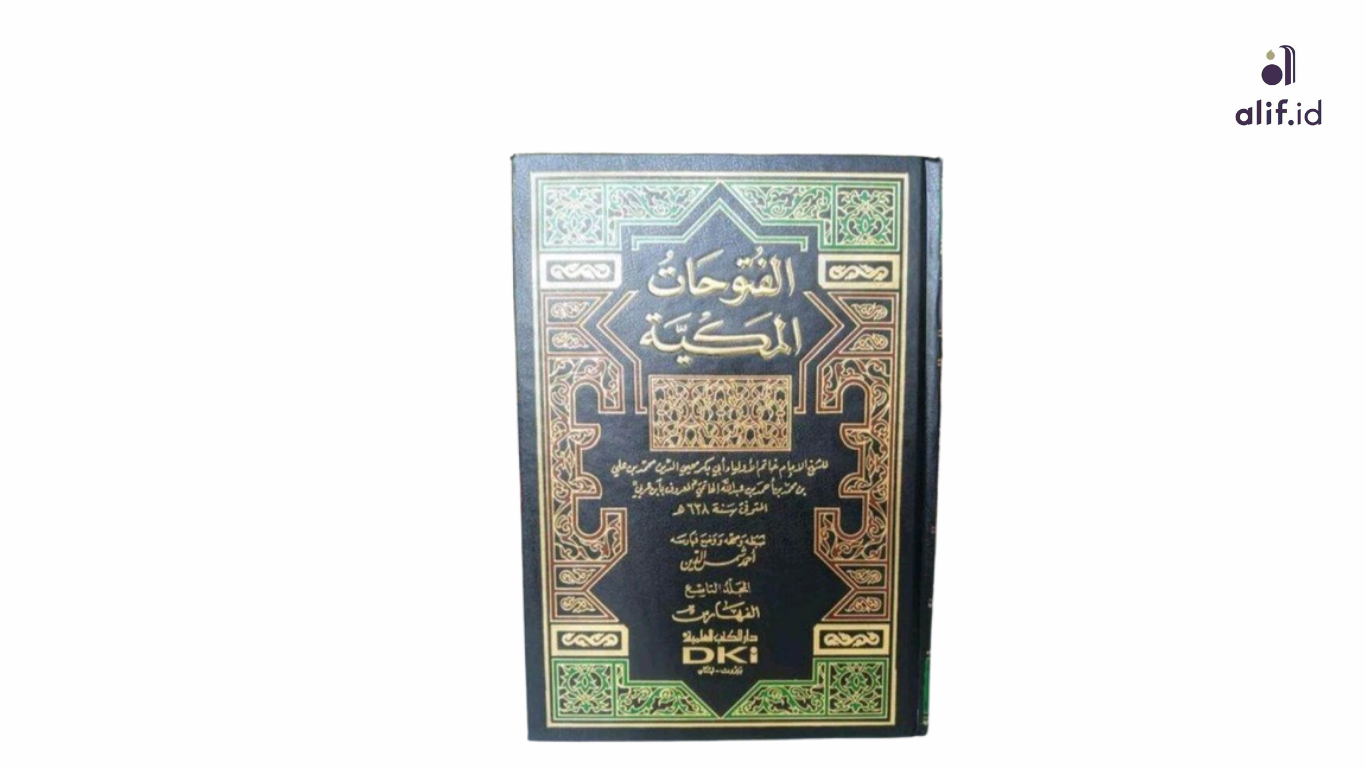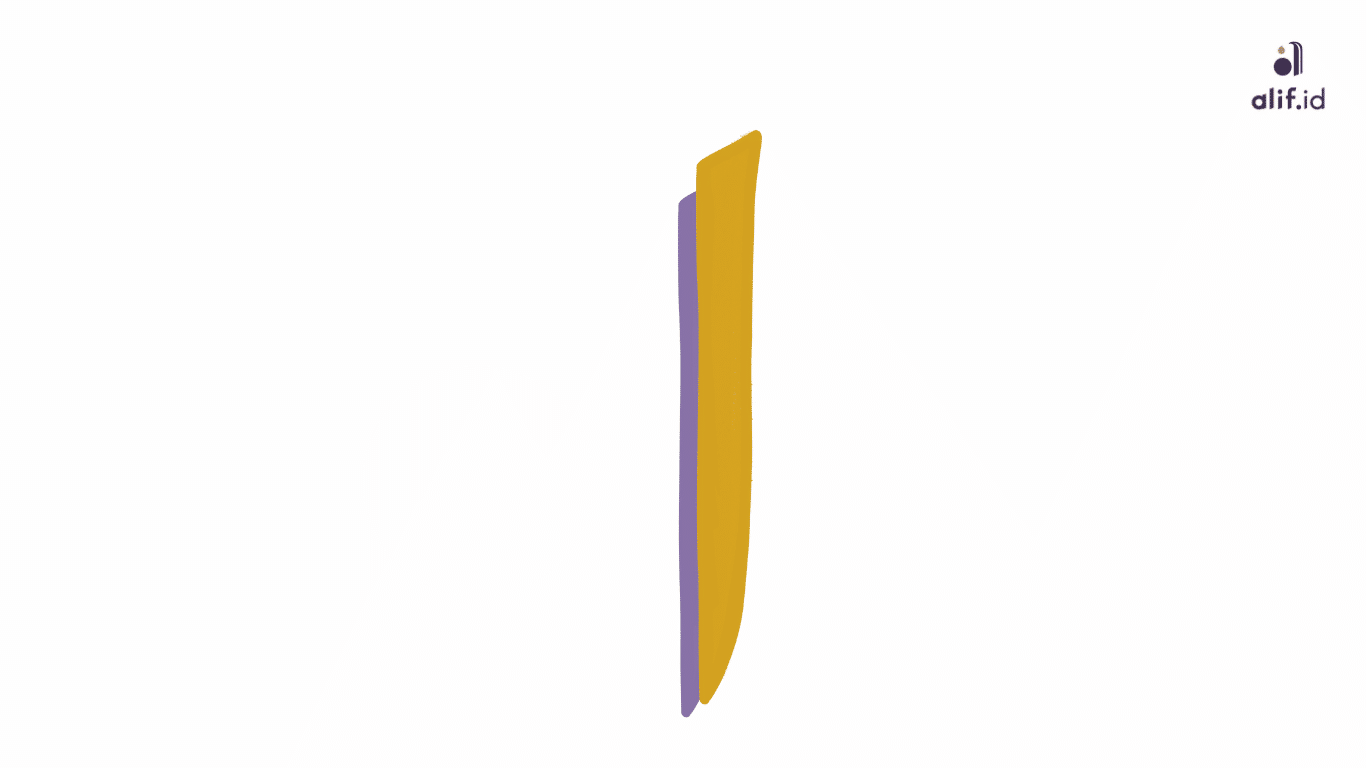Orang cenderung memilah waktu secara biner: siang dan malam. Pada berbagai ekspresi sastra-teosofis, dua waktu itu digunakan untuk melambangkan keramaian dan kesunyian, kebahagiaan dan kegalauan, pencerahan dan kegelapan. Sampai detik ini tak seorang pun teolog atau teosof yang saya jumpai menyajikan dan meramu waktu lain dalam kaitannya dengan sesuatu yang metafisis.
Saya berkunjung ke beberapa wilayah di pesisir utara dan singgah beberapa waktu di Karimunjawa, melacak sejarah yang tertuang dalam makam-makam yang terdapat di sana dan menjumput beberapa parak (sunrise) dan surup (sunset): dua waktu khusus yang lazimnya didamba para pelancong ketika menikmati suasana pantai, dua waktu khusus ketika gelap dan terang berbaur menjadi remang.
Saya teringat Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi al-Syafi’i, setelah mentok dengan berbagai pendekatannya selama ini—dari fikih, kalam, hingga filsafat. Kakak dari seorang sufi tak ternama ini, Ahmad al-Ghazali, memutuskan untuk meninggalkan segala status yang pernah disandangnya.
Ia melakukan uzlah selama 10 tahun hanya untuk menuntaskan krisis spiritual yang pernah menderanya. Tak ada catatan yang pasti perihal awal bagaimana pengarang kitab Ihya’ ini terjun ke telaga tasawuf. Ada versi yang mengatakan bahwa Sahal bin Abdullah al-Tustari yang pertama kali memengaruhinya. Tapi yang pasti, adiknya, Ahmad, telah terlebih dahulu menjadi seorang sufi.
Dalam kesendirian dan ketelanjangan itu, barangkali orang bertanya, bagaimana seorang ulama sufi yang wafat pada tahun 1111 M tersebut dapat hidup tanpa satu pun status yang disandang—entah ulama, suami, bapak, atau pun saudara?
Saya mengunjungi pulau Karimunjawa di Jepara, dan seperti biasa, singgah di beberapa makam yang dikenal oleh warga setempat sebagai pembabar agama Islam di sana. Adalah Sunan Nyamplungan yang saya tuju pertama kali, seorang yang konon berasal dari pulau Jawa yang kemudian diasingkan oleh bapaknya ke Karimunjawa. Ada versi yang mengatakan bahwa ia merupakan anak dari Sunan Muria.

Dapat dibayangkan bagaimana dahulu suasana Karimunjawa, di mana nama pulau ini berasal dari istilah kremun-kremun, objek yang tampak terpencil dari titik pandang gunung Muria. Keterpencilan, sebuah istilah yang senafas dengan keterjatuhan, seperti kisah yang terpampang dalam kitab-kitab suci, Adam dan Hawa, yang terbuang dari sorga: kosong dan sunyi.
Adalah seorang Amir Hasan yang karena kebengalannya akhirnya dibuang, diasingkan ke Karimunjawa, menempa diri, berkawan sunyi. Tapi tak ada secuil sesal pun di benak Amir Hasan atas segala hukuman pengasingan yang diterima dari Bapaknya. Ia memutuskan untuk tak kembali ke pulau Jawa. Satu versi mengatakan, Amir Hasan bertemu dengan seorang ulama yang lebih dahulu mendiami Karimunjawa: Sayyid Abdullah.
Dari berbagai komunitas yang berada di Karimunjawa—Jawa, Bugis, Madura, dst— tak jelas benar ajaran khusus apa yang dibabarkan oleh Sayyid Abdullah maupun Amir Hasan, yang kemudian bergelar Sunan Nyamplungan. Yang jelas, bagi warga sekitar, Sunan Nyamplungan dikenal dengan kemampuannya dalam menyulam berbagai perbedaan dan, saya kira, merajut keheningan.

Meskipun di masa kini telah banyak penganut tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah di daerah Nyamplungan, tapi dari kabar kawan-kawan Bugis, Sunan Nyamplungan sendiri memiliki hubungan dengan Syekh Yusuf al-Makasari. Dengan kata lain, ia juga merupakan pewaris tarekat Khalwatiyah.
Secara geografis, tarekat yang lebih dikenal dengan laku “beramai-dalam-kesunyiannya” itu memang cocok dengan kondisi pulau Karimunjawa: beberapa pantai yang elok dan keheningan yang tiada tara. Di sebuah pelosok, nun jauh dari pemukiman penduduk, di rerimbun hutan dan kerumunan bakau, saya pun menemukan sebuah kompleks makam yang dibangun secara bersahaja: beberapa onggok nisan yang beratap asbes.
Orang sekitar menyebutnya dengan gelar datuk, meski pada tiang penyangga atap tergurat sepenggal nama: Syekh Abdul Manan. Ada kesan kuat bahwa yang terbaring di ujung Barat pulau itu menghindari kemegahan: khumul.
Suasana pantai-pantai di Karimunjawa sebenarnya tak semata elok untuk dipandang, tapi ada kesan tertentu yang juga saya tangkap, semisal sesobek senja yang mengingatkan saya pada bait-bait Syair Perahu sang sufi Qadiriyah nusantara: Hamzah Fansuri.

Wahai muda kenali dirimu
ialah perahu tamsil tubuhmu
tiadalah berapa lama hidupmu
ke akhirat jua kekal diammu
Seonggok perahu dan sesobek langit yang beringsut jingga, sebuah perpaduan yang menarik yang mengisahkan suluk atau perjalanan ruhani. Lazimnya, perahu digunakan sebagai perlambang rumah tangga, tapi Fansuri memakainya secara lain. Bagi sufi yang menunjukkan kecenderungan filsafati dalam ekspresi sastrawinya ini—meski ia seorang penganut tarekat Qadiriyah—perahu adalah perlambang sebuah suluk.
Tapi saya kira senja di balik perahu itu dapat memperlihatkan konsep akhir suluk, yang dapat saya artikan sebagai “kematian,” sebagai konsekuensi logis ekspresi sufistik seorang Hamzah Fansuri. Pada senja itu saya merasakan segurat titik akhir yang bernuansa sendu tanpa guyu.
Dalam khazanah budaya Jawa, senja diistilahkan sebagai surup yang berasal dari kata dasar (woting tembung) urup: nyala. Dari urup–surup inilah kemudian istilah sumurup yang bermakna weruh, tahu atau “melihat” diderivasikan. Tapi ketika Hamzah Fansuri yang notabene adalah seorang penganut tarekat qadiriyah yang sudah tentu mendawamkan segurat niat ilahii Anta maqshudi wa ridhaka mathlubi a’tini mahabbataka wa ma’rifataka, kemudian ketika senja itu hanya menyisakan gelap, apa yang sesungguhnya terlihat?
Fansuri tak mengupas perkara ini secara gamblang. Barangkali, urup-surup-sumurup lebih tepat dikaitkan dengan weruh yang berkaitan pula dengan kawruh. Pada konsep kawruh-weruh—yang memiliki nuansa berbeda dengan mripat (baca: mata) yang merupakan kerata basa dari ma’rifat—saya kira orang berurusan dengan pemahaman akan letak segala sesuatu (tepung-dunung). Maka, pada akhirnya, siapa yang terpikat pada senja akan membuat nyala sendiri untuk menyertainya mengarungi gelap.

Suasana senja sungguh berbeda dengan suasana fajar di mana dalam khazanah sastra Jawa disebut pula dengan istilah parak. Dari istilah parak yang berarti pula “dekat” dan marak (kata kerja aktif) yang berarti “mendekat” inilah kemudian fajar mendapatkan pemaknaan yang lain. Parak itu disebut pula dengan istilah manyura, yang secara harfiah bermakna burung merak.
Istilah manyura ini jamak digunakan dalam pertunjukan wayang untuk menandai suatu babak yang secara teknis beralihnya tangga nada pada musik iringannya dan beberapa solah (sikap dan gerak) para wayangnya. Dan secara filosofis untuk menandai akhir lakon di mana suasana yang dikandungnya penuh dengan suasana kematian yang anehnya, secara sastrawi, justru dilukiskan dengan elok.
Meh rahina semu bang Hyang Aruna
Kadi netrane ogha rapuh
Sabdaning kukila ring kanigara
Saketer kekidunganing kung
Lir wuwusing winipanca
Papethaking ayam wana ring pagagan
Merak anguwuh
Bremara ngrabasa kusuma ring parahasyan arum
—Suluk Manyura Jangkep
“Nyaris terang semburat jingga sang bagaskara
Seperti bola mata yang sakit
Burung-burung berkidung di pepohonan
Memuji dengan merdunya
Seolah lenguhan sangkakala
Kokok ayam bersahutan di hutan
Merak merayu”
Kumbang mengambang mencumbu harumnya kembang
Pada fajar orang seperti tak lagi butuh kawruh (peta) atau nyala (urup) untuk mengarungi gelap. Segala sesuatunya telah nglegena, telanjang apa adanya: birunya langit, semu hijaunya lautan, putihnya pasir pantai, dan kesunyian batang kayu ataupun batu karang. Dengan lanskap seperti itu orang tak akan menemukan apapun kecuali sesesap keheningan.

Tapi berbicara tentang keheningan sebenarnya adalah berbicara tentang ketakheningan. Pada titik inilah orang secara sederhana mengalami apa yang pernah dialami oleh seorang Martin Heidegger di mana dalam kancah ilmu-ilmu humaniora pada gilirannya memunculkan apa yang disebut sebagai peristiwa “the linguistic turn” (Kisah Semar dan Syaikh Subakir di Belukar Tidar, Heru Harjo Hutomo, alif.id).
Heidegger, karena the linguistic turn itu, butuh waktu 30 tahun berkawan sunyi untuk sekedar menerangkan apa yang secara personal pernah dialaminya (On Time and Being, 1972). Sementara al-Ghazali butuh waktu 10 tahun untuk mengatasi krisis yang pernah menderanya. Barangkali, perihal cara mengekspresikan hal-hal yang sebenarnya tak dapat diekspresikan, Kalijaga—lewat Kidung Dharmawedha—memiliki kiat tersendiri.
Ana pandhita akarya wangsit
Mindha kombang angajap ing tawang
Susuh angin ngendi nggone
Lawan galihing kangkung
Wekasane langit jaladri
Isining wuluh wung-wang lan gigiring punglu
Tapaking alayang
Manuk miber uluke ngungkuli langit
Kusuma anjrahing tawang
Pada bait-bait kidung Kalijaga itu orang akan menemukan kata-kata yang sekilas tak nyambung: sarang angin (susuh angin), jantungnya kangkung (galihing kangkung), batasnya langit dan lautan, jejak burung yang terbang (tapaking alayang/ manuk miber uluke ngungkuli langit), dan kembang yang merekah di angkasa.

Dalam ekspresi sastra mana pun tak ada berbagai perangkat puisi—semisal metafora—yang sefantastis kidung tersebut. Tapi rupanya Kalijaga tak memaksudkan karyanya itu hanya didekati lewat kajian sastra belaka.
Karena filsafat dan ilmu-ilmu lainnya tak luput dari kerangka tata bahasa tertentu, maka pada titik ini orang tak lagi membicarakan pembicaraan, tapi sudah menginjak pada sesuatu yang eksperimental. Itulah yang dialami oleh al-Ghazali dalam kurun 10 tahunnya ataupun Heidegger dalam kurun 30 tahunnya: menyesap dering keheningan (swaraning asepi). (SI)