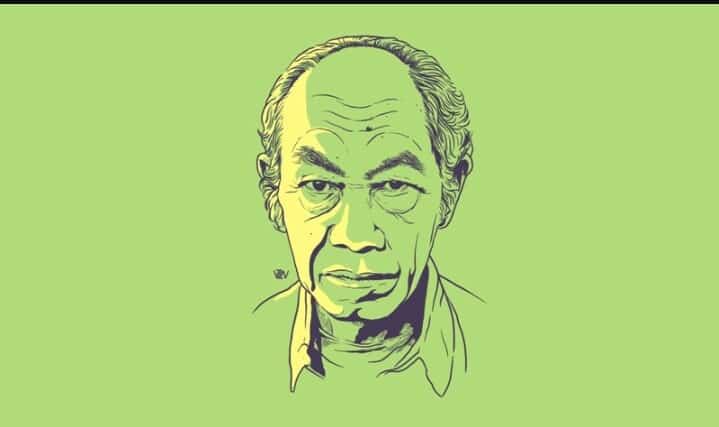
Gadis Pantai (GP) merupakan salah satu novel yang tidak selesai, yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer. Sebelumnya, kisah ini pernah dimuat di surat kabar Bintang Timur (antara 1962-1965) sebagai cerita bersambung.
Dua buku lanjutan GP, menurut pengakuan Pramoedya, diberangus oleh Jaksa Agung era rezim Suharto pada 1988, gara-gara vandalisme dan kepicikan cara berpikir mereka: buku ini didakwa menyebarkan ideologi terlarang, yakni Marxisme-Leninisme.
Novel GP mengagak-agihkan kehidupan seorang gadis kampung nelayan berumur empat belas tahun di pantai utara Jawa yang terpilih oleh Bendoro Rembang sebagai istri sementaranya.
Tokoh utama, yaitu GP digambarkan sebagai teman seranjang, bukan teman hidup Bendoro, yang menunggu pernikahan dengan perempuan priayi yang sederajat dengannya.
Buku ini mengisahkan perikehidupan seorang gadis belia yang dilahirkan di sebuah kampung nelayan di Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, yang merupakan kampung halaman ibunya Pramoedya. GP adalah seorang gadis yang manis. Dia cukup cantik untuk memikat hati seorang pembesar santri setempat yang bekerja untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Ia diambil sebagai istri sementara oleh pembesar itu dan menjadi perempuan yang melayani kebutuhan seks laki-laki, sampai kemudian dia memutuskan untuk menikah dengan perempuan yang setaraf dengannya.
GP tidur dengan Bendoro, dan membantu mengurus kompleks keresidenan, kandang-kandang ternak, dan bahkan sebuah masjid. Perkawinan itu memberikan semacam wibawa kepadanya di kampung halamannya, karena ia dipandang telah berhasil menaikkan derajatnya. Bendoro, seorang Jawa yang telah memilikinya, tega membuangnya, setelah Gadis Pantai melahirkan seorang bayi perempuan (GP, hlm. 6).
Kisah ini hasil imajinasi Pramoedya sendiri tentang neneknya dari pihak ibu, yaitu mbok Satimah, yang mandiri dan dicintai cucunya.
Meskipun fiksi atau imajinasi, kisah dan tokoh-tokoh Pramoedya selalu berkelindan atau diangkat dari kenyataan dan pengalaman sejarah sosial-budaya manusia Indonesia.
A. Teeuw dalam Citra Manusia Indonesia dalam Karya Sastra Pramoedya Ananta Toer (1997) menjelaskan, bahwa berdasarkan tema pokoknya, buku itu dapat disebut novel sosial-kritis ihwal nasib gadis rakyat jelata yang dihadiahi untung, baik menjadi teman seranjang seorang priayi dan melahirkan anak, serta tentang kesewenang-wenangan yang terakhir dan ketakberdayaan yang pertama. Namun, kritik tentang pembagian kekuasaan yang tak merata, tentang kemiskinan dan kekayaan, tentang tirani dan korbannya itu, sama sekali tidak disajikan dalam gambar realistis perihal kekayaan sosial (hlm. 218).
Mengingat gejala kesusastraan merupakan gejala sosial-budaya, dapat dikatakan bahwa gejala itu sebenarnya merupakan kesadaran terhadap realitasnya dengan mencerminkan realitas masyarakat tertentu. Seorang pengarang sebenarnya berminat juga kepada segala sesuatu gejala masyarakat, dan dia mengumpulkannya dalam karya-karya sastranya sendiri.
Dalam konteks Pramoedya, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mengkaji sang penulis sesungguhnya adalah bermaksud mengikuti tanggapan dirinya terhadap gejala masyarakat yang terpancar dalam karyanya.
Pramoedya merupakan seorang Jawa yang berasal dari Blora, dan ibu yang sangat disayanginya itu pun berasal dari Rembang, pantai utara Jawa Tengah, yang menjadi latar belakang novel GP. Pramoedya dengan sengaja mendedahkan aspek negatif budaya Jawa dalam beberapa hasil karya sastranya.
Maksud Pramoedya adalah bukan sekadar untuk menunjukkan budaya Jawa yang tidak masuk akal, melainkan bertujuan membangun kesadaran dan mawas diri atas budaya bangsanya, supaya tidak mengulangi sejarah bangsa yang terus kalah. Alih-alih kekalahan seperti itu dapat dikatakan bersumber dari kerakusan pihak penjajah yang pernah menguasai Indonesia, seperti Belanda dan Jepang, menurut Pramoedya, sebab bangsa Indonesia terus-menerus mengalami kekalahan seperti itu karena tidak lain dari kelemahan bangsa itu sendiri.
Kekuasaan dan ketakberdayaan
Dalam novel GP, tokoh Bendoro mewakili golongan priayi Jawa. Sebagaimana disebutkan di atas, Bendoro mengambil Gadis Pantai untuk dijadikan teman seranjangnya saja. Sesudah Gadis Pantai melahirkan anaknya, ia langsung diusir oleh Bendoro.
Pada bagian awal, Pramoedya memberi pertanda bahwa sang gadis tidak mempunyai harapan terhadap seorang priayi sebagai suaminya yang belum pernah bertemu. Kesangsian GP terhadap suaminya tergambar seperti berikut:
Dia? Siapa dia? Gadis Pantai menutup mata. Ia tak bisa bayangkan. Baik manakah dia dari Tumpon, abangnya yang hilang di laut waktu badai menerjang perahu? Baik manakah dia dari Kantang, abangnya yang seorang lagi, yang waktu angkat jala yang tersangkut pada batu karang, tidak timbul lagi untuk selamanya, dan hanya warna merah yang timbul ke atas? Dan itu adalah yang dihisap laut setelah ikat cucut membelah perutnya. Maukah orang itu memberikan dirinya buat hidup seluruh keluarga? Seperti Kantang (GP, hlm. 4).
GP dijelmakan sebagai seorang perempuan yang berpegang teguh kepada kepercayaannya. Meskipun ia terpaksa menikah dengan Bendoro, GP tetap mencurahkan sikap yang tidak feodal lagi.
Tingkah lakunya dipaparkan seperti: “Dan ia tak juga dapat mengerti, benarkah ia menjadi jauh lebih bersih karena basuhan air wangi?” (hlm. 23). “Jangan mempergunakan sahaya itu mBok.” (hlm. 32). “Ia merasai adanya jarak yang begitu jauh, begitu dalam antara dirinya dengan wanita yang sebaik itu yang hampir-hampir tak penah tidur menjaga dan mengurusnya, selalu siap lakukan keinginannya, selalu siap terangkan segala yang ia tak faham, bisa mendongeng begitu memikat tentang Jaka Tarub, dan bisa mengusap bahunya begitu sayang bila siap hendak menangis. Hatinya memekik: mengapa aku tak boleh berkawan dengannya? Mengapa ia mesti jadi sahaya bagiku? Siapakah aku? Apa kesalahan dia sampai harus jadi sahayuku?” (hlm. 32). “Apakah Bendoro lebih berkuasa daripada laut, sampai bapak melarikan diri? Dua abangnya telah tewas ditelan laut, mereka tidak pernah lari. Bapak pun tak pernah lari. Mengapa takut pada Bendoro? Mengapa? Bapak lebih kukuh dan kuat dari Bendoro. Bendoro bertubuh tinggi langsing, berwajah pucat, kulitnya terlalu halus, ototnya tak berkembang. Mengapa semua orang takut? Juga diriku?” (hlm. 34).
GP dijual kepada Bendoro. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian golongan priayi meremeh-temehkan nasib seorang perempuan yang berasal dari golongan wong cilik. GP harus bersaing dengan Mardinah yang merasa jauh di atas Gadis Pantai yang selalu merasa dihina dan terancam olehnya.
Sebenarnya Mardinah dititipkan oleh istri bupati Demak yang sangat jengkel, sebab Bendoro Rembang masih tetap belum kawin dengan yang sederajat; perempuan itu memainkan jarumnya lewat Mardinah untuk mendongkel Gadis Pantai. Sikap golongan priayi dicitrakan Pramoedya:
Mengapa tidak? Di kampung pria dan wanita sama-sama bertemu. Nampak bujang itu merasa kasihan kepada Gadis Pantai. Pengalaman selama ini membuat ia banyak tahu tentang perbedaan antara kehidupan orang kebanyakan dan kaum Bendoro di daerah Pantai. Seorang Bendoro dengan istri orang kebanyakan tidaklah dianggap sudah beristri, sekalipun telah beranak selusin. Perkawinan demikian hanyalah satu latihan buat perkawinan sesungguhnya: dengan wanita dari karat kebangsawanan yang setingkat. Perkawinan dengan orang kebanyakan tidak mungkin bisa menerima tamu dengan istri dari karat kebangsawanan yang tinggi, karena dengan istri asal orang kebanyakan–itu penghinaan bila menerimanya. (GP, hlm. 62-3).
Seorang priayi masih dianggap seorang pemuda (jaka) selama dia belum mempunyai istri utama (padmi) yang dinikahi dengan segala upacara adat, perkawinan, walaupun mungkin dia sudah memiliki beberapa orang selir. Seorang padmi mendapat tempat di bangunan utama dari dalem, dan turut dalam semua kehidupan sosial suaminya, terutama bila ia orang yang berpendidikan. Jadi, Gadis Pantai juga dianggap seorang selir yang tidak mendapat kedudukan sebagai istri utama.
Menurut Koentjoronigrat, suatu perkawinan dengan seorang selir jarang dirayakan dengan suatu pesta yang meriah. Seorang selir mendapat bagian yang kecil dari dalem untuk tempat tinggalnya. Ia juga memasak sendiri bagi dirinya sendiri dan anaknya, dibantu oleh seorang atau dua orang pembantunya. Suaminya akan memanggilnya ke rumahnya di bangunan utama dalem, apabila ia diperlukan (Koentjaraningrat, 1984 hlm. 264-5). dibayangkan Pramoedya sebagai seorang perempuan Jawa yang tidak mudah dikalahkan oleh nasib yang buruk itu. Walaupun GP seorang anak yang setia pada orang tuanya, ia tetap berpegang teguh kepada prinsip kehidupannya.
Pada suatu hari ia pulang ke kampung halamannya dengan hadiah yang diberikan Bendoro. Sebelum berangkat ke pantai Rembang, GP mengatakan, perkawinannya dengan Bendoro sudah tidak berarti lagi. Hal ihwal itu membuktikan bahwa perkawinan seperti itu tidak membawa kebahagiaan kepada Gadis Pantai, seorang korban yang dijual oleh ayahnya sendiri, meskipun ayahnya merasa bangga karena anaknya sudah menjadi istri seorang pembesar dan kaya.
GP menunjukkan sikap yang tegas terhadap ketidakadilan budaya yang sampai menyerahkan anak perempuannya kepada pembesar daerah, seperti berikut:
Setelah lebih dari dua tahun tinggal di gedung, tahulah aku, kami cuma punya kemiskinan, kehinaan dan ketakutan terutama pada orang kota. Di kampung, kami tahu benar tepung udang dibayar sebenggol, padahal mestinya empat sen. Itu tidak layak, tidak adil. Tapi lihatlah diriku ini.
Bukan lagi tepung udang. Manusia! Aku tak bisa dipungut begitu saja dari kampung, disimpan di dalam gudang. Kau, kau orang kota, apa yang kau tahu tentang orang kampung?” (GP, hlm. 129-30).
Semacam pemberontakan GP dilanjutkan seperti: “Ah, bapak aku cuma ingin diperlakukan seperti dulu. Pukullah aku, kalau aku bersalah. Tapi jangan tebarkan hatiku semacam ini. Apa tak cukup penanggunganku di kota? Apa kurang banyak yang kuberikan buat penuhi keinginan orang tua jadi bini priayi? Mengapa sesudah semur ini bapak sendiri bersikap begitu? Dan emak hampir-hampir tak mau bicara padaku? Apa dosaku?” (hlm. 150).
Pramoedya memerikan Bendoro sebagai seorang yang setia pada agamanya. Sebagaimana yang dikemukakan Clifford Geertz, masyarakat Jawa dapat dibagi dua golongan dari segi agama, yaitu santri dan abangan. Kalangan abangan benar-benar tidak acuh terhadap doktrin, terpesona oleh detail keupacaraan, sementara di kalangan santri, perhatian terhadap doktrin hampir seluruhnya mengalahkan aspek ritual Islam yang telah menipis. Selain itu, yang menjadi perhatian kalangan santri adalah doktrin Islam, utamanya penafsiran moral dan sosialnya (lihat Geertz, 1989: 165-78).
Jika ditinjau dari aspek agama, dapat dikatakan bahwa Bendoro merupakan seorang santri. Aspek ini dapat dilihat dari beberapa adegan antara lain seperti berikut ini:
Beruntung kau menjadi istri orang alim, dua kali pernah naik haji, entah berapa kali khatam Qur’an. Perempuan nak, kalau sudah kawin jeleknya laki jeleknya kita, baiknya laki baiknya kita. Apa yang kurang baik pada dia? (GP, hlm. 3-4).
…
Tasbih?
Dari Bendoro, buat bapak saja. Hitam. Dari kayu keras, buatan Mekah.
Buat apa tasbih?
Bendoro menyampaikan salam. Kalau kampung belum punya surau, Bendoro bersedia membiayai pendiriannya.
Betapa mulianya (hlm. 148).
Makin lama makin renggang hubungan Gadis Pantai dengan Bendoro. Meskipun Gadis Pantai sudah hamil, Bendoro tetap tidak menganggap ia sebagai seorang istri. Pada suatu hari yang cerah, datang seorang Tionghoa diterima menghadap Bendoro di pendopo. Mereka berdoa duduk di atas kursi goyang. Saat itu, Gadis Pantai sedang membersihkan perabot di ruang tengah. Ketika orang Tionghoa itu mengatakan bahwa Gadis Pantai itu nyonyanya Bendoro, Bendoro dengan tegas menanggapi bahwa “aku belum punya nyonya” (hlm. 203). Tedas bahwa sampai saat itu juga Gadis Pantai tetap tidak dianggap sebagai istrinya, melainkan hanya sebagai teman seranjang.
GP sendiri merasakan bahwa ia seperti orang asing dalam lingkungan hidupnya. Suasana seperti ini membuat GP mengaku bahwa “dia bukan suamiku, dia Bendoroku, yang dipertuanku, rajaku. Aku bukan istrinya. Aku cuma budak sahaya yang hina-dina” (hlm. 201).
Arkian, GP diceraikan Bendoro tanpa diberi alasan yang sesuai. Sebelum meninggalkan rumah Bendoro, GP mempersembahkan anak kandungnya kepada Bendoro.
Bendoro menunjukkan sikap yang dingin kepada perempuan yang telah memberikan kesenangan seperti “Kau tinggalkan rumah ini! Bawa seluruh perhiasan dan pakaian. Semua yang telah kuberikan padamu. Bapakmu sudah kuberikan uang kerugian, cukup buat membeli dua perahu sekaligus dengan segala perlengkapannya. … Dan, tak boleh sekali-kali kau menginjakkan kaki di kota ini. Terkutuklah kau bila melanggarnya. … Anak itu? Apa guna kau pikirkan? Banyak orang bisa urus dia. Jangan pikirkan si bayi” (hlm. 211).
GP memberi kesan penolakan yang lantang terhadap ketidakpatutan sikap kalangan priayi yang mengabaikan tugas sebagai orang tua bagi bayi yang baru lahir. Sikap seperti ini bersumber dari kesadarannya sendiri.
Namun, Gadis Pantai tidak berdaya untuk membawa anaknya ke kampung halamannya. Ia diusir oleh Bendoro dengan tangan kosong. Ayah Gadis Pantai pun menghibur anaknya dengan mengatakan bahwa ‘Nasib kitalah memang, nak. Nasib kita. Seganas-ganas laut, dia lebih pemurah dari hati priayi” (hlm. 226).
Penderitaan kultural
Novel GP sudah mendapatkan perhatian besar dalam kait-kelindannya dengan wacana gender dan feminisme. Pramoedya meneroka besarnya peranan perempuan atas citra-citra perempuan, khususnya perempuan Jawa, dalam berhadapan dengan sistem nilai kalangan priayi yang feodal. Sejak awal, Pramoedya beranggapan bahwa perempuan telah menanggung beban yang paling berat atas sistem nilai tersebut. Gadis Pantai membenum sikap pasrah kepada takdir atau nasibnya, tinimbang berjuang atau memberontak terhadap ketidakadilan budaya priayi yang feodal.
Bagaimanapun Pramoedya tidak gagal untuk menunjukkan budaya priayi yang negatif dalam novel ini. Pramoedya sangat peka terhadap kekalahan bangsanya yang bersumber dari kelemahan warisan budaya bangsa sendiri.
Dia berpendapat bahwa melepaskan beban sejarah yang tidak bermanfaat adalah salah satu jalan untuk memajukan bangsa yang pernah mempunyai sejarah yang gemilang, karena warisan budaya yang membebani itu membawa penderitaan kultural yang berkepanjangan (Koh Young 2011: 326).
Tokoh-tokoh dalam novel GP dilukiskan Pramoedya sebagai seorang pembesar Rembang yang merepresentasikan kalangan priayi feodal, seorang perempuan yang menanggung beban karena dijadikan istri sementara bagi seorang priayi. Maka, tidak dapat dinafikan bahwa segala usaha Pramoedya untuk memperlihatkan kesengsaraan perempuan ini bersumber dari kesadarannya tentang rasa “kemanusiaan”.
Dalam penggarapannya itu, dia lebih banyak berorientasi pada gugatan atas warisan budaya Jawa yang feodal dan pengorbanan perempuan untuk kepentingan kalangan priayi.


















