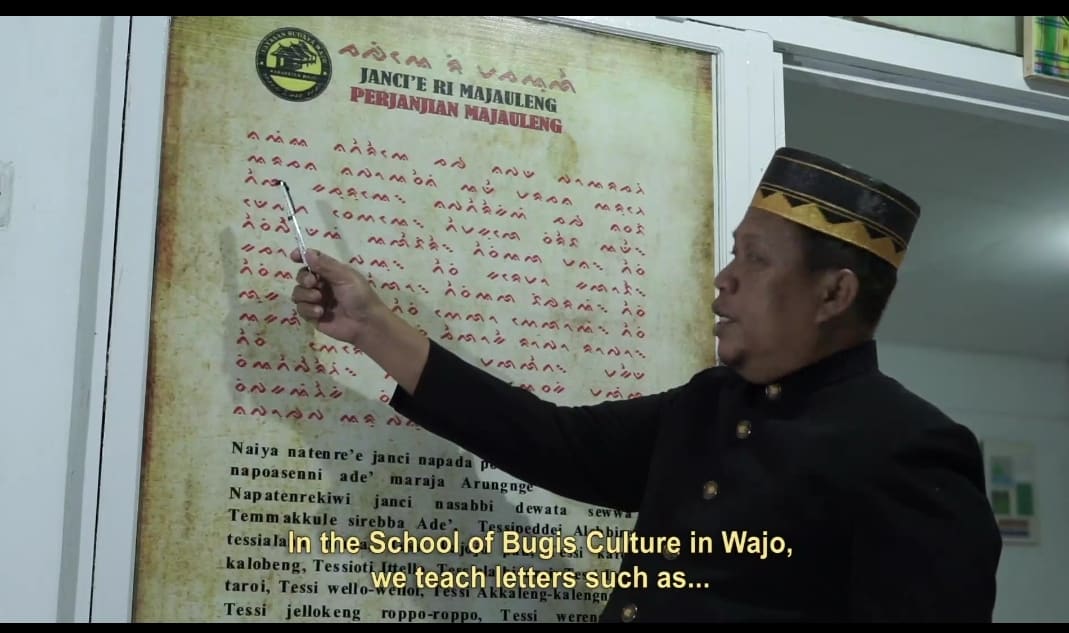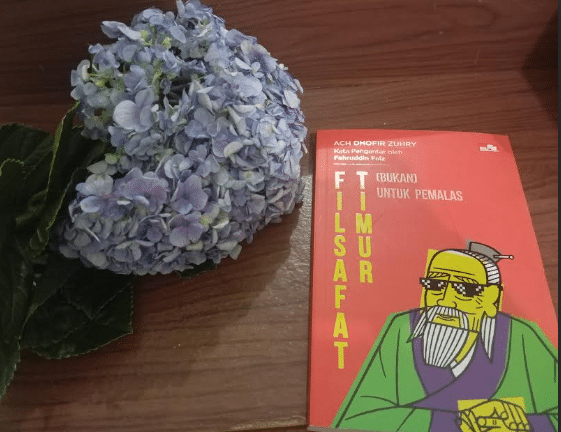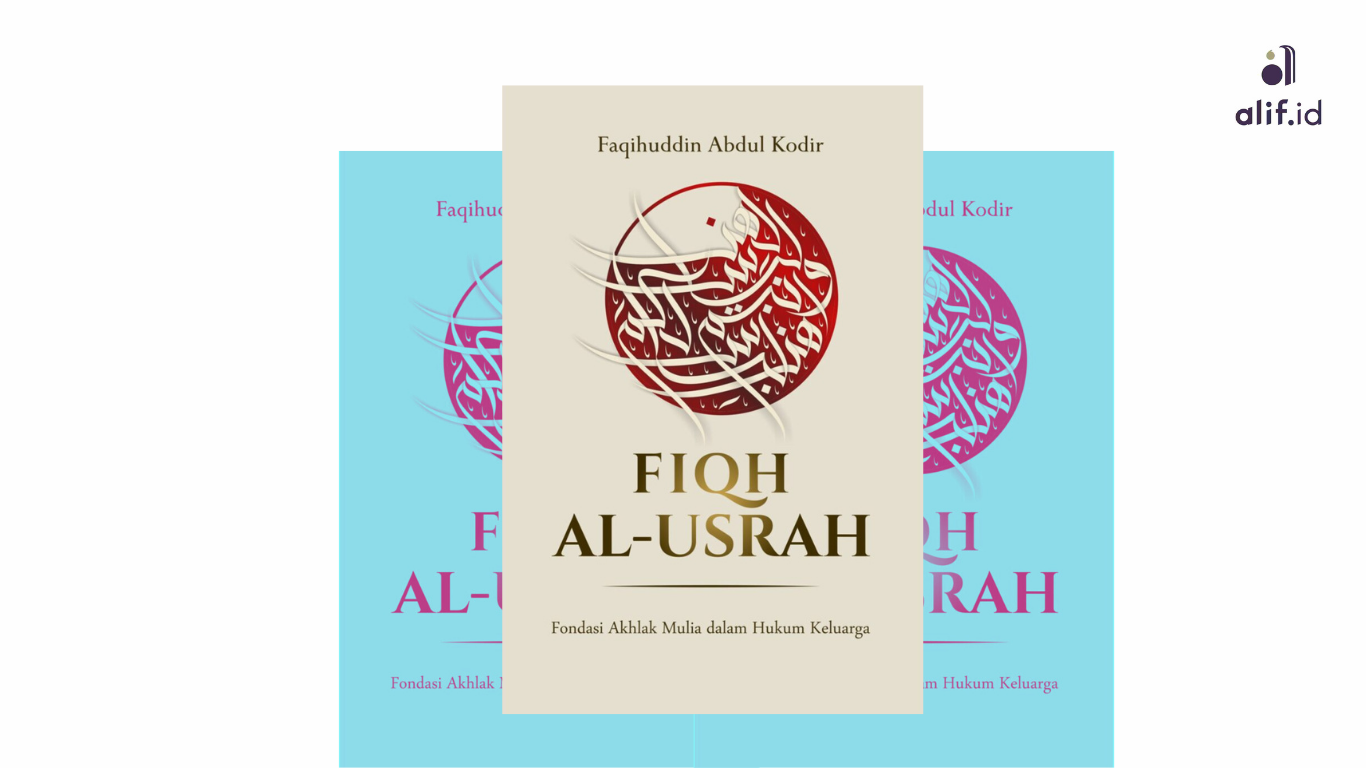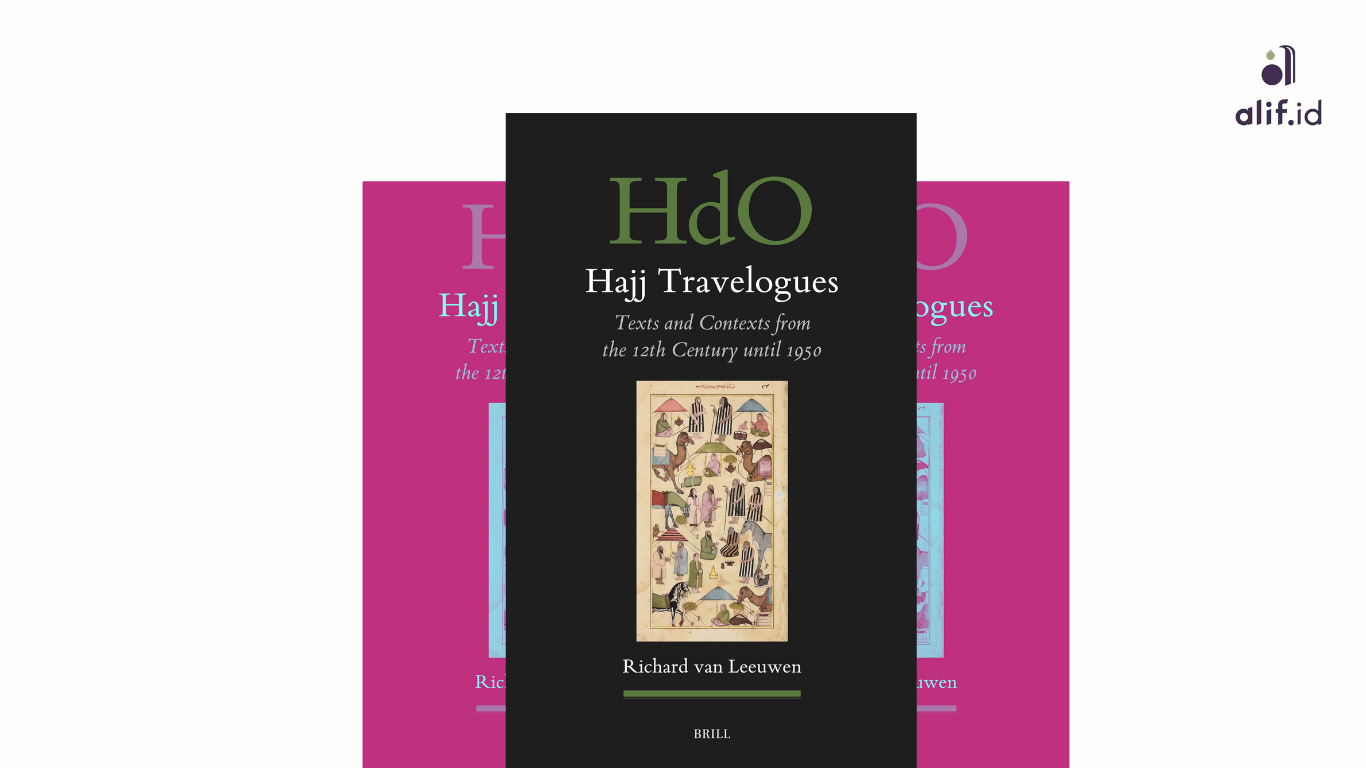Mencekoki buku bacaan kepada generasi Z ibarat menyuapi kedondong ke mulut orok baru brojol. Alot. Para misionaris literasi, baik individu maupun komunitas, tidak bisa secara frontal menggiring generasi yang lahir pada medio 90 tersebut mencintai buku. Pejuang literasi harus berkontestasi secara piawai dengan kompetitornya yang paling ulung: internet.
Kita sering menyinggung indeks membaca orang Indonesia. Dari seribu orang, hanya satu pembaca buku. Artinya, situasi literasi di Indonesia jauh di bawah “garis kemiskinan”.
Sebagai sampel, kita bisa memperhatikan dampaknya di media sosial. Kondisi mengerikan ini bisa kita telusuri dari begitu mudahnya orang menyebarkan berita hoaks, melihat sesuatu dari satu sudut pandang, asal bunyi, masih terjebak takhayul, dan sebagainya.
Berita hoaks mudah tersebar lantaran kita tidak memiliki budaya skeptis. Pengetahuan ditransmisikan dari seorang otoritas tanpa disangsikan kebenarannya. Tradisi takzim kita ternyata punya efek samping yang tidak menyenangkan.
Pada era di mana informasi bisa diakses dengan mudah dan cepat seperti saat ini, media malih rupa menjadi otoritas baru. Dalam hal ini, bias konfirmasi menjadi bahan bakar yang memicu orang menelan mentah-mentah informasi yang ditelusurinya di internet. Orang lebih menggemari informasi salah yang mendukung keyakinannya daripada data-data benar tetapi mematahkan apa yang disukainya.
Sementara itu, seseorang melihat sebuah peristiwa dari satu sudut pandang karena memiliki wawasan tidak luas. Sempitnya pengetahuan disebabkan sifat malas belajar, enggan berpikir terbuka, dan cuma bergaul dengan yang segolongan. Walhasil, kebenaran yang diyakininya dianggap sebagai realitas tunggal. Tidak ada kebenaran lain selain yang berputar-putar di areanya sendiri. Tidak punya empati adalah salah satu konsekuensi dari sempitnya wawasan. Orang cenderung membenci sesuatu yang tidak diketahuinya.
Dampak lain dari kurangnya pengetahuan adalah komentar asal bunyi. Di era media sosial seperti saat ini, budaya komentar kian meningkat. Orang kerap mengomentari sesuatu yang tidak diketahuinya.
Persoalannya, komentar yang dilontarkan seringkali salah. Pendapat keliru terjadi karena kurangnya informasi dan data tentang objek yang dikomentari. Komentar juga acapkali menjadi penghakiman dan usul yang dangkal atas persoalan pelik yang tidak cukup dipecahkan sehari dua hari bahkan oleh para ahli sekalipun.
Budaya komentar inilah yang membuat banyak orang awam mendadak jadi pakar. Jika yang berkomentar adalah figur publik, informasi keliru itu akan diikuti banyak orang.
Di Indonesia, tidak jarang pula warganet masih terjebak takhayul. Berita tentang fenomena natural sering ditanggapi dengan pola pikir mitis. Pisau Occam—juga kerap disebut “prinsip hemat”—merupakan metode mencari kebenaran dengan memberi penjelasan sederhana terlebih dahulu atas sebuah fenomena sebelum melangkah ke eksplanasi yang lebih rumit.
Jika pada suatu malam yang gelap Anda melihat kelebat warna putih melayang-layang, jangan terburu-buru berpikir bahwa apa yang Anda temui adalah hantu. Cari penjelasan sederhana terlebih dahulu. Misal, bisa jadi benda putih melayang-layang yang Anda lihat adalah jemuran yang diterpa angin.
Teknologi, sebagai produk sains, bukan benda asing bagi orang Indonesia. Namun, mengonsumsi teknologi tidak lantas membuat orang lepas dari takhayul. Cara berpikir ilmiahlah yang membebaskan orang dari takhayul.
Masalahnya, di Indonesia, sains tidak menjadi budaya. Literasi sains tidak ditanamkan kepada anak sejak dini. Pelajaran IPA di sekolah kerap menjadi pengetahuan yang menakutkan, jelimet, ditampilkan sebagai tumpukan rumus-rumus membosankan, dan guru gagal memberi tahu fungsinya.
Semua persoalan di atas terjadi karena orang tidak bisa berpikir kritis. Kompetensi tersebut hanya dimiliki orang yang terlatih berpikir. Pikiran tidak terlatih karena tidak terbiasa mengolah informasi yang terstruktur dan komprehensif. Salah satu kebiasaan yang membuat pikiran kita terlatih adalah dengan banyak membaca buku. Mengapa buku?
Karena buku adalah bahan bacaan yang menyajikan informasi yang relatif lengkap dan dalam—dibandingkan tulisan di internet, misalnya.
Kita kerap menganggap bahwa literasi berhubungan dengan budaya baca-tulis. Tetapi literasi tidak sesempit itu. Literasi juga berasosiasi dengan kompetensi mengolah informasi dan pengetahuan, tradisi diskusi, dan keterampilan dalam bidang tertentu.
Istilah literasi kerap diikuti oleh istilah-istilah lain, misalnya, literasi digital, literasi finansial, literasi gizi, literasi media, literasi teknologi, literasi visual, dan sebagainya. Literasi bukan tujuan akhir, melainkan cara mencapai hidup lebih baik dengan kecakapan yang dimiliki. Kecakapan itu diperoleh dengan menginternalisasikan pengetahuan yang baik ke dalam—paling tidak—gudang kognisi kita.
Sejauh ini, buku merupakan sumber terbaik dan adekuat untuk membuat orang menjadi lebih literat. Tetapi apakah program-program perbukuan pemerintah dan komunitas literasi mampu menyembuhkan bangsa ini dari buta bacaan? Apakah strateginya sudah tepat?
Di pundak generasi Z, nasib bangsa kita bertumpu. Para pejuang literasi mesti mati-matian berupaya agar generasi pascamilenial ini menjadi pribadi mencerahkan.
Persoalannya, generasi Z tumbuh di tengah kepungan budaya layar yang masif. Sejak belia, generasi Z telah hidup di peradaban internet. Membujuk generasi Z mencintai buku sama sukarnya—untuk tidak berkata mustahil—dengan memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum.
Buku merupakan tujuan ultim media literasi. Kita tidak bisa menjadikannya sebagai alat pertama. Jika ingin mewariskan budaya literasi kepada generasi Z seseorang harus memahami dunia mereka.
Belakangan ini, di Indonesia, kafe kian menjamur dan menjadi tempat nongkrong anak-anak muda. Di sanalah mereka banyak menghabiskan waktu bersosialisasi dengan sesamanya—selain sekolah. Kafe bisa menjadi media untuk mengakrabkan generasi Z dengan literasi (Saya membayangkan kafe menjadi pusat berkembangnya budaya berpikir dan berdiskusi sebagaimana yang terjadi pada zaman Sartre).
Tentu bukan dengan menyuguhkan buku terlebih dahulu. Cara yang bisa dilakukan adalah mengajak anak-anak muda itu ngobrol, membicarakan hal-hal ringan, dunia yang mereka akrabi. Topik krisis Suriah bisa jadi akan membuat mereka bosan. Melatih orang berpikir tidak harus dengan mendiskusikan hal-hal berat.
Golongan paling dekat dengan generasi Z adalah genarasi milenial. Generasi milenial merupakan golongan satu tingkat di atas generasi Z. Generasi milenial biasanya menjadi teman sepermainan dan guru/dosen generasi Z. Dengan demikian, perkembangan genersi Z relatif banyak dipengaruhi generasi milenial. Oleh karena itu, generasi milenial adalah golongan paling strategis menjadi duta literasi bagi generasi Z.
Wawasan luas, gaya penyampaian menarik, dan memahami dunia generasi Z adalah modal yang harus dimiliki seorang duta literasi. Kemahiran semacam itu merupakan daya tarik bagi generasi Z untuk menjadi semenyenangkan sosok literat yang kerap bergaul dengannya itu.
Dengan cara tersebut, generasi Z diharapkan dapat mencintai buku. Namun, apa yang telah diupayakan seringkali tidak sesuai harapan. Dari sekian generasi Z yang diusahakan menjadi literat, hanya satu atau dua orang yang berhasil—itu tidak masalah. Satu dua orang itulah yang selanjutnya kita harapkan mampu menjadi duta literasi bagi sesamanya. Literasi, harus kita sadari, adalah kerja bersama.