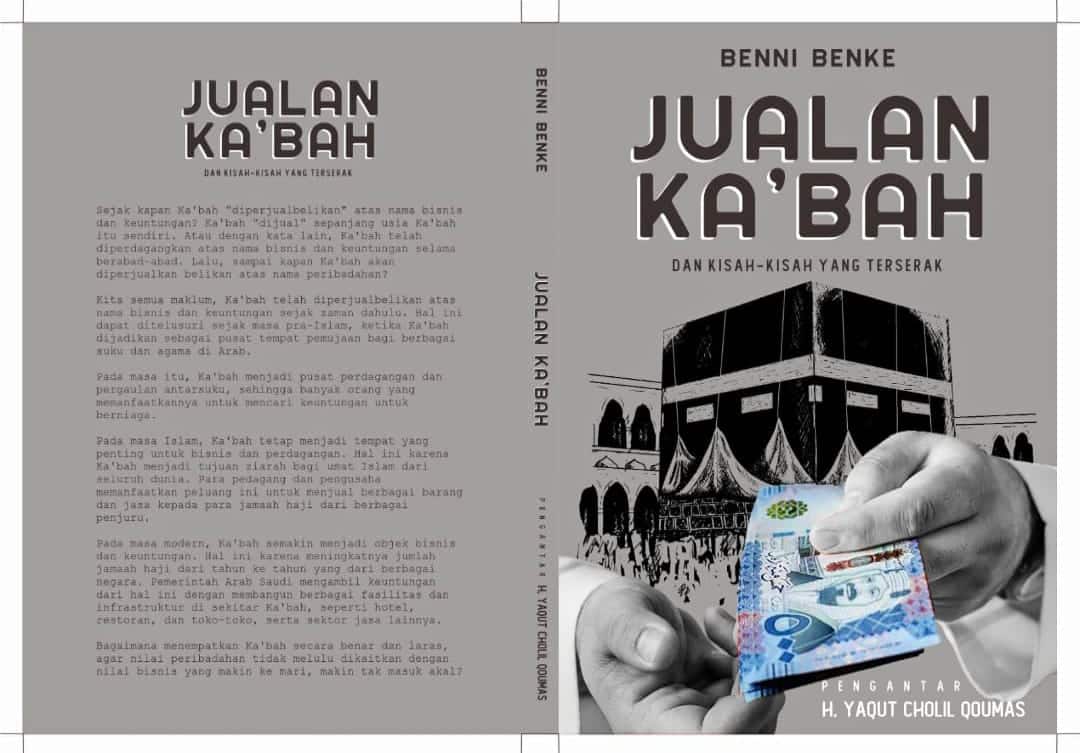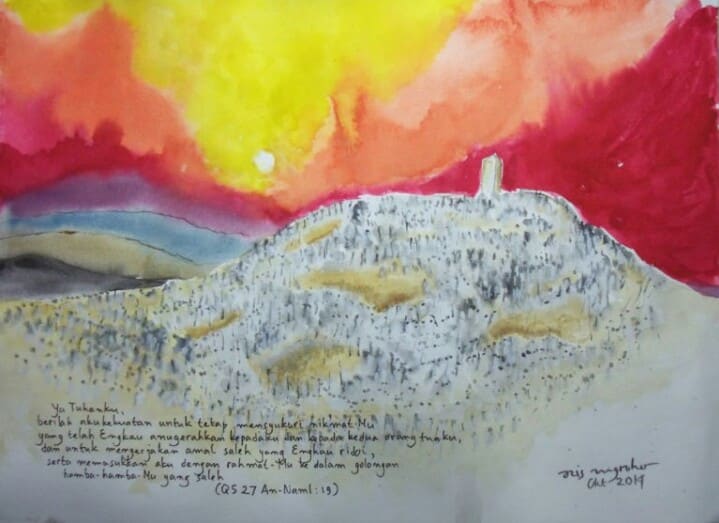
Haji merupakan individu baru menurut beberapa ukuran. Ibadah haji mempunyai efek yang menentukan atas manusia sebagai muslimin, orang Jawi (Indonesia) dan sebagai anggota umat muslim. Begitu catatan Laffan.
Hingga pertengahan abad ke-19, para jemaah haji menumpang kapal layar, kadang dari Singapura atau Tanjung Pinang (seperti Raja Ahmad dari Penyengat tahun 1828) langsung ke Jeddah, kadang dengan singgah dulu di sebuah pelabuhan di India (utusan Banten pada 1637 mendapat kapal di Surat; utusan Sultan Agung tahun 1640 juga begitu; Abdullah Munsyi pada 1854 mendapat kapal di Alfiah).
Selanjutnya orang Inggris disusul orang Belanda yang menyediakan kapal haji. Ekspedisi dilakukan dengan berangkat dari beberapa pelabuhan; pada awal abad ke-20, di Hindia Belanda, kapal bertolak dari Batavia, Padang dan Sabang. (Baca tulisan menarik: Kisah Haji dari Lombok)
Mulai saat itu, jemaah haji berada bersama-sama dengan jemaah yang berasal dari daerah lain di Indonesia; masing-masing mereka menyadari persaudaraannya antara suku-suku bangsa yang belum sempat dijumpai sebelumnya.
Di Tanah Suci, para jemaah dikelompokkan menurut suku asalnya dan dibimbing oleh syeikh (mutawif) yang menguasai bahasa ibu mereka masing-masing, tetapi mereka masih sempat bergaul dengan orang liyan. (Baca tulisan menarik: Senad, Kisah Perjalanan Haji Jalan Kaki)
Sampai awal abad ke-20, orang yang berasal dari berbagai daerah di Sumatra tidak berjumpa di Sumatra melainkan di Pulau Pinang, Singapura, atau Makkah (van Bruinessen, 1992: 134). Titimangsa 1954, Saiful U.A. masih sempat bersawala dengan orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, terutama di antara mahasiswa yang sedang studi di Makkah.
Baik berjumpa dengan sesama orang Indonesia atau tidak, jemaah dari Indonesia menyadari identitas “nasional” dirinya karena dikelilingi orang Arab serta jemaah dari berbagai bangsa, padahal umumnya tidak dapat berkomunikasi dengan mereka. Situasinya sebagai orang asing mendorongnya untuk mendefinisikan diri sendiri.
Pengalaman berhaji seperti juga pengalaman bermukim di Haramain menimbulkan perasaan kesamaan dan perbedaan sekaligus: persamaan dan solidaritas dengan sesama muslim dari seluruh dunia, dan perbedaan mereka semua sebagai orang Jawi. Kesadaran akan sebuah komunitas Jawi, yakni bibit suatu identitas nasional, lebih tinggi lagi di antara mukimin, yang bergaul satu sama lain selama bertahun-tahun (Chambert-Loir, 2013: 97).
Namun perasaan yang paling dahsyat, penemuan yang terpenting selama berhaji adalah kesadaran akan umat muslim. Ibadah haji menyebabkan pertemuan orang yang datang secara global, yang menganut agama yang sama, mempunyai tujuan yang sama dan berpakaian sama. Banyak penulis menyinggung perasaan menjadi anggota sebuah komunitas, terutama selama ritus wukuf di Arafah, tatkala semua jemaah berhimpun selama beberapa jam dalam kawasan yang terbatas.
Perasaan yang lahir dari pengalaman itu kadang hanya keheranan di depan sebuah fenomena manusiawi nan unik, tetapi sering juga perasaan kerukunan dan persaudaraan. Muhtar (1931) menuturkan perasaan bekersamaan itu sebagai berikut:
Semua orang yang bersama-sama sembahyang di dalam Masjidil Haram, meskipun masih berkumpul bersama bangsanya sendiri-sendiri, atau banyak yang tidak tahu bahasa bangsa lain, namun demikian terlihat sangat rukun, saling menghargai, dan menghormati antara satu golongan dengan golongan lainnya, tidak ada yang berselisih, mungkin terbawa oleh niat hati yang sudah menjadi satu.
Kongres (raksasa) tanpa dialog?
Dalam simpulan (bertajuk “Tetap Berada di Mina”) dari bukunya, Haji (1978), Ali Syari’ati menafsirkan kedua (atau ketiga) hari mabit di Mina sebagai kesempatan yang harus dimanfaatkan untuk berpumpun bersama umat muslim dari seluruh dunia, membicarakan pelbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa-bangsa muslim, dan menetapkan sebuah kebijakan bersama; itu suatu kewajiban agama dan politik.
Dia menunjukkan pertemuan itu dengan istilah yang dari satu ke lain terjemahan menjadi “musyawarah teologis dan ilmiah”, “konvensi sosial internasional”, “konvensi ilmiah”, dan “kolokium teologis dan ideologis” (Syari’ati, 1978: 207-210), atau “seminar ilmiah teologis”, “muktamar sosial internasional”, “muktamar ilmiah”, dan “seminar … teologis dan ideologis” (Syari’ati, 1978: 164-166).
Gagasan ihwal pertemuan ini terdapat juga dalam dalam beberapa tulisan Indonesia, meskipun tidak diteroka seteliti Ali Syari’ati. Karangan Aminu’ddin Junus, Haji: Pentjiptaan Internasionalisme dan Djiwa Universil jang Sedjati, 1951, misalnya menjelaskan bahwa ibadah haji, terutama karena pakaian ihram dan ritus wukuf, mendorong orang menyadari keperluan akan perdamaian, kemufakatan, serta sikap internasionalis antara berbagai bangsa, suatu gagasan yang menarik karena diutarakan segera pasca kemerdekaan Indonesia (Chambert-Loir, 2013: 98).
Saiful U.A., tahun 1954, mengkomparasikan ibadah haji dengan sebuah kongres Islam internasional: “Kongres Islam sedunia sedang berlangsung di daerah ini Saudara! Dikunjungi oleh berbagai bangsa tapi satu agama. Mengapakah tidak, sebab di tempat ini kulihat berkibar dengan jayanya bendera-bendera Mesir, Saudi Arabia, Turki, Indonesia, Kuweit, Pakistan, India, dan sebagainya.”
Istilah kongres ini digunakan oleh penulis lain selanjutnya, contohnya Harun Aminurrashid, pada 1960, mengenai Arafah: “Inilah tempat seluruh umat Islam berkongres pada tiap-tiap tahun”. Serta Moeslim Abdurrahman (2009: 106), “Wukuf di Arafah bagaikan ‘kongres internasional’ tahunan bagi umat muslim dari seluruh dunia”. Dan juga Munawar & Halim (2003: 16), “Haji merupakan kongres tahunan umat Islam yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana memupuk kesatuan dan persatuan umat.”
M. Toha Anwar (dalam Dharma, 2000: 136-7) memprotes bahwa ibadah haji era kiwari telah kehilangan “dimensi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lainnya”.
Kebanyakan jemaaah, kata Toha Anwar, menganggap ibadah haji sebagai suatu ibadah mahdhah, yang tidak mempunyai dimensi sosial, padahal berada “di Tanah Suci, di mana konferensi tahunan umat Islam dari segala bangsa itu diselenggarakan”.
Akan tetapi sebenarnya, buat kebanyakan jemaah, lautan manusia yang terkumpul di Arafah dengan segala keperluan, kesulitan, dan peraturannya, tidak mungkin lagi berkongres dengan siapa pun. “Kongres” itu telah menjadi sedemikian raksasa sehingga tidak memungkinkan dialog lagi.