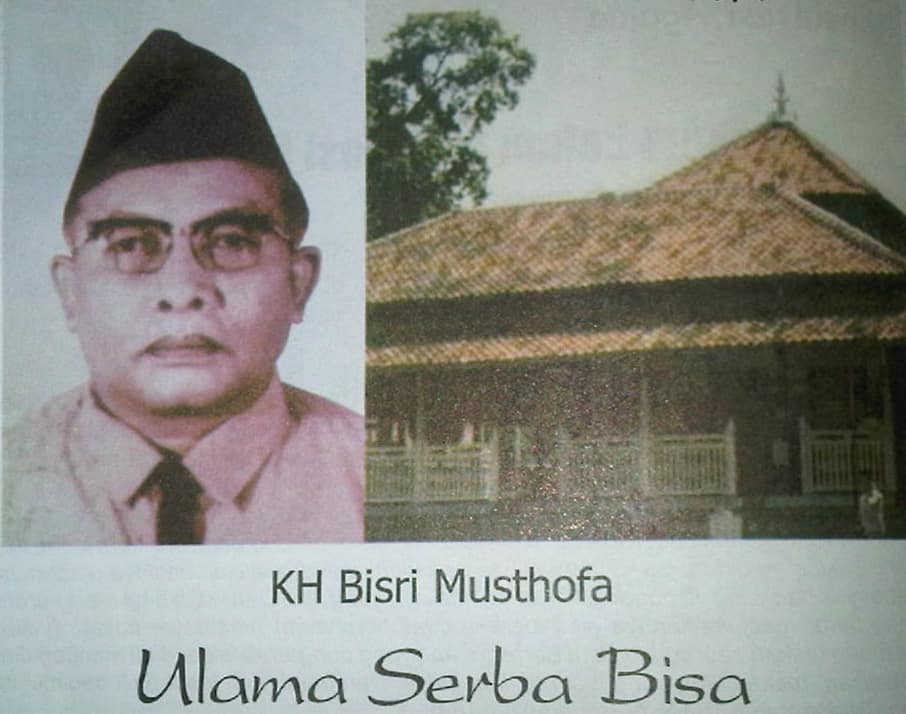Hikayat Hujan: Jangan Biarkan Kemarau di Hati

Seorang pembual tiba-tiba singgah di sebuah desa yang sedang diserang kemarau yang panjang selama beberapa waktu. Tak dinyana, dengan kecerdasan dan daya pikatnya yang tinggi, ia pun berjualan hujan di sana dan laku dibeli oleh sebuah keluarga yang terbawa oleh suasana panas kemarau.
Di sana ada seorang bapak, yang bagaimana pun caranya ingin menikahkan anak perempuannya yang belum juga kawin. Ada juga seorang lelaki yang berupaya menikahkan kakak perempuannya agar ia tak meninggalkan sopan-santun Jawa untuk tak melangkahinya. Tak elok kawin sebelum kakak perempuannya kawin duluan. Lalu ada lagi seorang lelaki yang terlalu terpaku pada catatan keuangan keluarga hingga saking perhitungannya ia pun lupa kawin pula.
Bintang Kejora (1986), sebuah film klasik yang dibintangi oleh El Manik dan Rini S. Bono, barangkali adalah sebuah film Indonesia yang kali pertama mengisahkan hujan—atau lebih khusus lagi: harapan.
Tak sebagaimana sajak-sajak tentang hujan Sapardi Djoko Damono yang mengemas hujan secara muram ala eksistensialisme, Bintang Kejora justru membawakan hujan sebagai sebentuk harapan.
Sebelum saya berkisah tentang kisah hujan itu ada baiknya saya sedikit berkisah tentang waktu dalam kaitannya dengan manusia. Barangkali, kesadaran manusia tentang waktu inilah yang membedakannya dengan makhluk lainnya.
Secara umum struktur kesadaran manusia normal terpilah dan terbentuk atas tiga hal: masa silam, kini, dan mendatang. Kesilaman itu terwujud dalam kenangan yang terpusat pada kekinian. Adapun mendatang berkaitan dengan harapan.
Seorang pemikir Prancis, Gaston Bachelard, menganalogikan kesadaran manusia dengan rumah: dapur, kamar mandi, tempat tidur, ruang tamu, dan dinding-dindingnya. Terkait dengan pemilahan saya, maka rumah sebagaimana yang dipahami Bachelard itu justru—menyangkut kesadaran manusia yang oleh Husserl disifati untuk selalu mengarah ke sesuatu (intensionalitas)—berada di masa silam dan mendatang.
Drama kehidupan manusia dalam perspektif agama misalnya, selalu meletakkan waktu kini sebagai “jalan” yang perlu dilalui dan dimanfaatkan untuk menuju rumah di masa mendatang yang, anehnya, justru menjadi tempat dari mana orang itu berasal (masa silam). Dalam bahasa agama hal itu direpresentasikan oleh sepenggal ungkapan “inna lillahi wa inna ilahi rajii’un”.
Setali tiga uang dengan berbagai sumber kearifan lokal. Dalam khazanah budaya Jawa terdapat ungkapan bahwa “urip mung mampir ngombe.” Bahkan dahulu pemahaman seperti itu terejawantah pula dalam bentuk arsitektural rumah Jawa. Di halaman depan selalu terdapat gapura di mana didekatnya ditaruh sebuah gentong berisi air. Gentong air itu diperuntukkan bagi para pejalan yang kehausan yang tengah melintas di depan rumah.
Ada beberapa catatan yang perlu dipahami di sini, tentang keterkaitan antara rumah sebagai analogi kesadaran dan air. Dalam berbagai bidang, air telah lama menjadi penanda resmi kehidupan. Konon kenapa manusia hidup di Bumi dan tak di Venus adalah karena volume planet yang pertama itu banyak diisi oleh air.
Pada mitologi Hindu, air identik dengan Wisnu yang dalam konteks konsep trimurti berkaitan dengan peran dan fungsi untuk memelihara. Pada kisah pewayangan, hanya para titisan Wisnu yang memiliki kembang wijaya yang dapat menghidupkan orang yang belum mati pada waktunya.
Secara eksistensial keterkaitan antara kesadaran dan air itu dapat dirasakan ketika orang sedang dipanggang oleh kemarau yang panjang. Dan ini menjadi bukti bahwa ada keterkaitan langsung antara jagad gedhe (makrokosmos) dan jagat cilik (mikrokosmos). Benarlah penggalan syair yang dinyanyikan oleh Elmanik di awal adegan film: “Jangan biarkan kemarau di hatimu.”
Apakah kemudian El Manik, yang dalam film itu bernama Bintang Kejora, tak pula menjadi korban dari keadaan, tak terusik olek lingkungan di mana ia berpijak? Sebermulanya ia tampak sebagai sosok yang jejeg suasana batinnya yang dapat mengubah keadaan keluarga Dahlia (Rini S. Bono) dan tentu pula keadaan sekitar.
Dengan bualannya itu ia mampu “mempermainkan” Sobrat, salah satu adik Dahlia, untuk tak terlalu serius dalam hidup hingga lupa bagaimana caranya tertawa. Dan terutama, dengan kepercayaan diri dan bualannya itu, ia mampu menundukkan Dahlia. Kakak perempuan Sobrat dan Sopan itu sedikit demi sedikit mulai tumbuh rasa percaya dirinya. Ia tak lagi seperti preman, mulai bersolek dan belajar tentang keanggunan.
Tapi begitu hujan tak turun sebagaimana yang dijanjikan, Bintang Kejora mulai gusar. Ia pun terjebak oleh keadaan. Dan ketika hujan itu tak turun-turun juga, Kejora mesti bersiap untuk diusir dari desa, untuk tak lagi dapat melepas lelah dan berumah. Sosok penumbuh harapan pun berganti pada si perawan kasep, Dahlia.
Dalam keputusasaan si Kejora, Dahlia meyakinkannya, setelah semua yang terjadi, setelah keadaan mulai berubah, entah si Kejora membual atau tidak, tak elok untuk meninggalkan gelanggang laiknya bukan pejantan. Dan hujan pun tiba-tiba turun membasahi desa itu. Semua bersorak girang dalam ranjapan air dari langit.
Sebagaimana kesadaran akan kesilaman dan kemendatangan, yang akan terang andaikata ada air yang oleh para sesepuh disebut sebagai ngelmu. Hanya dengan ngelmu itulah rumah itu akan ditemukan tanpa ketersesatan, dan bukannya dengan emas ataupun harta.
Mari, yuk, jangan biarkan hati kering. Mumpung musim hujan sudah tiba. (SI)