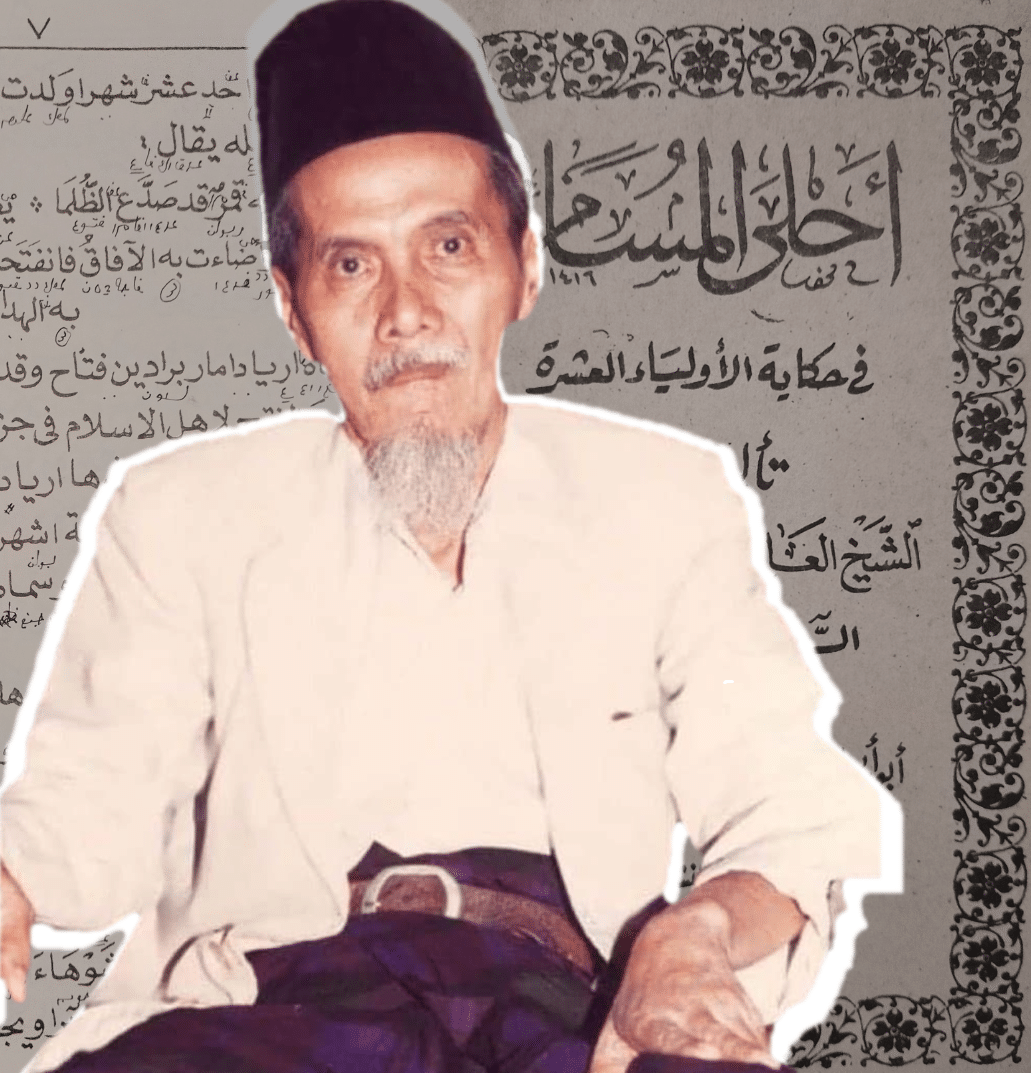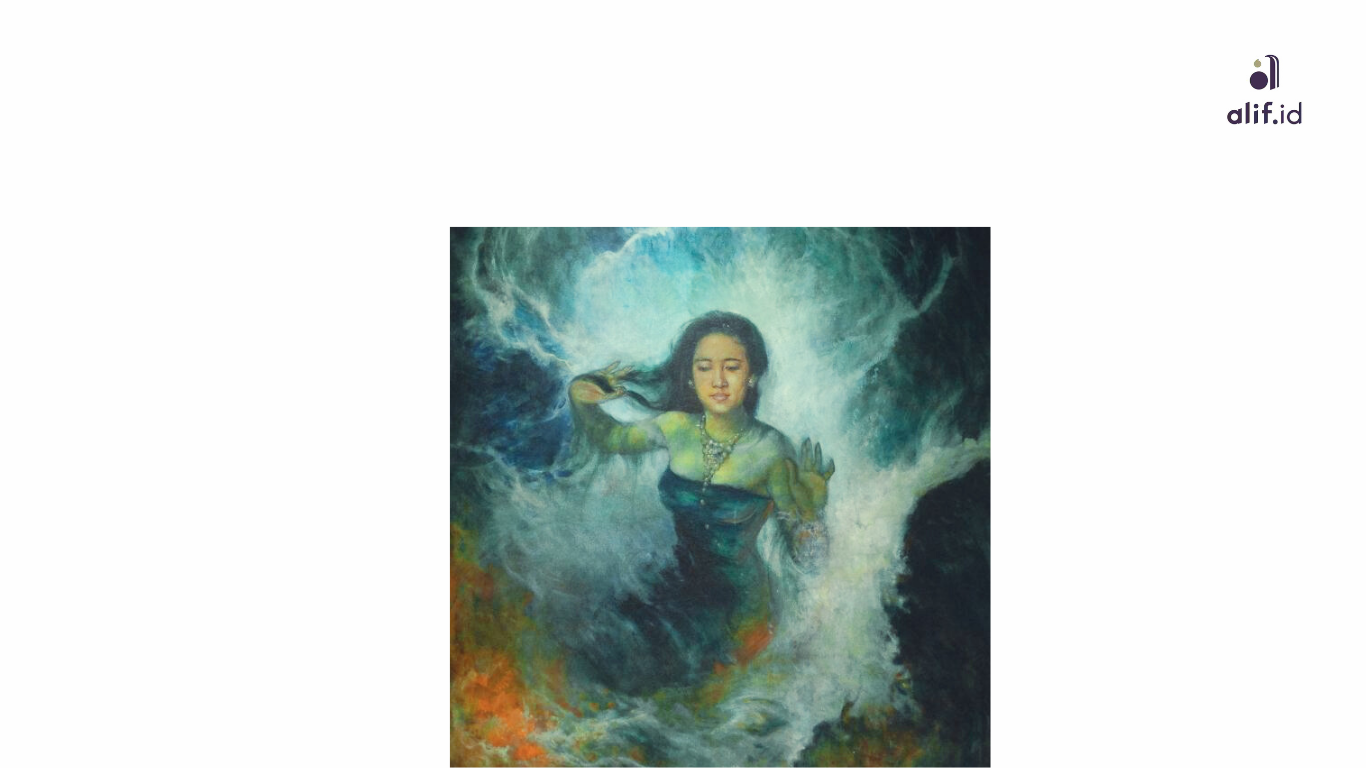Bertahun-tahun selama masa Order Baru, santri (yang berafiliasi ke NU) adalah kelompok yang hampir tak tercatat di atas peta perfilman Indonesia. Selain banyak santri menganggap teknologi pembuatan dan praktek pemutaran film sebagai hal yang tidak penting dan (ironisnya) kontroversial, representasi tentang mereka di layar bioskop Indonesia jarang sekali ditemukan.
Sekalinya ada, ia tunduk terhadap nafsu Orde Baru untuk mengontrol segala bentuk ekspresi politik Islam di ruang publik, atau kalau tidak, berhadapan dengan dominasi para pembuat film dari kelompok muslim non-tradisionalis.
Namun dalam satu dekade terakhir di masa post-Suharto, telah terjadi transformasi dalam sikap para santri terhadap film dan praktek pembuatan film. Hal ini pertama-tama ditandai dengan peluncuran 3 Doa 3 Cinta di tahun 2008. Ini adalah film Indonesia pertama yang dibuat oleh santri sutradara, Nurman Hakim, dan mengandung cerita eksplisit tentang karakter santri yang memiliki gairah kuat bermain-main dengan alat pembuatan dan pemutaran film.
Sejak saat itu, muncul komunitas-komunitas dan praktek-praktek perfilman di kalangan kaum muda santri, tak terkecuali mereka yang masih belajar di pesantren-pesantren (sekolah tradisional Islam dengan sistem asrama), yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Dari bilik-bilik pesantren mereka, para remaja muslim ini secara serentak terorkestrasi untuk menyelenggarakan pemutaran film, pembuatan film, perlombaan film, dan diskusi film, yang bersifat alternatif dan eksperimental, dan dikerjakan dengan spirit DIY (‘Do It Yourself’, Kerjakan Sendiri). Pencarian sederhana di laman YouTube dengan kata kunci “film santri”, misalnya, akan membawa Anda pada hasil yang mengejutkan.
Di dalam tulisan pendek ini, saya akan mencoba menjelaskan mengapa kelompok santri menjadi perlu dan mampu untuk terjun (lagi) ke arena perfilman Indonesia, setelah apa yang dilakukan oleh para santri pendahulu mereka di tahun 1960an, lewat Lesbumi.
Untuk itu, saya akan mengambil satu bagian dari adegan dalam fim 3 Doa 3 Cinta, dan menariknya ke dalam diskursus perebutan wacana Islam di arena perfilman Indonesia saat ini, khususnya antara kelompok tradisional NU, dan seteru lama mereka, kelompok modernis Muhammadiyah dan, yang muncul di periode 1980an, gerakan Islamis Tarbiyah.
Pesan Cinta Madzhab Pesantren
3 Doa 3 Cinta berkisah tentang Huda, Rian dan Syahid, para pelajar di sebuah pesantren tradisional di Jawa Tengah. Ketiganya digambarkan susah payah berjuang mencari cinta sejati mereka dengan caranya masing-masing, setelah sama-sama kehilangan hal yang paling berarti dalam hidup mereka. Pada akhirnya, para santri ini digambarkan berhasil menyelesaikan perjuangan mereka dengan baik, dengan cara berpegang pada ajaran-ajaran moral-Islam yang mereka pelajari di pesantren.
Adegan pembuka film ini sangat penting. Ia diawali dengan pengajian agama khas pesantren tradisional. Para santri, dengan kain sarung melilit di pinggang dan peci melingkar di kepala, duduk bersila mengadap guru-pemimpin agama mereka (kiai), yang dibedakan dengan kain sorban bergantung di leher. Sang kiai terlihat sedang membacakan sebuah teks Islam klasik berbahasa Arab (kitab kuning). Setiap selesai membaca potongan kalimat, ia merjemahan kalimat tersebut dalam bahasa Jawa, yang kemudian dicatat oleh para santri di kitab-kitab mereka, dengan aksara Arab pegon. Teks yang sedang dibaca oleh sang kiai adalah tafsir ayat Al-Qur’an tentang permusuhan abadi orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap Islam.
Melihat dahi para santrinya berkerut mendengar terjemah teks yang ia bacakan, sang kiai kemudian menjelaskan bahwa apabila orang Yahudi dan Nasrani itu berbuat baik dan menghormati orang Islam, maka orang Islam pun harus memperlakukan mereka dengan cara serupa.
Kain sarung, sorban, Arab pegon, terjemahan bahasa Jawa, dan penjelasan dari sang guru, membentuk pesan-pesan utama dalam 3 Doa 3 Cinta. Diantara pesan-pesan tersebut adalah (1) kelenturan adaptif Islam terhadap kondisi sosial dan budaya lokal (dalam hal ini Jawa) dan (2) otoritas transmisi dan tradisi keilmuan Islam di pesantren. Pesan-pesan in tentu saja tidak asing di dalam wacana keislaman para santri. Kenapa?
Sebab tradisionalisme mereka sesungguhnya banyak dihubungkan dengan, pertama, semangat merekonsiliasi ajaran dan ritual Islam dengan kondisi masyarakat dan budaya lokal (e.g. pribumisasi Islam); dan kedua, kesadaran menjaga sanad keilmuan Islam dengan para ulama terdahulu, terus keatas hingga Nabi Muhammad.
Kedua pesan di dalam adegan pembuka ini, dengan kata lain, hendak mengatakan kepada para audiens film bahwa 3 Doa 3 Cinta yang dibuat oleh Nurman Hakim adalah film Islam yang khas para santri, dan pesan Islam yang disampaikan film in adalah Islam yang otoritatif, yang sampai pada sumber utama Islam.
Pertanyaannya, mengapa pesan tersebut harus digarisbawahi? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan membangdingkan 3 Doa 3 Cinta dengan genre film Islam yang sedang populer di sinema Indonesia, di bagian berikut.
Melawan ‘Cinta yang Lain’
Enam bulan sebelum penayangan 3 Doa 3 Cinta, sebuah film bertema keislaman terlebih dahulu diputar di jaringan eksibisi utama film-film Indonesia, Sinema21. Ia adalah Ayat-Ayat Cinta, yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini berkisah tentang Fahri, pelajar Islam Jawa-Indonesia di program pascasarjana Universitas Al-Azhar: seorang santri dalam arti yang lebih luas. Hanya saja, dalam beberapa hal Fahri digambarkan berbeda dengan prototip santri tradisional.
Selain ahli agama, Fahri selalu bercelana panjang, jarang berpeci, fasih bergaul dengan budaya dan wacana politik-Islam internasional, dan di kelilingi perempuan-perempuan cantik dan kaya raya. Sebagai seorang Muslim kosmopolitan, Fahri adalah santri yang lebih dekat dengan Islam modernis Muhammadiyah, dan dalam tahap tertentu, gerakan Islamis Tarbiyah.
Hanung Bramantyo secara terbuka mengakui afiliasinya dengan Muhammadiyah, dan dalam membuat Ayat-Ayat Cinta, ia berkonsultasi dengan Din Syamsuddin, saat itu sebagai ketua umum Muhammadiyah. Ini adalah organisasi Islam kelompok modernis, yang muncul di masyarakat urban Indonesia pada awal 1900an. Muhammadiyah, terinspiasi dari gerakan Arab Wahabi yang kemudian dikembangkan oleh pemikir modernis Mesir Mohammad Abduh, memiliki misi membersihkan ajaran Islam dari praktek bid’ah dan taklid, serta mangajak bersandar kepada Al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman utama beragama.
Sementara itu, novel yang menjadi dasar film Ayat-Ayat Cinta, ditulis oleh Habiburrahman el-Shirazy dengan judul yang sama. Ia adalah seorang alumni pesantren tradisional Jawa, yang, seperti Fahri, melanjutkan belajar Islamnya di Al-Azhar.
Selama di Mesir, el-Shirazy lebih dekat dengan pergaulan Islam kelompok Tarbiyah. Ini adalah gerakan dakwah Islam yang mengambil inspirasi dari Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang dalam beberapa hal diilhami oleh ideologi modernis Abduh. Anggota gerakan Tarbiyah didominasi oleh keluarga muslim urban kelas menengah, mirip dengan Muhammadiyah.
Bedanya, mereka memulai pelajaran Islam dari halaqah masjid kampus yang sejak akhir 1980an menjamur di universitas-universitas sekuler papan atas Indonesia. Misi utama gerakan dakwah Tarbiyah adalah mengislamkan Indonesia pada tingkat individual, yang diharapkan dapat berujung pada pendirian negara Islam, di saat waktunya tiba. Dedikasi terhadap keislaman individual diterjemahkan oleh Ayat-Ayat Cinta, baik versi novel dan film, lewat dominasi penggambaran diskursus kesalihan yang bersifat personal: seperti kefasihan membaca Al-Qur’an, pemakaian jilbab besar dan cadar, ketertiban menjalankan sholat, dan pencarian jodoh di luar prinsip pacaran.
Pesan moral-Islam berorientasi individual semacam ini tampaknya menggusarkan para santri tradisional. Para santri yang saya ajak bicara, misalnya, mengatakan pesan-pesan tersebut sebagi Islam superfisial, yaitu sikap menyamakan simbol-simbol budaya dan bahasa Arab dengan kesalehan Islam. Hanya saja, film Islam bergaya Ayat-Ayat Cinta, justru makin banyak dirilis di sinema Indonesia. El-Shirzay bahkan berani terlibat lebih jauh dalam memfilmkan novel-novelnya yang lain seperti Ketika Cinta Bertasbih (2009), Dalam Mihrab Cinta (2010), dan yang terbaru Ayat-Ayat Cinta 2 (2017).
Di ketiga film ini, pesan Islam Tarbiyah yang oleh para santri dianggap bersifat artifisial, ditampilkan dengan cara yang lebih dramatis. Merespon keadaan ini, para santri merasa perlu memproduksi film Islam gaya mereka sendiri, sebagai wacana tandingan bagi diskurus Islam simbolik yang dikembangkan oleh film-film semacam Ayat-Ayat Cinta.
Arena Baru Pertarungan Wacana Islam
Hefner pernah menulis bahwa para santri selalu punya cara untuk merespon ‘inovasi’ yang dilakukan oleh lawan-lawan Muslim mereka, dengan ‘cara yang jelas-jelas serupa’ (2009: 25). Pendirian NU tahun 1926, misalnya, banyak dipengaruhi oleh kekhawatiran para santri terhadap pendirian organisasi Islam di kalangan modernis di tahun 1912, yang mengkritik keras tradisionalisme Islam.
Hingga saat ini persaingan kedua kelompok ini pun masih mempengaruhi ekspresi politik Islam mereka di ruang publik. Bedanya, persaingan keduanya sekarang diramaikan oleh kehadiran kelompok Tarbiyah (untuk menyebut diantara yang paling populer), yang memiliki beberapa kesamaan dengan kelompok Muhammadiyah.
Salah satunya, mereka tidak hanya lihai dengan budaya populer, tetapi juga melihatnya sebagai sarana dakwah Islam yang efektif. Maka, manakala kelompok-kelompok muslim saingan ini menggunakan film sebagai bagian dari sarana dakwah mereka, para santri pun memberi respon serupa: menyiapkan senjata dan berlari ke film arena. Dengan kata lain, peningkatan praktek dan diskursus perfilman di kalangan santri pada sepuluh tahun terakhir memiliki hubungan yang erat dengan pertarungan merebut wacana keagamaan di ruang publik.
Meski demikian, saya menolak berpendapat bahwa kemunculan santri sinematek adalah peniruan mentah-mentah dari para pembuat film di kalangan modernis dan islamis. Sebab kemampuan para santri untuk merespon “inovasi kelompok muslim lain dengan cara yang sama” tidaklah datang dari langit. Tetapi kemampuan tersebut telah disemai dan dipupuk oleh masyarakat santri sendiri, jauh sebelum popularitas film Islam gaya Ayat-Ayat Cinta muncul di jagad sinema Indonesia: sebuah pembahasan yang akan saya lanjutkan di kesempatan lain. Wallahu a’lam.