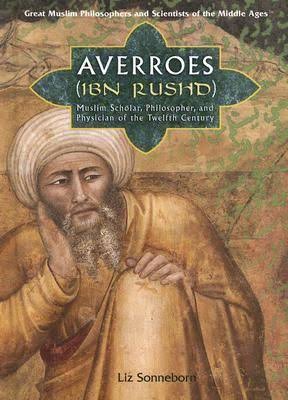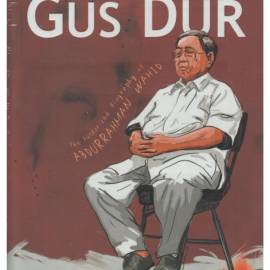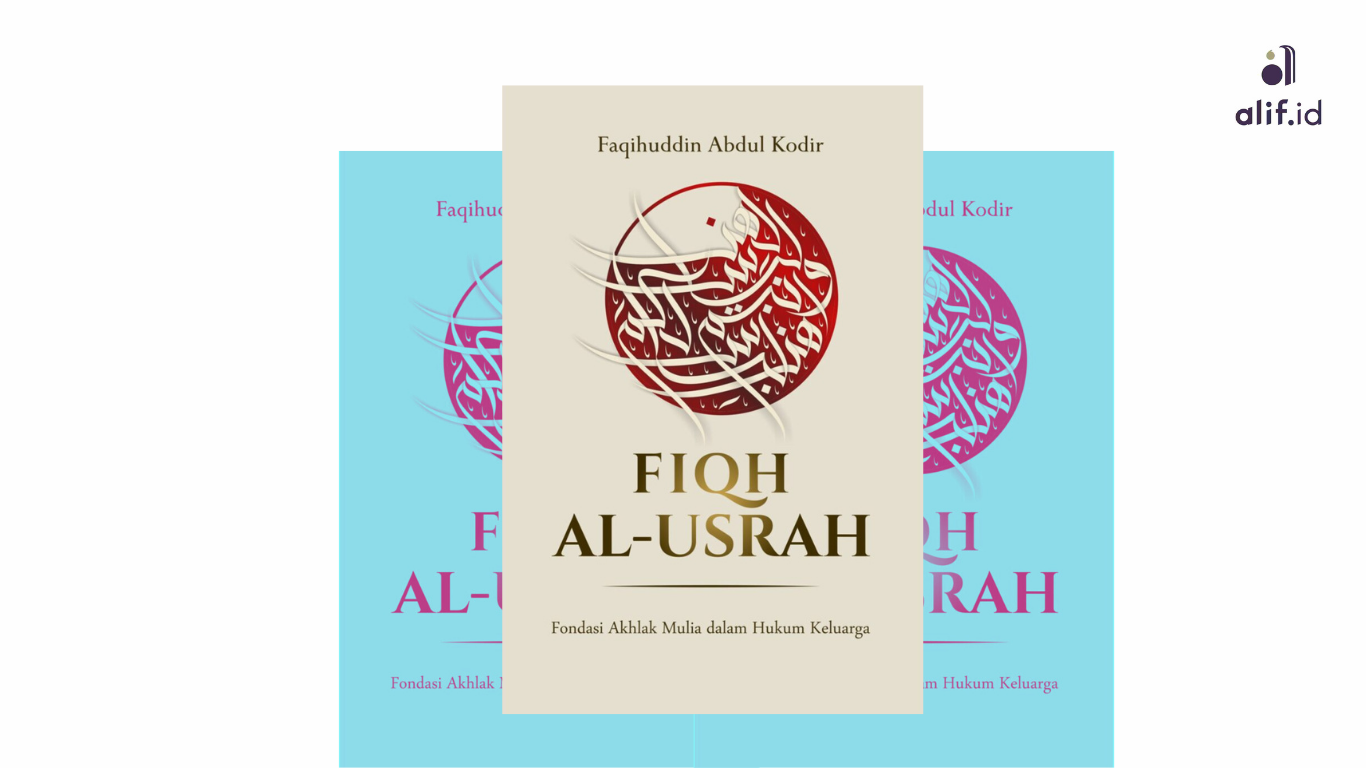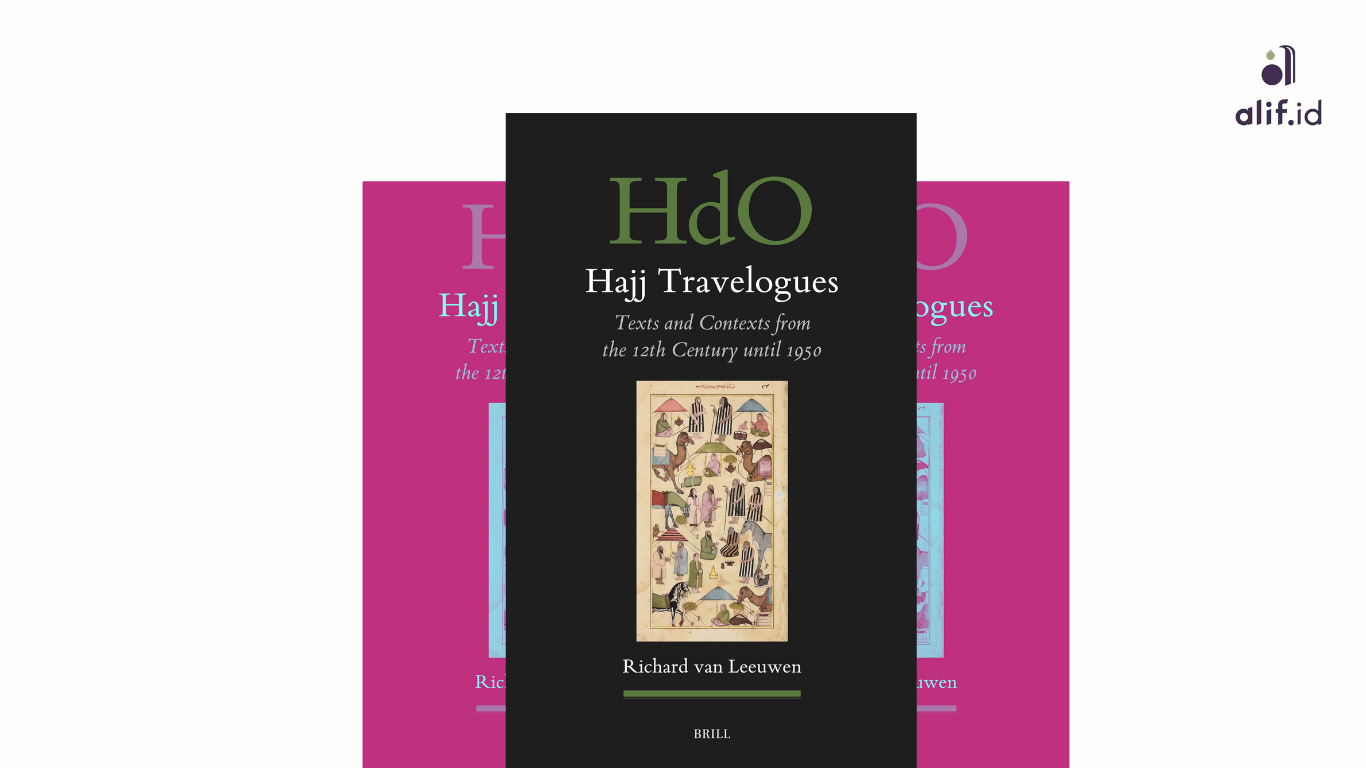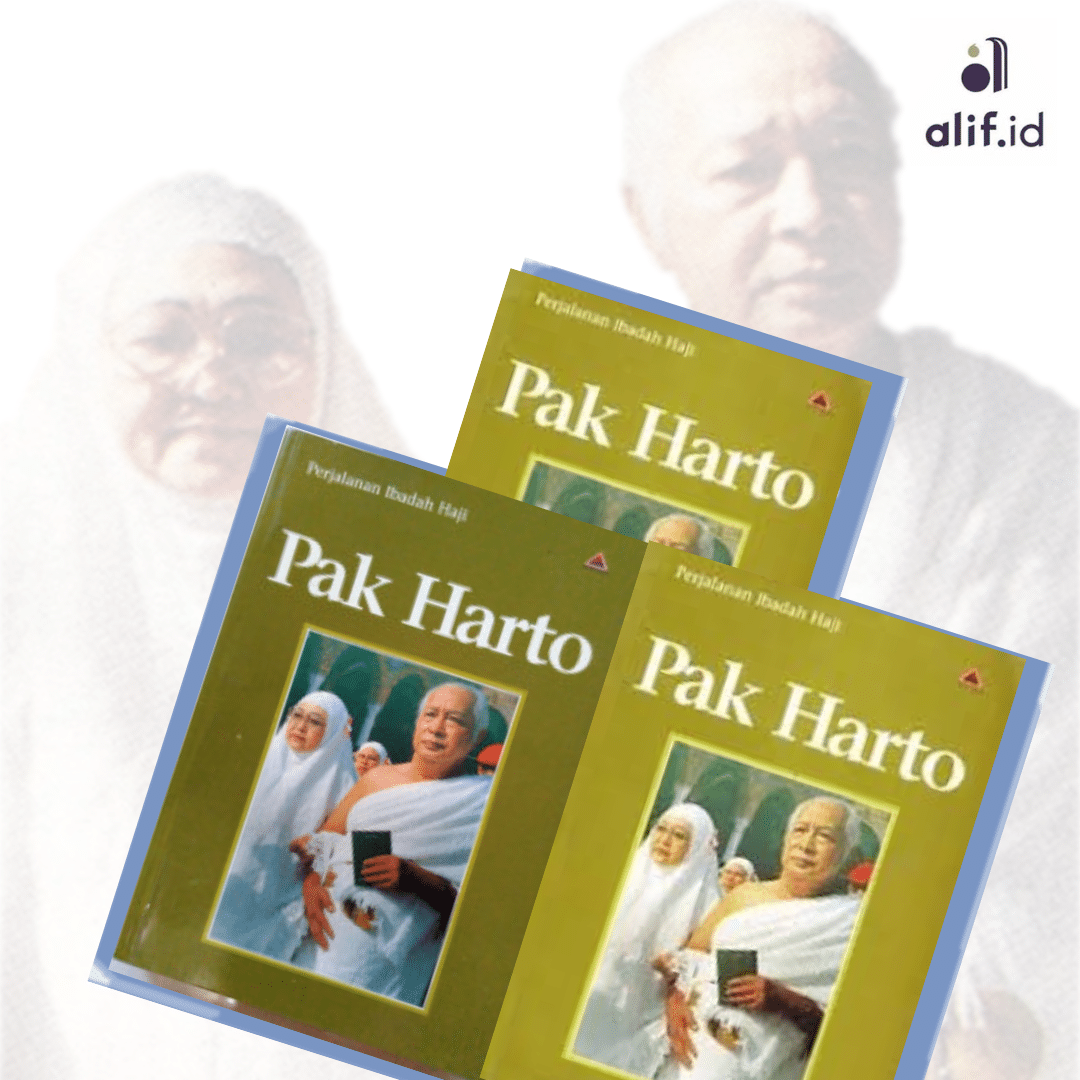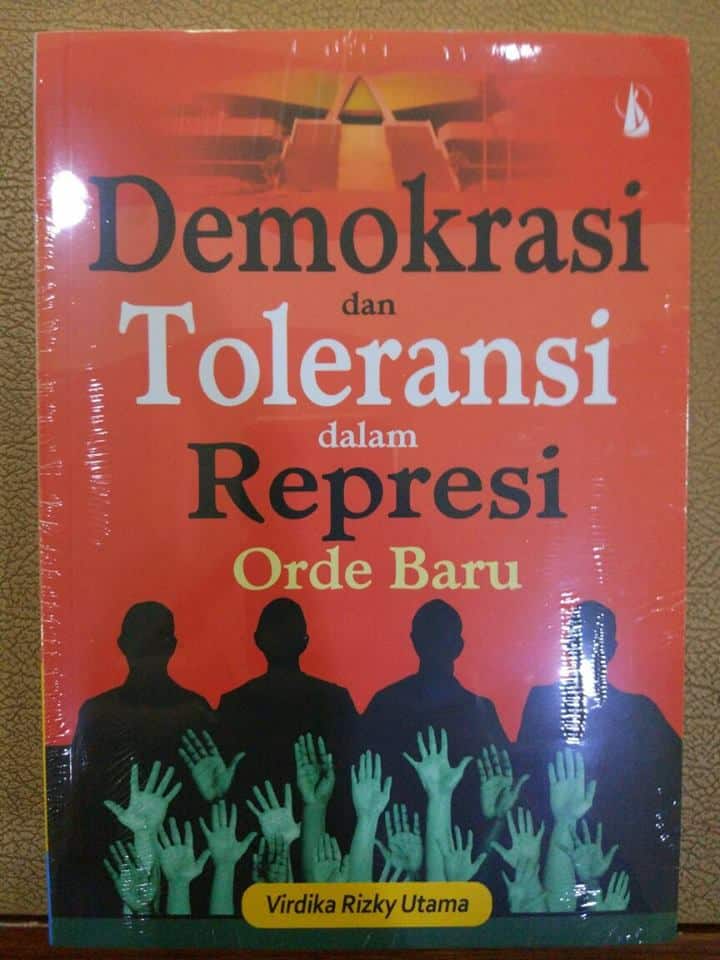
“Pilih pemimpin yang muslim!” “Calon yang satu lagi bukan orang Islam, tentu kebijakannya tidak mendukung umat Islam. Jangan dipilih! “Jangan pilih calon yang non-pribumi!”
Terdengar tak asing? Tentu. Beberapa ucapan di atas sering terdengar saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun lalu. Ucapan-ucapan di atas muncul jauh sebelum hari pemilihan berlangsung dan, ironisnya, bertahan cukup lama hingga saat ini dan melahirkan kembali politik identitas.
Tentu ini bukan preseden baik. Karena politik identitas mudah memunculkan kembali sikap sektarian dalam perhelataan demokrasi yang berlangsung beberapa tahun sekali. Memilih pejabat publik—perlu dibedakan dengan pemimpin—berdasarkan agama dan etnis tertentu. Itu merupakan dalil awal munculnya sektarianisme.
Sehingga ketika melakukan pemilihan tak lagi melihat kinerja dan rekam jejak, namun berdasarkan agama dan etnis. Ketika sudah seperti ini, demokrasi berjalan semu karena hilangnya kesempatan yang sama untuk orang bisa dipilih tanpa melihat latar belakang keagamaan dan ras.
Jika melihat ke masa lampau, awal tahun 1990 Indonesia pernah berada dalam diskursus masyarakat yang sektarian. Saat itu Orde Baru masih berkuasa penuh. Namun terdapat sekelompok intelektual publik yang gencar melancarkan gerakan yang tetap ingin mempertahankan keadaan Indonesia yang demokratis, tanpa adanya gejala sektarianisme. Mereka menamai diri dengan Forum Demokrasi—yang biasa disebut Fordem.
Mereka tergabung dari banyak intelektual publik dengan ragam latar belakang: Gus Dur, Marsillam Simanjuntak, Rahman Tolleng, Mangunwijaya, Franz Magnis Suseno, Arief Budiman, Daniel Dhakidae, hingga Todung Mulya Lubis. Dan masih banyak lagi.
Buku Virdika Rizky Utama ini mencoba membahas lebih dalam apa itu Fordem dan bagaimana sikap-sikap mereka terkait isu sektarian dan anti-demokrasi yang muncul saat Orde Baru.
Isu Sektarian Tahun 90-an
26 Oktober 1990, Arswendo Atmowiloto resmi menjadi tahanan Polda Metro Jaya dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Kasusnya dimulai saat Tabloid Monitor—dengan Arswendo sebagai Pemimpin Redaksinya—menerbitkan sebuah artikel tokoh-tokoh yang dikagumi oleh pembaca tabloid tersebut. Yang menjadi masalah: artikel itu tertulis bahwa Soeharto berada di posisi satu, Arswendo berada di posisi sepuluh, sedangkan Nabi Muhammad SAW. berada di posisi sebelas.
Hal tersebut membuat banyak umat Islam saat itu marah. Mereka menilai itu merupakan sebuah penghinaan terhadap nabi mereka. Sejak saat itu muncul ragam protes melalui pernyataan-pernyataan ormas Islam, hingga munculnya isu ini ke khotbah-khotbah masjid. Tak hanya itu, kantor redaksi Tabloid Monitor pun dirusak oleh massa. (hal. 48)
Itu yang membuat Tabloid Monitor diberedel dan Arswendo diseret ke ranah hukum. Namun Gus Dur menilai bahwa kasus itu merupakan kemunduran demokrasi dan melanggar kebebasan berpikir. Gus Dur tetap membela Arswendo karena ia dikriminalisasi atas nama agama. Dalam kerja jurnalistik seharusnya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan membuat surat pembaca atau memboikot tabloidnya, bukan dengan penangkapan dan pemenjaraan.
Dan juga pasca kasus itu terjadi, isu sektarian makin menguat dalam masyarakat kita. Isu sektarian yang diamati oleh Gus Dur adalah kepentingan-kepentingan kelompok agama mayoritas yang diakomodir oleh pemerintah dan hal ini dalam mengancam keharmonisan antar umat beragama.
Terlebih Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia yang rentan dapat memberi ancaman kepada kaum minoritas jika kepentingan mereka diprioritaskan oleh pemerintah. Alangkah berbahayanya jika semangat primordial dan sektarianisme tertanam dalam jiwa umat Islam di Indonesia. Padahal, bagaimanapun Indonesia sudah kadung hadir sebagai bangsa yang heterogen dan plural. (hal. 51)
Fordem Sebagai Perlawanan
Untuk menangkal isu sektarian yang menguat saat itu, hadirlah Fordem sebagai bentuk kegelisahan para kaum intelektual publik. Mereka resah dengan keadaan Indonesia yang semakin jauh dari diskursus yang demokratis dan cengkraman sektarianisme yang makin kuat. Mereka menilai Orde Baru yang berkuasa saat itu tak lagi menjalankan agenda-agenda demokrasi secara substansial, melainkan hanya formalitas belaka.
Selama berpuluh-puluh tahun Indonesia dalam kuasa Orde Baru hanya melakukan pemilu ‘yang seolah-olah’. Siapa pun yang dipilih, yang menang akan tetap Soeharto sebagai presiden. Itu alasan mengapa ia bisa berkuasa selama 32 tahun. Todung Mulya Lubis, pengacara kawakan yang juga anggota Fordem, menyebut demokrasi saat pemerintahan Soeharto hanya ‘demokrasi kosmetik’. (hal. 58)
Ditambah lagi pada tahun 90an pemerintah Orde Baru juga mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai satu-satunya organisasi Islam yang ada. Artinya, akan lebih mudah agenda-agenda kepentingan umat Islam terprioritaskan menjadi kebijakan publik, dan hal ini yang tak diinginkan oleh Gus Dur dan barisan Fordem.
Hal tersebut tak bisa dilepas dari konteks saat itu yang mana Soeharto mulai ditinggal oleh barisan jenderal yang dulu setia kepadanya. Ketika ia sudah mulai sadar tak bisa lagi berharap kepada militer untuk tetap berkuasa, jalan satu-satunya adalah merangkul umat Islam untuk menjadi basis pendukung dan tetap meneguhkan posisinya sebagai presiden. Itulah mengapa ICMI hadir.
Ini juga bisa menjadi langkah Soeharto untuk ‘membersihkan’ namanya di mata umat Islam, karena peristiwa berdarah Tanjung Priok tahun 1984 dan Talangsari tahun 1989 yang banyak membantai ulama dan umat Islam.
Revitalisasi Nilai Juang Fordem
Jika kita melihat keadaan realitas saat ini yang justru banyak hal-hal membikin demokrasi berjalan mundur, isu sektarian dan rasialisme menyebar di mana-mana, hingga menguatnya kembali politik identitas.
Sehingga perlu adanya upaya kaum intelektual, mahasiswa, hingga pemerintah untuk membumikan kembali gagasan dan nilai yang pernah Fordem deklarasikan puluhan tahun silam: membangun diskursus masyarakat yang demokratis dan anti-sektarian.
Keberagaman menjadi satu kunci utama bagaimana gagasan dan nilai di atas bisa hadir kembali dan menyelamatkan keadaan Indonesia sekarang. Bisa dilihat Fordem berisikan kalangan intelektual dari ragam latar belakang: kyai, pastur, filsuf, aktivis pro-demokrasi, pengacara, hingga dosen. Ini membuktikan bahwa Fordem dibangun dengan pemikiran yang berbeda dan dialektika atas kebebasan berpikir yang kokoh.
Terlepas dari pengemasan buku yang jauh dari sempurna—kesalahan penulisan diksi yang masih banyak, desain tata letak yang kurang enak di mata, hingga sampul buku yang kurang mengundang—buku perdana dari Virdika Rizky Utama ini memang hadir di waktu yang tepat: kebimbangan 20 tahun pasca reformasi yang belum pernah tuntas dan selesai.
Buku ini mengingatkan kita bahwa Indonesia pernah memiliki barisan intelektual yang dengan berani menantang tiran dan sektarianisme. Munculnya isu agama dan rasial saat ini perlu untuk dilawan bersama, demi menghadirkan wacana Indonesia yang damai, toleran, dan humanis.[]
Judul Buku : Demokrasi dan Toleransi dalam Represi Orde Baru
Penulis : Virdika Rizky Utama
Tahun Terbit : 2018
Penerbit : Penerbit PT Kanisius
Tebal : 184 hal.