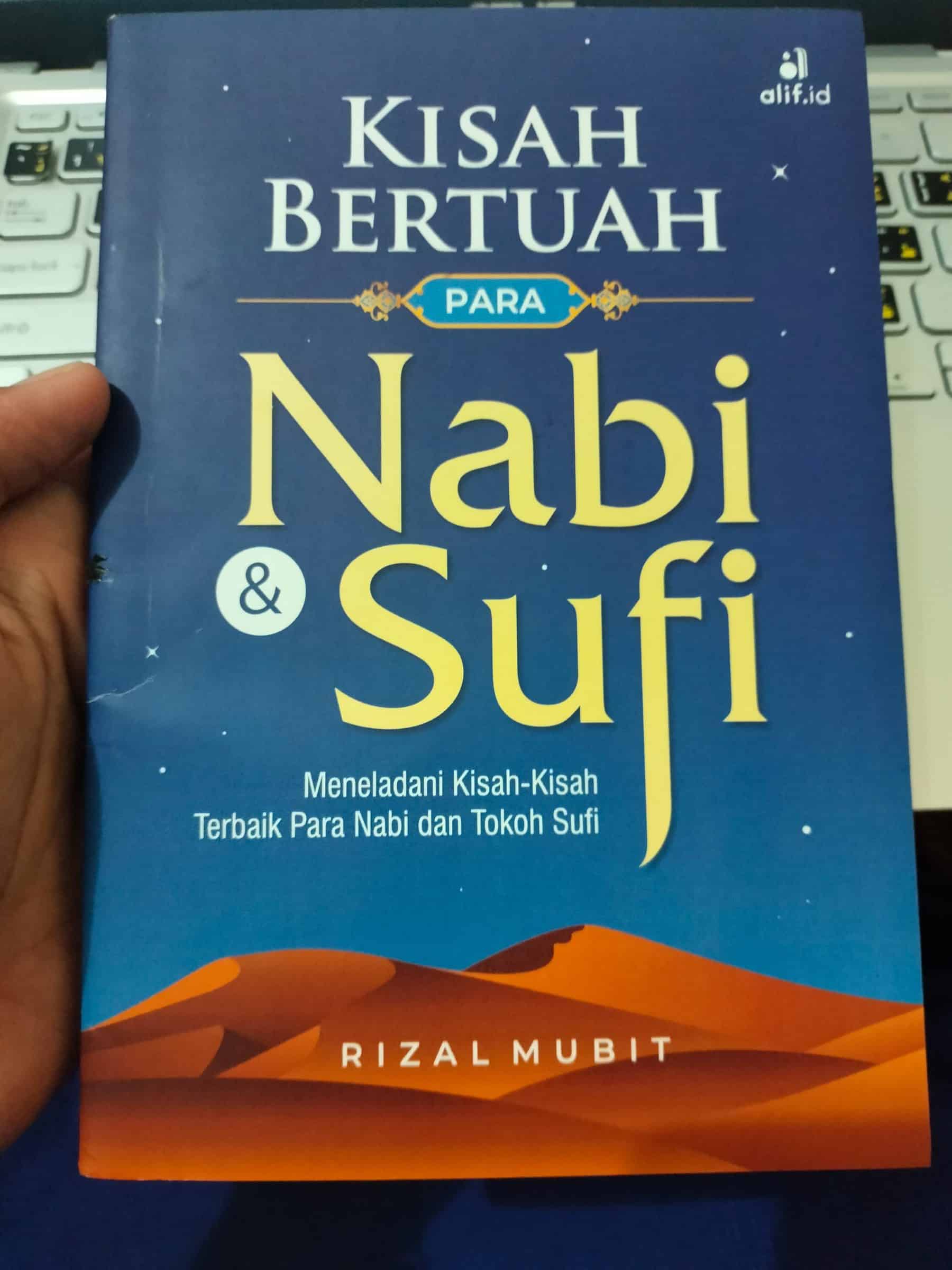Di dalam tulisan saya yang berjudul ‘keluhan ‘global’, rasa bersalah, dan kebenaran absurd media’ saya menjelaskan bahwa rasa bersalah tidak hanya bersumber dari persoalan pribadi yang dialami secara internal, tapi juga dapat dipicu oleh faktor eksternal yaitu ketika seseorang terpapar secara terus menerus oleh berbagai informasi yang kemudian menyudutkan ‘ego state’ seseorang.
Sebenarnya, jika dikelola dengan baik rasa bersalah ini dapat memberikan imbas yang positif bagi seseorang. Karena bahwa kondisi ini adalah kondisi yang normal dan sesungguhnya sangat penting. Beberapa riset membuktikan diantaranya, bahwa rasa bersalah dapat menurunkan tingkat ketidak jujuran akdemis seperti yang dapat ditemukan di dalam riset yang dilakukan oleh Brunell, Staats, Barden & Hupp (2011) di dalam artikelnya yang berjudul ‘narcissism and academic dishonesty : the exhibitionism dimension and the lack of guilt’. Atau, di dalam penelitian yang lain ditemukan bahwa rasa bersalah juga dapat membantu seseorang untuk berkomitmen dalam menjalani suatu bentuk pengobatan (treatment).
Di dalam hal ini, kesadaran untuk menjalani treatment bersumber dari kesadaran dirinya, bukan paksaan atau tekanan dari orang lain seperti yang dapat ditemukan dalam riset yang dilakukan oleh O’Brien & Michael (2017) di dalam artikelnya yeng berjudul ‘an exploration of responsivity among violent offenders : predicting access to treatment, treatment engagement and program completion’.
Mengapa hal ini dapat terjadi ? Nelissen (2012) di dalam artikelnya yang berjudul ‘guilt—induced self—punishment as a sign of remorse’menyebut fenomena ini sebagai ‘the dobby effect’ yaitu kondisi yang muncul di saat seseorang yang mengalami rasa bersalah memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik penyeimbang ketika dia tidak menemukan sasaran dari objek kegelisahannya secara langsung. Nah, ini adalah kondisi dimana seseorang memiliki kesempatan untuk mampu mengelola emosi atas rasa bersalah.
Dalam hal ini ada tiga kemungkinan karakter perilaku yang muncul. Petama adalah self affirmation objective yaitu orang yang cenderung untuk melindungi dan memulihkan integritas diri setelah pelanggaran moral atau pelanggaran interpersonal yang dia temukan atas dirinya. Sebagai solusinya, misalnya dia terlibat dalam kegiatan ritual keagamaan sesuai dengen keyakinannya sebagai strategi pengaturan emosi.
Kedua, social affirmation objective yaitu setelah seseorang merasa telah melakukan pelanggaran dan merasakan rasa bersalah orang mengalami kebutuhan untuk menghindari diri dari pengucilan dari lingkungannya. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan kepada orang lain meskipun tidak selalu harus pada tareget agresi, bahwa mereka memiliki karakteristik yang diinginkan untuk menegaskan nilai sosial mereka sebagai anggota kelompok.
Ketiga, relation affirmation objective yaitu ketika seseroang menyadari kesalahan dan merasa bersalah lalu mengafirmasi hubungannya dengan target yang menjadi sasaran agresif dan secara konsisiten membangun hubungan dan merestorasi fungsi rasa bersalahnya. Sehingga, rasa bersalah dapat menurut secara signifikan.
Rasa Bersalah dan Tindakan Agresif
Namun, rasa bersalah dapat menjadi bentuk tindakan agresif jika individu tidak mampu mengelola emosinya. Seperti yang ditegaskan oleh Nelissen (2012) yang didukung oleh Caprara, Barbaranelli, Pastorelli, Cermak & Rosza (2001) dalam artikelnya yang berjudul ‘facing guilt: role of negative affectivity, need for reparation, and fear of punishment in leading to prosocial behaviour and aggression’, bahwa membangun ikatan sosial yang positif dengan lingkungan menjadi bagian yang sangat penting dalam membantu mereka. Mereka yang tidak mampu beraptasi secara emosional akan cenderung melakukan apa yag disebutnya sebagai ‘self – punishment’ : menghukum diri sendiri.
Dan, jika ketiga bentuk ‘the dobby effect’ tidak dapat diupayakan, Caprara dkk (2001) mengingatkan kita kembali bahwa dalam setiap rasa bersalah selalu ada keinginan untuk memperbaiki diri (self-reparation) di satu sisi dan menghukum diri (self punishment) di sisi yang lain. Kedua hal ini tidak terpisahkan. Dalam hal ini, rasa takut akan hukuman dapat menjadi pencegah agresi (deterent) di satu sisi atau menjadi penyulut agresi (instigator) di sisi yang lain. Terutama jika sumber hukuman itu adalah bersifat ‘divine’ atau ketuhanan.
Caprara dkk (2001) menambahkan bahwa sebagai respon dari rasa frustasi dan untuk menghindari hukuman yang mungkin terjadi maka individu dapat melakuakn manuver untuk memperluas kontrol terhadap hukuman yang mungkin terjadi. Bisa anda bayangkan seseorang yang disadarkan atas dosa dosa yang dilakukannya lalu dibombardir dengan berbagai jenis dosa.
Apa yang akan terjadi? Semakin individu mendapatkan tekanan akan hukuman makan semakin besar kekhawatiran individu akan hukuman tersebut yang memungkinkan kondisi ketidak berfungsian perilaku (dysfunctional behavior) dan ketidak patutan perilaku (maladaptive behaviour) yang dialami indvidu. Hasil akhirnya adalah ‘transgression’ yaitu aktualisasi agresi terhadap objek tertentu sebagai bagian dari fungsi rasa tanggung jawab dengan mendasarkan pada ‘transcendental entity’ (God or fate) menggunakan nilai ketuhanan. Dalam situasi inilah seseorang akhinrya melakukan tindakan bom bunuh diri, atas nama Tuhan-nya.
Peran Agama dalam Tindakan Agresif: ‘The Religious Abuse Effect’
Apa fungsi dari agama? Dalam risetnya terhadap populasi LGBT, Super & Jacobson (2011) di dalam artikelnya yang berjudul ‘religious abuse: implications for transgender individuals’ menjelaskan bahwa agama selalu dianggap sebagai sumber kekuatan dan kesucian paling tinggi. Dia dapat menjadi sumber pembimbing, penyerta dan pendukung bagi seseorang yang berada dalam situasi kecewa, kehilangan arah atau kontrol. Tak hanya itu, agama dapat memberikan efek penyembuh yang dapat menurunkan kecemasan meningkatkan self esteem, dan mendorong integrasi baik sosial bahkan seksual khsusunya dalam identitas agama.
Oleh karena itu dalam kondisi penolakan, dan perasaan bersalah dengan latar belakang agama maka seseorang akan mengalami tekanan psikologis yang dahsyat. Super dan Jacobson (2011) menyebutnya sebagai ‘the effect of religious abuse’. Hal ini muncul terutama ketika kelompok atau pemimpin agama menggunakan kekuatan mereka untuk menekan atau memanipulasi korban atau sasaran mereka dengan keyakinan mereka sendiri dengan kata-kata yang penuh hinaan dan kutukan.
Lalich & McLaren (2020) di dalam artikelnya yang berjudul ‘inside and outcast: multifaceted stigma and redemption in the lives of gay and lesbian Jehovah’s withnesses’ menemukan bahwa individu bahkan dapat mengalami ‘the internalized homophobia’ yang kemudian mengantarkan mereka pada pesoalan yang lain seperti masalah kesehatan mental, penggunaan obat terlarang, dan ide bunuh diri.
Di dalam hal ini, Super dan Jacobson (2011) menemukan bahwa di dalam populasi masyarakat Kristen, pengalaman ditinggalkan oleh gereja akan mengakibatkan seseorang untuk meraskan adanya penolakan dari Tuhan, dari agamanya, dari gerejanya, dari keluarganya dan dari lingkungannya. Mereka merasa diri mereka sebagai pendosa penuh dengan rasa malu dan rasa bersalah.
Pernahkah anda merasa terteror dengan pernyataan pernyataan sebagian pemimpin agama yang membuat anda tertekan secara psikologis? Atau membuat anda galau seketika mempertanyakan kembali prinsip-prinsip yang anda miliki? Atau anda merasa terasing karena cara berpakaian anda tidak cukup agamis bagi kelompok yang lain? Bukankah gambaran seperti dapat dengan mudah kita temui juga di kehidupan kita sehari hari khsusunya melalui media? Berhati-hatilah memberikan nutrisi pada otak anda. Berhati-hatilah memilih penyuluh agama dan berita di media.