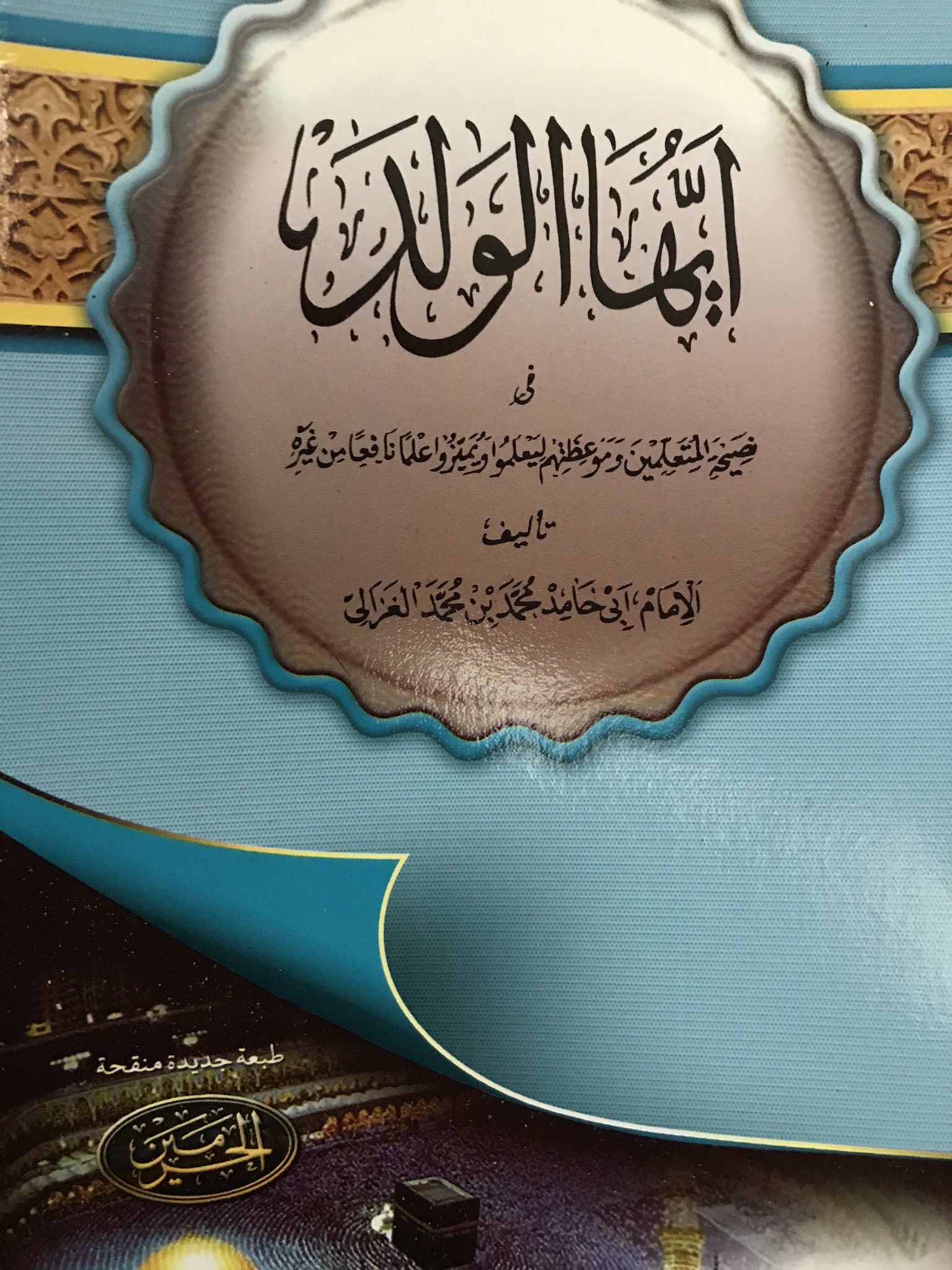Spiritualisme, baik yang berbentuk tasawuf (spiritualitas Islam) maupun kapitayan (spiritualitas yang berbasis budaya-budaya lokal), tak selamanya identik dengan kesalehan individual yang asosial dan cenderung eskapis. Kadang penilaian semacam itu masih muncul, terutama dari kalangan “revolusioner”.
Pada akhir dekade 80-an hingga awal 2000-an, sebagian dari kita—pada aras ideologis— tergila-gila pada wacana-wacana kritis, mulai dari marxisme hingga posstrukturalisme. Dan kita pun, saat itu, bangga menjadi semacam “santri-santri kiri.”
Kita, dengan jiwa yang masih bergelegak, mengakrabi sedikit dunia yang tak kita kenali semasa bocah: lapen, gunung, anjing, kaum pinggiran dengan segala kekelamannya, jalanan, stigma “komunis,” dan bahkan bui.
Sebagian dari kita pun ada yang bahkan sampai tertular sesat pikir kalangan pembaharu yang (barangkali karena usia muda) mencibir doktrin dan praktik-praktik keagamaan atau spiritualitas yang dapat menumpulkan semangat revolusioner: tasawuf dan kapitayan.
Pada tahun 1998, saat orde baru sampai pada titik-nadirnya, banyak pula para pendahulu yang berontak pada pendekatan visionernya swargi Gus Dur yang lebih memilih nguwongke Soeharto dan keluarganya saat orang nomor 1 itu beringsut memudar pengaruh dan wibawanya.
Seperti film Running On Karma (2003), banyak dari kita mencoba untuk keluar dari biara dan ambyur ing kahanan untuk sekedar menyelamatkan nyawa orang lain, meski di akhir film itu kita tahu bahwa Biggie, sang tokoh utama, tak mampu memutus rantai karma dan menghapus samsara. Syaikh Ibn ‘Athaillah, tentang “ketetapan” ini, suatu ketika berkata: “Maa qaadaka syai’un mistlul wahmi.”
Seorang sufi yang pernah berpolemik dengan Ibn Taimiyah itu mewedarkan apa yang kita kenal sebagai utopia (waham) yang tak dapat dijadikan pegangan. Semua bentuk ideologi, baik itu marxisme-komunisme, nasionalisme parasit maupun “Islam” (baca: khilafah Islamiyah), adalah idealitas semata yang tak bakal kita jumpai di dunia ini (Melongok Dari yang Tak Pokok, Heru Harjo Hutomo, http://jalandamai.org).
Barangkali, baru akhir-akhir ini apa yang disebut oleh Lyotard pada dekade 70-an sebagai kematian metanarasi terasa di Indonesia. Banyak orang tampak bosan dengan berbagai narasi-narasi besar.
Sebagaimana hikmah dari ‘Athaillah di atas, yang entah kenapa seperti seturut dengan para posstrukturalis semacam Derrida maupun Michel de Certeau, untuk lebih menitikberatkan pada hal-hal yang kecil tapi kongkrit, pinggiran tapi manusiawi. Kisah masyarakat Dieng tentang Abimanyu yang merupakan “anak jadah” seorang Bima seolah lebih memikat daripada anak Arjuna yang menjadi galur ksatria trah witaradya, puak para raja-raja Jawa.
Baik ‘Athaillah maupun Derrida seolah bersepakat bahwa semua kisah sejarah manusia yang berakhir pilu acap disebabkan oleh dibiarkannya idealitas (waham) menjadi kendali kehidupan manusia. Tentu, hal ini bukanlah sebentuk pesimisme, baik ‘Athaillah maupun Derrida hanya mencoba untuk bersikap realistis.
Mereka memang bukan para pahlawan layaknya Karl Marx ataupun Sayyid Qutub yang sama-sama bersemangat untuk mengubah dunia yang dipandang bobrok. Kerap niat baik seorang anak manusia berbuah muram dan kebengisan.
Sejarah radikalisme dan terorisme yang banyak menghiasi perjalanan manusia selama ini, salah satunya, adalah karena dibiarkannya waham menjajah akal sehat.
Irasionalitas dan kebengisan seorang Hitler merupakan teladan yang bagus perihal orang yang terkena waham. Dan, selama beberapa tahun berkecimpung dalam isu-isu seputar radikalisme dan terorisme, waham itulah yang rupanya juga menjangkiti para ekstrimis dan teroris.
Terkadang orang kerap lupa bahwa kehidupan memiliki logikanya sendiri yang tak selamanya klop dengan logika dan keinginan manusia. Untuk itulah dalam khazanah budaya Jawa orang cenderung memaknai hidup sebagai sebuah perjalanan yang, bagaimana pun, mesti dilalui.
Tapi ibarat perjalanan, tak seyogyanya orang silap dan kandeg (terhenti) di dalamnya, melainkan sekedar mampir ngombe.
Barangkali, dengan pemikiran semacam ini orang akan segera melabelinya sebagai sebentuk eskapisme. Tapi sejatinya, baik ‘Athaillah maupun Derrida, menyediakan ruang bagi pilihan lainnya: moderasi. Tak sekedar untuk tak selalu berlebihan, moderasi memuat pula sebentuk sikap untuk senantiasa realistis.
Tentang sikap realistis ini, penggagas karya yang di masa kini disebut sebagai esai, Charles de Montaigne, mengawali apa yang kemudian digemakan Voltaire: anti-fanatisme.
Montaigne pernah membicarakan hal yang bagi banyak orang adalah hal yang tak penting, yang saya misalkan sebagaimana kentut. Tak sebagaimana para pemikir pada masanya atau masa sebelumnya yang berbicara tentang omong-kosong “kehendak umum” seperti halnya Jean-Jacques Rousseau, yang kemudian diterjemahkan dalam kenyataan secara bengis oleh Maximilien de Robespierre dengan guillotine-nya (alat pemancungan), Montaigne justru melongok pada hal yang bagi banyak orang tak pokok.
Seperti Nietzsche pula pada dasarnya, bahwa di balik niat-niat agung, militansi, dan hal-hal yang tampak besar, terkadang terselip hal-hal yang dianggap kecil tapi secara alamiah justru mendorong niat-niat agung, militansi, dan hal-hal yang tampak besar tersebut, semisal kentut.
Di sinilah Derrida, dan kemudian ‘Athaillah, seperti memilih untuk terlebih dahulu melakukan apa yang oleh orang-orang nusantara dikenal sebagai mulat sarira (mawas diri). Secara sederhana, mulat sarira dapat ditelisik lewat pemeriksaan istilah “aku.”
Orang terkadang menerima secara apa adanya kata-kata atau istilah yang keluar dari mulutnya, seperti tak ada persoalan sendiri di dalamnya. Seumpamanya istilah “aku” di atas, banyak orang secara sekenanya membawanya dalam percakapan sehari-hari: “Aku sedang lapar,” “Aku sudah kenyang” ataupun “Aku mengantuk.”
Tapi ketika disuruh menunjukkan “aku” yang selalu disebut-sebut tersebut banyak orang akan mendamik dadanya atau secara keseluruhan sosoknya, misalnya, “Lha, ini, kan, aku, yang sedang di depanmu.”
Jawaban di atas jelas tak menjawab pertanyaan tentang “aku”. Ketika orang mendamik dadanya atau menunjukkan sosoknya, sebenarnya ia tak sedang menunjukkan “aku”, tapi dadanya si “aku” ataupun sosoknya si “aku”.
Atau pada kalimat yang secara tata bahasa menunjukkan subyek + predikat + obyek + keterangan—bandingkan dengan zikir isim mufrad dalam dunia tasawuf maupun kapitayan yang bagi kalangan ulama wahabi divonis bid’ah. Semisal kalimat yang terus-menerus diulang para penyair hingga para ABG: “Aku cinta kamu.”
Kalimat tersebut jelas problematis bagi nalar yang berpikir. Taruhlah istilah “cinta” yang memualkan, karena terus-menerus diulang sepanjang sejarah manusia. Sebagaimana “aku,” istilah “kamu” pun juga menyisakan banyak persoalan. Mengacu pada apa istilah “kamu” yang tersemat dalam ungkapan memualkan “Aku cinta kamu”?
Umumnya, istilah “kamu” dalam ungkapan memualkan itu merujuk pada kualitas diri: kecantikan, ketampanan, keperkasaan, kecerdasan, kesalehan, dst. Tapi persoalan timbul, seumpamanya ketika kualitas-kualitas diri itu memudar atau bahkan hilang, masihkah ungkapan memualkan itu bermakna?
Dengan kata lain, apa yang sebenarnya diucapkan manusia dalam keseharian dengan membawa-bawa si “aku” ataupun si “kamu” lazimnya selalu mengacu pada kualitas-kualitas diri dan bukannya diri itu sendiri. Pertanyaan tentang “aku,” pada akhirnya, selalu menguap di udara.
Di sinilah kemudian letak pentingnya mulat sarira yang memiliki fungsi praktis sebagai sebentuk moderasi, pemangkasan segala ekstrimisitas yang secara logis memang selalu berujung bunuh diri.
Karena itu, saya kira, radikalisme dan terorisme dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis atas sikap yang tak mau berkaca pada diri sendiri (ngilo githoke dhewe). Pada kasus radikalisme dan terorisme justru yang terjadi adalah sebentuk nandhing sarira (membandingkan diri) yang sudah pasti akan menemukan perbedaan yang sarat ketegangan, polarisasi aku dan kamu, kami dan mereka, secara tak kritis.
Kisah banyak revolusi berdarah di sepanjang sejarah manusia, terlepas dari baik atau buruknya, adalah kisah ekstrimisitas yang tak jarang berujung laiknya Frankenstein yang membunuh Bapaknya sendiri. Dari seorang Montaigne ataupun Derrida, kita belajar tentang sesuatu yang sekilas sepele, kecil dan tak barharga, tapi yang tanpanya hal-hal besar tak akan terbabar.
Hidup itu kentut
Tak peduli Jawa atau Tionghoa
Tak peduli muslim atau Buddha
Semua sama saja
Di mana pun kentut tetaplah kentut
Kenapa mesti ribut?