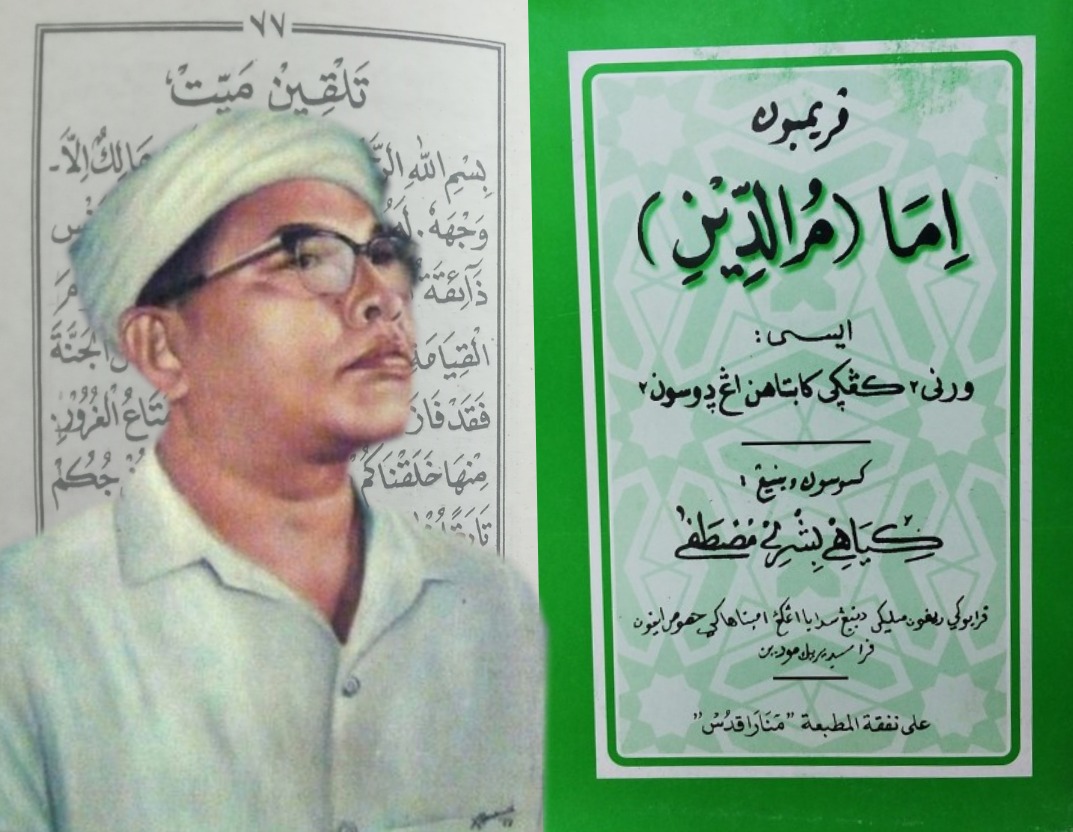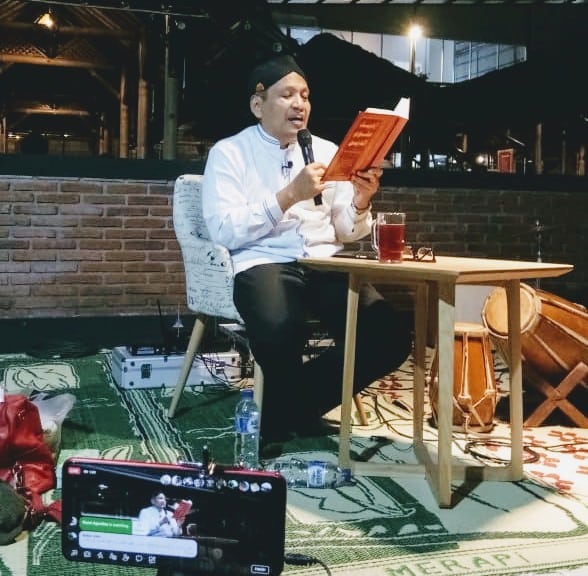
Kita tahu bahwa, filsafat di era al-Ghazali berbanding terbalik dengan filsafat dalam sekarang. Artinya, filsafat sudah mengalami penyempitan makna. Zaman dulu filsafat mencakup segala pengetahuan yang merupakan hasil dari penelitian (penalaran) manusia seperti, fisika, biologi dan lainnya. Ilmu-ilmu yang sekarang kita sebut sebagai sains (science), era al-Ghazali disebut sebagai falsafah atau filsafat. Jelasnya, filasafat adalah suatu bidang kajian yang cakupannya luas sekali. Dalam teori al-Ghazali, filsafat adalah segala ilmu rasional atau dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut “ilmu aqliyyah” yang berdasar pada penalaran rasional murni.
Alih-alih sempit, justru ilmu-ilmu yang dulunya masuk dalam bagian filsafat, sekarang sudah memerdekakan diri (independen). Sikap al-Ghazali kepada filsafat sebetulnya memilah-pilih. Ada bagian-bagian filsafat yang diterima sepenuhnya seperti logika. Al-Ghazali sendiri membagi filsafat dengan enam kategori.
Pertama adalah ilmu yang disebut riyadiyat yaitu ilmu hitung-hitungan (matematika), kedua adalah ilmu mantiqiyat ilmu kaidah berpikir (logika), ketiga adalah tabi’iyat ilmu yang berkaitan dengan masalah atau fenomena kealaman, keempat ilmu ilahiyah ilmu yang terkait dengan masalah ketuhanan, kelima adalah ilmu al-asyasiyat yaitu ilmu politik dan cara mengatur negara, keenam adalah al-akhlaqiah ilmu moralitas. Enam kategori diatas dulu era al-Ghazali adalah garis besar ilmu filsafat.
Karena itu, sekiranya al-Ghazali dianggap membunuh sains dalam dunia Islam jelas itu keliru, justru dalam bagian filsafat yang berkenaan dengan tabi’iyat dan alam fisik al-Ghazali menerima seluruh kesimpulan dalam bidang filsafat yang diajarkan oleh Aristoteles dan para hipokrates, kemudian ptolemeus dalam bidang astronomi. Meskipun, tidak semuanya, ya tapi diterima, karena hal itu adalah ilmu netral yang oleh al-Ghazali orang beriman bisa mempelajari ilmu itu demi kemanfaatan (untuk mengetahuinya).
Hanya saja, disini, yang dipersoalkan al-Ghazali masalah ketuhanan dan keimanan. Al- Ghazali scrutinizing (meneliti dan menguji) dengan seksama kesimpulan-kesimpulan filsafat yang menyangkut aqidah dan ilahiyat. Dalam masalah ilahiyat, al-Ghazali hanya mengkritik filsafat dalam 20 masalah dari sekian masalah ilahiyat. Diantara 20 ada tiga masalah yang serius sekali sehingga sampai pada kesimpulan para filosof itu kafir, karena pandangannya bertentangan dengan aqidah Islam. Kafir disini maknanya adalah pandangan filsafat kontras bertentangan dengan aqidah Islam.
Dalam tiga hal ini, filsafat melawan aqidah dan disitu para filosof kafir. Sementara kalau dalam 17 masalah lainnya terkait masalah ilahiyat, para filosof dianggap al-Ghazali sekedar Bid’ah saja. Jadi kritik al-Ghazali terhadap tubuh filsafat hanya dalam tiga hal saja. Namun, yang demikian ini dianggap membunuh filsafat oleh mereka yang kontra.
Syahdan, para filosof mengakui tentang pandangan mereka bahwa Allah itu tidak tahu tentang juziyyat, dan hanya tahu tentang kulliyat, itu bukan ta’wil. Dalam al-Qur’an disebutkan والله عليم. Lalu bagaimana para filosof itu memaknai ayat ini? Apakah mereka menta’wil? Dengan ambigunya, mereka mengatakan bahwa yang juziyyat harus di ta’wili. Menurutnya, masalah kebangkitan setelah mati, hanyalah teknik agama untuk mendorong orang agar berbuat baik. Karena yang bangkit sesungguhnya adalah ruh atau akal (menurut mereka akal itu abadi).
Kebangkitan akal akan sulit dipahami oleh nalar awam, maka diberikanlah gambaran tentang kebangkitan jasad yang lebih masuk akal. Bagi para filosof, Rasul boleh mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan demi kemaslahatan umat, termasuk meyakini tidak ada kebangkitan tubuh yang ada hanya kebangkitan akal.
Dalam perspektif al-Qur’an, tentu hal ini batil karena menganggap Nabi berbohong. Kedua, mereka batil, karena mencari alasan untuk membenarkan kenapa Nabi boleh berbohong. Lalu bagaimana cara al-Ghazali menerapkannya dalam konteks sekarang? Al-Ghazali membedakan pengetahuan dengan akidah. Pengetahuan (ulumul aqliyah, rasional, empiris, nalar) itu mengandung dua pengertian. Yaitu ilmu itu sendiri yang bersifat faktual dan, kedua adalah ideologi ilmu yang perlu ditelaah secara serius, karena itu bukan menyangkut ilmu.
Ini persis dengan jawaban pengkritik Richards Dawkins, ilmuwan yang mewakili sains modern dan penganut aliran new atheism. Dia mengatakan bahwa, ilmu saja sudah cukup, tidak perlu aqidah dan agama. Para agamawan dan saintis yang beriman mengkritik balik Richard dengan mengatakan bahwa sains yang mengkritik Tuhan itu bukanlah sains. Sains punya wilayah empiris yang bisa diteliti dengan instrumen yang bisa mendeteksi fisik atau indrawi seperti, alam raya yang notabene bisa dilihat.
Seharusnya, mereka tidak bicara di wilayah yang tidak kasat mata karena, hal yang tidak bisa di indrawi dan bukan menjadi kajian mereka. Sains tidak bisa menjangkau wilayah non indrawi. Karena itu, ia tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada atau Tuhan itu ada. Kesimpulan saintis tentang wilayah ilahiyat adalah kesimpulan yang tidak saintifik.
Al-Ghazali mengkritik para filosof yang punya pandangan soal ilahiyat karena, pandangan mereka yang tidak saintifik dan tidak didasarkan pada dalil burhaniyat atau dalil yang kuat, melainkan dalil yang spekulatif. Begitulah seharusnya cara kita memandang pemikiran al-Ghazali dalam masalah aqidah. Kita tidak boleh naif dalam menerima pandangan sains terutama tentang ilahiyat.
Di dalam kitab Al-Munqid min al-Dhalal dan Tahafutul Falasifah, al-Ghazali mewanti-wanti bahwa, ada jebakan dalam belajar ilmu thabi’at atau material. Jangan sampai kita percaya kepada apapun yang ilmuwan sampaikan di bidang itu, hanya karena ilmu mereka luar biasa dalam bidang materi. Karena belum tentu semua pandangannya valid. Termasuk ketika mereka bilang bahwa Tuhan itu tidak ada. Sebab, hal itu bukan wilayah keilmuan mereka yang materialistik. Sepanjang yang dibicarakan para saintis itu adalah fatwa tentang sains, itu tidak menjadi masalah. Sekiranya melintasi wilayah ilahiyyat maka, mereka melewati batas (karena itu adalah wilayahnya aqidah).
Pemikiran yang melewati batas, oleh al-Ghazali dikategorikan sebagai zindiq tingkat satu. Setara di wilayah pemikiran antara mu’tazilah dengan zindiq. Zindiq (Persia/Yunani) sepadan dengan pengertian kafir atau musyrik (Arab pra Islam). Kita tahu bahwa, Filosof Yunani yang masih percaya konsep ilahiyyat seperti Plato dan Aristoteles, meskipun konsepsi mereka tentang Tuhan berbeda dengan akidah Islam. Sedangkan mu’tazilah tetap dianggap sebagai Muslim, karena hanya mentakwil ayat yang tidak bisa dijelaskan dengan makna dhahir. Asy’ariyah juga mentakwil, tetapi dalam wilayah yang terbatas.
Al-Ghazali membuat hierarki spektrum takwil, pertama Filosof semua di ta’wili. Kedua, Mu’tazilah sebagian besar di ta’wili. Ketiga, Asy’ariyah sebagian kecil di tawili. Keempat, Ahlul Hadits paling minimal melakukan ta’wil. Menurut golongan Salafi, mereka tidak melakukan ta’wil sama sekali atau bila kaifa (بلا كيف), tanpa ada tanya, yang ketentuannnya dirumuskan oleh Imam Malik.
Menurut Gus Ulil, sebenarnya semua ini merupakan wujud spektrum keimanan. Yang paling kanan diwakili oleh Ahlul hadits yang paling kiri diwakili oleh para filosof seperti, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Al Farabi dan lainnya. Tetapi pada dasarnya, semua itu masih beriman atau al-ilahiyyun. Di luar itu, mereka adalah para naturalis atau Ath-taabi’iyyuun yang percaya bahwa, yang ada hanyalah nature atau yang kasat mata yang indrawi. Selain itu tidak ada, termasuk Tuhan. Oleh karenanya itu mereka kafir.
Dengan demikian, Plato dan Aristoteles termasuk kelompok yang beriman (Ilahiyyun) karena mereka percaya Tuhan. Hanya saja, akidahnya beda dengan Islam. Alkisah, dalam sejarah Islam tentang Plato. Konon, Khalifah Al-Makmun dari Dinasti Abbasiyah pernah bermimpi bertemu dengan Plato. Hal ini, konon yang mendasari Khalifah Al-Makmun untuk mendirikan “Baitul Hikmah”, salah satu perpustakaan yang berisi banyak sekali buku-buku terjemahan pemikiran Yunani. Selain Al-Makmun, rupa-rupanya masih ada beberapa orang yang juga pernah bermimpi bertemu Plato.
Sudah mafhum, Plato dalam tradisi Islam disebut dengan Al-Mualim Al-Awwal atau guru pertama. Aristoteles adalah Al-Mualim Ats-Tsani atau guru kedua. Sedangkan Ibnu Sina adalah Asy-syaikhu Ar-Rais. Pada dasarnya, al-Ghazali melakukan kritik terhadap filosof semata-mata dalam rangka untuk melindungi aqidah Islam Asy’ariyah ala NU. Jelas, kafir yang disebut di sini adalah filosof atau sekelompok saintis yang melawan akidah Asy’ariyah. Wallahu a’lam bisshawab.