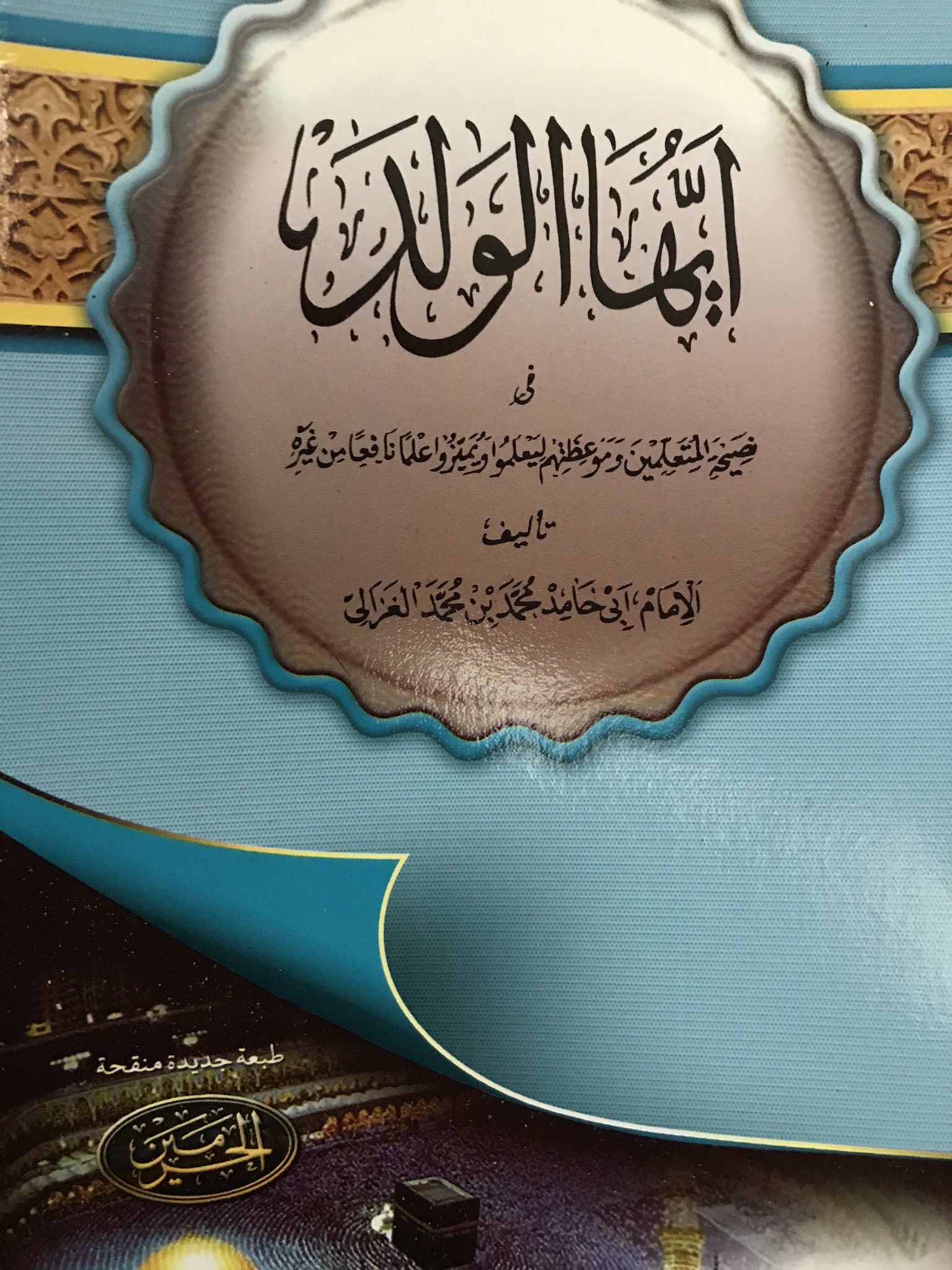Jangan kau katakan: “Semua orang bertikai, untuk apa aku bicara perdamaian?”//Meski engkau satu, bukan seribu, tetaplah nyalakan lenteramu! (Rumi, Divan-e Kabir, bait 1197)
Mantra perdamaian Rumi di atas, terdengar lantang memenuhi ruang pertemuan Perpustakaan Nasional Teheran, Iran. Hanieh Gerayli, membacanya penuh semangat, seolah ingin memenuhi pundi-pundi harapan para hadirin dengan rasa optimis, keindahan untuk perdamian 2019.
Kota Teheran, hari Sabtu terakhir bulan Desember yang cerah, setelah semalaman hujan mengguyur langit Teheran di penghujung tahun 2018. Saya berkesempatan menghadiri seminar bertajuk “Perdamaian Menurut Pandangan Rumi”.

Acara ini digagas oleh salah satu lembaga independen Rumi: Souros Maulana. Selain sastrawan dari Iran, hadir juga para pengkaji Rumi asal negera tetangga seperti: Afganistan, Turki, dan Tajikistan. Negara-negara tersebut dikenal giat dalam mengkaji Rumi dari berbagai perspektif. Tapi juga rentan dengan konflik.
Di tengah kepungan konflik yang semakin membara, acara seperti ini menjadi terasa begitu penting. Hampir Tiap hari saya mendengar dan melihat berita perang yang terus merenggut korban. Dari perang Yaman yang berbuntut krisis kemanusiaan, perang Suriah dan Irak yang ditunggangi isu SARA, hingga konflik di Palestina yang tak kunjung reda.
Belum lagi pertikaian antar kelompok beragama di Pakistan, serta berbagai konflik regional dan dunia yang seolah mengoyak seluruh harapan kita. Lebih-lebih Afganistan yang sudah puluhan tahun dilanda perang saudara, antarsuku dan mazhab internal Islam yang berbeda.
Shokofeh Akbarzadeh, pemerhati Rumi asal Afganistan melukiskan kekerasan yang masih berkecamuk di negaranya. Ia yang tumbuh di jantung peperangan, menyadari bagaimana rasa aman dan harapan semakin tercerabut dalam kehidupan masyarakatnya. Kata perdamaian seolah hanya ilusi dan fatamorgana yang sulit diwujudkan. Tapi, ia memilih untuk tidak menyerah.
Bait-bait Rumi yang ia pelajari bertahun-tahun, seperti memberikan harapan untuk terus optimis dan bergerak.
Sebuah pertanyaan mungkin akan singgah di benak kita, “Mengapa syair-syair Rumi penuh nuansa harapan, cinta, dan perdamaian?”
Hamidreza Tavakoli, sastrawan muda Iran, memetakan situasi sosial-politik pada masa kehidupan Rumi yang justeru penuh gejolak. Invasi yang dilakukan bangsa Mongolia meluluhlantahkan kampung halaman Rumi bersama seluruh kenangan masa kecilnya di Balkh, Khorasan. Di tempat hijrah, ketegangan antara mazhab juga ia rasakan begitu kuat. Belum lagi, sayup-sayup genderang perang salib masih kerap didengungkan.
Di tengah situasi politik corat-marit, alih-laih terseret kubu yang saling bertikai, Rumi memilih menepi bersama bait-bait puisinya. Ia membangun kesadaran masyarakat dengan caranya sendiri. Karena menurut Rumi, perdamaian sejati harus dimulai dalam diri. Sebagaimana diungkapkan dalam buku Masnawi, jilid 6, bait 51-54:
Situasi batinku saling bertentangan
Satu sama lain menjelma amal berlainan
Ketika aku masih saja berperang dengan diriku
Bagaimana mungkin aku bisa berdamai dengan selainku
Tengoklah keriuhan dalam diriku
Satu sama lain saling berjibaku
Jika kau belum juga usai berperang dengan dirimu
Untuk apa kau sibuk berperang dengan selainmu
Tentu maksud bait di atas bukan membuat kita malah apatis dengan persoalan sosial. Justeru, melalui syair-syainya, Rumi mengajak umat untuk memperkuat karakter agar kelak dapat membangun masyarakat yang lebih madani.
Dari penulusuran syair-syair Rumi, ada berbagai faktor yang menyebabkan manusia saling bertikai, seperti ketemakan penguasa, ketidakadilan, dan kesalahpahaman yang seringkali berujung pada sikap fanatik buta.
Dalam buku Masnawi, Rumi banyak memberikan ilustrasi tentang kesalahpahaman ini. Di antaranya cerita gajah dari India juga empat orang yang berebut anggur. Lalu, bagaimana cara Rumi menjembatani berbagai pertikaian itu?
Amir Akrami, sastrawan dan pemikir muda Iran, dalam seminar ini menyampaikan gagasan menarik, visi perdamaian yang diusung Rumi berangkat dari pandangan keagamaannya yang inklusif dan terbuka. Akrami, memberikan dua catatan penting berkaitan dengan pandangan tersebut.
Pertama, untuk bisa duduk setara, kita perlu menghormati serta mengakui secara tulus segala perbedaan keyakinan keagamaan, baik perbedaan mazhab maupun agama. Rumi, dalam banyak syairnya mengajak kita untuk belajar menerima perbedaan itu.
Ada banyak tangga tersembunyi di dunia
Tahap demi tahap menuju jagat angkasa
Setiap kelompok adalah tangga
Setiap cara adalah jalan menujuNya
(Masnawi, jilid 5, bait 2556 dan 2557)
Kedua, pandangan Rumi ini tidak berhenti hanya pada memahami perbedaan. Tapi, Rumi juga menawarkan ruang yang dapat menjadi irisan dari berbagai mazhab, bahkan agama yang berbeda. Menurut Rumi, dimensi tasawuf, bisa menjadi titik berangkat untuk memahami kesatuan entitas agama-agama.
Lampu-lampu beragam bentuk
Namun cahayanya adalah Satu
Saat kau lihat lampu dengan teliti
Kau akan temukan esensi
(Masnawi, jilid 3, bait 1255 dan 1257)
Sepuluh lampu dalam ruangan yang sama
Masing-masing berbeda bentuk dan warna
Jika kau fokuskan pada cahaya
Lampu-lampu itu tiada berbeda
(Masnawi, jilid 1, bait 678-679)
Dalam dua puisi di atas, Rumi memberikan ilustrasi menarik, aneka lampu mewakili berbagai bentuk formal agama, sedangkan cahaya menggambarkan sisi batin sebuah agama.
Di tengah segala perbedaan agama-agama yang tampak secara lahiriah, Rumi meyakini ada dimensi batiniah yang bisa mempersatukan. Dari sinilah, puisi-puisi sufistik Rumi menemukan kontekstualisasi dalam mendamaikan berbagi konflik keagamaan.
Menurut Rumi, untuk sampai di titik ini, manusia memang butuh perjalanan panjang, yang dimulai dari mendamaikan dua sisi pertentangan dalam diri.