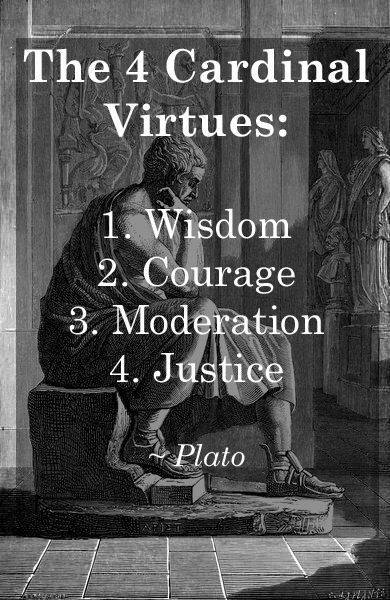
Minggu-minggu ini, saya amat menikmati “Ngaji Ihya'” yang saya ampu setiap minggu, baik melalui Facebook atau Kopdar di mana saya bertemu dengan audien secara langsung di sejumlah daerah. Saya menikmati, karena pembahasan kitab Ihya’ yang sedang saya baca saat ini sedang mengulas tema penting — soal akhlak. Saya sangat menikmati ulasan filsafat etika dalam gagasan Imam Ghazali ini.
Pembahasan Imam Ghazali mengenai tema ini sangat mendalam, sistematis, dengan pendekatan yang dengan jelas menampakkan keakraban imam besar ini dengan filsafat etika yang digeluti oleh para filsuf muslim besar seperti Ibn Sina, Al-Farabi, Abu Bakr al-Razi, dll.
Saya mulai dengan definisi Imam Ghazali tentang akhlak. Beliau mentakrifkannya sebagai: kondisi kejiwaan yang permanen (dalam teks Arab-nya: hai’atun li al-nafsi rasikhatun), dan keadaan ini memungkinkan seseorang melakukan suatu tindakan tertentu dengan mudah, alamiah, tanpa dipaksa, atau dibuat-buat (artifisial).
Seseorang yang berakhlak dermawan atau pelit, misalnya, kedua sifat itu menetap pada orang tersebut, sehingga tindakan kedermawanan atau kepelitan keluar dari dirinya, dengan mudah, tanpa dipaksa-paksa. Akhlak membuat suatu tindakan nampak alamiah, normal, tanpa ada kesan keterpaksaan di dalamnya.
Jika seseorang menjadi dermawan mendadak karena kondisi tertentu (misalnya karena menjelang Pilpres atau Pileg), tetapi setelah itu kemudian ia menjadi pelit kembali, maka tindakan kedermawanan pada orang tersebut tidaklah terbit dari kondisi kejiwaan yang permanen. Kedermawanan pada orang itu, dengan demikian, tak bisa disebut sebagai akhlak.
Dengan kata lain, sesuatu disebut sebagai akhlak manakala ia telah melekat pada struktur kejiwaan seseorang, sehingga menyerupai sebuah tabiat atau kebiasaan. Cak Nur pernah menyebut akhlak sebagai second nature, tabiat kedua yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama.
Dalam pandangan al-Ghazali, akhlak bukanlah sesuatu yang secara alamiah ada pada seseorang. Akhlak adalah sesuatu yang bisa diperoleh seseorang melalui sebuah latihan — atau riyadlah dalam bahasa Imam Ghazali.
Salah satu gagasan penting Imam Ghazali adalah kemungkinan akhlak untuk berubah (taghyirul akhlaq), melalui sebuah latihan yang sabar dan konsisten. Ia serupa dengan sejumlah kecakapan pada seseorang yang bisa diperoleh melalui sebuah latihan pelan-pelan, misalnya kecakapan bermain bola.
Kecakapan main bola bisa “ditanamkan” pada seseorang yang memang memiliki bakat bermain bola, melalui sebuah “training”. Latihan ini akan membentuk apa yang oleh para filsuf etika Muslim seperti Ibn Miskawayh (w. 1030 M) disebut sebagai “malakah”.
Malakah adalah kecakapan (skill) yang melekat sehingga menyerupai suatu “property”, hak milik (ada keserupaan akar kata antara istilah malakah dan “milk” yang artinya hak milik).
Dalam pandangan al-Ghazali, fondasi akhlak adalah dua daya atau “quwwah”, force, yang ada pada manusia: yaitu daya syahwah dan daya ghadlab.
Syahwah adalah daya yang secara alamiah ada pada semua manusia. Melalui daya ini seseorang memiliki hasrat akan sesuatu; misalnya hasrat untuk mengonsumsi makanan atau minuman.
Sementara ghadlab (marah) adalah daya yang melahirkan pada diri manusia apa yang oleh Imam Ghazali disebut sebagai “hamiyyah”, atau semangat, passion, motivasi yang kuat untuk melakukan sesuatu.
Teman saya dari Pati, Habib Anis Sholeh Ba’asyin, mempunyai observasi yang menarik tentang dua daya ini. Menurut dia, karakter syahwah adalah “menyerap sesuatu ke dalam diri manusia”. Sementara karakter ghadlab (marah) adalah “mengeluarkan sesuatu ke luar diri manusia.”
Pada dirinya sendiri, syahwat dan marah bukanlah hal yang jelek, negatif. Menurut al-Ghazali, baik syahwat dan gadlab adalah daya-daya yang secara niscaya ada pada semua manusia, dan diciptakan oleh Tuhan karena tujuan tertentu (khuliqat li fa’idatin).
Akhlak yang baik muncul pada diri seseorang manakala ia berhasil mengendalikan dua daya itu agar tak terjatuh pada dua titik ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah apa yang oleh al-Ghazali disebut dengan “ifrath”, atau ekstrim kanan, berlebihan — esktrim surplus.
Ekstrim yang kedua adalah “tafrith”, yaitu ekstrim kiri, berlebihan karena defisit, kekurangan. Seseorang menjadi berakhlak jika ia bisa mengendalikan dengan AKAL-nya kedua daya tadi — syahwat dan marah.
Inti teori akhlak ala Imam Ghazali adalah ide tentang tengah-tengah ini (al-wasath, al-i’tidal, al-tawazun). Akhlak menjadi hilang manakala terjadi ketiadaan keseimbangan. Dengan kata lain, setiap kecenderungan ekstrim jelas berlawanan dengan, sebut saja, “ke-etika-an”, ke-akhlak-an.
Syahwat yang “njomplang” ke kanan (ifrath), akan melahirkan sikap-sikap destruktif seperti israf, berlebihan dalam mengonsumsi sesuatu. Sementara syahwat yang terlalu condong ke kiri (tafrith) akan melahirkan sikap “taqtir“, thrift/frugality, medhit (bahasa Jawa: pelit), dsb.
Seseorang disebut berakhlak jika ia berhasil menyeimbangkan diri di antara dua titik ekstrim tersebut. Sikap yang muncul dari keseimbangan itu adalah apa yang oleh Imam Ghazali disebut dengan sakha‘ atau kedermawanan.
Begitu juga dalam hubungannya dengan daya ghadlab atau marah. Daya ini akan melahirkan akhlak yang baik jika bisa diseimbangkan, tidak “doyong” terlalu berlebihan ke kanan atau ke kiri.
Daya ghadlab yang terlalu doyong ke kanan (=marah yang berlebihan) akan melahirkan tindakan-tindakan agresif, menyerang, yang destruktif, merusak — apa yang oleh al-Ghazali disebut dengan “tahawwur“.
Sebaliknya, jika daya ghadlab ini doyong berlebihan ke kiri (mengalami kondisi kekurangan, defisit, yang berlebihan), yang muncul dari sana adalah sikap “jubnun”, ketakutan, kepengecutan, kekhawatiran yang eksesif terhadap sesuatu.
Sebagaimana sikap agresif bisa destruktif, sikap takut yang berlebihan juga bisa merusak mental seseorang. Kondisi akhlak yang sehat tercipta manakala ada titik keseimbangan antara dua sikap ekstrem itu.
Inti teori akhlak dalam pandangan al-Ghazali, dengan demikian, adalah kemampun melakukan pengendalian diri, self-restrain; tidak membiarkan diri terserap ke dalam luapan jiwa yang berkobrar-kobar pada suatu saat. Syahwat dan gadlab bisa meluap seperti banjir bandang yang susah dikontrol. Saat “banjir” ini terjadi, biasanya akhlak menjauh dari seseorang.
Pandangan al-Ghazali tentang akhlak ini memang berseberangan dengan karakter zaman kita di mana semangat yang menonjol adalah “menenggak semaksimal mungkin kenikmatan sesaat”. Kapitalisme modern menciptakan “kelimpahan material” karena mesin-mesin modern yang mampu memproduksi barang secara massal.
Dalam situasi yang serba bekelimpahan seperti ini, godaan untuk “meluapkan syahwat konsumsi”, juga godaan untuk menikmati “the joy of consumption”, kelezatan mengonsumsi segala hal secara kebablasan, sangatlah besar.
Teori akhlak al-Ghazali bisa kita pandang sebagai kritik atas kecenderungan-kecenderungan yang berlebihan (ekstrimisme dalam pengertian yang luas) yang menjadi karakter zaman kita sekarang.















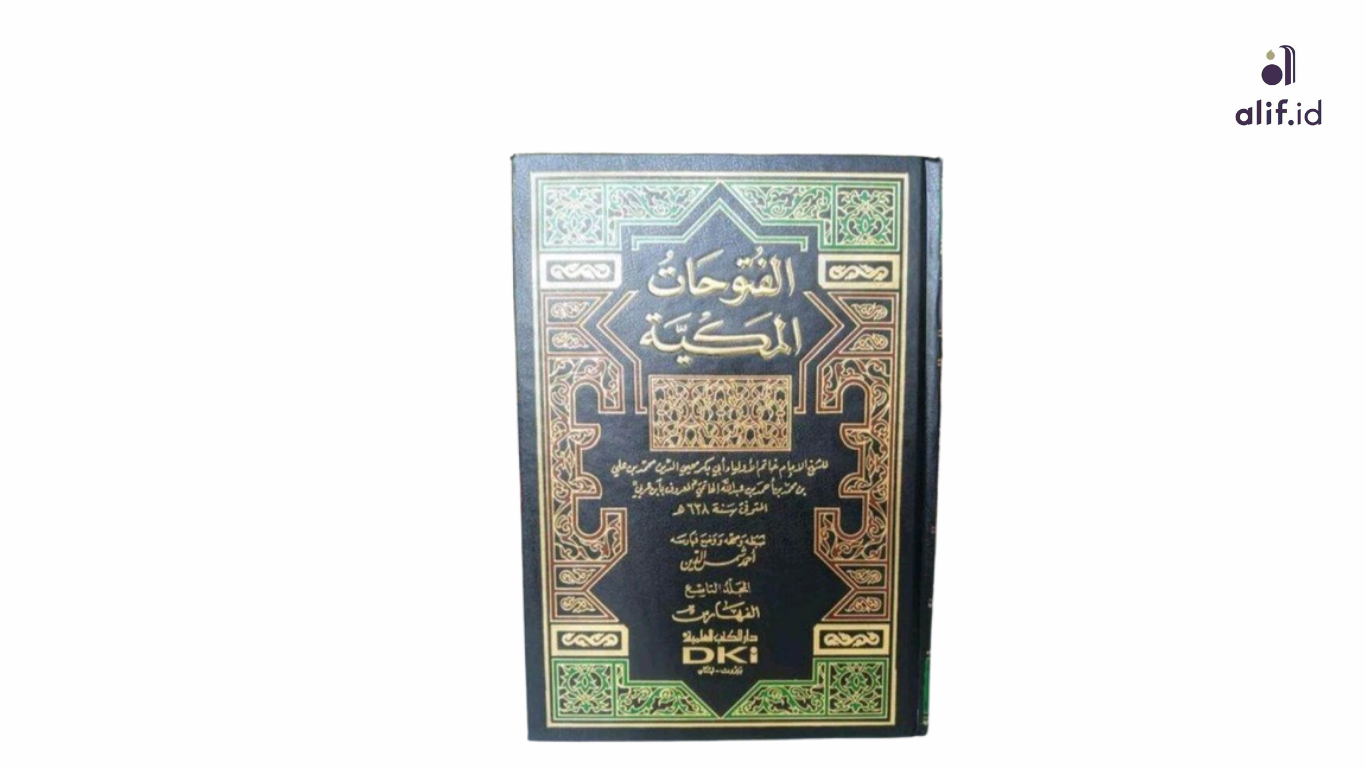




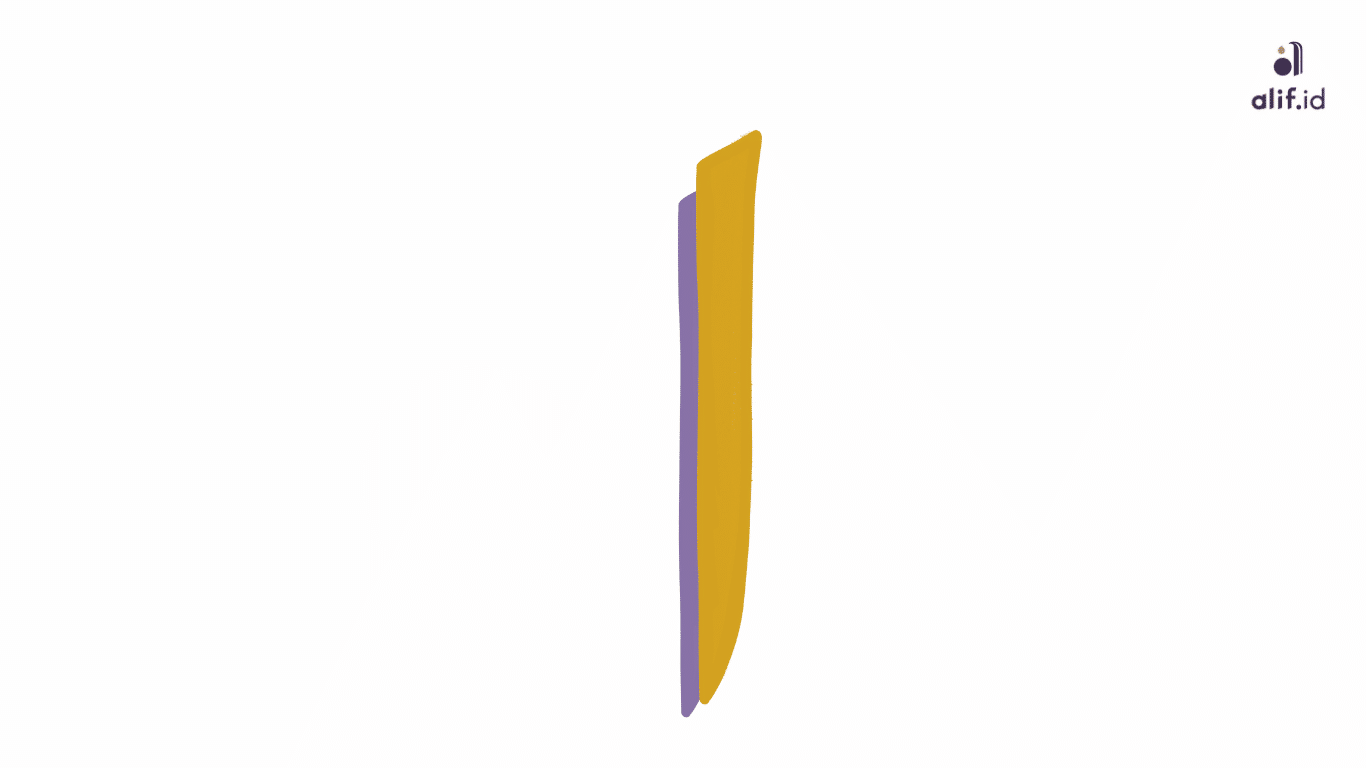
menyimak tulisan Al Ghazali tentang Akhlak menimbulkan beberapa pertanyaan dibenak saya. pertama, dengan menampilkan ilustrasi fisuf Yunani, Plato, apakah penulis bermaksud ingin mengatakan bahwa Al Imam Al Ghazali mengikuti alur pikir Plato? atau konsep akhlaknya Al Imam Al Ghazali itu sama dengan konsep etikanya Plato? Kedua, apakah akhlak itu sama dengan adab? dengan demikian orang yang tidak beradab berarti orang yang tidak berakhlak. ketiga, apakah akhlak seseoang juga dipengaruhi oleh faktor keturunan? sebab dalam tradisi islam juga ada semacam pengangungan terhadap nasab, kalau tradisi jawa ada istilah bebet bibit. syukron!