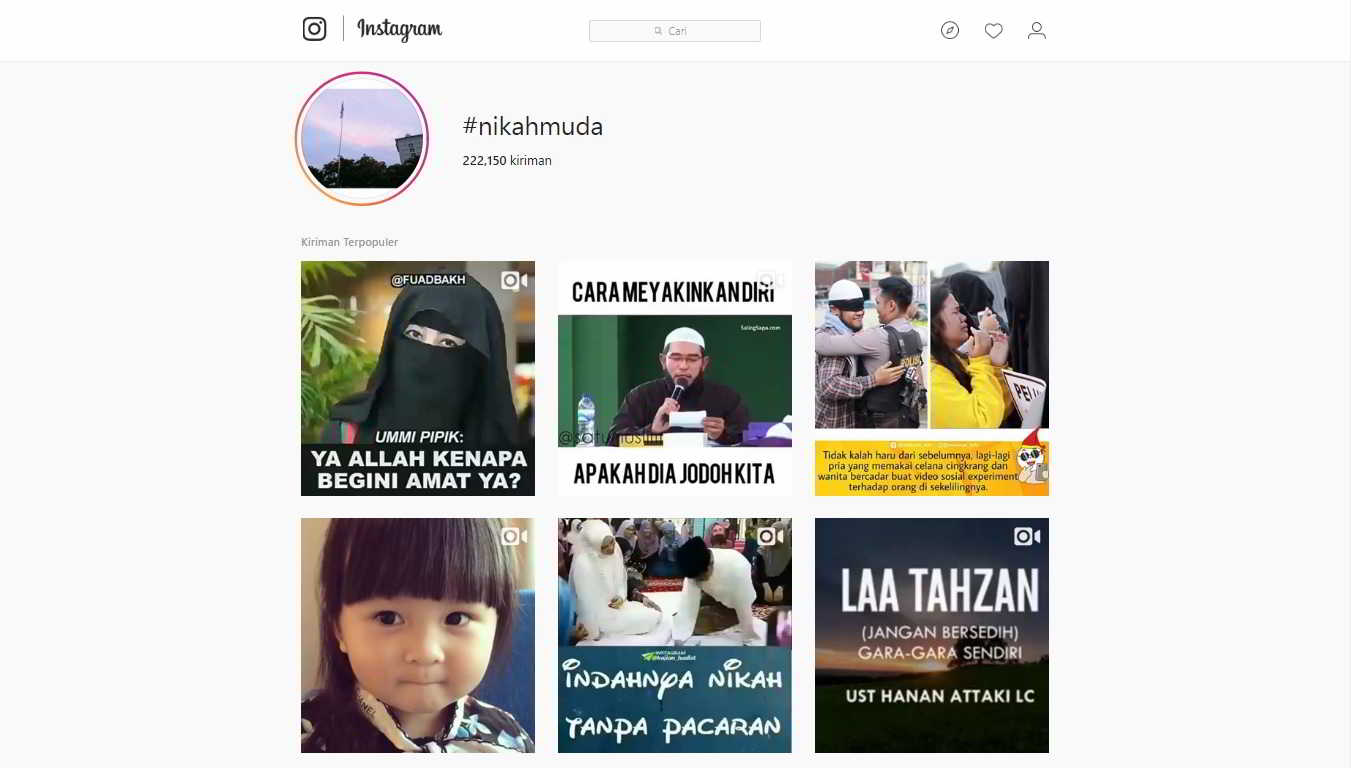Kisah Sinta Nuriyah: Cinta, Toleransi Agama hingga Sahur Bersama

Ketika perempuan berkerudung itu ditanya oleh media Amerika Serikat, The New York Times, pada 2017 mengenai apakah kalangan muslim moderat di Indonesia dapat membalikkan gelombang fundamentalisme Islam, dia menyodorkan jawab nan menyiratkan kecemasan.
Menurutnya, "perjuangan kita kini lebih berat" ketimbang saat melawan kekuatan kolonial dan imperial, "karena yang kita hadapi bukanlah orang asing, melainkan bangsa sendiri".
Setahun setelah pernyataan tersebut terapung, kami menyambanginya Mei tahun lalu ke kediamannya di Ciganjur, Jakarta Selatan, untuk menanyakan perkara yang sama.
Di atas kursi roda elektrik--dalam naungan ruang berhawa sejuk yang disesaki cendera mata--perempuan berusia 70 itu kini menyahut dengan nada positif.
"(Saya) masih optimistis" dengan kain keberagaman Indonesia. Soalnya, karakter orang-orang Indonesia "sebenarnya baik. Kalau diajak secara baik-baik (ihwal) kerukunan, persaudaraan, Insya Allah mereka bisa," ujarnya.
Lagipula, dia melanjutkan, "Tuhan bersama kita".
Ekspresi sedemikian muskil diproduksi oleh insan berkarakter lembek. Rekam jejak Sinta Nuriyah Wahid, begitu nama sosok yang tengah dibicarakan ini, persis memamerkan ketinggian integritasnya.
Sebagian kecil afirmasi atas kekukuhan persona itu diimpor dari media internasional. Pada 2017, The New York Times menabalkannya sebagai satu dari 11 perempuan berpengaruh dunia yang dianggap telah melakukan "hal-hal luar biasa".
Tahun ini, giliran Time mendudukkannya dalam lis 100 manusia paling berpengaruh sejagat pada kategori "Ikon" bersama Jennifer Lopez dan Rihanna, untuk menyebut sedikit saja nama.
Time menilai Sinta Nuriyah--yang duduk di kursi roda sejak mengalami kecelakaan mobil pada awal dekade 1990-an--"pantang mundur" menjaga kerukunan beragama, satu kondisi yang dia ibaratkan sebagai kebun bunga.
"Di dalam (kebun itu) ada mawar, melati, anggrek, asoka. Semuanya cantik. Tak satu pun bisa memaksa mawar untuk menjadi melati, atau anggrek menjadi asoka," ujarnya seperti ditulis Mona Eltahawy.
Sesobek diri Sinta Nuriyah yang mengupayakan kerukunan itu melekat pada kegiatan sahur keliling Ramadan. Aktivitas yang ditelurkan pada ujung milenium kedua itu tergolong out of the box karena melibatkan komunitas lintas agama.
"Kita mencoba mengundang yang Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Setelah bertemu, mereka senang karena merasa diwongke, merasa dianggap," katanya.
Awalnya, kegiatan itu merangkul "10 komponen yang ada di masyarakat". Sasarannya, "kaum duafa", yakni warga yang status ekonomi dan sosialnya lemah. Posisi mereka hampir selalu dipinggirkan.
"Saya membayangkan bagaimana mereka menyiapkan sahurnya, kalau pengin puasa dengan baik. Lalu saya membayangkan tukang-tukang becak kalau malam seringkali tidur meringkuk di becaknya. Kalau seperti itu kan, ya, kasihan banget," ujarnya.
Jakarta menjadi kota pelopor sahur keliling. Perhentian pertama persis di muka Pasar Rumput, Jakarta Selatan.
Dari situ, Sinta Nuriyah menjamah lokasi lain seperti "kolong jembatan layang menuju Tanjung Priok, di dekat terminal, dekat stasiun kereta api," di area Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).
Namun, setahun usai suaminya, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, digulingkan dari kursi kepresidenan pada 2001, sahur keliling bergerak ke wilayah lain. Surabaya menjadi kota pertama di luar Jabodetabek yang mewadahi kegiatan tersebut. Ikut membantunya saat itu, Yosef Eko Budi Susilo, sosok yang sekarang menjabat Vikaris Jenderal Keuskupan Surabaya.
"Pertama acara itu kita lakukan, yang menemani saya itu keuskupan (Surabaya) bersama Romo Eko, dan Matakin," kata Sinta Nuriyah. Matakin disebut di situ kependekan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. "Romo Eko itu setiap minggu keliling ngasih makanan untuk kaum duafa, untuk mereka sahur, meski enggak ada saya."
Sinta Nuriyah tak mau sahur keliling cuma jadi medium berbagi pangan belaka. Bayangan terbesarnya, kegiatan itu dapat membuka kesempatan bagi manusia marginal--kelompok yang menurutnya "tidak pernah disapa" dan "dilirik"--untuk membagikan perasaan terpendamnya. Tujuan itu berhasil meski di awal-awal lebih banyak mengungkap problem ekonomi.
"Jangan diperlakukan apa pun, diam saja. Pasrah aja disuruh begini-begini. Kalau kita ajarin mereka ngomong, mereka akan berani menyampaikan keluhan. Mereka juga memahami situasi bangsa dan negara. Sedikit demi sedikit, (masalah yang diutarakan) berkembang," ujarnya.
Sudah begitu, Sinta Nuriyah pelan-pelan menanamkan intisari perintah puasa, menggeret peserta sahur keliling untuk mulai mengamalkan agama hingga menukik ke substansinya.
"Mungkin kan mereka sudah pernah dengar waktu pengajian (mengenai perintah puasa). Tapi, kan lewat saja. Kita mengingatkan kepada mereka agar puasa kita itu diterima oleh Allah", supaya tidak termasuk golongan yang "dikatakan oleh Nabi (Muhammad): banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga," katanya.
Setelah biasa mengajak peserta sahur keliling untuk memahami hakikat puasa, lalu Sinta Nuriyah mulai menjangkitkan ide keberagaman--yang seturut hematnya merupakan "inti Bhinneka Tunggal Ika"--yakni "saling toleran, saling menolong, dan sebagainya".
Menularkan Kesetaraan Gender
Sobekan lain pribadi Sinta Nuriyah menempel pada Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan PUAN Amal Hayati. Serpih dirinya pada dua lembaga itu agaknya berakar pada masa ketika dia belajar di pesantren dan Program Kajian Wanita Universitas Indonesia--sekarang Kajian Gender.
Sinta Nuriyah menginisiasi PUAN pada Juli 2000, tiga tahun setelah membidani kelahiran Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) pada 1997.
"PUAN itu (akronim) Pesantren untuk Pemberdayaan Perempuan. Amal artinya harapan. Hayati artinya hidupku," ujar Sinta Nuriyah.
PUAN Amal Hayati bergerak dalam kasus-kasus yang di antaranya melibatkan kekerasan terhadap perempuan. Dalam bergiat, lembaga tersebut menjadikan pesantren sebagai basis gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
Pasalnya sederhana: kiai atau pengasuh pesantren berpengaruh kuat di masyarakat. Jika mereka menerima, perjalanan dakwahnya akan selalu menjinjing misi sama dengan PUAN Amal Hayati.
"Kita mulai mencoba masuk pesantren untuk memberikan pencerahan kepada para tokoh agama di pesantren, para pengasuh pesantren, tentang masalah keadilan gender," katanya.
Sementara, titik berat FK3 adalah melakukan kritik sekaligus tafsir ulang atas kitab kuning yang cenderung bias gender. Satu produknya berjudul Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab Uqudul Lujjayn.
Terbitan yang dianggap kontroversial itu membongkar Uqudul Lujjayn, bacaan beken di lingkungan pesantren, meski bukan buku rujukan utama.
"Itu kitab tentang hubungan suami-istri. Di situ, di dalam kitab itu, dijelaskan penindasan kepada perempuan betul-betul. Perempuan harus melayani suami dengan sedemikian rupa. Apa-apa harus pamit, harus segala macam," ujar Sinta Nuriyah sedikit menyingkapkan kandungan buku.
Tafsir ulang atas karya Nawawi al-Bantani, seorang ulama abad ke-19 asal Indonesia yang lantas mengajar dan berdomisili di Arab Saudi, tersebut diupayakan dengan cara mencari tandingan dari "ayat-ayat dan penjelasan-penjelasan" terpacak.
Prosesnya tidak mudah. Dan anehnya, Sinta Nuriyah bilang para kiai senior justru sanggup menerima hasil reinterpretasi tim FK3. Menurutnya, itu mungkin terjadi "karena bacaan (para kiai sepuh itu) kitab-kitab (rujukan) yang besar dan tebal".
Pihak yang berdiri pada posisi berontak, "yang melakukan perlawanan," ujarnya, malah "ustaz-ustaz muda". Kata dia, sikap itu bisa jadi tercungkil karena mereka merasa "kenyamanannya terancam dengan adanya reinterpretasi bahwa suami-istri setara".
Demi menebalkan argumentasi, Sinta Nuriyah pun di depan kami lancar menukil potongan firman Tuhan dari Alquran mengenai relasi 'ke-saling-an' suami-istri. "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna," katanya saat melafalkan bagian ayat 187 surat Al-Baqarah; mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun pakaian bagi mereka.
Melalui sepak terjangnya di dunia pemikiran dan aktivisme pada dasawarsa 1990-an, Sinta Nuriyah tergolong sebagai tokoh perempuan gelombang pertama dari Nahdlatul Ulama (NU), organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yang aktif menyuarakan wacana gender serta agama.
Dia tidak sendirian. Berdiri sejajar dengannya adalah Siti Musdah Mulia, penerima Yap Thiam Hien 2008. (Generasi berikut yang patut disebut di antaranya Farha Ciciek dan Neng Dara Affiah).
Padahal, kesadaran Sinta Nuriyah mengenai ketidakadilan gender baru bersemi saat dia menempuh studi di Program Kajian Wanita awal 1990-an. Meski begitu, pertanyaan mengenai ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan sesungguhnya sudah muncul waktu dia masih menjadi santri di usia belasan.
"Karena masih kecil, (pertanyaan mengenai ketimpangan) hilang begitu saja," katanya.
"Neng geulis."
"Segala sesuatu urusan rumah tangga itu urusanmu. Aku yang bagian keluar," begitu Sinta Nuriyah mengingat perkataan suaminya, Gus Dur--Presiden Indonesia 1999-2001 dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 1984-1999--saat keduanya membicarakan urusan domestik.
Apa pun yang Sinta Nuriyah lakukan, "Mas Dur tidak pernah komplain, tidak pernah menegur. Percaya 100 persen," ujarnya.
Ruang sedemikian telah terbangun sejak masa awal perkawinan. Pasangan itu luwes berbagi tugas rumah tangga; hal yang acap kali dipandang merendahkan martabat laki-laki. Sang suami pun mengambil pembagian tugas itu dengan pikiran sadar dan hati ringan.
Jalan yang dipilih itu mewarnai hidup baru mereka yang tak terisi hak-hak istimewa, walau pada paruh awal dekade 1970-an, Gus Dur mendapat pekerjaan di LP3ES dan tekun berulang-alik Jombang-Jakarta.
Honorarium yang diterima sang suami sebagai imbalan atas tulisan-tulisan dan ceramahnya di hadapan khalayak tak sanggup menutupi biaya hidup keluarga. Menurut penulis Biografi Gus Dur, Greg Barton, keluarga kecil ini miskin bahkan jika diukur dengan standar waktu itu yang merekam sedikit saja orang kaya.
"Baju anak-anak, saya sendiri yang motong. Beli empat meter, jadi empat (pakaian). Coba kalau beli jadi, cuma dapat satu. Bahkan, sampai motong rambutnya Gus Dur. Saya yang motong," katanya mengenang.
Padahal, Sinta Nuriyah--seorang lulusan Fakultas Syariah--ikut menyumbang pemasukan dengan bekerja sebagai pengajar honorer di Universitas Hasyim Asy'ari dan Universitas Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur. Sialnya, katanya, "gaji habis hanya untuk ongkos kendaraan".
Dia lalu memutuskan berbuat sesuatu demi menutupi tekanan finansial. Jalan yang diambil, berjualan makanan. Sinta Nuriyah dan Gus Dur memilih berdagang es lilin dan kacang kulit yang telah disangrai dalam pasir panas.
"Harus dihitung berapa biji satu isi kantong. Kalau kelebihan, kita rugi," ujarnya mengenai jumlah kacang dalam tiap bungkus.
Meski melakoni kesusahan seperti itu, Sinta Nuriyah merasa kebersamaan dengan Kiai Abdurrahman Wahid "sudah jodoh": situasi yang mulanya bertolak dari persinggungan di ruang kelas saat Sinta Nuriyah menjadi murid Gus Dur di Madrasah Mu'allimat, Jombang, paruh awal dekade 1960-an.
"Kalau masuk di kelas, (Gus Dur) suka nyanyi "neng geulis". Caper. Lagu Himne "Syukur" yang ngajarin juga Gus Dur," ujar Sinta Nuriyah. "Itu biasanya kalau pagi atau siang, Gus Dur datang ke rumah saya main catur dengan ayah saya. Nanti kira-kira kalau ayah saya kalah kali, ya, (dia) menyampaikan keinginannya untuk menjadikan saya sebagai istrinya."
Pinangan tersebut disampaikan oleh sang ayah kepada sang ibu. Sang ibu menyampaikan kepada sang nenek. Sang nenek menyampaikan kepada Sinta Nuriyah. "Karena saya tidak ditodong langsung (oleh Gus Dur), saya berani mengatakan enggak mau," kata Sinta Nuriyah.
Gus Dur pun mengulangi proses serupa hingga tiba hari saat penggila sepak bola itu beroleh beasiswa sekolah ke Mesir. Gus Dur lalu menulis surat berisi lamaran kepada Sinta Nuriyah. Kurirnya seorang santri perempuan. Jawaban ditunggu hari itu juga, dengan menyisakan dua pilihan: ya atau tidak.
Sinta Nuriyah terjepit dilema. Di satu sisi, Gus Dur gurunya. Di sisi lain, dia belum memikirkan pernikahan.
Dilanda kegugupan, secarik surat balasan ditulis. "Jodoh itu bagian hidup dan mati," ujar Sinta Nuriyah mengenang surat itu, "yang tahu cuma Tuhan. Kalau kita memang berjodoh, sekalipun kita berjauhan, kita akan bisa bertemu. Tapi, kalau bukan jodoh, sekalipun berdekatan, kita juga tidak bisa bersatu".
Surat balasan itu mungkin jadi bekal bagi Gus Dur selama mengais ilmu dan pengalaman di luar negeri. Surat yang menjadi bibit korespondensi keduanya. Dan demi membangkitkan semangat Gus Dur, Sinta Nuriyah mensyaratkan hal khusus kepada sang guru.
"Kalau menulis surat kepada saya, harus tulisan sendiri, dan memakai bahasa Jawa," katanya mengingat pesan kepada Gus Dur. "Dengan begitu, surat itu asli, enggak bisa dimanipulasi oleh orang lain. Romantis, ya?"
Dengan bahasa Jawa pula, berpuluh bulan kemudian, Sinta Nuriyah akhirnya membuka pintu hatinya lebar-lebar bagi laki-laki yang tak kenal berputus asa mengirimkan sinyal cinta itu.
"Panjenengan wis kasil nuwuhake wijining katresnan ono ing sajeroning atiku," ujar Sinta Nuriyah tentang salah satu isi suratnya. Anda sudah berhasil menumbuhkan benih cinta di hati saya.
Artikel ini pertama kali dimuat Beritagar.id