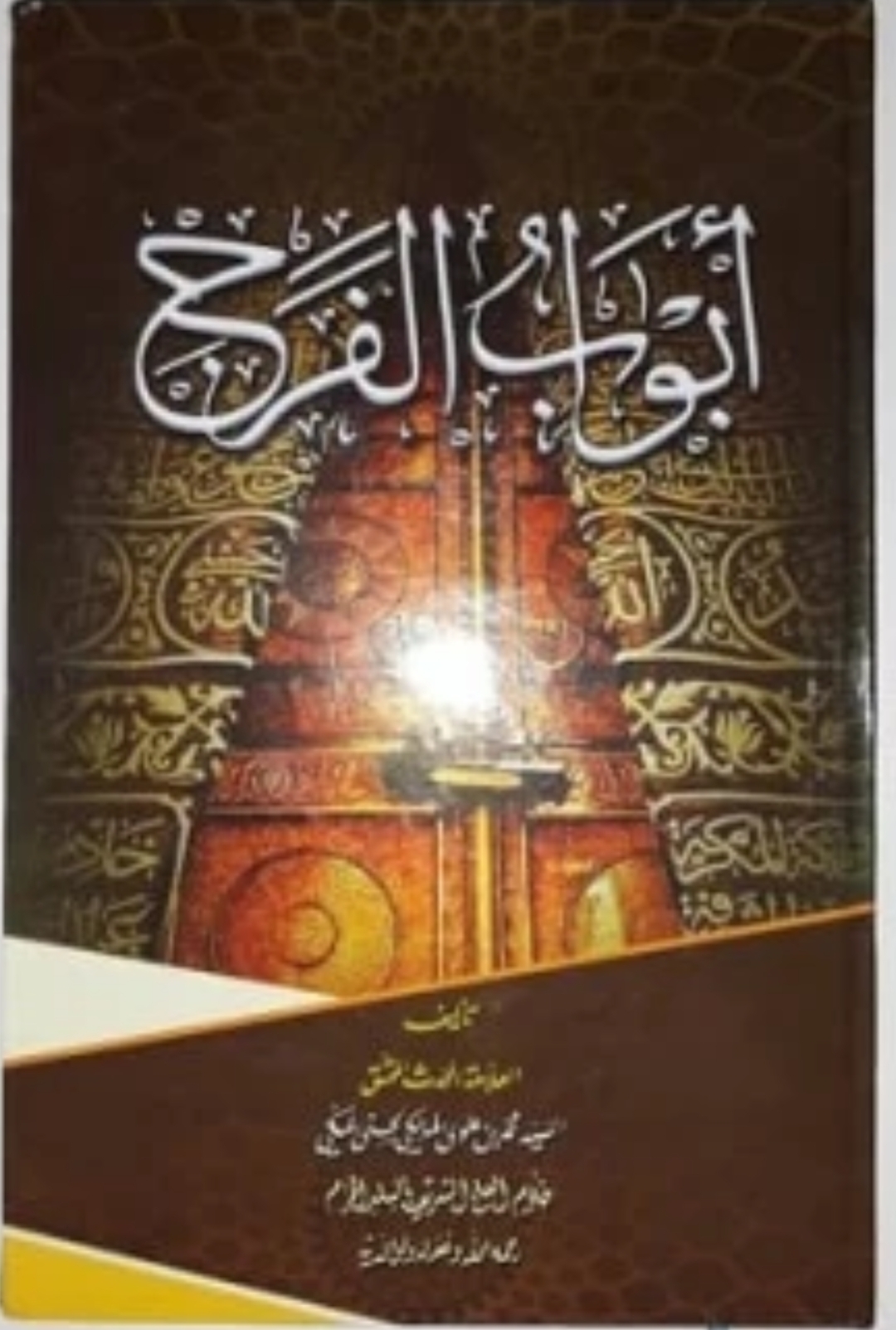Perdebatan di sekitar pemahaman teks (sejarah) dan sudut pandang merupakan perdebatan yang sangat klasik. Perdebatan itu sering meninggalkan jejak aliran dan mazhab-mazhab tertentu, seperti ahlul hadits dan ahlul ra’y atau ahlul harfi dan ahlut ta’wil. Sudut pandang “kanan” (tekstual) dan sudut pandang “kiri” (kondisional).
Menurut Ibnu Thamalus, Imam al-Ghazali pun pernah merasakan hujatan dari ulama lain, terkait sudut pandangnya, ketika ia mengatakan dalam pembukaan buku ushul fiqihnya al-Mustashfa, “bahwa orang yang tidak menguasai ilmu mantiq, keilmuannya belum bisa dipercaya.”
Hujatan kemudian datang dari Imam Ibnu Sholah, katanya apa yang dikatakan oleh Imam al-Ghazali terlalu berlebihan mengenai mantiq yang berasal dari Yunani itu, bahkan pendapat ini cenderung merendahkan ushul fiqh.
Kemudian, Imam Nawawi, murid kinasih dari Imam Ibnu Sholah itu, menjelaskan soal pendapat Imam al-Ghazali dan gurunya itu, bahwa sebenarnya antara keduanya tidak ada perbedaan prinsip yang perlu dibesarkan, karena yang terjadi hanyalah perbedaan sudut pandang.
Buktinya, dalam tindakan, al-Ghazali telah menulis kitab Mi’yarul Ilmi, yang sejatinya ini adalah kitab mantiq dan Imam Ibnu Sholah dengan tekun mempelajarinya. (Sami Nasyar, Manahij al-Bahts al-Ilm, 84-85).
Bercermin dari kisah ini, apa yang disampaikan Gus Muwafiq dalam ceramahnya mengenai masa kecil Nabi yang dekil dan secamanya itu. Lalu hujatan keras salah satunya dilontarkan oleh Habib Abu bakar Assegaf, karena dianggap merendahkan Nabi, barangkali tak terlalu berbeda dari kisah di atas. Pangkal masalahnya tentu saja sudut pandang yang digunakannya berbeda. Tetapi sebagaimana Imam Nawawi, saya haqqul yakin, bahwa kedua mubalig itu sama-sama mencintai Kanjeng Nabi Muhammad saw.
Tentu saja ada dua sudut pandang ketika melihat pribadi Kanjeng Nabi. Pertama secara al-khalaq al-ardliyah. Mungkin pada kelompik ini saya mengatogorikan ahlul harfi. Bahwa Nabi Muhamamd itu manusia biasa, sebagaimana yang lazim pada umumnya, perilakunya juga dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya, biologis-genetik, psikologi-neurologi, dan seterusnya.
Kedua secara al-haq as-samawiyah, sebagai ahlut ta’wil, yaitu makhluk spiritual, perilakunya langsung dari bimbingan Allah, tak tersentuh kekurangan dan sifat negatif, bahkan mempunyai kedudukan istimewa dalam kosmos dan inti mikrokosmos, yang telah dijadikan sebagai sebab fundamental penciptaan alam.
Dengan sudut pandang pertama, tentu saja bermuatan nalar-realistis, sebagaimana banyak digunakan oleh penulis sirah (sejarah), dan hal yang paling bisa dimengerti adalah Muhammad bin Abdullah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiulawal “tahun Gajah” atau 20 April 571 Masehi. Beliau adalah seorang manusia biasa yang tunduk kepada “sunnatullah” hukum semesta sebab-akibat. Allah berfirman: Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. (Al-Kahfi; 110).
Sudut pandang kedua, tentu saja bermuatan nalar trasendental-metafora, sebagaimana banyak digunakan oleh para sufi, dengan menggunakan term Insan al-Kamil, Nur Muhammad, Al-Mutha dan lain sebagainya. Selain itu, sudut pandang kedua juga sering digunakan oleh sastrawan. Bahkan, Ibnu Jauzi, seorang ulama bermazhab Hambali dengan sangat indah menggambarkan peristiwa yang agung ketika Nabi dilahirkan, menjadi bayi, balita, remaja, dewasa sampai berumur senja.
Menurut Imam al-Ghazali, justru karena kedua hal itu, kedudukan Nabi benar-benar paripurna, tetapi kadang sebagian orang sering sulit membedakan mana koridor harfi, mazaji, dan ta’wil, sehingga mengundang polemik (Maqhasid al-Falasifah, 74-76).
Singkatnya, apa yang dikatakan Gus Muwafiq, itu masih dalam batas “wajar”, sebab menggunakan sudut pandang pertama. Begitu juga apa yang menjadi keberatan Habib Abu Bakar Assegaf itu juga “lumrah”, sebab menggunakan sudut pandang kedua. Tetapi menjadi tidak wajar, jika orang membenturkan dua sudut pandang itu. Wallahu’alam.
Yogyakarta, 03 Desember 2019