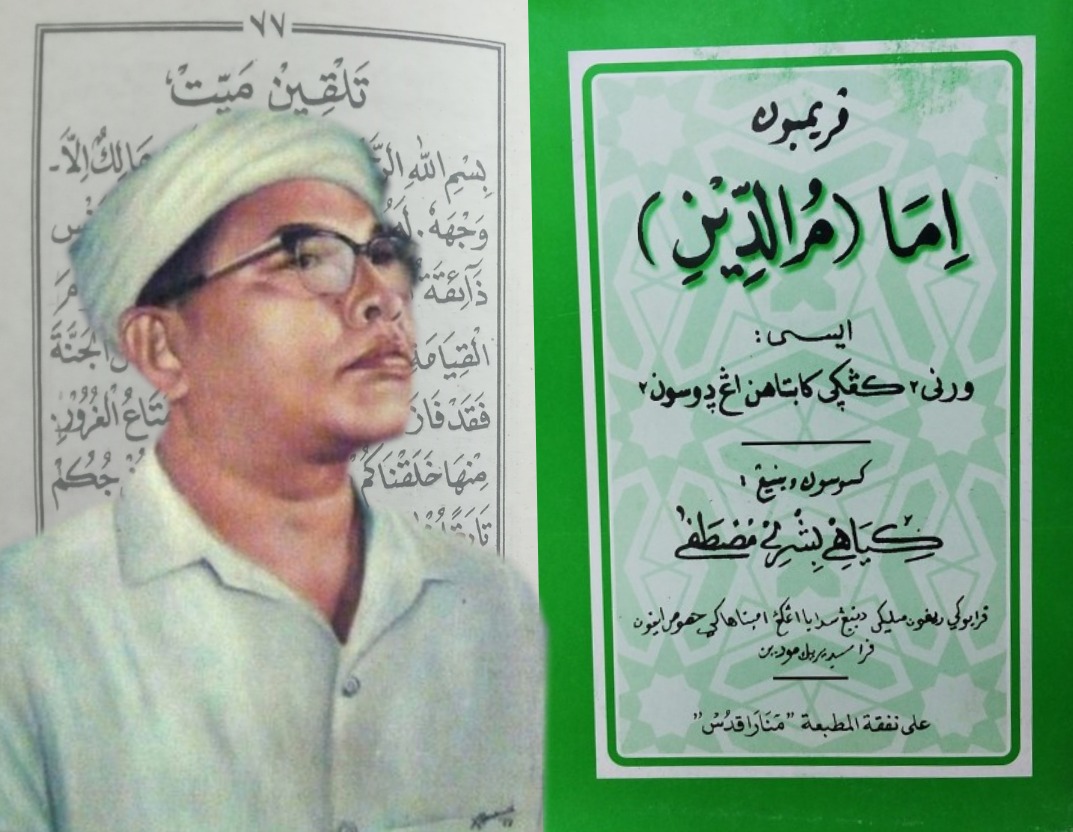Kita telat tapi tak mesti kuwalat. Nama besar dan penting lupa diperingati meski tak wajib. Pada1 Februari 2024, tanggal keramat untuk membuat peringatan 100 tahun Subagio Sastrowardoyo. Ia mula-mula sibuk dalam beragam seni. Pada masa 1950-an, ia serius dalam sastra. Nama itu mendapat perhatian besar gara-gara puisi.
Kini, kita mengenang sosok turut memberi pengaruh dalam arus sastra Indonesia. Ia memberi warisan-warisan mengesankan berupa puisi, cerita pendek, dan esai. Orang-orang teringat puisi-puisi gubahan Subagio S kadang berlumuran filsafat. Subagio itu pemberi puisi-puisi sering terkutip bertema kematian.
Orang-orang pun mengakui esai-esai buatan Subagio menguak hal-hal penting dalam kesusastraan Indonesia. Ia tak sekadar menulis esai mengenai sastra. Julukan kritikus sastra pantas diberikan. Ia berbeda corak dari HB Jassin atau A Teeuw. Kesibukan menulis esai atau kritik sastra berlanjut dengan mengajukan esai-esai mengenai seni, peradaban, kekuasaan, dan lain-lain. Kita mungkin memilih menempatkan Subagio sebagai pemikir setelah babak-babak silam berusaha menjadi seniman.
Pada 1957, ia memikat umat sastra di Indonesia dengan buku puisi berjudul Simphoni. Perhatian besar diberikan HB Jassin, memicu percik-percik polemik. Subagio bukan penggubah puisi bersikap diam di hadapan kritikus dan pembaca. Ia rajin “menerangkan” dan membuat “pembelaan” bukan untuk gubahan-gubahan sendiri tapi mengarah pemajuan sastra Indonesia.
Kita memilih membaca lagi puisi berjudul “Setasion”, mengingat Indonesia masa 1950-an dalam kesaksian Subagio. Puisi tak dimaksudkan fragmen sejarah. Kita dapat membaca sebagai tanggapan zaman atau dokumentasi sosial. Subagio mengisahkan: Adakah sorga seperti setasion ini/ tempat kereta telah berhenti/ dengan tulang besi-besi bersilang/ dengan muka penumpang gilap berkeringat/ dan debu arang mengendap./ Adakah gerimis itu di djendela/ dan puntung rokok mengepul./ Dan berita politik dari koran/ dengan inflasi, kelaparan dan bunuh diri. Indonesia sedang terseok dengan segala gejolak politik, pemberontakan, dan kesibukan revolusi.
Indonesia belum perlu bermimpi “sorga” dengan pengertian kemakmuran, kebahagiaan, kerukunan, dan keindahan. Indonesia masih bopeng, ringkih, kacau, dan ruwet. Kita mengandaikan Subagio berkelakar Indonesia sulit menjadi sorga. Ironi dihadirkan dengan sindiran “adakah sorga di stasion”. Kita mengerti stasiun bukan tempat atau alamat kekal. Di situ, orang memikirkan kedatangan dan keberangkatan. Stasiun, tempat mengisahkan manusia-manusia datang dan pergi. Kita memang tak lekas mengingat “sebentar” atau “fana”. Subagio berani memikirkan surga dengan stasiun. Tempat mendapat deskripsi cukup terang.
Suasana hidup kacau dan rumit kadang menimbulkan guncangan religius. Guncangan itu membesar ketimbang curiga kekuasaan dan mengutuk modernitas. Subagio lazim mencantumkan kata-kata merujuk religiositas tapi sadar sedang berfilsafat dan “bergurau” ata zaman tak keruan.
Di puisi berjudul “Bulan Ruwah”, kita berhadapan puisi berat. Puisi pantas mengesahkan kecondongan berfilsafat dalam sodoran puisi-puisi gubahan Subagio. Puisi tak kentara diperalat dalam sesumbar menuntut jawab: Orang rus itu komunis jang menghina nabi dan agama./ Orang tjina suka makan babi. Itu terang djadi larangan./ Orang djawa malas sembahjang dan gemar pada mistik. Definisi tak mengandung kebenaran mutlak. Kita membaca sindiran dan pendapat umum mudah terbantah.
Kita sampai dalam larik-larik mendebarkan: Apakah bahasamu, apakah warna kulitmy, apakah asalmu?/ Apakah kau pakai petji dan sarung pelekat/ atau telandjang seperti budak habsji hitam pekat/ – atau seperti bintang pilem berpotret di kamar mandi?/ antara tanda kurung: adakah dia punja tuhan? -/ Daftar tanja kita tandai dengan tjakaran hitam/ seribu tangan. Kita berpikir Indonesia setelah kolonialisme. Indonesia terhubung dengan dampak-dampak global setelah Perang Dunia II.
Pada masa 1970-an, para pembaca tetap menemukan gandrung berfilsafat dan suara-suara religius dalam puisi-puisi gubahan Subagio. Buku berjudul Daerah Perbatasan dipersembahkan meski mencekam dalam tema kematian. Subagio belum rampung dengan perkara kematian.
Di puisi berjudul “Tjerita Tua”, kita merasakan “api membakar” dan ikhtiar mengerdakan berita dan cerita. Subagio menginsafi terbakar dan hangus itu memberi ajakan memikirkan hidup, kebangkitan, pembaharuan, atau kelanjutan. Puisi bermula dengan “api jang membakar” mendapat pengukuhan: Lalu lahir pikiran baru/ Lembut sebagai kupu/ Melepaskan diri dari himpitan debu/ Dan terbang dari batu ke batu/ Dari kalbu ke kalbu/ Timbul semua jang tak pernah dimimpi/ Seni jang baru, kesusasteraan, filsafat, agama/ Lebih agung dari semula/ Membangunkan rumah, gedung, kota jang lebih indah/ Dimuka bumi, diatas derita jang menghangus sampai ke hati. Puisi mengesankan keinginan mendatangkan larik-larik berat kepada pembaca.
Puisi-puisi gubahan Subagio jarang memberi girang. Para pembaca tak mendapat pengentengan dalam hidup tapi diberi “beban-beban” tak berkesudahan. Puisi memang bukan hiburan. Subagio tak bermaksud mengajak pembaca tertawa, tepuk tangan, atau gembira. Puisi berjudul “Di Podjok Djalan” terbaca (tak) sederhana: Bahwa kita hidup adalah perdjandjian/ dengan bumi: bahwa kita akan setia/ kepada istri, dan kepada anak/ merasa sajang. Kita bersatu dengan awan/ dengan bunga dan binatang. Kepada/ tanah terikat dengan kebaktian dan tekad/ Perdjandjian diikrarkan dengan darah/ dinihari, di daerah perbatasan/ antara lahir dan mati. Kita mungkin “salah waktu” atau “salah baca” bila menghadapi puisi itu sebelum tidur. Di ujung puisi, pembaca bakal gemetar: Amat sederhana: di podjok djalan/ manusia kurus menangkup bunuh diri. Pembaca boleh menghindari puisi-puisi pemberian Subagio tak bosan-bosan mengenai kematian.
Pada suatu masa, orang-orang membaca kematian dalam puisi-puisi gubahan Amir Hamzah, Sutan Takdir Alisjahbana, atau Chairil Anwar. Pada masa 1950-an sampai 1970-an, kematian terus ditulis dalam puisi-puisi gubahan Rendra, Sapardi Djoko Damono, Ajip Rosidi, Kirdjomuljo, Taufiq Ismail, dan lain-lain. Kita mungkin menandai sekian puisi dianggap “puncak-puncak” dalam penulisan kematian. Subagio S tentu nama penting dengan puluhan puisi bertema kematian.
“Sajak adalah suara bawah sadar,” pengakuan Subagio. Ia menganggap sajak atau puisi itu mengejawantahkan segala hal merujuk bawah sadar. Pengakuan makin mengukuhkan ketekunan menulis kematian. Ia sedang berfilsafat kematian tapi mengikutkan kesanggupan mengisahkan Indonesia, mengamati situasi dunia, menilik pertumbuhan kota-kota, sadar keterpecahan identitas, dan pemujaan semu estetika. Pada masa 1950-an, ia pernah menulis: Ah, sadjak ini,/ mengingatkan aku kepada langit dan mega/ Sadjak ini mengingatkan kepada kisah dan keabadian/ Sadjak ini melupakan aku kepada pisau dan tali/ Sadjak ini melupakan kepada bunuh diri. Kita agak mengerti saat ia menggubah puisi, dunia sedang dilanda filsafat eksistensialisme. Di Indonesia, Subagio pun fasih menjelaskan filsafat berkiblat Barat.
Pada masa 1950-an, ia pun memberi larik-larik agak menggelikan tapi mengingatkan kematian: “Seorang diri pasti aku mati keisengan.” Ia tak ingin berkhotbah tapi kematian tapi orang kadang memang mati dengan muram, girang, putus asa, minder, rikuh, tulus, atau iseng.
Kita membuat peringatan 100 tahun Subagio Sastrowardoyo sambil membuat catatan besar atau garis bawah dengan tebal tentang ketekunan menulis kematian. Puisi-puisi mencantumkan kematian itu menandai tema tak pernah usang dalam arus puisi modern di Indonesia. Subagio seperti berperan sebagai pemberi pengesahan “takdir” puisi di Indonesia itu kematian. Begitu.