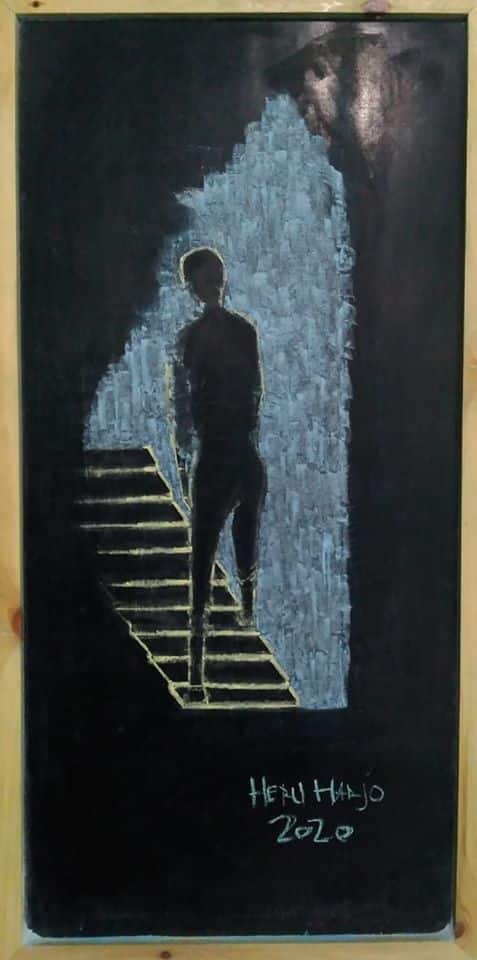
Hidup di alam kemajemukan memang membutuhkan kiat khusus agar kemajemukan itu senantiasa terjaga. Tak bisa dipungkiri bahwa manusia selalu memiliki kepentingan pribadi. Mulai dari Nietzsche hingga Freud, dedahan-dedahan tentang kepentingan pribadi manusia yang bersifat tersembunyi, selalu berbalut topeng-topeng, dibabarkan dengan istilah-istilah khusus, the will to power pada Nietzsche dan eros–thanatos pada Freud.
Atas dasar kepentingan-kepentingan pribadi yang seolah innate itulah kemudian muncul berbagai teori tentang masyarakat dan negara. Salah satu teori tersebut adalah teori nalar publik sebagaimana yang diprakarsai oleh John Rawls dan Habermas pada konsep demokrasi deliberatifnya.
Nalar publik ini menjadi penting ketika demokrasi—yang secara sederhana diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat—menyaratkan civil society yang kuat agar hakikat demokrasi itu terimplementasikan secara nyata.
Dalam logika sistem demokrasi rakyat tak lagi seperti halnya bocah yang mesti diatur-atur laiknya dalam sistem pemerintahan otoritarian, seumpamanya komunisme dan khilafah islamiyah. Tapi ia mesti dewasa, mesti mampu mengatur kehidupannya sendiri atau mandiri tanpa harus diintervensi kehidupannya oleh pemerintah.
Hal ini tak berarti bahwa kemudian rakyat sama sekali berhadapan dengan pemerintah sebagaimana yang selama ini diimani oleh kalangan aktifis yang saya kira salah-kaprah dalam memahami semangat dan konsep civil society.
Saya pernah membahas tentang salah-kaprah konsep civil society yang selalu saja diartikan harus berhadapan dengan pemerintah (UU Desa dan Radikalisme di Akar Rumput, Heru Harjo Hutomo, https://jalandamai.org).
Paradigma seperti ini, andaikata terus dipelihara, akan selalu berujung pada pengkambinghitaman pemerintah. Meski, tak jarang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini senafas dengan kehendak rakyat, karena dalam konsep civil society, semua kebijakan pemerintah idealnya datang dari inisiatif masyarakat sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi urgen dalam hal ini.
Tapi seumpama segala sesuatunya, pada tataran idealitas, mesti datang dari aspirasi masyarakat, lantas bagaimana pemerintah memilih dan menentukan aspirasi siapa dan yang mana yang mesti diikuti dan diterapkan di ruang publik, mengingat kepentingan setiap orang ataupun kelompok berbeda-beda dan bahkan bertentangan?
Dalam sistem demokrasi, kebebasan menyatakan pendapat merupakan salah satu sendinya yang tak dapat diabaikan. Sistem pemerintahan yang lazimnya “masturbasif” atau otoritarian memang tak menyukai kebebasan berpendapat masyarakatnya.
Pemerintah laiknya seorang “mursyid” yang setiap titahnya mesti ditaati tanpa reserve. Tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat tersebut tentu saja demokrasi akan kehilangan maknanya. Kehidupan sosial manusia dan kekuasaannya sama sekali tak serupa dengan kekuasaan Tuhan.
Karena sederhana saja, hanya Tuhan yang maha sempurna dan maha suci, sedangkan manusia tempatnya lalai dan kesalahan. Tentu di sini orang ingat sebuah pepatah bahwa power tends to corrupt.
Dalam agama pun, seperti yang dinyatakan oleh al-Ghazali, sebenarnya ada larangan untuk bersikap taqlid. Setiap orang mesti tahu tentang alasan kenapa harus berbuat atau tak berbuat begini atau begitu. Oleh karena itu, dalam terang al-Ghazali, bertanya (baca: sikap kritis) pada akhirnya menjadi suatu hal yang justru dibutuhkan agar tak beriman secara buta—termasuk andaikata hal itu pun berkaitan dengan keagamaan dan ketuhanan.
Radikalisme dan terorisme berkedok agama adalah salah satu bukti nyata tentang tak adanya ruang bertanya dalam beragama. Sehingga banyak orang akan merasa sok suci dan sok benar alias “masturbasif” dan akhirnya seolah mengkudeta kekuasaan Tuhan dan dengan mudahnya berhak memvonis orang lainnya sebagai kafir.
Kontestasi wacana di ruang publik melalui nalar publik, karena itu menjadi hal yang lumrah dan mesti ditempuh agar menemukan sesuatu yang terbaik bagi keseluruhan orang ataupun golongan. Tentu syarat-syarat bernalar publik haruslah selihai mungkin menerjemahkan dan menegosiasikan kepentingan pribadi yang sifatnya partikular menjadi kepentingan bersama yang sifatnya universal, dapat mengakomodasi kepentingan keseluruhan orang dari latar-belakang apapun.
Nalar publik dikatakan gagal seandainya masing-masing orang atau golongan bersifat “masturbasif,” mengukuhi kebenarannya sendiri tanpa hirau kebenaran orang lainnya. Dan hal itu sesungguhnya, atas nama Pancasila UUD 1945, sudah dapat dikategorikan sebagai sebentuk pelanggaran berat, karena telah memakan ruang publik, sepetak ruang yang tak hanya ia yang memiliki.
Dengan demikian, publik berhak tahu dan ikut menegosiasikan di ruang publik tentang sebuah kebijakan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Karena sederhana saja, yang tahu mana yang terbaik bagi masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Keterlibatan publik pada akhirnya menjadi hal yang pokok andaikata hakikat demokrasi dan civil society ingin dicapai.
Di sinilah kemudian nalar publik menjadi salah satu cara masyarakat untuk menentukan apa yang terbaik bagi mereka, bagi kehidupan bersama. Karena tak jarang terdapat perbedaan dan bahkan pertentangan pendapat serta kepentingan dalam masyarakat itu sendiri.
Masing-masing orang atau golongan seolah ingin menjadi the ruling class dan hal ini memang sudah menjadi tabiat dasar manusia yang bersifat innate. Untuk melihat ini semua, kontestasi wacana tentang wabah corona di ruang publik menjadi fenomena yang menarik untuk ditelaah.
Semua orang atau pun golongan berupaya menyikapi wabah itu sesuai dengan caranya masing-masing, apalagi ketika isu corona tersebut bersinggungan dengan agama. Bukankah pemerintah pusat dan beberapa pemerintah daerah, dalam hal ini, ketika menyikapi kebijakannya atas pandemi corona juga beriringan dengan sikap beberapa golongan masyarakat?
Sebutlah LBM PBNU (Pandangan Keagamaan LBM PBNU Tentang Pelaksanaan Shalat Jumat Di Daerah Terjangkit Covid-19 (https://alif.id), MUI, PRD, beberapa ulama dan cendekiawan muslim, dst. Artinya, pemerintah dalam hal ini tak semata memutuskan kebijakan publiknya secara sendirian tanpa adanya nalar publik dari beberapa golongan tersebut.
Pada tataran diskursif, civil society dan nalar publik telah secara apik dipraktikkan. Inisiatif tak hanya datang dari pemerintah, melainkan juga dari beberapa golongan masyarakat. Negosiasi di ruang publik dapat pula dikatakan telah terbentuk (Tumengeng Tawang: Penyikapan Budaya atas Sebuah Bencana, Heru Harjo Hutomo, https://jalandamai.org).
Baik yang pro maupun kontra atas penyikapan pandemi corona semuanya ingin memberi tafsir, sikap, dan solusi masing-masing. Setidaknya, semuanya sudah menunjukkan keterlibatannya di ruang publik dan, sebagai bagian dari warga negara dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.
Kita, mereka, semuanya mesti mengatur kehidupannya sendiri, berupaya ikut menentukan pilihan terbaik bagi masyarakat. (SI)




















