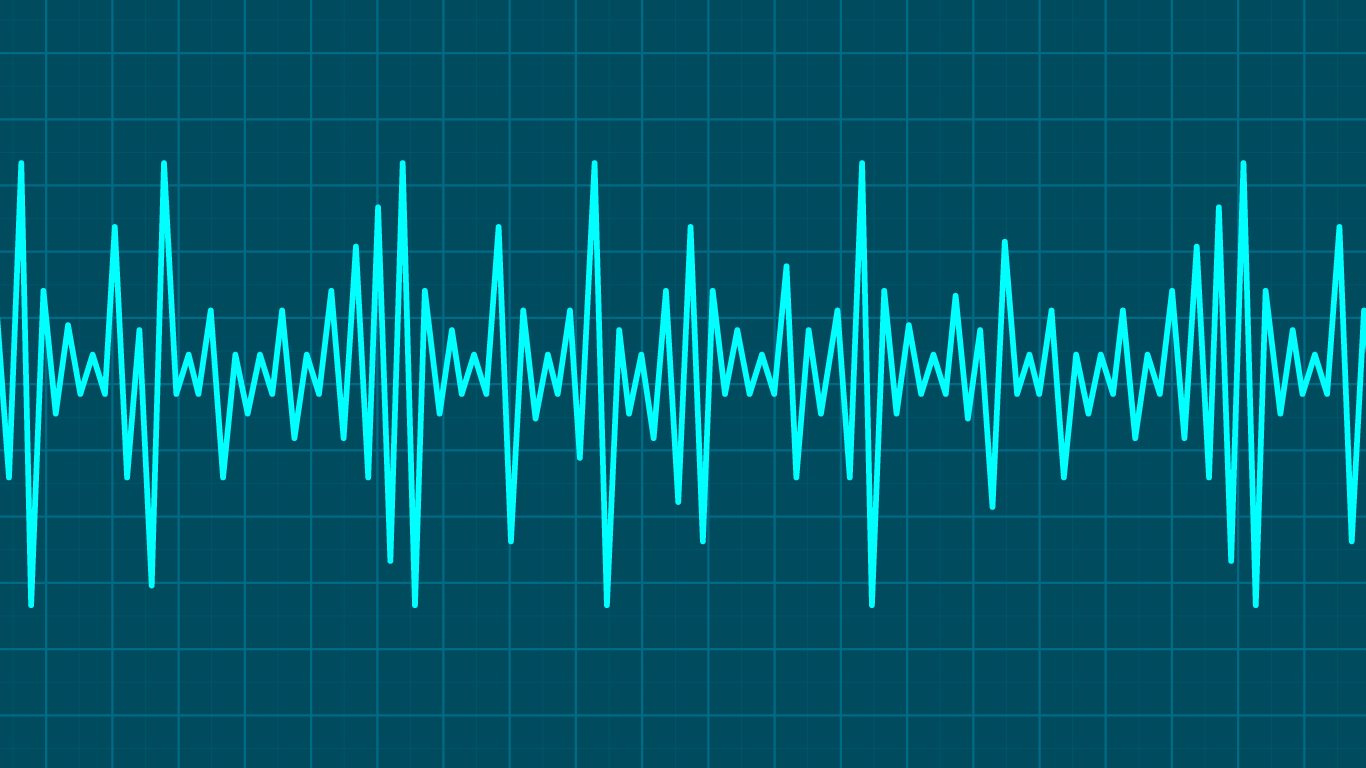
Kalamun nandhing sarira
Tinemu beda malah nyulayani
Benere dhewe ginunggung
Tinampik liyaning lyan
Beda kalyan tepa sarira puniku
Ika kang den upayaa
Tinemu samining sami
—Punkchoir Kabhinekan, Heru Harjo Hutomo
Barangkali kita cukup akrab dengan kisah Sidharta Gautama yang menemukan pepadhang dengan ilham dari musik. Seusai merasa tak menuai hasil dari tirakatnya yang seolah sampai menyiksa dirinya sendiri, ia tersadar oleh sebuah kecapi dimana ketika dawainya terlalu kencang terpasang ia akan rentan putus dan ketika terlalu kendor justru tak mengeluarkan bunyi.
Musik, sebagaimana bentuk-bentuk kesenian lainnya, mengalami evolusi pula. Pada awalnya, sebelum modernisme mengubah segala tatanan nilai, ia masih lekat dengan citra dan fungsi spiritualnya. Maka tak heran ketika di Jawa seumpamanya, olah seni tradisional disepadankan pula dengan sebentuk olah rasa.
Citra dan fungsi seni ini pelahan bergeser dengan tumbuhnya modernisme dengan spesialisasi laiknya sains yang terpilah dengan filsafat. Tapi citra dan fungsi spiritual seni tak hilang begitu saja, idealitas-idealitas lama tetap menjadi paradigma meskipun gelembukan modernisme sedemikian menggiurkannya.
Pada bidang musik kita masih dapat menikmati sajian seni karawitan dengan idealitas lamanya, musik pengiring sema’ dalam tradisi tarekat Mawlawiyah atau yang bersentuhan dengan Rumi, dan musik oxitron yang salah satunya dikembangkan oleh Indra Q, dkk. Dalam hal ini paradigma modernisme, dengan semboyan khasnya, seni untuk seni, seolah bukanlah harga mati.
Memang, perdebatan motivasi berkesenian sempat membuat jalannya musik-musik yang motivasinya terkesan luhur tak mendapatkan segmen yang luas. Pada dekade 60an, menjelang peristiwa Gestok, perdebatan itu cukup direpresentasikan oleh Lekra, penggaung realisme sosial, dan Manikebu, penggaung humanisme universal.
Seni-seni yang bersifat spiritual pada dasarnya tercakup pula dalam argumentasi Lekra, meskipun berbeda penekanannya. Seni, bagi Lekra, mestilah bermanfaat bagi orang lainnya. Dalam bahasa saya istilah manfaat ini lebih mengena daripada istilah bertujuan, mengingat pula bahwa Manikebu membela seni-seni yang “ngocokan” dengan dalih humanisme universalnya.
Maka ketika fakta ini ditautkan dengan fenomena radikalisme-terorisme ternyata hasilnya adalah di luar dugaan. Tentu di sini saya tak sedang membela Lekra yang berprinsip seni untuk yang lain ataupun menyalahkan Manikebu yang berprinsip seni untuk seni. Tapi penemuan saya tentang melankolia sebagai salah satu akar dari radikalisme-terorisme membuktikan bahwa humanisme universal yang kerap biru dalam ekspresinya juga ditampakkan oleh kalangan yang ditengarai radikal (“Petaka Melankolia dan Sekelumit Bom Surabaya,” dlm. (ed.) idenera.com, Merawat Ingatan Merajut Kemanusiaan, Kanisius, Yogyakarta, 2019).
Tentu, dalam hal ini, Ivan Karamazov, salah satu karakter dalam novel Dostoyevski yang popular itu adalah jelas seorang humanis universal persis para pahlawan yang dihidangkan oleh para eksponen Manikebu. Kesan muda memang cukup terasa ketika mengeksplorasi karya-karya para pelaku seni yang cenderung berafiliasi ke Manikebu.
Taruhlah sajak-sajak Sapardi Djoko Damono, “Aku Ingin,” yang sebegitu dahsyatnya membuat siapapun meleleh yang kebetulan musikalisasinya dibikin oleh Ags Arya Dipayana. Atau prosa liriknya seorang Goenawan Mohamad yang sempat dipentaskan menjadi opera tari, “Gandari,” yang mungkin dapat membikin para wanita iba hingga membela karakter-karakter wayang yang secara tradisional dikenal kurang baik.
Citra para pahlawan yang diekspresikan seni-seni yang dapat diusung oleh Lekra memang jauh kalah ganteng daripada yang diekspresikan oleh seni-seni yang dapat ditampung oleh Manikebu dengan humanisme universalnya—meskipun kegantengan itu kerap pula dihasilkan dari efek yang biru mengiba.
Sekali lagi dalam hal ini saya tak sedang menyalahkan Manikebu yang bagaimana pun pernah menghiasi perjalanan kebudayaan secara umum di Indonesia. Hanya saja pada tataran konseptual kemerdekaan yang terisolir yang pernah mereka sajikan secara biru—atau dalam kata-kata Goenawan Mohamad “Kesunyian masing-masing”—justru membuka ruang terhadap politik identitas dengan kadar yang bahkan ekstrim: radikalisme.
Ketika menilik hal itu dengan prinsip etis Jawa, konsekuensi dari pilihan estetis sekaligus politis bentuk-bentuk kesenian yang dapat ditampung oleh Manikebu pada dekade 60an itu adalah nandhing sarira yang ketemunya adalah perbedaan yang mengasingkan satu sama lain. Konon, nandhing sarira ini adalah tahap terendah dari proses pengidentifikasian diri. Cukup mengagetkan ketika menilik pilihan sikap Lekra atau segala bentuk kesenian yang nilai-nilainya dapat diusung olehnya. Dalam hal ini Lekra justru berada pada tahap tepa sarira dengan asumsi untuk mengenal diri sendiri dapat bercermin pada orang lainnya. Maka dapat dimengerti ketika tepa sarira ini disepadankan dengan tenggang-rasa atau toleransi.
Dengan demikian, ketika mencoba untuk tak munafik dimana tak ada yang sama sekali dapat lepas dari politik, tak salah seandainya segala bentuk kesenian yang nilai-nilainya dapat ditampung oleh Manikebu berpotensi “ngocokan” dan secara konseptual dapat membuka ruang bagi hadirnya radikalisme yang secara umum dikenal mengagungkan kebenaran sendiri. Bukankah konon, pada dekade 60an, para seniman yang kerap mencitrakan dirinya religius dan moralis cenderung berafiliasi ke Manikebu?
Meskipun Lekra, atau segala bentuk kesenian yang secara tata nilai dapat diusung olehnya, berada pada tahap tepa sarira tak pula pilihan etis ini dapat merengkuh tahap identifikasi diri ketiga dimana dalam kebudayaan Jawa disebut sebagai mulat sarira. Saya tak mengatakan bahwa mulat sarira inilah yang sebenarnya juga diacu oleh penggagas the Global Ethic, Hans Kung. Tapi setidaknya, bahasa yang lebih konkrit dan terkesan ilmiah dari mulat sarira ini sedikit banyak pernah dibahasakan olehnya yang secara resmi, pada tahun 2018, arahan ke-limanya dikeluarkan oleh parlemen.
Saya pribadi sebenarnya, ketika ditautkan pada evolusi manusia, tak terlalu muluk ketika membahasakan tahap ketiga pengidentifikasian diri ala kearifan Jawa yang disebut sebagai mulat sarira ini. Di bidang musik modern, orang pastinya paham akan istilah interferensi dimana pola sebuah akor berubah, yang tadinya secara konsensus dianggap sebagai root seolah tak lagi menjadi root. Sehingga, ketika sekilas didengarkan akan terasa bunyi dua akor padahal secara bentuk adalah satu akor.
Memang, di satu sisi, interferensi ini dapat memperkaya dan memperelok sebuah musik. Tapi, di sisi lain, kadang dapat merusak sebuah musik. Interferensi ini lazim dipakai pada musik jazz dimana disonansi adalah hal yang justru merupakan kekhasannya. Seolah-olah, pada musik jazz, sebuah kesalahan adalah hal yang manusiawi. Barangkali, karena ujung segala bentuk pengidentifikasian diri ala kearifan Jawa ini adalah kebhinekaan, maka interferensi adalah satu langkah yang mesti ditempuh. Lagi pula, bukankah pada musik jazz laku improvisasi merupakan sebentuk pakem dimana masing-masing individu boleh menonjolkan individualitasnya tanpa merusak harmoni? Dan bukankah demikian pula dengan ideal kebhinekaan kita?















