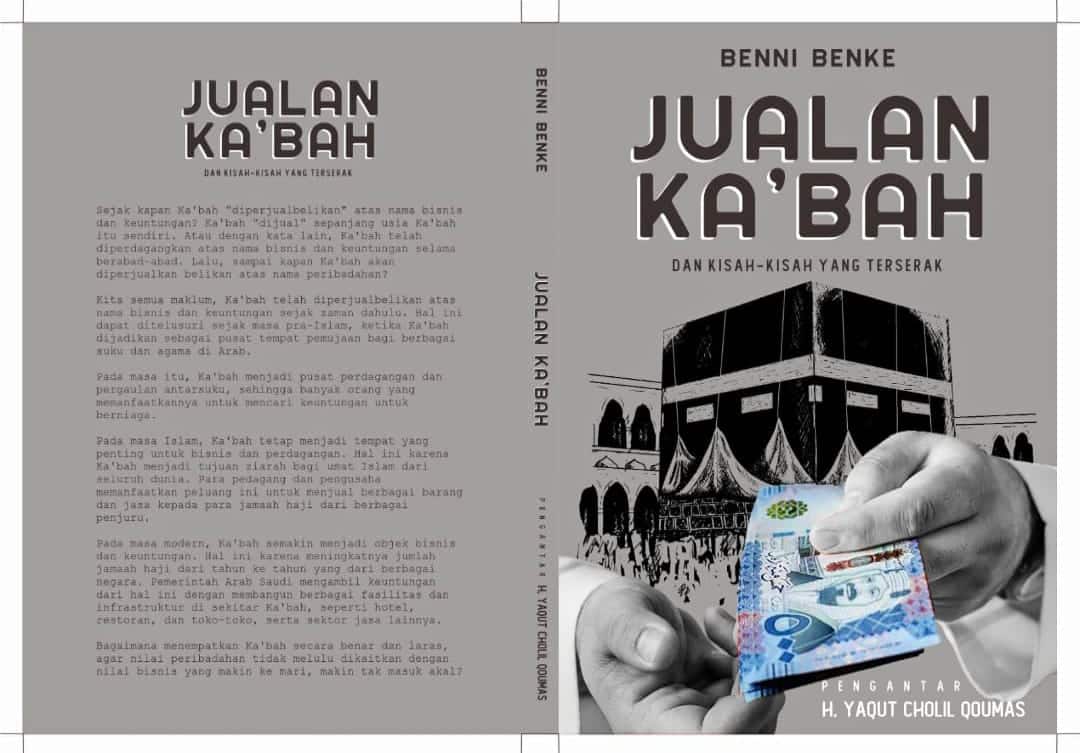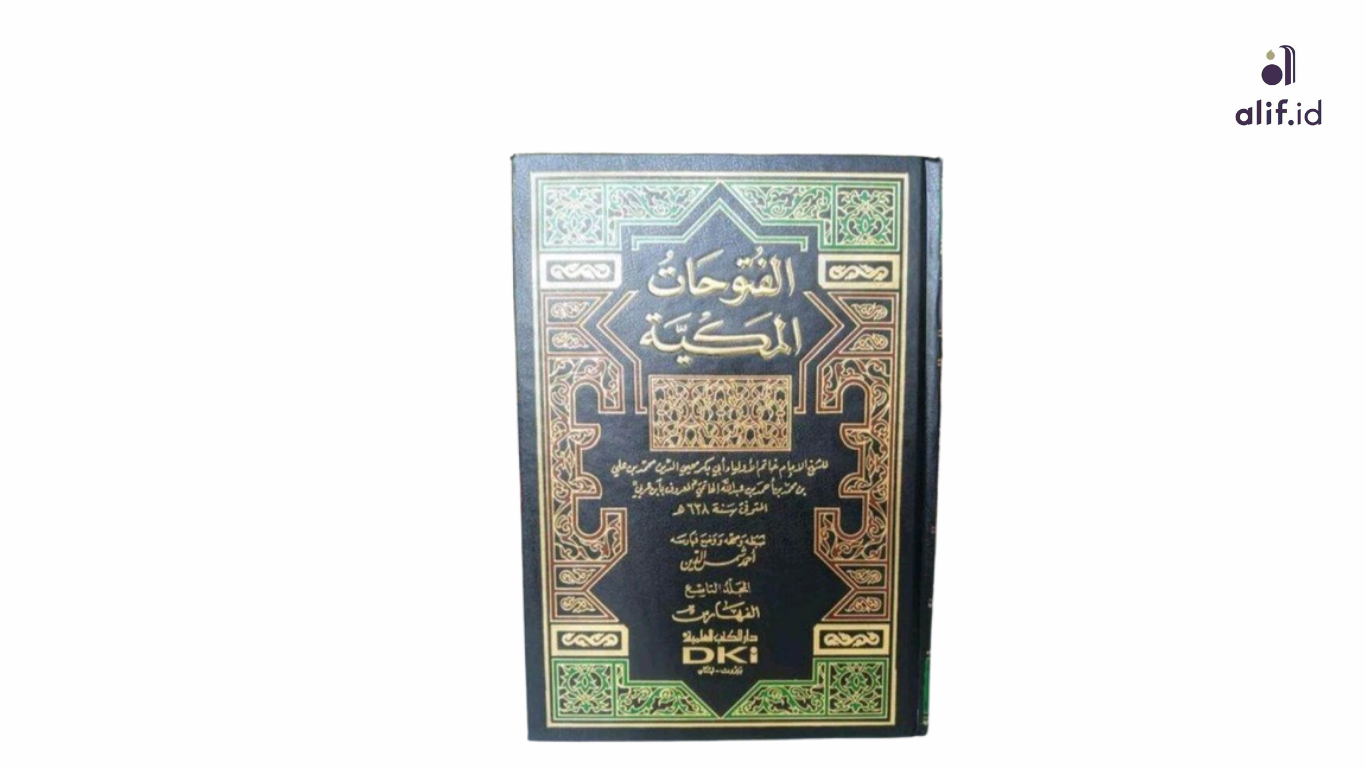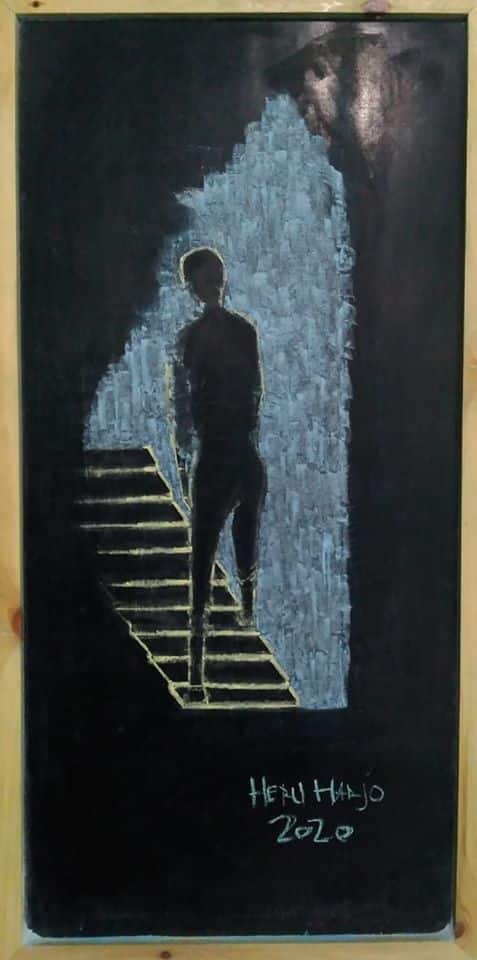
Tan ingsun maparangah mring kahananmu
Sakaliring dudu jati
Amung daden kang ngreridhu
Nanging tumraping margi
Linampahan kanthi tanggon
—Megatruh (Heru Harjo Hutomo)
Di tengah suasana yang hiruk-pikuk, histeris dan berjubel, lelaki itu tetap memeluk isterinya. Ramai orang melempar kerikil, batu, ke tiga tugu—ula, wustha, aqabah—yang konon merupakan personifikasi para setan.
“Bismillahi Allahu akbar rahman lissyayathini waridhan lirrahmani...,” deras sang isteri yang gemetaran oleh suasana yang penuh desak.
Lelaki itu terus memeluk isterinya, mengamankannya untuk leluasa melempar jumrah. Kanan-kiri, depan-belakang, mengepung orang-orang Timur Tengah dan Afrika yang berpostur besar. Tak ada yang peduli pada keadaan orang lainnya. Semuanya larut, berebut untuk membalang tugu-tugu itu.
Sepasang suami-isteri itu telah lama menabung, menjual beberapa petak sawahnya untuk menunaikan sebuah proses penempaan diri, atau apa yang saya sebut sebagai suluk sangkan-paran. Demikianlah, haji tak sekedar salah satu rukun Islam (bagi yang mampu), tapi juga sebentuk suluk, laku ragawi sekaligus rohani untuk membuktikan (haqq al-yaqin) sepenggal pesan perenial: Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un (sangkan-paraning dumadi).
Untuk itu kemelekatan yang mesti “diperlonggar” –atau bahkan dilenyapkan—ternyata tak melulu identik dengan Buddhisme, tapi juga Islam yang kental terasa dalam bentuk ibadah haji. Satu hal yang pasti dalam serangkaian ritual haji adalah keberanian untuk mati. Maka jamak para jamaah yang akan berhaji dianjurkan untuk meninggalkan secarik wasiat.
Mereka mesti bersiap untuk tak sekedar menanggalkan keduniawian, tapi juga meninggalkannya. Ditanamkanlah di relung jiwa mereka bahwa ketika mereka benar-benar meninggal di sana, di tanah yang diyakini suci itu, mereka syahid.
Pada titik itu, mereka semua benar-benar “nol”, benar-benar rendah, tak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa kecuali satu: hamba Tuhan. Pangkat, derajat, semat, dan keramat, benar-benar ditanggalkan—persis para bikhu dan bikhuni di mana hanya beberapa lembar kain putih yang boleh menghiasi jasmani (ihram).
Mereka berkitar melingkari ka’bah, merunut jejak balik, seperti berdzikir hingga lenyap segala lafadz dan sifat. Tersisa ruang yang hampa, tanpa suatu apa di dalamnya—hati yang sudah tersapu dari segala isi (nafi), tinggal isbat yang sudah bukan kuasa manusia lagi. Arya Sena yang nyaris mati, tenggelam dalam samudera minangkalbu, hingga sesosok bocah bajang (kerdil) menggugahnya (yajtabi): Dewa Ruci.
Menyeksamai kisah Arya Sena atau Bima dalam pewayangan Jawa seakan menyeksamai pula leliku Siti Hajar dalam mencari air. Di sini segala sistem spiritual seolah menemukan titik-sambungnya. Semuanya hanya menggemakan pesan kerinduan purba pada sang sangkan-paran.
Berbagai perubahan penampilan menandakan hasil dari proses pengenangan (pencarian) itu. Bima yang kemudian mesti menggelung rambutnya yang semasa muda diurai sepinggang dan berganti nama menjadi Wrekudara.
Dari pemaknaan ritual haji yang merupakan sebentuk suluk sangkan-paran itu, orang pada akhirnya menjadi sadar bahwa hidupnya pada dasarnya adalah sebuah kealpaan, atau untuk meminjam terminologi Heidegger dengan konteks berbeda, “seinsvergessenheit” (kealpaan-akan-mengadanya).
Maka, dalam istilah keseharian masyarakat berbahasa Jawa, kealpaan tersebut sering diungkapkan dengan istilah “manungsa nggone luput lan lali,” bahwa manusia itu tempatnya kesalahan dan lalai). “Salah” dan “lalai” di sini tak sekedar berkaitan dengan dosa dalam kosa-kata agama—di mana dalam eksistensialisme Heideggerian diistilahkan sebagai “verfallen” atau hanyut dalam suasana keseharian. Tapi, lupa akan jejer-nya: siapa, mengapa dan untuk apa ia hidup.
Agama mengabarkan bahwa diciptakannya manusia (dan jin) adalah untuk beribadah kepadaNya. Sementara, untuk lebih detailnya, dalam bidang tasawuf, Jalaluddin Rumi dan Ibn ‘Arabi memaknai keberadaan manusia tak lebih dari sekedar untuk mencintaiNya dan mengetahuiNya. Untuk itulah, konon, Rumi ditahbiskan sebagai sang kutub cinta dan Ibn ‘Arabi sebagai sang kutub pengetahuan.
Saya sama sekali tak menampik Rumi, hanya saja jalur Ibn ‘Arabi sepertinya lebih dekat dengan kultur dan filosofi Jawa. Istilah “mengetahui” dalam pemikiran Ibn ‘Arabi sepadan dengan istilah “weruh” di mana kemudian istilah “kawruh” diturunkan. “Kawruh” (baca: pengetahuan) ini lazimnya dianggap sebagai hasil dari tindakan “weruh.” Karena itulah, lantas ia dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai “kawruh kasampurnan.”
Adakah pemaknaan di atas erat kaitannya dengan anggapan bahwa haji merupakan sebentuk kesempurnaan dalam berislam? Secara sufistik, andaikata ritual haji dimaknai sebagai sebentuk suluk sangkan-paran, memang terdapat kaitan yang erat. Bukankah Ibn ‘Arabi sendiri mengarang Futuhat al-Makiyah sambil menunaikan ibadah haji?
Dan di atas semua itu, ada satu ruang dalam ritual haji yang menandakan ruang kearifan. Bahwa agama tak semata soal kejatuhan, bahwa menjadi manusia tak selamanya sebentuk duka dan nestapa.
Seperti lelaki itu yang terpisah dari isterinya, ibu saya, dan mesti berlari di usia senjanya hanya untuk tak tertinggal, telat, dalam beradab ria denganNya—sesuai isyarat seorang lelaki aneh yang mengacungkan jari telunjuknya ke langit.
Tak akan aku terperangah
Oleh keadaan segala sesuatu
Tak ada yang Haqq
Hanya semu yang membelenggu
Tapi ibarat jalan
Sudah semestinya dilewati. (SI)