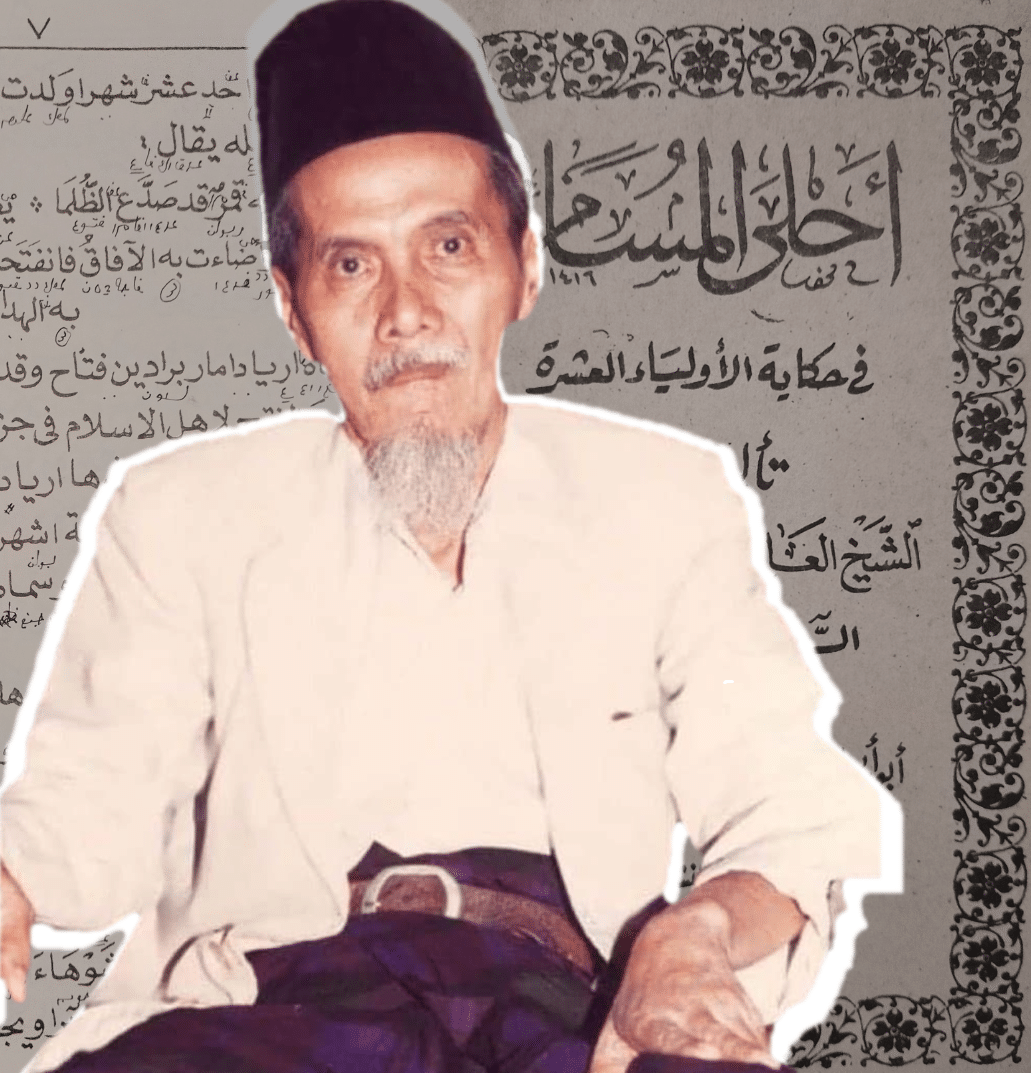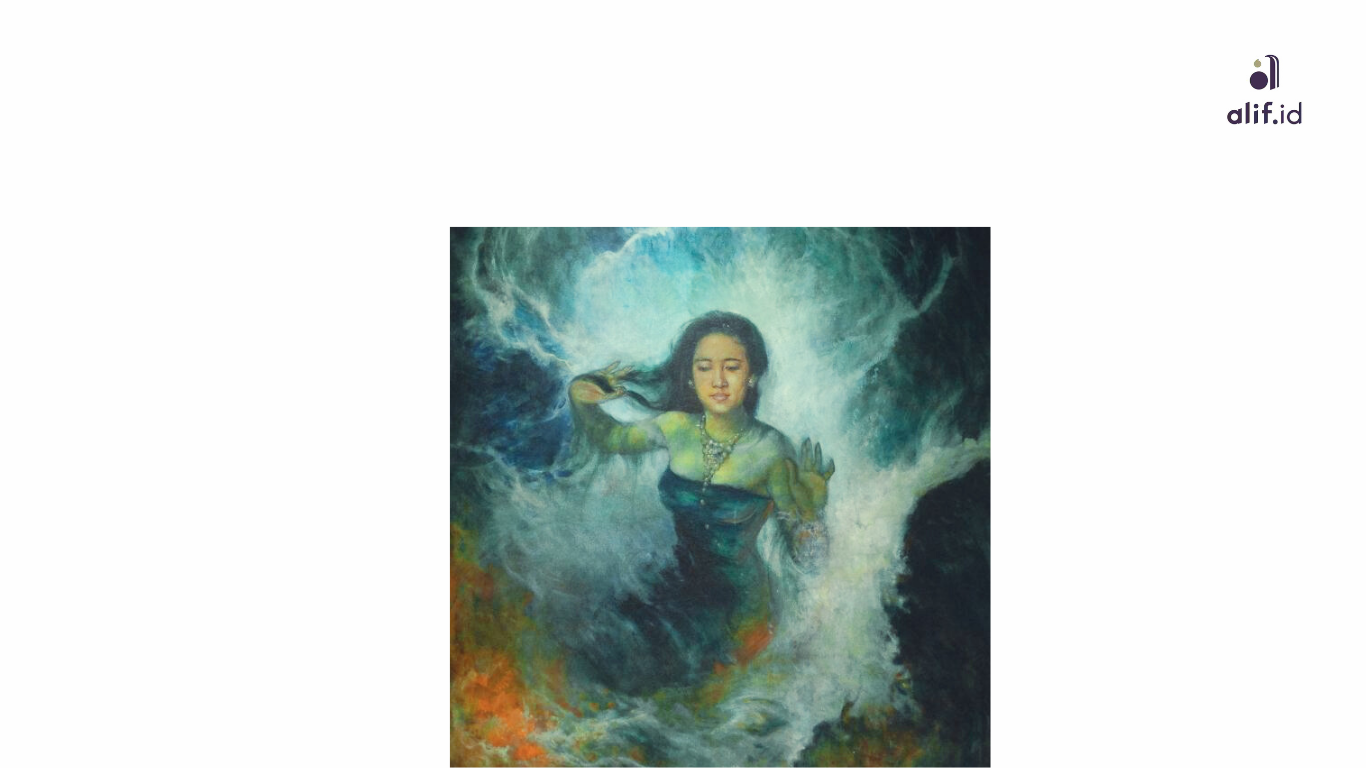Di masa kekuasaan Daulah Utsmaniyah, seorang gubernur bernama Dawud Basha merasa terpanggil untuk mempelajari bahasa Arab. Maka diundangnya seorang ulama dari negerinya untuk mengajarkannya ilmu nahwu. Tapi suatu hari, ia mendadak gelisah oleh satu kalimat yang selalu dijadikan contoh dalam ilmu tata bahasa:
“ضرب زيد عمرا” — Zaid memukul Amr.
Dengan nada tinggi dan kaki menghentak tanah, ia bertanya, “Apa kesalahan Amr sampai Zaid boleh memukulnya setiap hari? Apakah dia sebegitu rendahnya?”
Sang guru menjawab sebagaimana umumnya para ahli nahwu: bahwa kalimat itu hanya contoh, tidak ada yang benar-benar memukul atau dipukul. Tapi jawaban itu justru membuat sang gubernur murka. Ia memenjarakan sang guru. Dan ketika para ulama lain mencoba memberi jawaban yang serupa, nasib mereka pun sama: satu per satu dikurung. Madrasah-madrasah menjadi sunyi, ilmu seakan dihentikan oleh kemarahan satu orang yang merasa kalimat sederhana terlalu kejam.
Kegemparan ini menyebar, hingga akhirnya Dawud Basha mengundang para ulama dari Baghdad. Dari mereka, seorang alim paling sepuh dan tenang maju menyambut pertanyaan yang sama. Tapi kali ini ia tidak menjawab dengan dalil atau penjelasan teknis. Ia menatap sang gubernur dan berkata: “Kesalahan Amr adalah karena mencuri huruf wawu yang seharusnya milik Anda, wahai Gubernur.” Ia menunjuk nama ‘Amrun yang memiliki huruf wawu (ﻭ) setelah huruf ra, sementara nama Dawud hanya memiliki satu. “Maka para ulama nahwu menjadikan Zaid berhak memukul Amr sebagai hukuman atas pencurian itu.”
Dawud Basha pun tertawa puas. Amarahnya reda oleh satu jawaban yang bukan hanya cerdas, tapi juga tahu caranya merayu ego dengan humor. Ia menawarkan hadiah apa saja kepada sang ulama. Tapi sang alim hanya meminta satu hal: bebaskan semua ulama yang telah Anda penjarakan. Dan permintaan itu dikabulkan. Para ulama pulang, madrasah kembali hidup, dan bahasa Arab selamat dari amarah yang tidak paham bahwa kadang, kalimat hanyalah cara sederhana untuk belajar berpikir.
Saya sering memutar ulang kisah itu dalam kepala saya, lalu diam-diam bertanya: bagaimana jadinya jika ulama itu tidak menjawab dengan cerita? Mungkin para guru tetap terpenjara, dan pelajaran nahwu tinggal kenangan yang pahit. Tapi ia memilih jalan yang tidak biasa—bukan dengan dalil—, tapi dengan dongeng kecil yang menyelipkan kebenaran. Dan di situ saya belajar satu hal: bahwa cerita punya cara sendiri untuk tinggal di hati seseorang.
Kadang saya juga berpikir, mungkin kita terlalu sering mendengar dakwah dalam bentuk perintah—bukan cerita. Terlalu sering diberi tahu apa yang benar, tanpa diberi ruang untuk merasakan kenapa itu benar. Kita diajak taat, tapi jarang diajak duduk, mendengarkan, dan terlibat dalam kisah. Padahal, bukankah hati manusia lebih mudah disentuh oleh cerita?
Saya menyukai cerita bukan karena semua tokohnya baik, tapi justru karena mereka sering gagal. Nabi yang dibenci kaumnya. Anak muda yang tertidur berabad-abad. Perempuan yang menyusui di tengah ancaman penguasa. Dalam kisah-kisah itu, kita tidak sedang diajari, kita sedang diajak merasa. Dan entah bagaimana, dakwah yang disampaikan lewat cerita terasa lebih hidup. Ia tidak memaksa percaya. Ia hanya menemani, diam-diam, sampai kita sendiri yang ingin berubah.
Mungkin itu sebabnya al-Qur’an penuh dengan kisah. Bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diulang. Karena manusia berubah bukan hanya lewat logika, tapi lewat perasaan yang disentuh perlahan. Seperti Yusuf yang dikhianati saudara-saudaranya. Seperti Musa yang takut bicara. Seperti Luqman yang mengajari anaknya dengan lembut. Mereka tidak memberi fatwa. Mereka hanya hadir, dan dengan itu saja, kita belajar banyak hal tentang menjadi hamba.
Lagi pula pengarang kitab al-Yaqut an-Nafis juga pernah menyatakan bahwa cerita mempunyai maziyah tersendiri. Dan itulah mengapa beliau sering menyisipkan sebuah cerita di sela-sela kajian fikihnya.
Saya juga pernah mendengar ceramah seorang kiai, bahwa cerita dan humor dalam ngaji itu seperti sambal di atas nasi. Tidak wajib, tapi tanpanya, sesuatu terasa kurang. Kita tetap bisa makan tanpa sambal, tetap kenyang, tetap paham. Tapi bagaimana dengan rasa? Kadang justru tinggal di bagian yang pedas.
Tapi sambal tetaplah sambal. Kalau semua lauk diganti sambal, bukan kenyang yang datang, tapi maag. Humor yang berlebihan akan menguapkan makna. Cerita yang terlalu panjang bisa menenggelamkan pelajaran. Ngaji tidak harus selalu lucu, tapi akan lebih manusiawi kalau tidak terlalu kaku. Karena bisa jadi, yang membuat seseorang jatuh cinta pada ilmu bukan daftar istilah, tapi satu cerita kecil yang membuatnya merasa: “aku juga ada di situ.”
Intinya mah: ngaji tuh sambil cerita. Titik. Saya malah kepikiran lagi kalau seandainya waktu itu yang masyhur adalah “Zaid memeluk Amr,” mungkin sejarah nahwu jadi lebih romantis. Tapi ya nasib, yang ada malah jadi adegan smackdown tiap bab. Saya juga bingung, ini pelajaran bahasa atau kompetisi WWE. Dahlah.