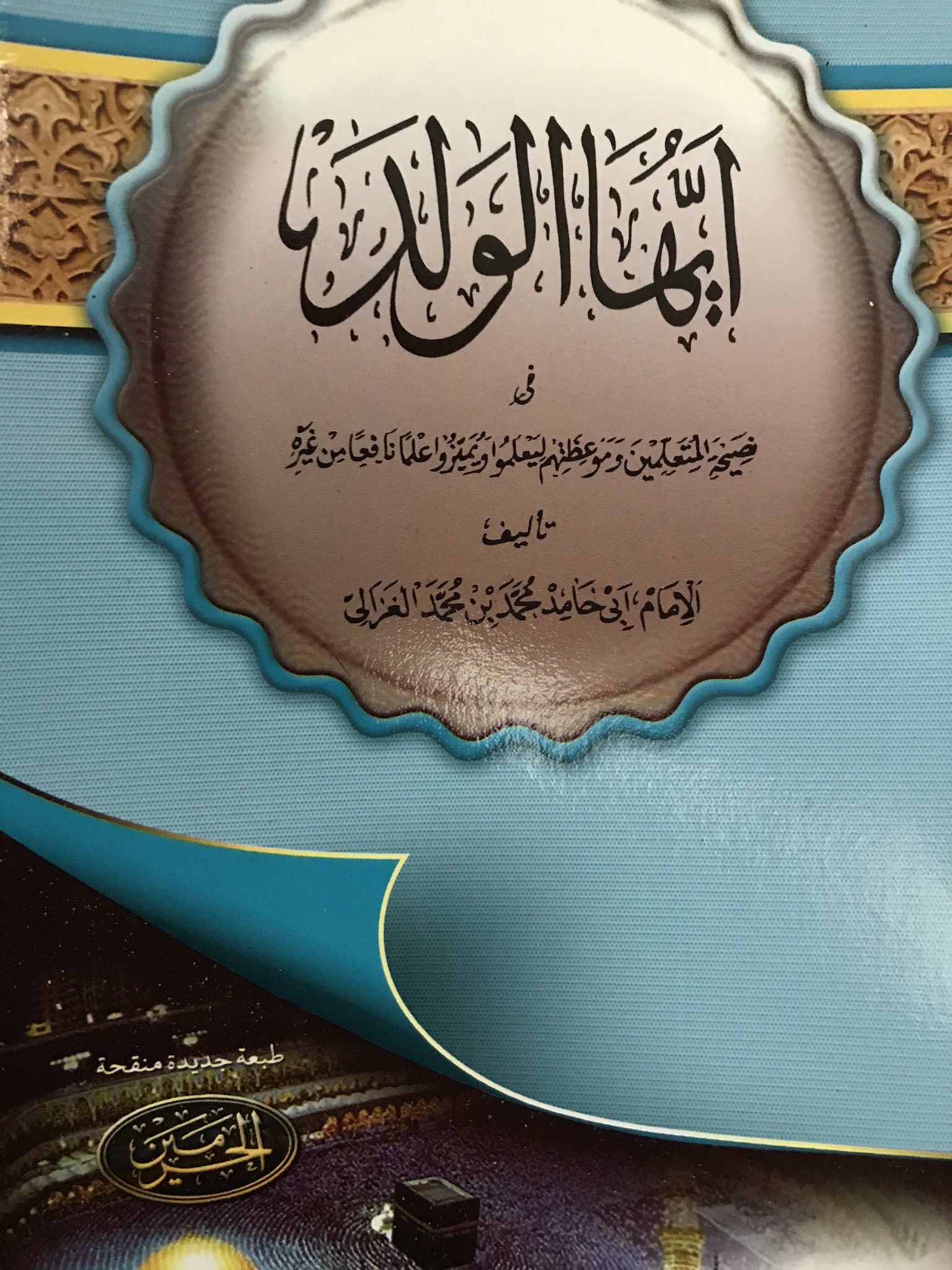Secara tipikal Ibnu Arabi dianggap sebagai seorang sufi. Anggapan ini relatif benar jika memahami istilah sufisme untuk menunjuk pada tambatan pemikiran dan praktik Islâm yang menekankan pengalaman langsung dari objek-objek iman.
Terlepas dari perbedaan mengenai asal-usul kata yang membentuk artinya, yaitu ṣafa (suci); ṣaf (penghuni masjid); sophia (hikmah); atau sûf (bulu domba), tasawuf mengandung makna yang dalam yang merujuk pada kebersihan batin, mendekatkan diri pada Tuhan, menjauhkan diri dari kesombongan dan ketamakan terhadap daya tarik dunia.
Tasawuf secara umum adalah falsafah hidup dan cara tertentu dalam tingkah laku manusia dalam upaya merealisasikan kesempurnaan moral, pemahaman hakikat realitas, dan kebahagian rohaniah.
Dari sekian pengertian tasawuf (sufisme) di atas adalah benar jika dikatakan bahwa Ibnu Arabi adalah seorang tokoh sufisme. Karena jika kita menyimak kembali riwayat hidupnya, adalah sosok yang memilih jalan ruhani yang penuh kesederhanaan pada saat kenikmatan duniawi mengelilinginya. Harta, jabatan, dan segala kemewahan ditinggalkannya demi mencari kebahagiaan hakiki.
Dalam banyak literatur, Ibnu Arabi memang lebih sering dimasukkan dalam ketegori tokoh sufi atau dalam disiplin bidang tasawuf. Tetapi jika ada yang menyebutnya sebagai seorang filosof, seperti hanya AE. Affifi yang memandang Ibnu Arabi dari sudut pandang filsafat, maka tidaklah mudah untuk menyangkalnya. Hal ini dikarenakan corak pemikirannya yang mensintesakan antara tasawuf dan filsafat.
Dari segi epistemologi, sufisme, atau tasawuf adalah hasil dari proses mujâhadah (mengekang hawa nafsu), musyâhadah (pandangan bathin), dan intuisi. Sedangkan filsafat adalah hasil dari cara kerja akal (logika) dan argumentasi yang kuat. Keduanya mempunyai objek yang sama, yakni alam beserta isinya, manusia serta perilakunya, dan eksistensi Tuhan.
Pemaduan kedua unsur ini, yakni filsafat dan tasawuf menjadi sinergi luar biasa yang melahirkan corak berpikir rasional transendental. Inilah yang mewarnai corak pemikIran Ibn ‘Arabi. Hasilnya adalah sebuah sintesa antara perspektif nalar dan spiritual.
Dalam wacana ilmu tasawuf, dibedakan adanya tiga corak atau aliran pemikIran sufisme, yaitu: Tasawuf akhlaqi, tasawuf ‘amali dan tasawuf filosofis atau falsafi. Kemudian pembagian tiga corak ini disingkat oleh Prof. H.A. Rivay Siregar menjadi dua aliran yaitu tasawuf sunni (gabungan antara tasawuf akhlaqi dan tasawuf amali) dan tasawuf filosofi.
Keduanya mempunyai sejumlah kesamaan yang prinsipil di samping perbedaan-perbedaan yang mendasar. Persamaannya adalah bahwa keduanya mengaku bersumber dari Alquran dan Sunnah dan sama-sama berjalan dalam maqâmât dan aḥwâl. Perbedaanya adalah mengenai kedekatan antara sufi dengan Tuhannya.
Penganut tasawuf sunni mengatakan bahwa sedekat apapun antara seorang manusia dengan Tuhannya tidak mungkin tumbuh karena tidak satu esensi. Sedangkan penganut tasawuf filosofis mengatakan bahwa manusia berpadu dengan Tuhan karena manusia tercipta dari esensi-Nya. Selain itu perbedaan bersumber dari perbedaan instrumen yang digunakan dalam memecahkan persoalan.
Di satu pihak, tasawuf sunni cukup menggunakan dalil-dalil naql dari ajaran Islâm, cenderung ortodoks dan sederhana dalam pemikIran. Di lain pihak tasawuf filosofis sangat gemar terhadap ide-ide spekulatif dengan menggunakan analisis filsafat yang mereka kuasai, baik filsafat Timur maupun Barat.
Cikal bakal kemunculan dua aliran dalam tasawuf ini, terjadi pada abad ketiga dan keempat Hijriyah. Pada saat itu muncul dua alIran dalam tradisi asketisme. Aliran pertama melandaskan diri pada Alquran dan sunnah dan memegang tradisi kalâm dan fiqih dengan kuat. Aliran inilah yang menjadi pangkal munculnya tasawuf sunni.
Aliran kedua adalah aliran yang selain berprinsip pada Alquran dan sunnah juga pada tradisi di luar Islam yang cenderung pada hal-hal yang metafisis yang disebut union mystica. AlIran ini sering menunjukkan keganjilan (syaṭahat) sehingga menimbulkan pertentangan dan dianggap menyimpang dari ajaran Islâm. Aliran inilah yang menjadi awal munculnya tasawuf filosofis.
Kemudian pada abad kelima Hijriyah, aliran sunni mengalami masa kejayaan di tangan Abû al-Ḥasan al-Asy’ârî (w. 324 H.) dengan teologi Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah dan mengeritik keras terhadap keekstriman tokoh sufi seperti Abu Yazid al-Busthami dan al-Hallâj, yang ungkapan-ungkapannya terkenal ganjil.
Pada abad kelima Hijriyah ini tasawuf aliran filosofis tenggelam dan baru muncul kembali dalam bentuk lain, yaitu pada pribadi para sufi yang juga filosof pada abad keenam Hijriyah dan setelahnya. Mulai saat itulah tasawuf filosofis berkembang lagi dan sampai pada puncaknya, aliran ini melahirkan sesosok sufi filosofis yang menggemparkan pada abad-abad berikutnya yakni Syaikh al-Akbar Ibn al-‘Arabi. Bahkan sampai saat ini terus menjadi bahan kajian yang aktual.
Umumnya para sufi filosofis begitu gigih mengompromikan ajaran-ajaran filsafat yang berasal dari luar Islâm ke dalam ajaran mereka, serta menggunakan terminologi-terminologi filsafat, tetapi maknanya telah disesuaikan dengan ajaran tasawuf mereka.
Para sufi yang juga filosof ini mengenal dengan baik filsafat Yunani seperti pemikiran-pemikiran Socrates, Plato, dan aliran Stoa (didirikan oleh Zeno), serta aliran Neoplatonisme dengan filsafatnya tentang emanasi. Selain itu mereka juga mempelajari filsafat-filsafat Timur Kuno, baik dari Persia maupun India, serta menelaah karya-karya filofos Islâm, seperti al-Farâbî, Ibn Sina, dan lain-lain. Begitu pula yang dilakukan Ibn ‘Arabi .
Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pemikiran Ibn ‘Arabi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni tasawuf dan filsafat, meskipun tidak secara murni. Jika dalam membahasnya kita menggunakan kaca mata tasawuf, maka pemikirannya dapat dikategorikan sebagai tasawuf filosofis. Jika menggunakan kaca mata filsafat, maka pemikirannya dikategorikan filsafat mistis.
Kita dapat melihat dari segi tasawuf karena ia menjalani laku kehidupan rohani seperti sufi pada umumnya dan kehidupannya dipenuhi pengalaman spriritual yang agung dan secara epistemologis ia mendapatkan pengetahuan dari intuisi, kasyf (penyingkapan) dan zauq (rasa).
Sedangkan dari sudut pandang filsafat, Ibn ‘Arabi dapat disebut seorang filosof, karena selain dia paham betul dengan teori-teori filsafat dari berbagai unsur sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa filsafat, tetapi juga pemikIrannya menambah pada objek-objek kajian filsafat, yaitu problem metafisika.
Menurut A.E. Affifi, secara keseluruhan Ibn ‘Arabi dapat digambarkan sebagai filosof bertipe tidak beraturan dan eklektik. Ia mengatakan bahwa gaya Ibn ‘Arabi yang ambiguity (mendua) disebabkan paling tidak oleh tiga hal. Pertama, Ibn ‘Arabi menggunakan istilah-istilah yang diambilnya dari berbagai sumber, seperti The Good-nya Plato, The One-nya Plotinus, Substansi Universal-nya Asy’ari dan Allah-nya Islâm. Kadang-kadang ia menggunakan satu kata untuk beberapa makna, misalnya kakikat, diartikan sebagai realitas, kadang esensi, kadang suatu ide atau suatu ciri.
Kedua, bahwa Ibn ‘Arabi selalu berusaha merekonsiliasikan dogma-dogma ortodoks Islam dengan pemikiran panteistik. Ketiga, ia menggunakan bahasa yang puitis dan fantastis sehingga mengaburkan pemikiran yang logis dan ketat.
Siapapun tidak menyangkal bahwa memahami pemikiran Ibn ‘Arabi bukanlah hal yang mudah. Meskipun karya-karyanya yang berjumlah ratusan dapat memberikan gambaran yang utuh buah pemikirannya, tetapi ungkapan-ungkapan yang digunakan bersifat simbolis dan mengandung makna yang begitu dalam sehingga sulit dimengerti oleh orang-orang yang mempelajarinya.
Tidak mengherankan jika pada suatu waktu di musim dingin di parlemen Mesir terjadi perdebatan seru di tengah para tokoh pemikir, mengenai boleh tidaknya salah satu karya Ibn ‘Arabi diterbitkan secara bebas. Sebagian berpendapat boleh, sebagian melarangnya karena dikhawatirkan menyesatkan pembacanya.
Memang diperlukan sikap kritis dan ekstra hati-hati karena pembahasannya merambah hal-hal yang sangat fundamental dalam pemikIran, yaitu spekulasi tentang hakikat segala realitas. Itulah mengapa karya-karyanya cenderung dicurigai dan dianggap membahayakan keimanan, terutama di kalangan sunni yang notabene dianut oleh mayoritas umat Islâm.
Namun lain halnya bagi sejumlah sarjana, yang sebagian berasal dari kalangan Syi’ah dan sebagian dari luar Islâm. Mereka memiliki sikap yang lebih apresiatif terhadap konsep-konsep tasawuf filosofis, termasuk di dalamnya pemikIran Ibn ‘Arabi . Hal ini antara lain disebabkan karena pandangan para sufi dianggap lebih liberal dan mengandung pesan universal bagi bentuk agama apapun, sehingga adanya keragaman di dunia ini tidak menjadi halangan untuk terjalinnya harmoni kehidupan, karena hanya ada satu realitas yang mendasarinya.