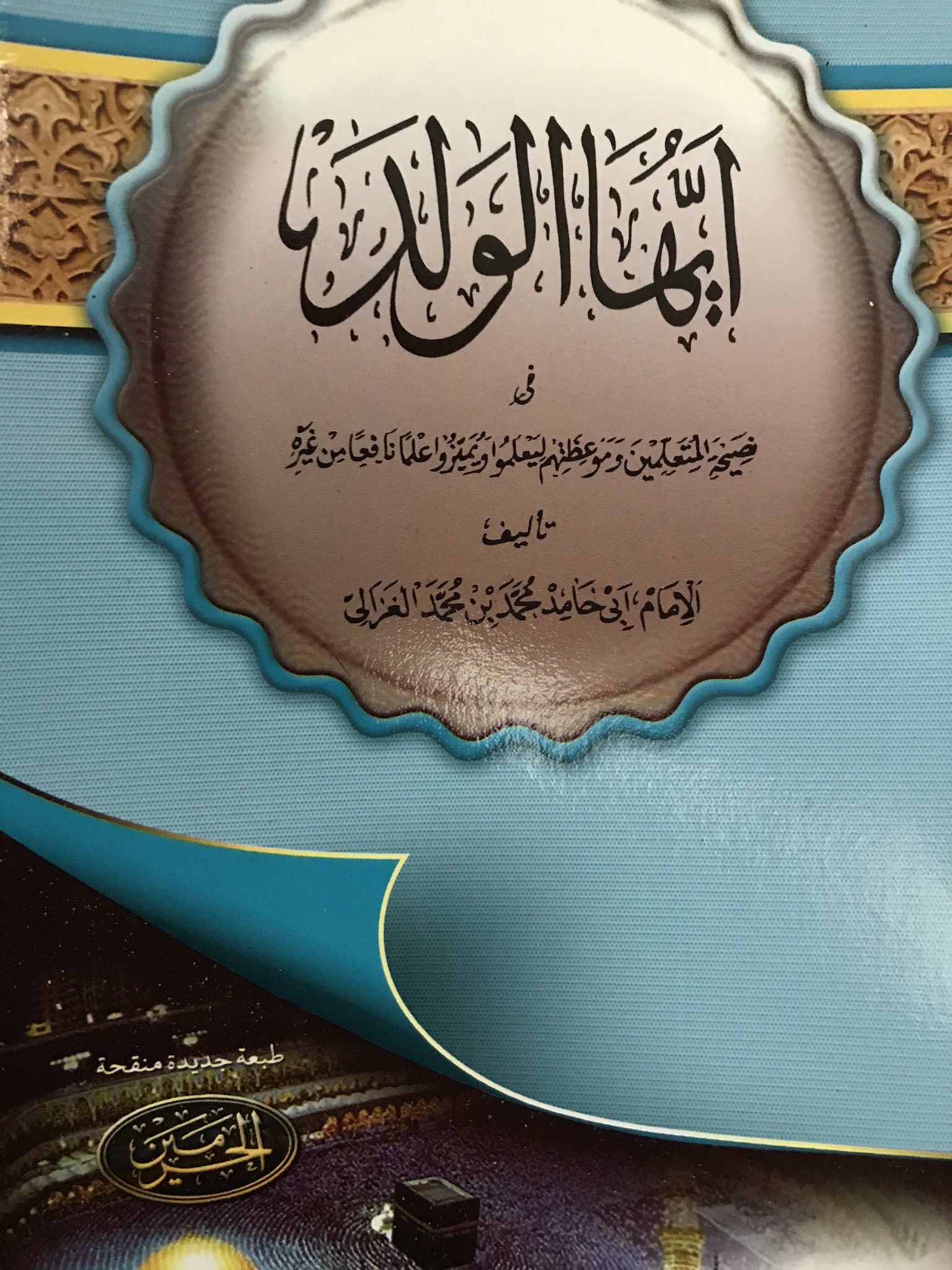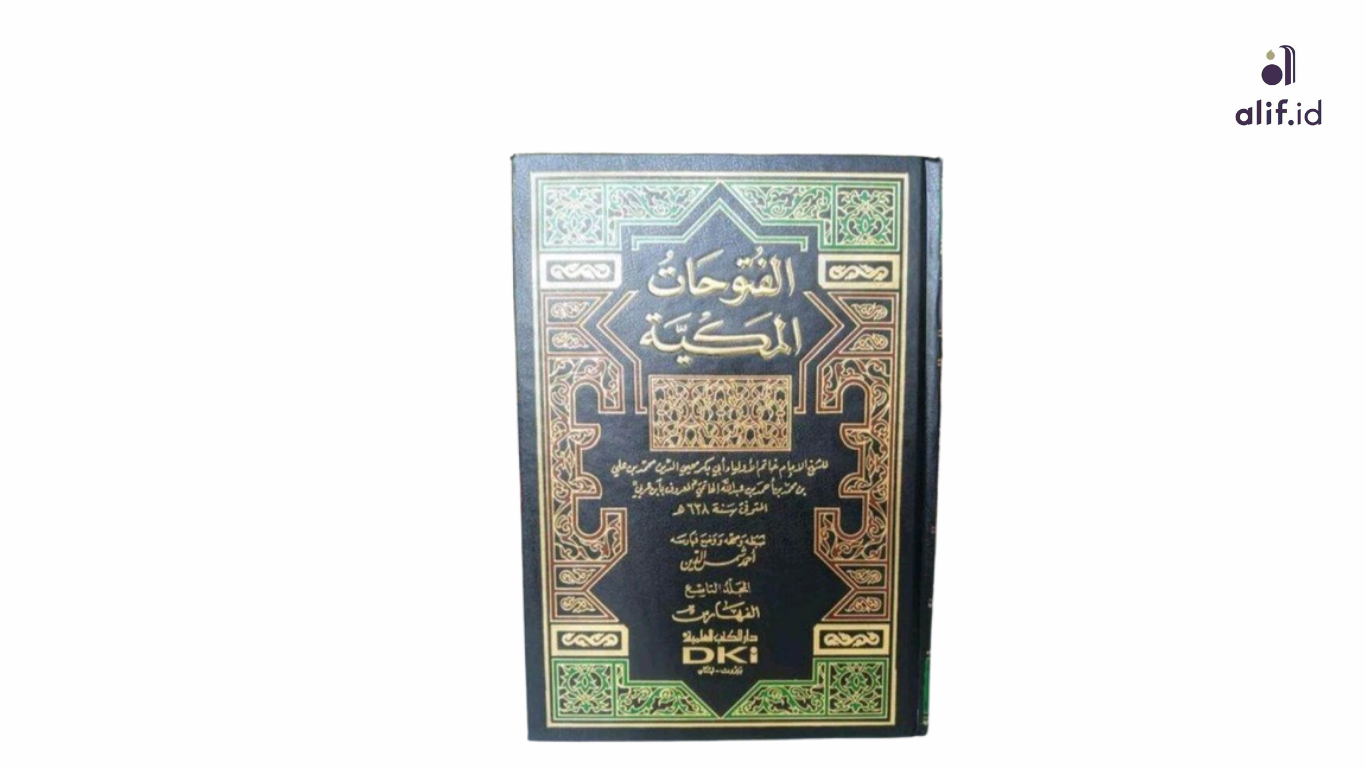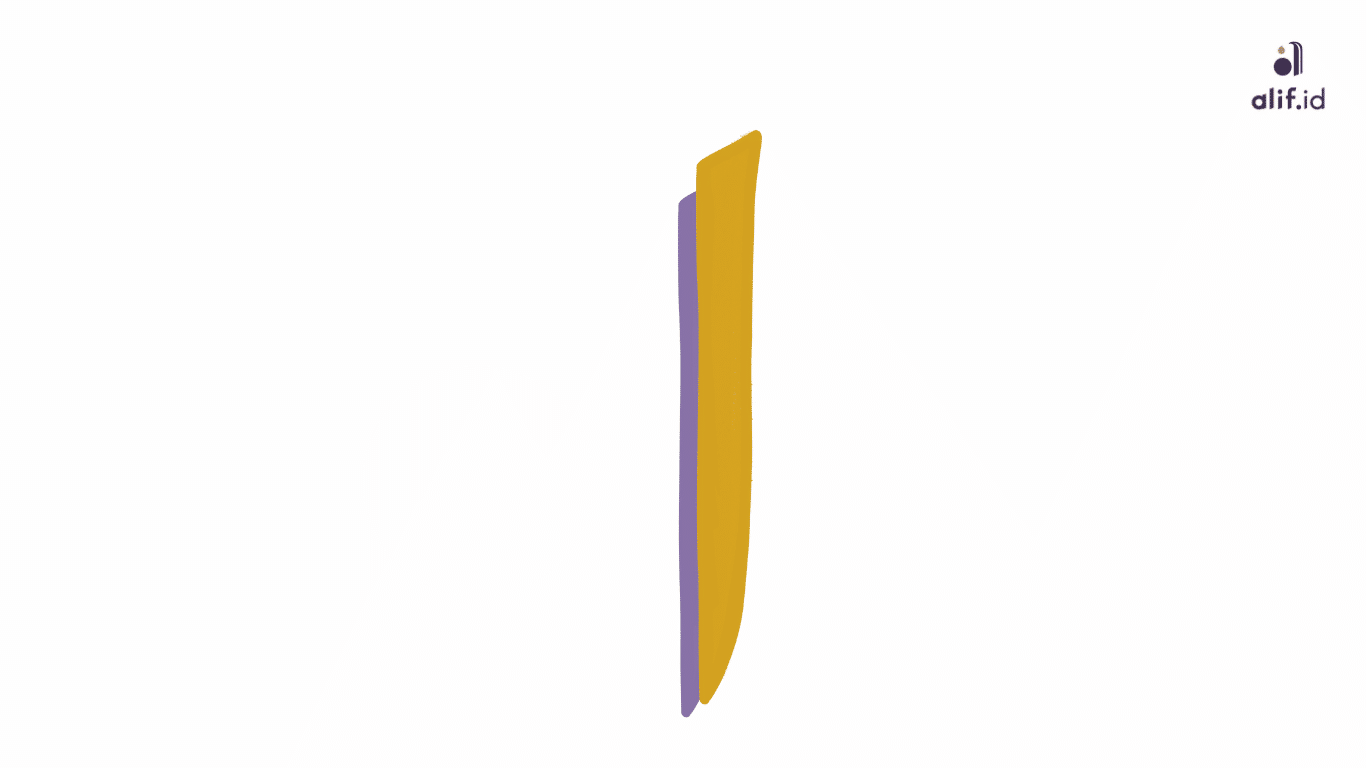Dalam aspeknya yang mana pun, agama tidak bisa disebut profan. Namun banyak penganutnya – setidaknya dalam masa-masa belakangan ini – secara bersama-sama membentuk suatu wilayah profanitas, yang cenderung memandang segala sesuatu pada nilai luarnya, suatu wilayah yang seakan-akan hanya berdimensi dua belaka. Profanitas adalah suatu kelahiriahan yang hampa, setidaknya menurut saya.
Terbebasnya tasawuf dari hal tersebut (keprofanan) terungkap dalam kata-kata Alquran, “Katakan Allah, dan kemudian biarkan mereka tenggelam dalam omongan kosong mereka.” Seperti telah kita lihat, Nama Allah adalah kata mulia (kalimah tayyibah) yang oleh Alquran diibaratkan pohon yang baik.
Omongan kosong yakni ucapan lahiriah yang hampa, adalah kalimat hina (kalimah khabisah) yang oleh Alquran diserupakan dengan pohon yang buruk, yang telah dicabut beserta akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) berdiri sedikit pun.
Agar lebih jernih, dipaparkan bahwa tasawuf tidak begitu saja – dan memang tidak akan dapat – menolak kelahiriahan, karena “Yang Lahir” itu merupakan satu di antara nama-nama Ilahi. Akan tetapi dalam realitas, “Yang Lahir” dan “Yang Batin” itu satu. Bagi sufi, semua kelahiriahan harus dipertalikan dengan yang batin, yang merupakan cara pengungkapan lain bahwa baginya dunia ini adalah dunia simbol-simbol.
Yang ditampilkan oleh tasawuf adalah kelahiriahan atau profanitas yang ‘independen’, yang di sini sang ego menumpahkan perhatiannya pada sesuatu semata-mata karena ‘sesuatu’ itu sendiri. Namun secara metode, karena kelahiriahan telah menjadi ‘watak kedua’ manusia, keseimbangan dibutuhkan dengan menyingkirkan semua kelahiriahan itu, secara temporer.
Dari titik pandang inilah, Syaikh Hatim al-Asamm mengatakan, “Setiap pagi setan bertanya kepadaku, apa yang akan aku makan, apa pula yang akan aku kenakan dan di mana aku akan tinggal? Aku menjawab, aku akan makan ajal, mengenakan kafan, dan tinggal di dalam kubur”.
Tasawuf itu sentral, dimuliakan, menghunjam, dan misterius. Ia tidak bisa ditawar-tawar, serba tepat, kokoh, musykil, terpencil – dan dibutuhkan. Aspek terakhir ini berkaitan dengan keinklusifannya, sedang atribut-atribut lainnya merupakan aspek-aspek keeksklusifannya.
Keempat aspek pertama dapat dipadukan dalam kata ‘sakral’. Dalam menyingkirkan yang profan, tasawuf tak hanya mengeliminir ateisme dan agnotisisme, tetapi juga eksoterisme yang menganggap dirinya serba cukup.
Tasawuf berhak untuk tidak dapat ditawar-tawar, sebab ia didasarkan pada keyakinan-keyakinan, bukan pada pendapat-pendapat. Ia memikul kewajiban untuk tidak bisa diganggu gugat, karena mistisisme itulah satu-satunya gudang kebenaran dalam pengertian sebenarnya, terutama menyangkut Yang Maha Mutlak, Yang Maha Agung, dan Yang Maha Abadi.
Dan, “Jika garam telah kehilangan rasa, dengan apa ia harus diasinkan?” Tanpa mistisisme, realitas (haqiqah) tidak bakal punya suara di dunia ini. Tidak akan ada rekaman tentang hierarki yang benar, dan tidak pula ada saksi bahwa ia senantiasa dilanggar.
Tasawuf itu teguh, karena ia tidak lain daripada sarana Ilahi pencapaian keberhasilan untuk melampaui segala yang berasal dari Yang Mutlak. Nabi berkata tentang syahadah yang merupakan intisari doktrin dan metode sufi: “Jika tujuh langit dan tujuh bumi diletakkan di salah satu sisi neraca, bobot keduanya akan dikalahkan oleh la ilaha illa Allah di sisi lainnya”.
Akan tetapi, kekuatan-kekuatan aktif semacam ini membutuhkan keselarasan dari kekuatan pasif jiwa yang mendorong seseorang untuk bertindak. Dengan kata lain, ia menuntut kesabaran dan ketabahan yang akan meluaskan jangkauan tindakan mereka sehingga memadai untuk merasakan pengaruh dalam suatu wilayah dan waktu tertentu.
Kegagalan memenuhi kebajikan-kebajikan ini, yang merupakan sebagian dari kualifikasi untuk memasuki sebuah tarekat sufi, dapat mendatangkan bahaya besar dalam pengamalan tasawuf. Ini sebagaimana terjadi dalam pertarungan antara kekuatan dan kelemahan yang tak berimbang – tak ubahnya seperti “anak-anak bermain api”.
Mungkin benar bahwa setiap mukmin cepat atau lambat akan menjadi seorang sufi. Jika bukan di dunia ini, ya di dunia yang akan datang kelak. Tidak semua orang mampu ketika mencoba menempuh jalan mistik, dan “syukurlah” jarang yang tertarik untuk mencobanya. Bisa bahaya. Bahayanya terletak pada apa yang dinamakan “kasus-kasus garis-perbatasan”. Ia bisa terjebak.
Jiwa Mubtadi
Jiwa pendatang baru (mubtadi) cenderung tidak murni. Seorang mubtadi mustahil memiliki dorongan yang sepenuhnya murni ketika memasuki sebuah tarekat. Aspirasi yang murni bisa berbaur dengan ambisi pribadi. Zikr itu sendiri akhirnya menepis “butiran padi dari sekamnya”. Aspirasi menyambut zikr dengan suka cita, sebaliknya ambisi memunculkan perlawanan.
Dan ketika jiwa telah terbelah menjadi dua kubu dalam kecamuk jihad akbar, neraca harus lebih diberatkan pada perjuangan menentang musuh-musuh ruh. Tanpa kecenderungan hati yang tepat untuk memulai, biasanya jiwa tidak akan sampai pada titik penentuan untuk memasuki suatu tarekat. Bagaimana pun juga, bukan mustahil bahwa seseorang tertarik pada tasawuf karena alasan-alasan yang sangat keliru.
Dari berbagai teks dan formulasi otoritatif tentang neraca ukuran Ilahi, terbaca bahwa doktrin tentang “kesatuan wujud”, berikut doktrin “identitas tertinggi”, dalam hal-hal tertentu bisa menjadi jalan tak langsung menuju kemurkaan. Bagi penganut awam, jauh lebih baik mengesampingkan doktrin ini, daripada membiarkannya bekerja sebagai penenang untuk bertakwa kepada Tuhan, sementara pada saat yang sama doktrin itu menyeretnya ke dalam pertentangan batin, padahal ia tidak memiliki kekuatan.
Intelektual menyaksikan identitas tertinggi itu seolah-olah menembus tirai fana, peluruhan, jiwa yang menolak ambisi. Sebaliknya seseorang yang kurang intelek namun congkak akan menghasilkan jiwa tak tercerahi yang bahkan tidak mampu menyelami dirinya sendiri, sehingga ragam pengetahuan apa pun berada di luar jangkauannya. Bagi jiwa semacam ini, kontak dengan tasawuf dan penemuan doktrin serta sasarannya dapat membuahkan bencana dan bentuk ‘kekerasan hati’ yang amat sulit disembuhkan.
Manusia profan hanya menyadari sebagian kecil saja dari jiwanya sendiri. Karena keseluruhan substansinya harus digali, praktik-praktik mistik tak jarang mengantar kepada pengalaman-pengalaman bukan spiritual melainkan hanya bersifat psikis, meski tampak menakjubkan.
Bahaya terbesar ialah kalau titik kesadaran individual ini dipandang sebagai diri tertinggi dan bahwa seluruh doktrin ini, berikut pengalaman-pengalaman para wali yang terekam secara tradisional, ditafsirkan demi kepuasan diri sebagai pengukuhan dan santapan penipuan diri. Bahaya-bahaya tersebut dapat sepenuhnya dihindari dengan kepatuhan kepada seorang guru ruhani – dengan bersikap “seperti jenazah di tangan orang-orang yang memandikannya”, demikian menurut para sufi.
Eksklusivitas tasawuf
Keeksklusifan dalam tasawuf adalah suatu cara pendalaman, seperti menunjuk teluk yang menantang manusia untuk menyeberanginya. Bagi beberapa jiwa, tantangan semacam ini bisa lebih bernilai dari profesi. Makin dimuliakan suatu pendirian, semakin universal ia. Satu contoh adalah penyebaran Islam di berbagai tempat tertentu -India, misalnya – itu terjadi (sebagian) berkat pengagungan mistisismenya.
Para ahli hukum dan ahli kalam memiliki tanggung-jawabnya sendiri. Para mistikus Islami “dibebaskan” dari upaya menarik pengikut dan penyampaian ajaran syariat, dan bebas pula untuk menganut suatu titik pijak yang eksklusif. Para mistikus mengatakan, “Hayatilah tasawuf dengan sungguh-sungguh dan mendalam, atau tinggalkanlah ia”.
Kebanyakan tuturan yang sampai kepada kita merupakan tipikal tasawuf yang eksklusif. Satu contoh adalah perkataan yang keluar dari bibir wanita zahid ternama Islam, Rabi’ah al-Adawiyyah. Ketika seorang lelaki berkisah bahwa selama 20 tahun dia tidak pernah melakukan dosa, Rabi’ah berkata, “Wahai anakku, keberadaanmu itu sendiri adalah suatu dosa yang tidak tertandingi oleh dosa mana pun juga”.
Dalam ungkapan ini, tercakup semua kualitas eksklusivitas. Rabi’ah menggugurkan konsesi-konsesi bagi kebodohan dan kedunguan, atau kelemahan dan pembatasan. Dengan cercaan tajam atau paradoks, ia memaparkan hak-hak Sang Mutlak, mengorbankan titik pandang lainnya. Hukum serta teologi praktis diabaikan begitu saja.
Hal yang sama diucapkan al-Hallaj, “Barangsiapa bersaksi bahwa Allah itu esa, berarti meng-ada-kan sesuatu di samping Dia”. Ungkapan itu dapat pula diterjemahkan, “Mengatakan satu Tuhan berarti menyembah dua Tuhan”. Tampak rumit, ya.
Isa pernah bertanya, “Mengapa kalian menyebutku baik?”. Muhammad pernah bersabda, “Setiap bagian tubuh anak Adam adalah makanan api neraka, kecuali yang merupakan bekas-bekas sujud”. Dalam kedua ujaran profetik ini, terkandung hierarki makna-makna pada berbagai tataran berbeda dalam kesesuaiannya dengan aspek keinklusifan mistisisme sebagai bagian utuh agama.
Segenap kemungkinan penafsiran bisa disingkirkan saja, sehingga orang tak mencobanya dan bingung.