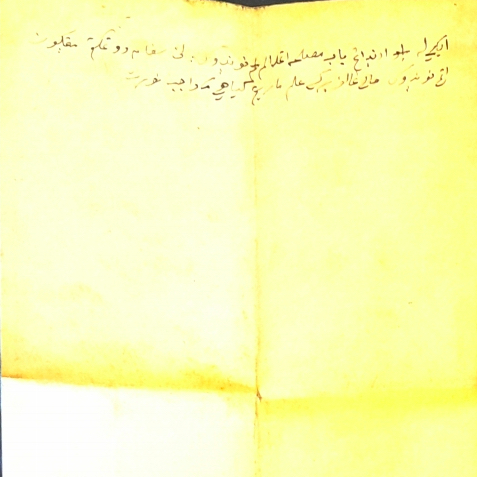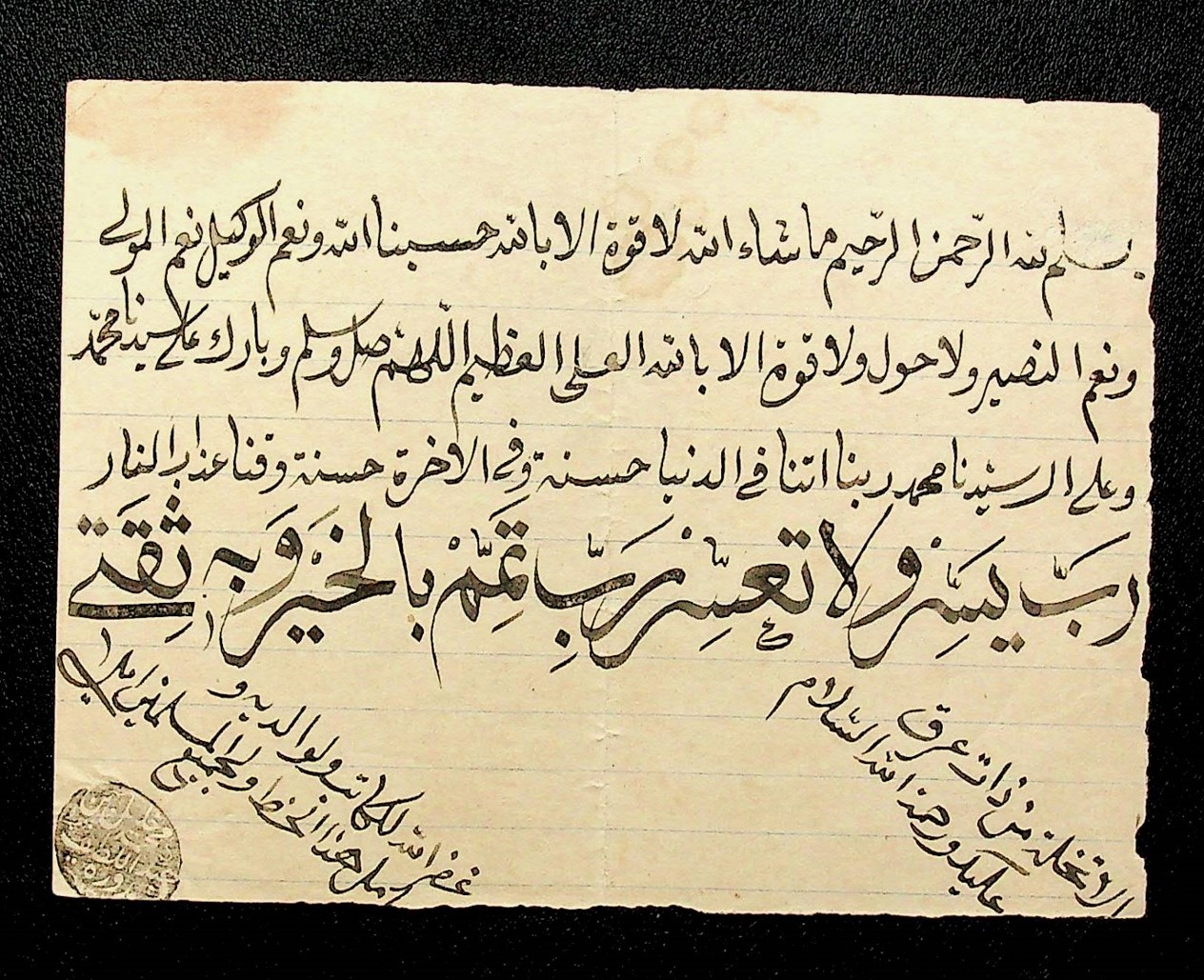Sejumlah pelanggan lokal yang duduk dekat jendela, di seberang pintu masuk warung makan “Toko Pak Camat” tampak lahap menyantap makanan yang terhidang.
Saya mengamati dengan tanpa terlalu sengaja, karena posisi saya memang tepat satu meter di luar pintu, menunggu antrian untuk makan di warung yang terletak di Schoolstraat 97, 2251 BG Voorschoten, Belanda itu. Ya, kami harus mengantre karena meja telah penuh. Kami diminta menunggu sekitar 20 menit.

Ketika saya menengok ke arah pintu, pas melihat mereka melahap aneka makanan itu. Tentu perut langsung menyahut melihat sapaan menu yang tersaji di meja. Apalagi mengingat perjalanan menuju Toko Pak Camat serasa “penuh tantangan”.

Gak perlu dibayangkan, cukuplah dirasakan, begini: saya, Ginanjar Sya’ban, dan Afnan Anshori sudah diguyur hujan sejak siang pada 5 Juni 2022 itu (salah sendiri tidak mengecek prakiraan cuaca sehingga tidak sedia payung sebelum hujan).

Namun, tekad untuk sampai ke Breda harus dipenuhi. Saya mengingat Perjanjian Breda, kesepakatan antara Inggris dan Belanda terkait penyerahan Manhattan kepada Inggris, yang sebagai kompensasinya Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda pada 31 Juli 1667. Perjanjian ini mengakhiri perang Anglo-Belanda kedua. Meski akhirnya hanya nongkrong di kafe dan jalan-jalan di seputaran stasiun kereta karena hujan makin deras, setidaknya kami sudah tiba di Breda.
Dari Breda, kami kembali kuatkan tekad untuk makan bakso di Toko Pak Camat. “Dari stasiun Voorschooten itu cuma 700 meter,” kata Afnan, yang Ketua PCINU Belanda itu.
Baiklah, 700 meter tidaklah jauh. Tapi jalan kaki 700 meter di tengah guyuran hujan (meski tidak deras)? Tapi, baiklah, kami terus berjalan, sedikit salah arah (peta dari Google memang tidak selalu tepat benar), berteduh sebentar, berjalan lagi.

“Ini sih sudah satu kilometer,” kataku. “Ini kok posisinya aneh ya,” sahut Afnan sambil menunjukkan Google Map. “Nah, itu ternyata sudah di depan kita,” tukas Ginanjar yang matanya ternyata lebih awas, mungkin karena filolog itu terbiasa memelototi manuskrip. Alhamdulillah…
Akhirnya, Bakso
Siang makin beringsut ke petang. Sudah jam 18.00. Sejumlah pelanggan sudah keluar–masuk warung milik Budi Cahyono (43), warga Madura yang sudah 25 tahun menetap di Belanda.
Mereka membeli makanan untuk dibawa pulang. Mbungkus. Bukan hanya karena ruang untuk “dine in” memang terbatas, namun juga karena warga sekitar memilih untuk makan di rumah.

Setelah 15 menit berlalu, kami dipanggil untuk masuk. Rupanya pelanggan di meja pojok telah selesai makan. Akhirnya. “Baksoooo kami menunggumu…”.
Kami berpapasan dengan pelanggan sebelumnya, dan ternyata mereka adalah keluarga Pak Naf’an Sulchan, sahabat Gus Dur sewaktu belajar di Mesir dan kini Syuriah PCINU Belanda. Alhamdulillah lagi. “Oh ini Afnan ya,” kata Bu Naf’an. Kami pun bersalaman dan tak lupa meminta foto bersama.

Setelah dapat tempat duduk, saya buru-buru membuka menu. Selain karena lapar perut, juga lapar “narasi”, ha-ha-ha, karena sejak sehari sebelumnya sudah diberi tahu bahwa bakso dan iga bakar di Toko Pak Camat sangat enaaaak.

Yak, kami pun memesan dua menu itu, tiga porsi bakso dan satu porsi iga bakar (karena isinya cukup banyak dan termasuk nasi goreng pula). Oh ya, plus mendoan satu porsi isi lima.

Saat sedang menunggu pesanan datang, pelanggan lokal di dekat pintu telah selesai bersantap siang. “Lima bintang untuk semua masakan. Enak semua,” kata seorang di antara merekat, sedikit berteriak.

Seorang yang lain mendekati kasir untuk membayar sambil mengobrol dengan Budi dalam bahasa Belanda yang tidak saya mengerti sedikit pun. Sejauh ini cuma paham in, uit, zuid, ik houd van je, dan dankjewel.
Gisma, mahasiswa master di The International Institute of Social Studies (ISS) The Hague (satu grup dengan Erasmus University Rotterdam) yang bekerja sambilan di warung itu dengan cekatan menggesek kartu. Sat set. Terbayar. Selesai.

Gisma ini lulusan Planologi ITB yang hampir menyelesaikan masternya di ISS. Ia hanya bekerja pada Sabtu dan Minggu, masing-masing delapan jam. Lumayan untuk menambah uang jajan. Apalagi jika banyak pelanggan memberi tips.

Baru Buka Enam Bulan
Warung makanan Indonesia bisa selaris itu, tentu karena sudah lama buka teruji masakannya. Begitu saya membatin. Namun, dugaan saya ternyata salah. “Saya baru buka enam bulan,” kata Budi. Daebak, sahut saya spontan, tiba-tiba mencuat bahasa Korea.

Saya hendak bertanya lebih jauh, namun pesanan sudah datang. Alhamdulillah. Sejujurnya saya katakan, bakso dan iga bakarnya memang enak.
Kuah kaldu baksonya berasa, dan daging iganya sangat empuk. Bumbu iganya pas manis dan asinnya, dan rasa mericanya pun terdeteksi.

Mendoannya gurih dan renyah, lebih pas kalau dikatakan tempe goreng tepung. Nasi gorengnya khas nasgor Jawa. Meski saya lebih berselera dengan nasgor di resto-resto Cina, tapi yang ini cocok juga.
Kami selesai makan menjelang tutup warung, jadi sekalian saja kami numpang salat dan setelah itu mengobrol santai.
Kali ini kami ditraktir dawet ayu khas Banyumas yang ada buah nangkanya sebagai teman mengobrol. Manisnya pas buat saya yang tidak terlalu suka makanan manis.

“Saya baru enam bulan buka warung, tapi saya sudah punya pengalaman lama bekerja di resto. Peralatan, bumbu, manajemen, tinggal menerapkan,” kata Budi, meneruskan obrolan yang terputus tadi.
Budi pindah dari Madura ke Belanda saat berusia 16 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya yang bekerja di Belanda (awalnya ikut kapal pesiar lalu bekerja macam-macam di darat) mengajaknya turut.

“Saya itu malas belajar dan tidak naik kelas. Pikiran saya memang mau nyusul ayah. Pas kebetulan ayah menawari, saya langsung berangkat. Saya pikir enak kerja di Eropa, tapi sampai di sini saya seminggu nangis terus harus kerja keras,” tutur ayah dua anak ini.
Pada akhirnya, tekad kuat membuat Budi mampu melalui waktu dan semua rintangan. Daripada harus kembali ke Bangkalan dan sekolah, lebih baik bekerja mengasah kemampuan tersembunyi.

Rupanya Budi memang lebih cepat belajar mengaduk bumbu dan mengolah adonan daripada menghapal pelajaran Geografi apalagi memahami Fisika dasar.
Budi mampu belajar banyak hal termasuk berjejaring dengan komunitas orang Indonesia, sehingga katering makanannya pun diminati. Ia dan istrinya juga sering ikut pengajian di Masjid Al-Hikmah Den Haag.
Dari pergaulan itulah, Toko Pak Camat makin dikenal. Selain Gisma, tiga karyawan lain berasal dari Bangkalan Madura, dan satu di antaranya baru tiba sebulan lalu.
Oh ya, mengapa namanya Toko Pak Camat? Mengapa tidak Pak Lurah atau Pak Bupati? Ternyata, camat itu singkatan dari “cara makan hemat”. “Ditambah jadi Pak Camat, kok rasanya pas, ya, he he he”.
Baiklah, Pak Camat, eh Pak Budi… Dankjewel. Mator selangkong…