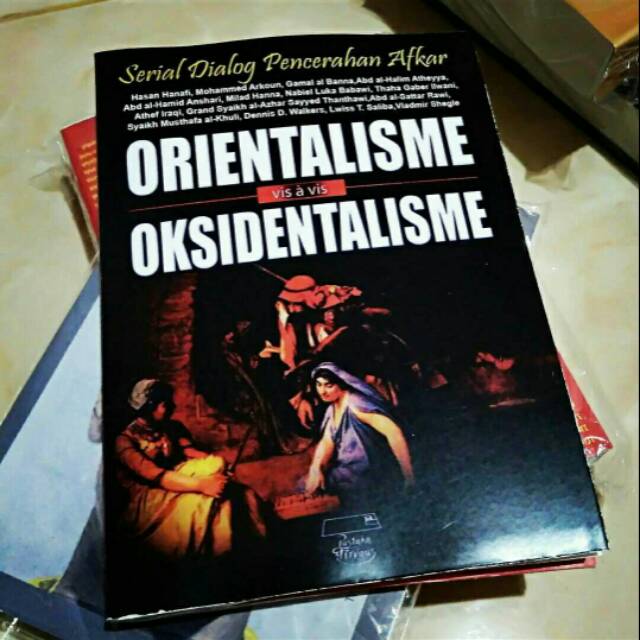
Sudah menjadi suatu jargon bagi akademisi dan para calon akademisi di kampus-kampus, bahwa sebagai pengkaji keilmuan, mereka mesti objektif. Akademisi tidak boleh berpandangan bias atas dasar perasaan suka atau benci terhadap objek kajian. Ia mesti bekerja untuk menghasilkan kajian keilmuan yang jernih, jujur dan netral. Hal ini dimaksudkan, agar akademisi lebih bisa mendekati kebenaran.
Namun pada kenyataanya, dunia akademisi tidak berjalan seidealis itu. Kajian-kajian keilmuan tidak bisa terhindar dari bias-bias. Sebagian kajian keilmuan yang kita baca dan pelajari sedari kecil, ternyata tidak lepas dari wacana superioritas dari pihak yang berkuasa di dunia: dunia Barat. Maka, dari kajian itu sebenarnya kita tidak sedang membaca objek kajian secara objektif keilmuan sepenuhnya, tapi membaca “prasangka” Barat atas objek kajian itu, lengkap dengan wacana superioritas kekuasaannya.
Orientalisme: Wacana Superioritas Barat atas Timur
Orientalisme secara bahasa berarti ilmu tentang ketimuran. Dalam istilah keilmuan, orientalisme adalah ilmu yang membahas segala sesuatu yang berbau “Timur” mulai dari bahasa, budaya, politik, ekonomi, dan sejarah; oleh para Sarjana Barat. Batasan antara “Barat” dan “Timur” sendiri bukan merujuk pada kondisi geografis, melainkan hanya bersifat imajiner. Karena negara-negara seperti Rusia dan Australia pun, dianggap representasi negara Barat, meskipun secara geografis masih berada sejalur dengan negara-negara Timur yang ada di Asia.
Ilmuwan yang berjasa menjelaskan orientalisme adalah Edward Said yang menulis buku Orientalism. Said sendiri menyusunnya bertolak dari wacana pengetahuan dan kekuasaan dari Michael Foucault, yang menjelaskan bagaimana pengetahuan menjadi senjata kekuasaan dan kekuasaan bisa memonopoli pengetahuan agar menjadi langgeng. Wacana bagi Foucault adalah sebuah gerakan tak terlihat, kesadaran kolektif, akumulasi kekuatan, dan sesuatu yang bersifat memaksa bagi semua yang terlibat untuk mengikuti arus itu, tanpa disadari oleh kebanyakan kita.
Sementara itu, dalam wacana orientalisme yang telah lama diterima di belahan dunia, dibangun dari perasaan Barat merupakan ilmuwan, sedangkan Timur adalah objek kajianya. Ilmuwan Barat akan mengamati sejarah, kebiasaaan, masyarakat, adat istiadat, logika, dan bahasa masyarakat Timur. Ada sarkasme yang menggambarkan fenomena ini, bahwa Timur seperti orang utan yang unik, khas, dan eksotik. Sedangkan Barat sebagai ilmuwan yang serba ingin tahu, telaten, totalitas, dan siap berkorban segala hal demi orang utan yang dipelajarinya (Al Makin, Antara Timur dan Barat, 2016).
Anggapan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah. Orientalisme merupakan pertemuan pelancong dan pelaut Eropa untuk pertama kalinya dengan budaya lain. Orang Eropa sebelumnya tak yakin apakah ada dunia dan makhluk lain selain di Eropa (sebagaimana kini, ilmuwan penasaran apakah ada makhluk lain di planet selain bumi). Mereka pada mulanya meyakini, kebudayaan dan peradaban mereka adalah satu-satunya yang hadir di Bumi. Sehingga kemudian ketika mereka menemukannya, mereka menganggap kebudayaan lain sebagai “other” dan melahirkan diskriminasi.
Orientalisme menurut Edward Said juga menjadi semacam proyek juga bagi para pengkajinya. Karena ilmu merupakan alat dari kekuasaan, dan juga bagian yang sangat penting dari kekuasaan. Ilmu kketimuran atau orientalisme tentu digunakan untuk mendukung kekuasaan Barat pada waktu itu, yakni kolonialisasi.
Persepsi Barat terhadap Timur itu bias dengan subyektifitas Barat, terutama dalam era kolonialisasi. Dalam pandangan itu yang muncul adalah ego Eropa. Barat melihat Timur dengan kacamata, ukuran, dan budaya Barat. Barat menjadikan pijakan dirinya untuk melihat apa dan siapa itu Timur. Maka jelas sekali, bahwa Barat meletakkan dirinya pada posisi superior, Timur sebagai orang lain, budaya dan tradisi lain, dan diletakkan pada posisi inferior.
Dari konsep yang dikembangkan Said, bisa dilihat bagaimana orientalisme bukanlah perangkat teori yang didalamnya mengandung asas-asas dan syarat-syarat kebenaran, melainkan konstruksi otoritas yang dibangun atas dasar kebutuhan legitimasi dan afirmasi politik, budaya, etika, dan ekonomi. Ringkasnya, menurut Edward Said, orientalisme adalah bagaimana ilmu-ilmu yang berkembang, seperti sosial dan humaniora, di Barat itu merupakan turunan dari semangat kolonialisme.
Oksidentalisme: Respon Sarjana Timur
Bermula dari melihat kenyataan bagaimana Barat mewacanakan superioritasnya atas Timur dalam berbagai kajian pengetahuanya, Hasan Hanafi, seorang tokoh Mesir yang dididik sejak awal dengan tradisi Marxisme atau tradisi kiri, meneriakkan bahwa perlu adanya gerakan tandingan. Gerakan itu berupa pembalikan posisi Barat dan Timur, bahwa Timur juga harus bisa melihat, mengkaji, dan mempelajari Barat. Itu merupakan reaksi terhadap pembacaan Said terhadap hegemoni Barat. Hanafi meneruskan, dan merupakan respons terhadap wacana hegemoni itu.
Oksidentalisme, pada dasarnya, diciptakan untuk menghadapi westernisasi yang memiliki pengaruh luas tidak hanya pada budaya dan konsepsi kita tentang alam, tapi juga mengancam kemerdekaan peradaban kita, bahkan juga merambah pada gaya kehidupan sehari-hari: bahasa, manifestasi kehidupan umum dan seni bangunan. Oksidentalisme adalah alat atau ilmu baru bagi Timur untuk mempelajari Barat, namun tanpa berniat menguasainya, tapi meningkatkan posisi tawar Timur. Semangat keilmuan inilah yang diimpikan oleh Hanafi.
Berbeda dari Said yang menjelaskan wacana superioritas Barat, Hanafi membayangkan idealisme, bahwa Timur seharusnya bukan hanya sebagai objek kajian, tetapi juga subjek yang aktif pula dalam memproduksi pengetahuan tentang dirinya, juga tentang budaya lain. “Oksidentalisme bertujuan mengakhiri mitos Barat sebagai representasi seluruh umat manusia dan sebagai pusat kekuatan“ (Hanafi, 1999).
Oksidentalisme yang diusung oleh Hassan Hanafi memperjuangkan netralitas perspektif antara ego (Timur) dengan the other (Barat). Relasi keduanya harus dibongkar dari hierarkinya yang superior dan inferior menuju model dialektika yang berimbang. Bukan untuk saling dibenturkan, melainkan hubungan dialektis yang saling mengisi dan melakukan kritik antara yang satu dengan yang lain, sehingga terhindar dari relasi yang hegemonik dan dominatif dari dunia Barat atas dunia Timur (Abdurrohman Kasdi dan Umma Farida, 2013).
Sementara itu, Mukti Ali, seorang intelektual studi agama terkemuka di Indonesia, mengartikan oksidentalisme secara berbeda dengan Hasan Hanafi. Mukti Ali menyuarakan pentingnya membuat wacana tandingan Orientalisme dengan cara mempelajari kembali karya Barat tentang Timur (Ali, 1992). Oksidentalisme menurutnya adalah kajian tentang Timur, oleh orang Timur, dengan metode Barat. Dengan begitu, kesalahpahaman yang dihasilkan dari bias wacana superioritas Barat dalam Orientalisme bisa dijelaskan dan dapat ditanggapi oleh Timur sebagai natif yang selain menjadi objek kajian, juga mempunyai kemampuan daya pikir untuk mengkaji dirinya sendiri.
Tanggung Jawab Akademisi
Akademisi adalah para punggawa ilmu pengetahuan yang menjadi temuan luar biasa dari sejarah kebudayaan manusia. Dengan pengetahuan, kita bisa memahami sesuatu dengan lebih baik. Tapi, ternyata pengetahuan bisa menjadi alat kekuasaan pula. Pengetahuan yang sebelumnya membantu kita memahami hal lain dengan lebih baik, tanpa ada prasangka atau mitos-mitos tertentu, menjadi alat yang bisa dijadikan untuk menindas kebudayaan lain.
Berangkat dari sana, orientalisme dan oksidentalisme menjadi kajian keilmuan yang penting untuk dipelajari. Keduanya memberikan kita pengetahuan mengenai wacana superioritas para akademisi tertentu terhadap pihak lainya. Bahwa keilmuan yang seluruh akademisi dari segala penjuru dunia berada di dalamnya, tidak bisa lepas dari bias akademisi yang berasal dari dunia yang sedang berkuasa.
Dengan begitu, kita bisa mengambil sikap dan tanggung jawab sebagai akademisi maupun calon akademisi. Dalam melakukan pembacaan terhadap referensi pengetahuan, kita tidak bisa melepas dari perspektif bias itu. Untuk kemudian selanjutnya, menghasilkan karya pengetahuan yang mengembalikan marwah akademisi yang objektif, netral dan pro-kebenaran. Selain itu, penting juga untuk menjadikannya amunisi dalam melawan hegemoni-hegemoni selanjutnya dari dunia lain, agar bisa melakukan pembebasan atas penindasan dari pihak manapun.
Wallahu a’lam bish showab.















