
Di Kepulauan Madura, kesenian Diba’ dan kasidah (samroh) adalah jenis kesenian khusus untuk kaum perempuan, yang terkadang diadakan dalam acara arisan oleh para jemaah arisan bersangkutan. Apa itu Dima’?
Diba’ adalah doa dan ayat Alquran yang dibacakan atau diucapkan secara lisan, berselang-seling dengan kasidah yang dinyanyikan tanpa koreografi dan musik. Sedangkan samroh (kasidah) ialah kesenian Islam dengan iringan musikal, dan lagu profan bertema moral, dengan iringan musikal, dalam bahasa Madura atau Indonesia, tanpa koreografi.
Diba’ bukanlah pertunjukan; lain halnya dengan samroh yang dapat ditonton sewaktu perayaan nasional atau hari raya Islam. Di dalam masyarakat pedesaan Madura kontemporer, para perempuan tidak mempunyai kesempatan lain untuk mempraktikkan kesenian, terkecuali untuk para sinden dan para gadis penggemar pencak silat.
Diba’ sendiri lebih tampak sebagai pengungkapan iman tinimbang ekspresi kesenian. Selain itu, diba’ tidak selalu dicantumkan di dalam daftar kegiatan kesenian dalam masyarakat Madura, dan para penggiatnya secara umum menolak istilah “seni” untuk kegiatan mereka.
Sesungguhnya, sebagai acara pembacaan ayat Alquran, dan ucapan doa yang berciri litani atau dinyanyikan, Diba’ tampak sebagai tahap pertama pertemuan antara agama dan seni: Ayat suci Alquran yang hanya dapat dibacakan atau diucapkan, tetapi tidak boleh dinyanyikan dan apalagi diiringi musik, disertai ucapan yang sekaligus tidak suci dan tidak profan, yaitu kasidah.
Tampil tanpa iringan musikal, dengan nada suara sedatar mungkin, para peserta duduk berbentuk lingkaran dengan perempuan yang membimbing doa atau nyanyian. Mereka berselang-seling duduk atau berdiri, tanpa koreografi apa pun, dengan wajah yang tidak berekspresi. Diba’ tidak memerlukan penonton, dan ekspresi apa pun dibatasi sebanyak mungkin. Acara itu membawa kesan kepiluan yang mendalam.
Doa-doa dibacakan secara bergiliran dengan nada tangis; qasidah dinyanyikan perlahan-lahan, tanpa semangat, dengan suara yang terus-menerus bernada tunggal. (Baca: Musik dalam Khazanah Islam)
Acara qasidah biasanya berlangsung antara satu hingga dua jam bersamaan dengan penyelenggaraan arisan, dan hampir selalu diselenggarakan pada siang hari, jarang malam hari. Para perempuan kamitua menyerahkan tempatnya kepada putri atau menantu-perempuan mereka, sementara ibu-ibu muda hadir bersama bayi yang mereka susui.
Antropolog Hélène Bouvier (2002) meneroka bahwa istilah Diba’ berasal dari tokoh Islam berkebangsaan Arab, yaitu (ulama Abdurachman Addiba’i?) yang syahdan telah menyusun referensi rujukan untuk diba’, yakni Kitab Diba’. Agaknya jelas bahwa Diba’ telah tersebar ke semua desa di Kabupaten Sumenep melalui masyarakat Arab dan pondok pesantren. Dan, menurut Bouvier, ini adalah fenomena budaya masyarakat Madura yang relatif baru.
Di desa Gedang-Gedang, hampir semua perempuan muda adalah anggota kumpulan Diba’ yang bagi mereka merupakan satu-satunya kesempatan berkala untuk mengambil bagian pada arisan, untuk bergaul antara sesama perempuan di luar rumah tangga, serta untuk belajar Islam. Urutan itu sama dengan urutan motivasi yang diberikan perempuan yang ingin mengambil bagian pada acara Diba’.
Menurut catatan Bouvier, unsur musikal dari genre itu, samroh rupanya baru muncul di kabupaten Sumenep pada 1950-an. Kumpulan samroh di pedesaan mempunyai orkes campuran yang terdiri dari rebanna dan instrumen dari orkes Malayu. Kelompok itu sering berkelindan dengan kumpulan Diba’ yang lebih besar dari sebuah pesantren.
Di kelompok pedesaan, usia anggota samroh berkisar di antara tujuh dan delapan belas, dan pada umumnya para anggota berhenti sesudah menikah, sedangkan mereka dapat mengambil bagian pada kumpulan Diba’ selama masih ada keinginan untuk itu.
Samroh sering menyusul acara Diba’ sebagai padanannya yang lebih muda dan lebih menghibur. Kumpulan ini juga berpentas pada kesempatan perayaan umum, tetapi biasanya selalu di luar masjid.
Sebenarnya apabila dibandingkan dengan seni Islam laki-laki, pementasan itu tampak kaku dan membosankan karena terkekang oleh kewajiban kaum perempuan untuk bersikap malu.
Tidak terlihat rasa gairah atau kesenangan apa pun di wajah gadis yang berpentas. Kekakuan tubuh dan wajah itu agaknya mengimbangi keberanian mereka melanggar aturan kesopanan lama yang sempat melarang kaum perempuan Madura untuk berpentas, kecuali sinden. (Baca: Sarung, Madura, dan Inferioritas)
Busana yang dikenakan kumpulan samroh diilhami oleh busana pesantren dan hanya menampakkan wajah, tangan, dan kaki untuk memastikan tingkat kesopanan itu. Kalau pun acara arisan diselenggarakan di rumah anggota arisan, tanpa kehadiran penonton yang dapat mengganggu, suasana tetap tak bergairah. Para perempuan belia itu tetap menyanyi dan bermain instrumen musik dengan sepasif mungkin.
Agak mengherankan melihat mereka bermain gitar listrik, tom, dan organ listrik dengan secuil gairah dan gerakan tubuh itu. Pola permainan itu amat berlawanan dengan penampilan para lelaki pada kesenian haddrah dan dangdut yang amat berdekatan itu: dengan instrumen yang sama dan dengan gaya musik dangdut yang kini mengilhami samroh, para pemusik dan penyanyi laki-laki tersenyum, menari, melompat-lompat di sekitar instrumennya dan tidak segan-segan memperlihatkan kesenangan yang mereka rasakan dari bermain musik dan menyanyi itu.
Demikian pula pada pementasan hadrah, para pemain rebana membimbing sekelompok besar penari yang berputar-putar berdasarkan suatu koreografi nan istimewa. Tanpa bergerak, sifat pelaku samroh memang bertentangan. (Baca: Mengintip Dolalak, Tarian yang Dilarang Ulama)
Bila ekspresi suara dan penggunaan tubuh di dalam tarian dikesampingkan, dan jika ditengarai dari perspektif instrumen dan repertoar nyanyiannya, maka samroh bertempat di antara dua jenis kesenian lelaki, yaitu hadrah dan dangdut. Sebelum evolusi mutakhir ke arah gaya dangdut dan repertoar profan, samroh mungkin merupakan adaptasi statis dari hadrah, dengan mengambil repertoar nyanyian qasidah dan rebanna sebagai instrumen dasar, namun tanpa simbal kecil.
Prinsip penampilan silih berganti penyanyi solo dan paduan sama dengan yang kita temukan di dalam hadrah; yang tidak ada hanyalah “penampilan tubuh” dalam suatu koreografi: mungkin dari awalnya samroh diciptakan sebagai versi “tanpa tubuh” dari hadrah. Mungkin juga, berkat beberapa hadrah, ia muncul dari pengiramaan kasidah yang sudah disenandungkan tanpa iringan musikal pada acara diba’.
Iringan musikal awal itu kemudian diperkaya dengan instrumen-instrumen lain hingga menjadi orkes yang ada era kiwari. Kelompok-kelompok pedesaan masih menampilkan bentuk awal itu di luar diba’.
Sedangkan berbagai kelompok di Surabaya cukup cerkas beralih ke arah dangdut. Pengaruh itu juga lebih dirasakan di kelompok dari kota Sumenep tinimbang di kelompok desa-desa sekitarnya. (Baca: Gus Dur, Diana Sastra, dan Tarling Remang-Remang)
Meski sebenarnya teknik pementasan ini adalah turunan dari dangdut, tetapi wajah mereka tetap serius dan murung, satu tanda yang mungkin saja mengisyaratkan bahwa “mereka takut kemurkaan Allah Swt”.










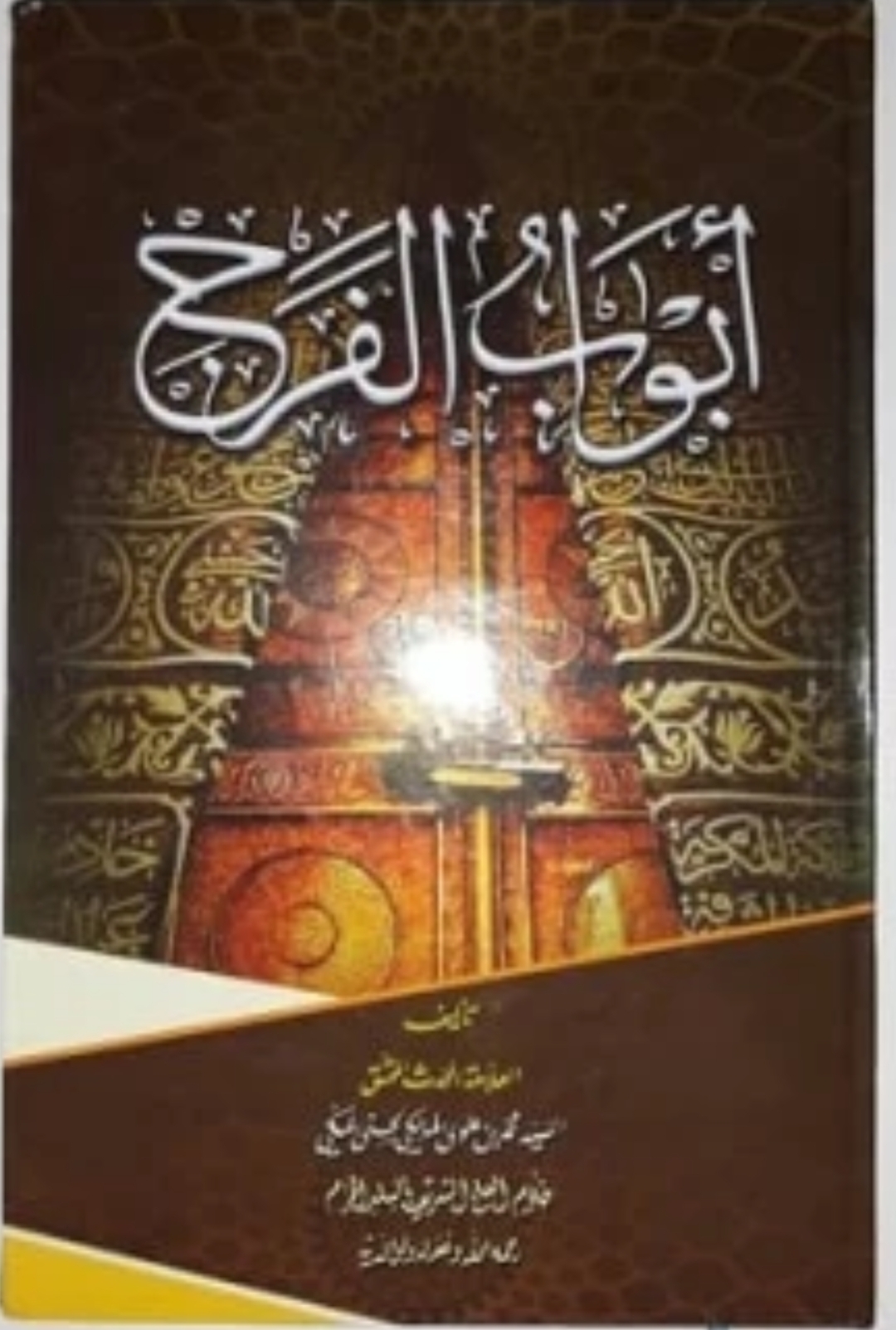










(Imam al Jalil) Abdurrahman Ad Dayba’i dari Yaman.