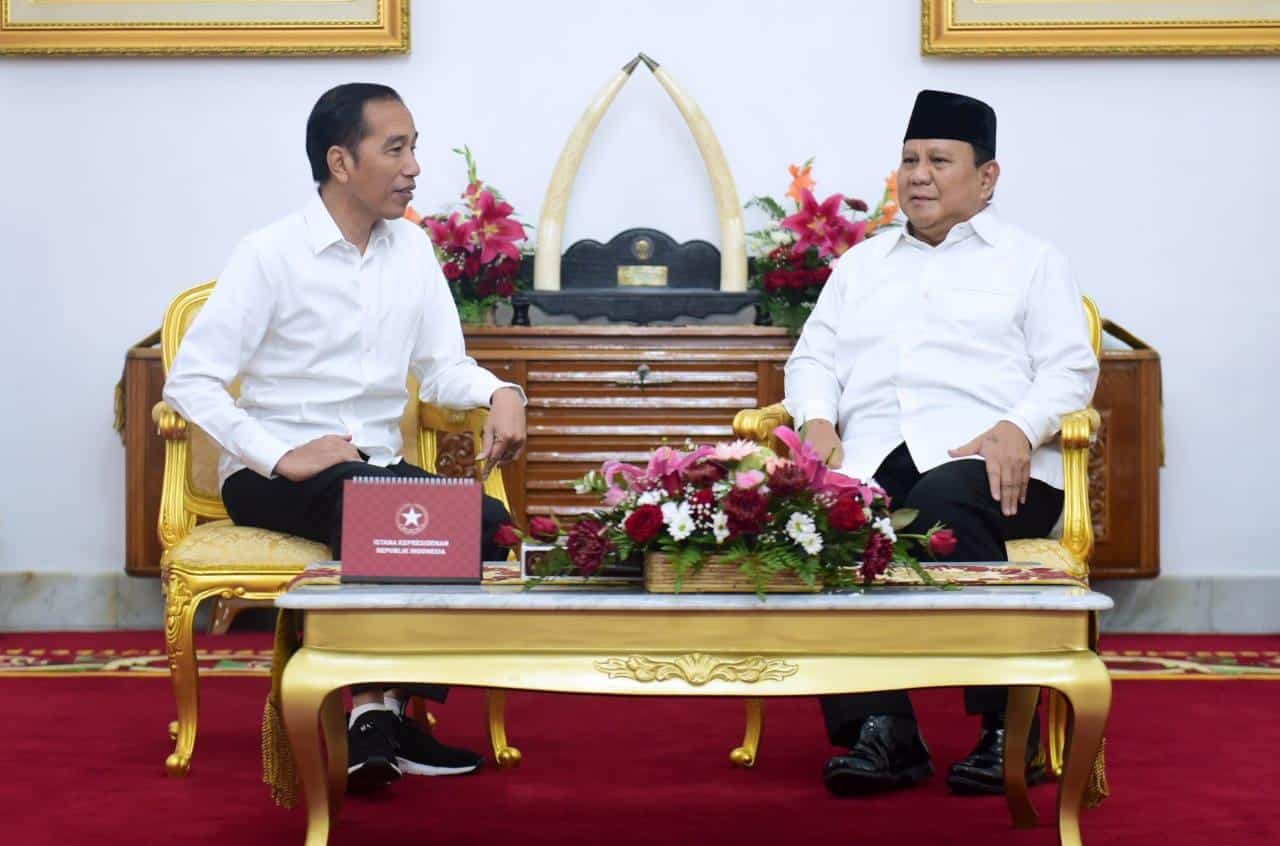Neda dika sumahura/Lah Ki Ahmad Mutamakin/Mumpung neng ngarsa bendara/Puniki ngene toh pati/Ki Cebolek nahuri/Liyep-liyep sarwi ngantuk: “Inggih yektos pun anak/andhatengi amituturi/ning kawula prapteng maot tan suminggah” (Yasadipura, Serat Cabolek)
Pada sebuah kesempatan saya berpapasan dengan dua orang santri. Usia mereka masihlah belasan. Dengan fashion yang khas, sarung dan songkok, mereka melenggang di depan sebuah rumah yang terdapat beberapa anjing di sana.
Syahdan, seekor anjing tiba-tiba menyalak dan menggigit salah satu santri itu. Dalam kepanikan santri itu berteriak-teriak. Sarung yang tepat dipinggulnya digigit dan ditarik-tarik. Saya pun menyuruh santri itu untuk diam dan tenang, sebab semakin panik semakin menambah keberingasan si anjing yang sebenarnya hanya ingin mencari perhatian dan mengajak bermain.
Santri, yang menurut Gus Dur secara kebahasaan merupakan derivasi dari istilah sansekerta “shastri” yang bermakna orang yang sedang mendalami kitab Weda, merupakan salah satu khazanah khas nusantara. Dari istilah inilah kemudian istilah “pesantren” diasalkan. Dengan demikian, santri dan pesantren merupakan fenomena yang khas nusantara. Secara antropologis, pesantren—di mana para santri belajar dan bermukim dengan pantauan ketat sang kyai beserta jajarannya—merupakan salah satu subkultur dalam kultur mayor nusantara (baca: Jawa). Budaya dan habitusnya sama sekaligus berbeda dengan budaya dan habitus Jawa.
Dari terang ini ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan dari gambaran umum selama ini tentang santri dan pesantren. Kita ingat tripartisme santri-priyayi-abangan dari seorang antropolog ternama, Clifford Geertz. Dalam kategorisasinya tersebut bagaimana ia kemudian memandang “aksara pegon” di mana akasaranya adalah aksara Arab tapi pengucapan dan maknanya adalah Jawa yang secara kebahasaan tak dapat dirumuskan secara definitif baik dengan tata bahasa (gramatika) Arab maupun Jawa? Aksara pegon ini menjadi semacam penanda resmi identitas pesantren dalam mengkaji kitab-kitab klasik (makna jenggot).
Pertanyaan tersebut patut saya utarakan karena sangat tampak bahwa gambaran Geertz tentang santri dalam The Religion of Java (1976) merupakan suatu entitas budaya yang seolah benar-benar lepas dari kultur mayor Jawa. Dan gambaran ini, celakanya, kuat memengaruhi gambaran umum tentang santri dan habitusnya sampai kini. Dengan kata lain, santri dalam betikan Geertz identik dengan apa yang kita kenal sekarang sebagai kalangan penganut Islam puritan—padahal penelitian Geertz dilakukan di Mojokuto (Pare) Kediri yang notebene menjadi salah satu pusat kota santri di Jawa Timur.
Di masa sekarang pemakaian istilah santri dan pesantren seperti dilakukan secara semena-mena. Acap sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang terkenal puritan atau bahkan yang wahabi sekali pun—yang sudah jelas-jelas anti-kenusantaraan—menyebut diri mereka sendiri sebagai santri dan lembaga pendidikannya sebagai pesantren.
Sialnya, banyak orang pun ikut mengamini kesewenang-wenangan penggunaan istilah ini. Bagaimana mungkin, misalnya, kalangan yang terkenal dengan sikap anti kearifan lokalnya dapat mengklaim diri mereka sebagai kalangan santri, di mana dari segi bahasa pun sangat tampak berbau lokal, berbau nusantara, berbau Jawa, berbau Hindu, berbau—untuk meminjam cibiran mereka—takhayul, bid’ah, dan churafat (TBC)?
Saya teringat Serat Cabolek di sini, salah satu karya Yasadipura, eyang sang pujangga panutup, Ronggawarsita. Banyak orang mengatakan bahwa serat ini merupakan buah tangan Yasadipura I. Tapi sebenarnya serat ini merupakan buah tangan Yasadipura II, sebab terdapat intertekstualitas dengan Serat Centhini yang merupakan karya di mana Yasadipura II menjadi salah satu pujangganya.
Pengertian santri dalam betikan Geertz di atas, saya kira, tampak diperagakan oleh Sultan Agung dan andahan-nya, Ketib Anom Kudus. Adapun santri yang konsisten dengan makna istilah itu justru diperagakan oleh Ki Cabolek atau yang lebih tenar dengan sesebutan Kaji Mutamakin yang dipandang menyimpang oleh kekuasaan Mataram.
Kaji Mutamakin sebenarnya seperti Begawan Bima Suci dalam kisah pewayangan Jawa. Setelah jumbuh dengan Dewa Ruci, ksatria panengah Pandawa itu menjadi bijak bestari, paham tentang hakikat segala sesuatu. Transformasi dirinya menjadikan goncangnya bagi segala tata nilai yang selama ini dipegang. Tak ada lagi kawula dan Gusti bagi Bima, keduanya telah tak terceraikan—seperti lautan dengan ombaknya atau gula dengan manisnya.
Demikian pula Kaji Mutamakin, banyak pemikiran dan perilakunya yang dianggap menyimpang dari tata nilai yang selama ini ada. Serat Cabolek menyebut beberapa pendahulunya yang sama-sama kontroversial: Syekh Siti Jenar, Pangeran Panggung, Ki Bebeluk dan Syekh Amongraga. Dalam sejarahnya, mereka semua selalu divonis sebagai para pembangkang raja hanya karena tenggelam dalam telaga kejaten. Sultan Agung pun segera mengutus salah satu andahan-nya, Ketib Anom Kudus, untuk memimpin sarasehan atau perbantahan ngelmu dengan Kaji Mutamakin.
Tak ubahnya Sunan Panggung, Kaji Mutamakin memelihara pula dua ekor anjing yang bernama Abdul Kahar dan Kamarodin. Ia pun dituduh mewedarkan ngelmu Haqq dan mengaku sebagai Muhammad Hakiki. Saya menilai Kaji Mutamakin yang dikisahkan dalam Serat Cabolek sesanad dengan Syekh Siti Jenar, Sunan Panggung, Ki Bebeluk dan Syekh Amongraga dalam urusan tarekat dan tasawuf. Paling tidak, mereka semua mengikuti jalur Sayyidina Abu Bakar al-Shiddiq. Alasan saya jelas, sanad Siti Jenar—pendahulu para sufi Jawa yang dipandang kontroversial—sampai ke hadhirat Abu Bakar al-Shiddiq.
Meski dalam Serat Cabolek versi Yasadipuran Kaji Mutamakin sekilas seperti tersudut dan disudutkan, tapi sejatinya serat itu sangat ambigu dalam menarasikannya. Untuk membungkam dan memvonisnya, Ketib Anom Kudus beserta jajarannya perlu terlebih maka mencari pembenaran atas tuduhannya pada Kaji Mutamakin. Maka dipakailah kasus yang menimpa Siti Jenar beserta sanksi hukum pancungnya, Pangeran Panggung—pengarang Suluk Malang Sumirang—beserta sanksi hukum bakarnya, Ki Bebeluk dan Syekh Amongraga beserta sanksi penenggelamannya ke laut. Tapi tidak dengan Kaji Mutamakin, serat yang ditulis di sekitar abad ke-18 tersebut tak mengetengahkan hukuman terhadap Kaji Mutamakin. Yasadipura seperti menyajikan teksnya sebagai teks terbuka (open text).
Sebagai penulis Serat Cabolek, Yasadipura seolah ingin menjelaskan apa yang sebenarnya dialami oleh Kaji Mutamakin. Dalam beberapa kesempatan sarasehan ngelmu, Kaji Mutamakin kerap digambarkan seperti tak memiliki antusiasme: “Liyep-liyep Ki Cebolek/ kadya wong angkat sakarat ” atau “liyep-liyep sarwa ngantuk.” Artinya, Yasadipura sebagai penulis Serat Cabolek dan sekaligus seorang sufi—untuk kesufian trah Yasadipuran baca Jalan Jalang Ketuhanan: Gatholoco dan Dekonstruksi Santri Brai, Heru Nurcahyo, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2011—paham tentang apa yang dialami oleh Kaji Mutamakin. Tapi karena terbentur oleh kekuasaan, Yasadipura seolah menyajikan Kaji Mutamakin yang dapat dijinakkan oleh Sultan Agung, di mana secara geopolitik adalah juga sebentuk penundukkan epistemologis-kultural wilayah Pati ke Mataram.
Sebagaimana Tuban, Pati dan beberapa wilayah pasisiran memang merupakan aliansi utama Brang Wetan (Jawa Timur) sebelum penundukkan Surabaya pada tahun 1625 M. Adakah semangat Hadratussyekh Hasyim Asy’ari dalam mengeluarkan fatwa jihad untuk melakukan bela negara waktu itu tak ada embrionya dalam semangat Kaji Mutamakin yang berupaya pula membela (sub)kultur, paham, dan tanah di mana ia berpijak? Dan bukankah secara historis dan geopolitik kultur nahdliyin memang merentang dari Jawa Timur hingga pesisir utara?
Tak seperti Kalijaga yang berhadapan dengan Siti Jenar, Ketib Anom Kudus digambarkan oleh Yasadipura sebagai seorang ulama yang bukan ulama-sufi yang paham tentang fenomena jadzab sebagaimana yang pernah dialami oleh Sang Wulung yang Agung itu dalam Suluk Linglung (Menyingkap Jadzab, Heru Harjo Hutomo, https://alif.id). Pendekatannya selalu saja terpatri pada aspek lahiriah semata, semisal menilai sahnya sebentuk shalat apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Yang luput dari mindset seperti ini adalah aspek batiniah shalat, seumpamanya apa yang disebut sebagai tuma’ninah.
Persis mindset inilah yang tak pernah dipakai oleh Ketib Anom Kudus dan junjungannya, Sultan Agung, ketika memandang Kyai Mutamakin—sebagaimana kaum puritan di mana kadar kesucian hanya ditentukan oleh aspek lahiriah belaka yang dapat diukur. Sejatinya tak ada satu rumusan pun tentang apa yang disebut sebagai tuma’ninah maupun khusyu’ dalam kamus orang-orang puritan—sebagaimana tak ada rumusan yang baku tentang ikhlas ataupun ridha.
Dengan demikian, dilihat dari konsekuensi istilah “santri,” adalah Kaji Mutamakin yang justru memenuhi kriteria itu. Dan Ketib Anom Kudus beserta rajanya, Sultan Agung, cukup memenuhi kriteria “santri” sebagaimana yang diteropong oleh Geertz yang akan terus-menerus menolak kenusantaraan dan kebhinekaan.
Jawab dan berbicaralah
Ki Ahmad Mutamakin
Mumpung di depan junjungan
Di mana nyawamu dipertaruhkan
Ki Cebolek menyambung
Di ambang kesadaran:
“Sungguh kedatanganmu
untuk mengguruiku tentang kematian yang tak pernah kuelakkan”