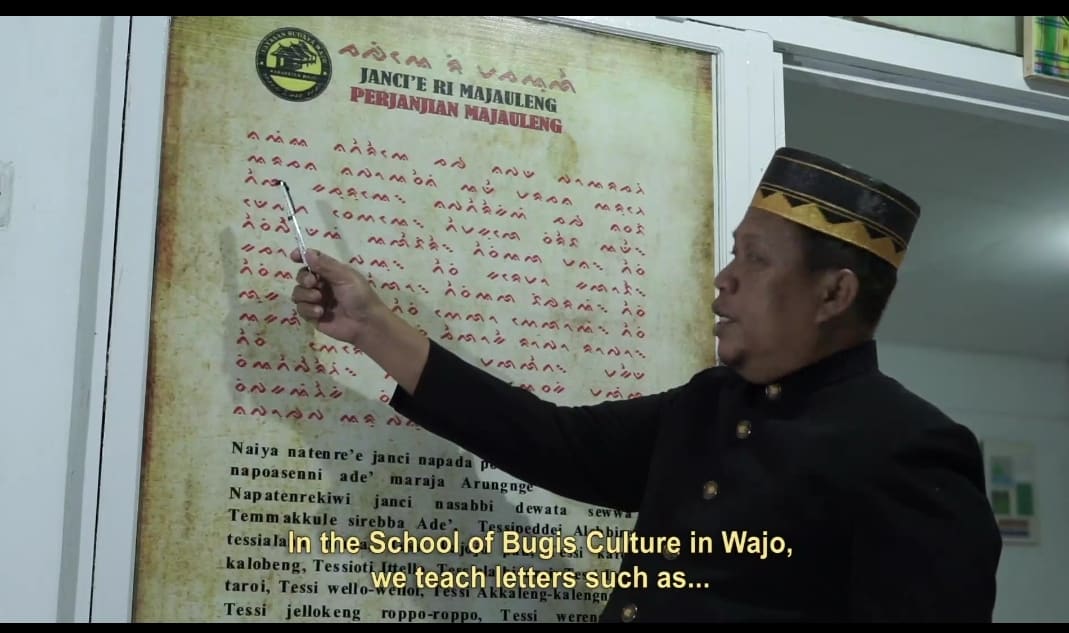Seminggu di awal Ramadan kemarin, istriku menunjukkan video tongklek pocong di Tuban yang viral di WhatsApp. Video berdurasi kurang dari satu menit itu setelah saya cari di Youtube diunggah sejak 2012. Kemudian, diunggah ulang dan diberitakan kembali sampai 2018 ini.
Tak hanya di Tuban, namun di Bojonegoro dan daerah lain, tradisi ini dikemas menarik dengan kostum pocong, kuntilanak, genderuwo, dan lainnya. Tujuan berkostum setan itu agar menarik dan tetap lestari. Meski sedikit mistis, justru warga antusias menontonnya.
Tradisi serupa juga masih lestari di Pati, tempat kelahiran saya. Modelnya hampir sama, namun tak semistis dengan mengenakan baju-baju setan seperti di Jawa Timur itu. Inovasi sepert itu bernilai positif meski telihat guyonan. Namun, dampaknya sangat besar untuk menjaga khazanah budaya di Nusantara ini.
Dakwah Sunan Bonang
Tongklek, tong-tong klek, tongthek, atau ada yang menyebut tetek, merupakan tradisi lawas khas masyarakat Jawa untuk membangunkan orang sahur. Tongthek belum masuk KBBI dan dikenal semua masyarakat Indonesia. Namun tiap Ramadan, tradisi ini selalu ada meski tak semua pemuda mengetahuinya.
Dari beberapa warisan Raden Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang (1465-1525) yang masih lestari adalah tongklek. Tradisi ini menjadi bukti, bahwa pendekatan dakwah Walisongo sangat ramah akan budaya dan kebutuhan masyarakat. Banyak sekali nilai-nilai terkandung di dalam tradisi ini.
Hidayati (2017: 1) dalam penelitiannya menemukan tongklek merupakan kesenian terbentuk dari paduan antara tradisi setempat dengan tradisi dari luar khususnya di Tuban. Tongklek sudah ada zaman Sunan Bonang dan dinamakan tongklek karena berasal dari sumber bunyi ‘tong’ dari alat musik peking, saron, kenong, gong. Sedangkan bunyi ‘klek’ dari kentongan yang digunakan untuk ronda.
Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tongklek ada 10 nilai. Mulai dari nilai religi, moral, sosial, keindahan, kedisiplinan, kejujuran, pendidikan, seni, kerukunan, sportifitas dan hiburan. Secara praktis, tongklek bermanfaat untuk membangunkan orang sahur meski sekarang sudah ada toa, sirine, dan alarm.
Tak hanya terkenal di Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Surabaya, dan sekitarnya, tongklek juga lestari di Jawa Tengah. Sejak saya kecil, hampir semua pemuda se kampung selalu senang memainkannya, bahkan sampai rebutan menabuh alat tong tong klek ketika akan main menjelang sahur.
Saya sudah terbiasa tidur di musala sejak kelas empat MI. Di tempat kelahiranku, Pati, anak-anak dan remaja terbiasa tidur di musala/masjid ketika puasa Ramadan. Tujuannya, selain bersiap-siap menabuh tongklek, mereka juga menghidupkan tradisi tidur di masjid setelah tadarus.
Sebulan sebelum Ramadan, anak-anak sangat gembira. Kegembiraan itu tak hanya pada ritual Ramadannya, akan tetapi juga tongkleknya. Bahkan, sebulan sebelum Ramadan, anak-anak sudah menyiapkan alat-alat musik tongklek.
Selain membawa sarung, mereka ada yang membawa buku, kitab, tugas PR dari sekolah, atau sekadar bercerita tentang berbagai hal-hal sepele sampai urusan negara. Saya pun, tahu cerita-cerita mistis dan gaib termasuk para wali dari musala sekitar dua puluh tahun silam. Tampaknya, tradisi tidur di masjid ini menjadi penting di era sekarang untuk mendekatkan anak-anak kita dengan masjid.
Sugiharyadi (2016) menjelaskan tong-tong klek sangat kental akan nilai-nilai kerukunan. Tong-tong klek menjadi manifestasi kerukunan umat beragama. Alasan ini didasari tiga hal pokok yang ditonjolkan dalam tinjauan Islam Nusantara. Mulai dari pendorong peningkatan SDM yang memahami pentingnya kerukunan, meningkatkan partisipasi karya dan kreasi, serta penanam nilai-nilai.
Bangunkan Orang Sahur
Di tiap daerah, memiliki tradisi masing-masing untuk membangunkan warganya yang mau sahur. Di desa-desa, tiap daerah seperti di Pati, Grobogan, Rembang, Blora, Kudus, Jepara, Demak, dan sekitarnya, sejak dulu sampai sekarang masih ada sebagian anak-anak desa melestarikan tradisi tongklek.
Tongklek ini merupakan kesenian musik lokal dengan alat utama kentongan, kendi dari tanah liat, drum dari tong, peking, saron/gambang, piano, padasan, jun atau tembayan untuk bas, sampai kecret dan lainnya. Semua itu diinovasi dengan menggarap sejumlah lagu-lagu, mulai kasidah, campursari, dangdut, pop, rock, sampai reggae dan lainnya sesuai yang sedang ngepop.
Biasanya, tongklek ini ada di tiap musala/masjid dengan membentuk grup sendiri. Mereka, secara umum mulai berkeliling di sekitar masjid sekitar pukul 00.00 WIB sampai menjelang sahur pukul 03.00 WIB. Namun, secara umum takmir masjid menganjurkan pukul 01.00 sampai selesai agar tak menganggung istirahat warga.
Di tempat kelahiran saya, Pati, tongklek tak punah. Awal puasa Ramadan kemarin saat pulang ke rumah, masih banyak grup tongklek berkeliling desa. Dulu sampai sekarang, tiap anggota grup tongklek berkeliling tak hanya di desanya, melainkan sampai ke desa di kecamatan sebelah dengan jalan kaki.
Tak hanya jalan kaki, kami membawa semua alat musik tanpa bantuan kendaraan, kecuali drum, saron, dan bas yang biasanya dimuat di songkro/sepeda. Uniknya, meski sebagian terganggu, namun banyak yang senang dengan musik kami ketika berkeliling. Meski terganggu, namun warga paham dan toleran karena tradisi ini hanya ada di bulan puasa.
Contohkan saja, di Desa Banyutowo tetangga desa kami. Di sana banyak umat Kristen, namun sangat senang ketika kami berkeliling ke sana. Bahkan, kami dulu sering mendapat permintaan memainkan lagu dan itu tentu dengan imbalan makanan bahkan saweran. Di sinilah, berkah tong-tong klek yang tentu menyenangkan semua umat.
Di daerah lain juga sama meskipun bentuknya beda. Di Blora, tradisi tongklek diberi inovasi menarik dengan memanfaatkan barong/barongan dan perlengkapan lainnya. Di sini, musiknya justru berbasis musik langgam Jawa karena ada campuran demung, bonang, dengan jenis slendro dan pelok. Uniknya, ada pemain barong yang ikut berkeliling yang diiringi grup tongklek tersebut.
Di Temanggung tradisi membangunkan orang yang mau sahur berbeda. Ada yang tongklek, memakai alat dapur seperti panci, ompreng, dan lainnya yang biasa disebut “bedug pentung”. Mereka juga memakai bedug untuk membangunkan warga agar bangun sahur dengan berkeliling desa.
Secara umum, tugas membangunkan orang yang mau sahur memang dipasrahkan pada takmir. Ada yang cuma lewat bacaan qori di speaker, tarhim, sirine, dan lainnya. Namun yang paling banyak, para takmir membangunkan warga dengan mikrofon di masjid dengan anjuran untuk segera sahur, baik dengan nada kalem atau keras.
Mendekatkan Anak pada Masjid
Di era milenial ini, budaya tidur di masjid, musala, surau, atau langgar harus dilestarikan. Sebab, tidak hanya urusan ibadah, anak-anak harus dekat dengan masjid dengan mendekatkan tradisi dan budaya Nusantara. Tradisi tidur di masjid tentu penting dilestarikan agar anak-anak memiliki bekal ganda.
Pertama, mendekatkan diri pada Allah lewat tidur di masjid. Meski tak selamanya tiduran, namun setelah tarawih, tadarus, anak-anak di masjid biasanya juga iktikaf dilanjutkan ngobrol dan tidur menanti waktu tongklek tiba. Usai itu, saat Ramadan biasanya dilanjutkan tarhim, sahur bersama di masjid, tadarus subuh, baru pulang rumah.
Kedua, mendekatkan anak-anak pada tradisi jaga malam. Solidaritas sosial bisa tumbuh ketika mereka terbiasa bangun, terjaga, dan berkeliling desa untuk memastikan desanya aman sekaligus membangunkan orang sahur. Tak sedikit warga mudik jauh-jauh ke asalnya dan meninggalkan rumah dan isinya.
Ketiga, membangunkan orang sahur dan berdakwah lewat lagu-lagu yang dibawakan grup tongklek. Meski semua lagu bisa masuk, ada dangdut sampai reggae, namun dakwah tongklek merupakan warisan dari Walisongo yang harus dijaga. Sebab, saya sendiri zaman dulu lebih suka mengajak teman-teman untuk bermain tongklek di daerah yang banyak umat Kristennya daripada daerah yang padat penduduk muslimnya.
Tujuannya jelas, berdakwah lewat pendekatan budaya dan kearifan lokal lewat tongklek itu. Buktinya, saudara-saudara kita non-muslim dulu selalu rindu, dan meminta grup tongklek mampir ke rumahnya bahkan sampai menyediakan sahur.
Zaini (2017: 127) meneliti tongthek berfungsi membangunkan orang-orang untuk sahur.
Tongthek selalu ditunggu kehadirannya dan membuktikan budaya ini dapat dijadikan sarana silaturahmi para penabuh tongklek dengan warga. Tradisi ini menjadi sarana membentuk kerukunan, karena sama-sama memiliki misi dan tujuan yang sama untuk membangunkan orang-orang untuk sahur sehingga tak terlambat.
Tradisi ini harus dilestarikan. Bisa dengan mengenalkan pada anak-anak di lembaga pendidikan. Kemudian, membuat festival tongklek, sampai pada pendataan grup tongklek ke Dinas Pariwisata atau dewan kesenian. Pembinaan ini perlu untuk regenerasi agar tradisi ini tetap membumi.
Tongklek dalam jagat musik memang bukan segalanya. Namun, sukses dan tidaknya orang berpuasa, bisa berawal dari sana. Sudah saatnya tongklek diduniakan sebagai khazanah Islam Nusantara yang sarat akan nilai-nilai duniawi dan ukhrawi.
Dakwah di era milenial tak harus lewat media siber, medsos, dan layanan pesan. Namun, bisa digerakkan melalui tradisi tongklek ini. Jika tidak sekarang, kapan lagi?