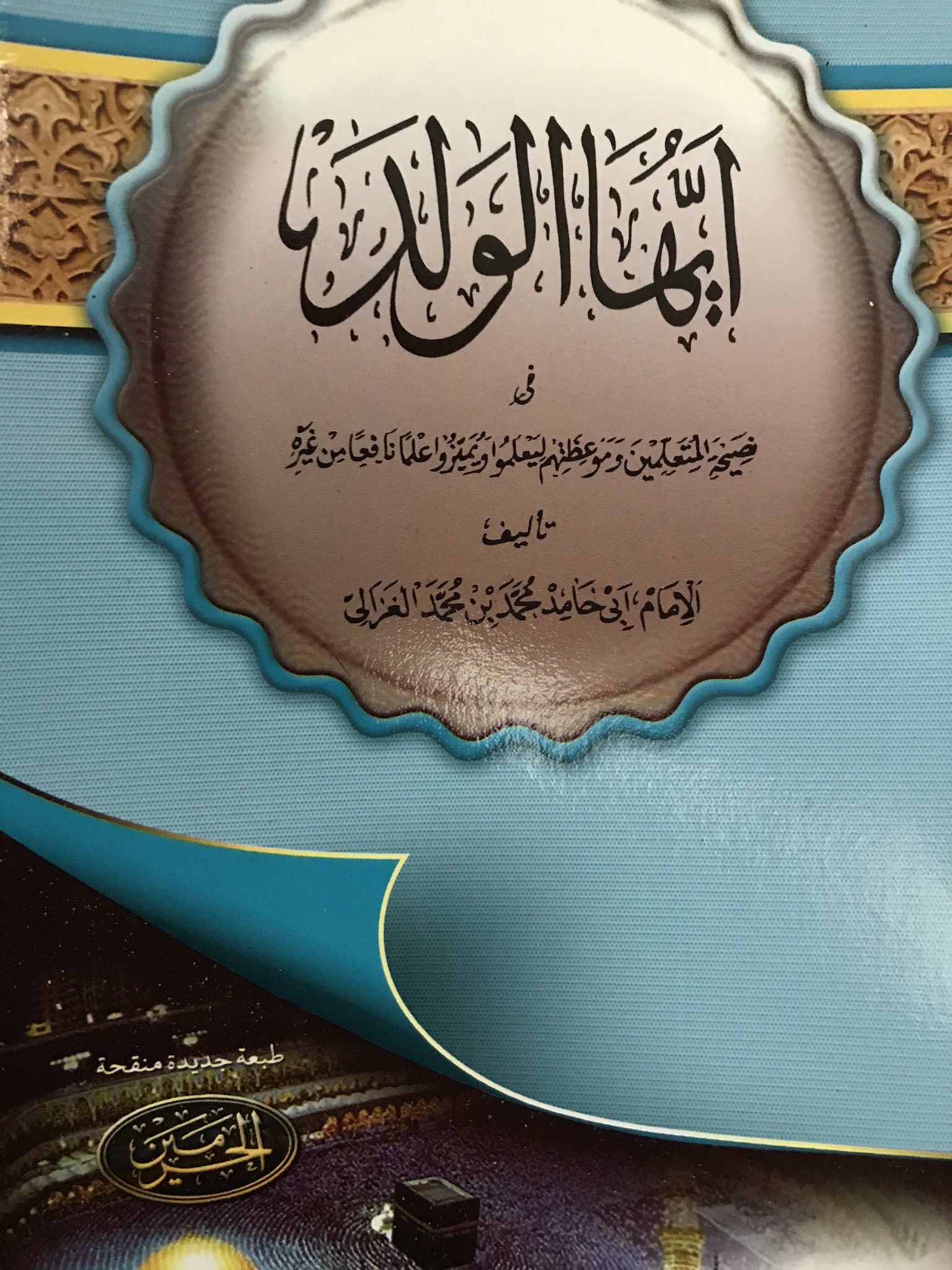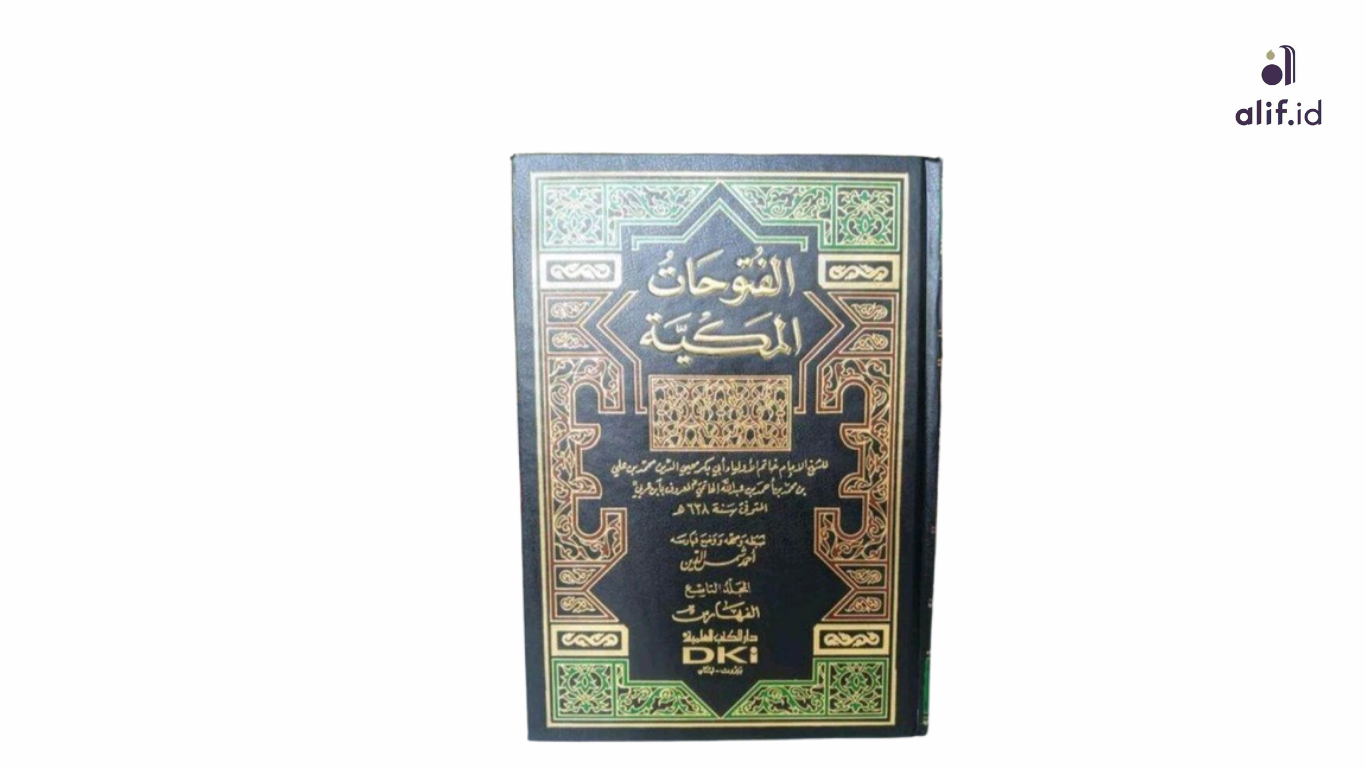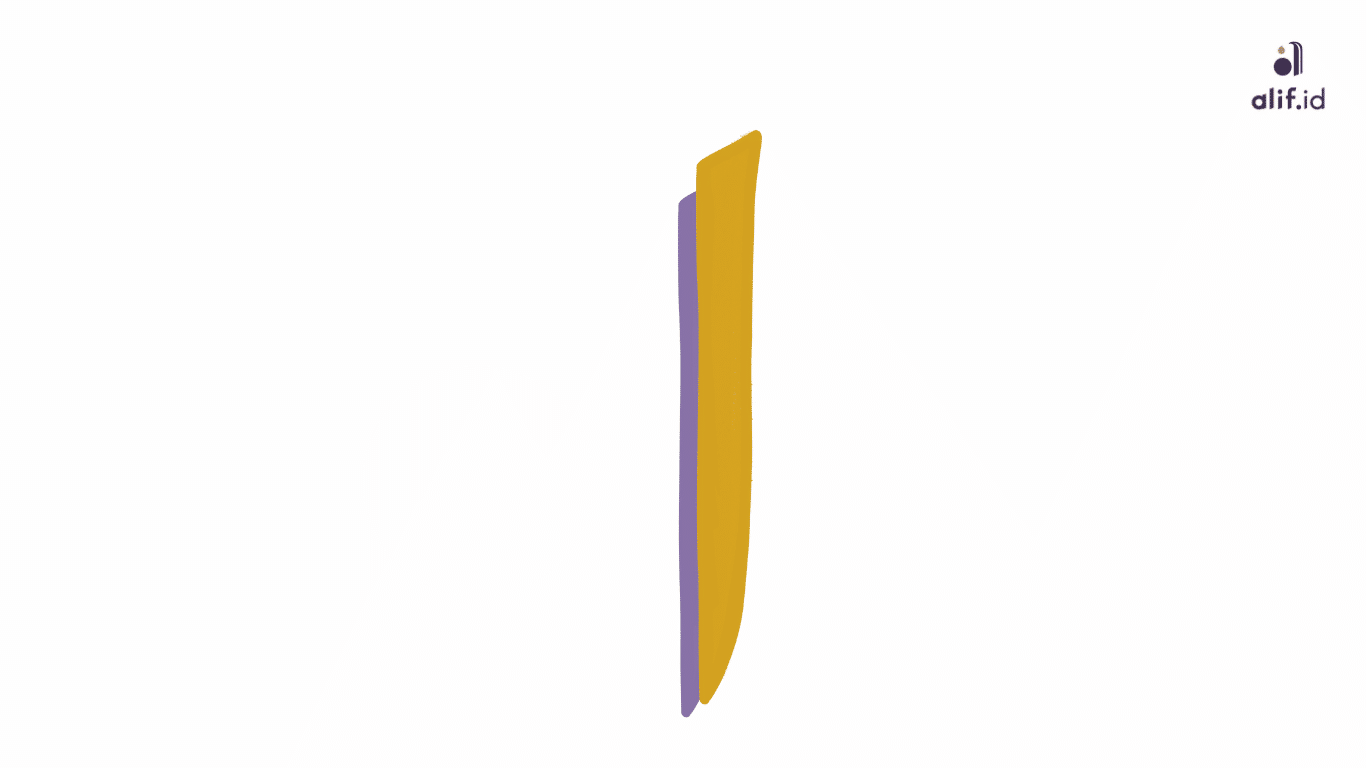Di Indonesia, beberapa masjid kuna meletakkan burung buatan di bagian atas, yang sekarang banyak di pasang bulan dan bintang. Burung, oleh para kaum sufi adalah tanda, tanda-tanda “keluhuran”. Mengapa para sastrawan sufi gemar menggunakan imaji burung?
Jawaban konvensionalnya adalah karena burung melambangkan ruh. Mulanya, demikian kaum sufi mendongeng, burung-burung ruh beterbangan di angkasa surga, bertengger di pepohonannya, dan bermain di tamannya. Pada waktu yang telah ditentukan, burung-burung ruh diamanahi tugas mahaberat.
Mereka menerima perintah untuk keluar dari surga, mengembara di bumi, untuk kemudian—lucunya—pulang kembali ke surge dengan pengalaman, derajat, dan status spritual yang lebih tinggi.
Pengembaraan kawanan burung ruh di belantara bumi tak berjalan mulus dan berlangsung mudah. Sebab, ketika sampai di bumi, mereka terkurung dalam sangkar tubuh. Karena begitu kuatnya pengaruh tubuh, mereka melupakan jati dirinya sebagai penghuni surga yang luhur dan agung. Bahkan, mereka lupa dengan tugas yang dulu diamanahkan.
Kini mereka berpikir bahwa bumi merupakan satu-satunya tempat kelahiran, kehidupan, dan kematian. Tidak ada kehidupan lain selain kehidupan dunia. Tidak ada pengembaraan—tepatnya perjalanan—spiritual dari surga ke surga melintasi bumi. Burung lupa bahwa dirinya adalah burung.
Dalam bencana lupa jati diri itu, dari surga diutuslah sang burung pemandu, satu demi satu, untuk mengingatkan umat burung tentang jati diri dan tugas mereka, juga untuk membimbing mereka pulang ke kampung halaman sejati, yaitu surga.
Pada panggung sejarah, burung pemandu tampil sebagai guru spiritual dari beragam aliran, agama, dan tradisi. Dalam karya sastranya masing-masing, Ibnu Sina, lalu juga Fariduddin Attar, secara alegoris mengisahkan perutusan, pembimbingan, dan penyelamatan kawanan burung ruh oleh sang burung pemandu ini.
Itulah jawaban konvensional mengapa kaum sufi gemar menggunakan imaji burung dalam bersastra. Namun demikian, sebenarnya ada jawaban segar yang berhubungan dengan kemajuan sains dewasa ini. Berdasarkan penelitian ornitologi mutakhir, diketahui bahwa burung bukan binatang bodoh. Secara kognitif, burung seperingkat dengan spesies fauna pintar lain: simpanse dan lumba-lumba.
Menurut catatan majalah National Geographic (edisi Februari 2018, h. 110-111), di antara semua anggota keluarga avian, tiga besar burung paling pintar adalah gagak (corvus corax), nuri abu-abu (psittacus erithacus), dan pelatuk jambul (dryocopus pileatus).
Gagak mampu memecahkan teka-teki, menggunakan (dan menciptakan) alat, meneliti pihak lain, mempelajari vokal, bersosialisasi, mengingat, dan bermain. Demikian pula nuri abu-abu. Pelatuk jambul punya kemampuan kognitif tinggi dalam memacahkan teka-teki, menggunakan alat, dan bermain.
Hasil penelitian mutakhir tentang burung itu, apakah maknanya?
Maknanya sederhana: burung adalah binatang pintar. Bahkan, lebih dari sekadar kepintaran kognitif, binatang itu juga memiliki kepintaran empatis. Itu artinya, selain melambangkan ruh, burung pun menandakan akal. Tidak heran bila Fariduddin Attar menjuduli kitab alegori burungnya dengan Manthiq al-Thair, sebuah frasa kaya makna yang diambil dari Alquran.
Biasanya, judul ini diterjemahkan secara lugu menjadi ‘musyawarah burung’. Padahal, dalam bahasa Arab, kata manthiq tidak hanya mengacu pada ‘musyawarah’, tetapi juga mengandung nuansa arti ‘ujaran’, ‘kata’, ‘akal’, dan ‘logos’.
Tampaknya Attar memang memandang burung juga sebagai simbol kecerdasan manusia. Burung melambangkan akal. Potensi akal itu memungkinkan manusia mengadakan perjalanan spiritual dari surga ke surga melintasi bumi, “melupakan” tugas dan amanah yang dibebankan di atas pundaknya, dan “mengingat” kembali tugas dan amanah tersebut.
Sudah terang, hal ini menunjukkan bahwa kaum sufi tidak memusuhi filsafat dan anekaragam aktivitas intelektual lain. Yang dikritik tasawuf adalah sikap tertutup dan taklid buta baik dalam dunia ilmu pengetahuan umum, apalagi dalam dunia ilmu pengetahuan agama.
Yang diserang tasawuf bukanlah intelektualitas, melainkan penyakit hati intelektualisme. Intelektualisme adalah hijab amat tebal yang menutupi mata hati. Karena hijab intelektualisme, kita gagal menyaksikan kehadiran Ilahi dalam realitas keseharian yang sesungguhnya merupakan pancaran cahaya-Nya.
Akal tidak dibenci dan disingkirkan apalagi dimusnahkan. Akal hanya diletakkan dalam konteksnya dan digunakan sesuai dengan porsinya. Ketika akal menjelma berhala, kaum sufi angkat suara dan turun tangan untuk meluruskan penyimpangan fungsi akal. Inilah yang dilakukan al-Ghazali, sufi besar Persia yang berjuang mengharmonikan nalar dan agama, filsafat dan tasawuf, akal dan hati. Ia mengarang sejumlah kitab yang mengkritik intelektualisme ulama kalam, ulama fikih, dan ulama filsafat. Karena itu, dalam magnum opus-nya, Ihya Ulumiddin, kita menemukan ulasan filfasat tentang betapa mulia, berharga, dan bermanfaatnya akal bagi manusia beragama.
Jaladuddin Rumi, sufi besar Turki yang masyhur sebagai mahaguru cinta (al-‘isyq; al-mahabbah), juga menjelaskan nilai positif akal. Hingga tahap dan dalam konteks tertentu, akal (rasio) dan hati (cinta) harus mengambil jalan berlawanan arah. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa cinta tak memerlukan akal.
Dalam proses pendakian spiritual, akal ibarat tangga. Setelah berhasil memetik mutiara rohani dari pohon tauhid, tangga itu tak perlu dibangga-banggakan, apalagi dipamerkan kian ke mari.
Akal, betapa pun jauh daya jelajahnya, pada titik tertentu menghadapi jalan buntu. Akal berbatas sedangkan hakikat itu nirbatas. Akal memang dapat menjelaskan sifat, kualitas, dan sejarah manusia. Tapi, hakikat terdalam manusia di luar batas jangkauan akal. Akal, bagi Rumi, merupakan sarana atau alat, bukan tujuan. Bila ditempatkan sebagai tujuan, akal menjadi berhala.
Dan dalam literature sastra sufi, makna akal sebagai sarana pendakian rohani bagi manusia ini dilambangkan dengan imaji burung. Sebenarnya, burung sebagai lambang akal, tidak hanya kita temukan dalam sastra sufi. Dalam Alquran pun, dari mana sastrawan sufimengambil inspirasi puitik, burung berkaitan dengan akal.
Alquran mengisahkan “perang saudara” anak-anak Adam. Segera setelah membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil, Qabil bingung. Dia tidak tahu cara yang layak untuk mengurus jenazah Habil. Seekor gagak kemudian mendarat dengan membawa serta bangkai gagak lain. Dia mengais tanah dan menggali liang, lalu memendam bangkai gagak yang dibawanya.
Setelah menonton adegan itu dan mengambil pelajaran darinya, Qabil mengikuti teladan sang gagak. Ia menggali tanah, lalu mengubur jenazah Habil. Itulah peristiwa penguburan jenazah pertama yang dilakukan dalam sejarah umat manusia. Ternyata, salah satu avian paling cerdas itu adalah guru yang mengajari manusia bagaimana memuliakan manusia lain yang telah meninggal. Ironis tetapi luar biasa: manusia belajar menjadi manusia justru dari gagak yang adalah binatang.
Alquran juga mengisahkan hubungan Nabi Sulaiman dengan burung hud-hud kesayangannya. Konon, yang dimaksud hud-hud dalam Alquran adalah burung pelatuk, salah satu burung terpintar. Hud-hud terbang melintasi angkasa negeri yang dipimpin seorang perempuan dan menyembah matahari. Dia melaporkan hasil “observasi”-nya kepada Nabi Sulaiman.
Sang Nabi lalu mengutus hud-hud sebagai diplomat dengan misi menyerahkan surat kerajaan kepada sang ratu. Alih-alih berisi perintah takluk dan maklumat perang, surat tersebut pada dasarnya mengandung pesan damai: bismillah al-rahman al-rahim.
Dengan demikian, dalam cerita ini, di samping menandakan kecerdasan, burung juga mengisyaratkan perdamaian, rahmat, dan cinta. Wajarlah kalau orang modern kini memandang burung merpati sebagai simbol kasih sayang yang pantang roboh dilanda banjir bandang sungai waktu.
Dari pembicaraan ngalor ngidul di atas, apa yang dapat kita simpulkan? Pada burung sebagai imaji sufistik, terdapat keterpaduan makna antara ruh, akal, dan cinta.Itulah anugerah rohani yang dilimpahkan bagi manusia dengan mana dia dapat pulang ke kampung halamannya: surga.