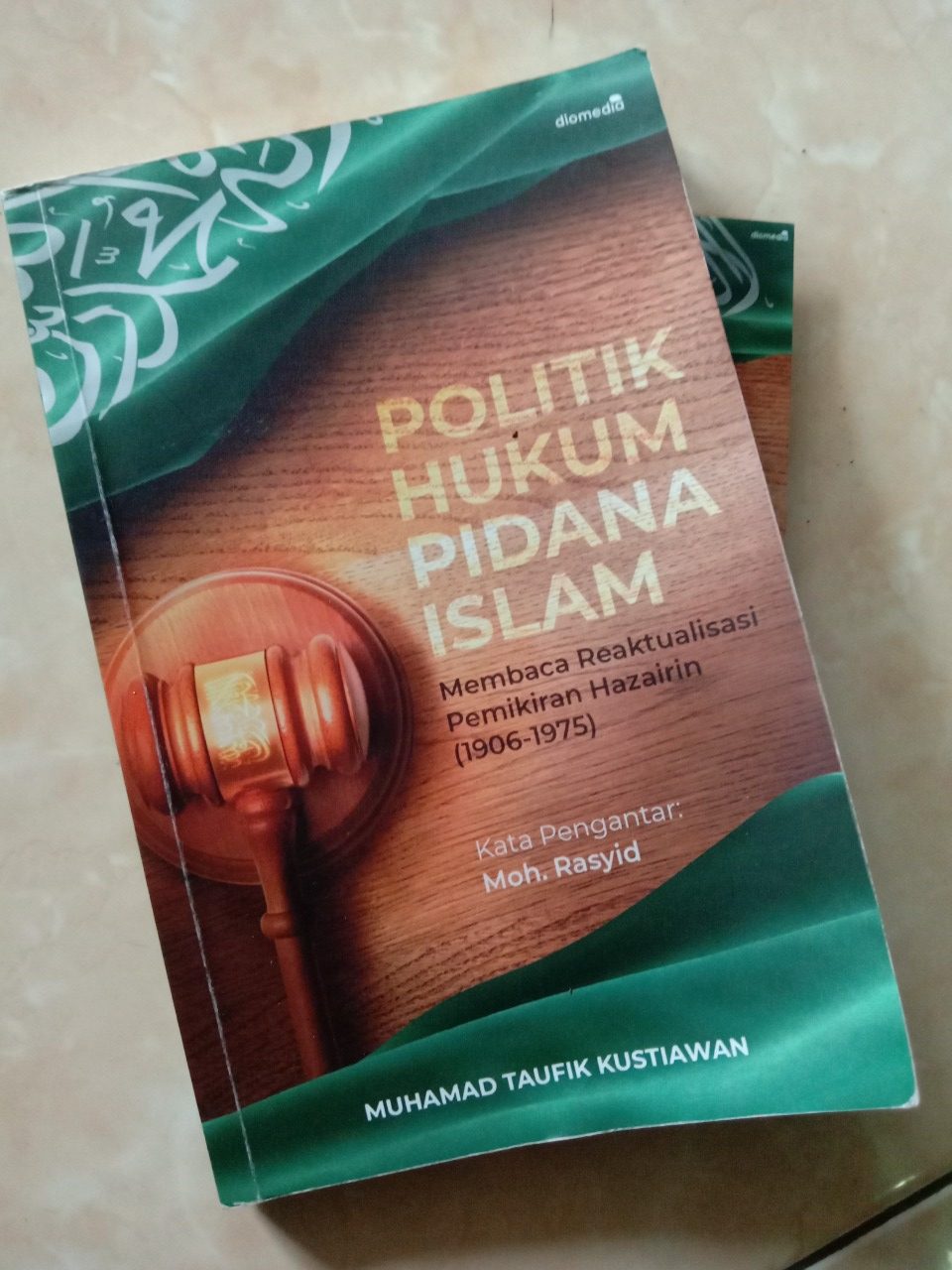Pengarang babak Poedjangga Baroe pernah mengeluh bermula pengamatan: pengarang-pengarang Indonesia mudah mematikan tokoh. Pada masa berbeda, Iwan Simatupang menulis cerita dengan tokoh-tokoh aneh. Sekian tokoh mati dengan enteng dan mengejutkan. Persoalan pelik dalam sejarah dan perkembangan novel di Indonesia memang tokoh-tokoh dimatikan pengarang. Konon, kematian-kematian membenarkan adat, asmara, filsafat, kekuasaan, dan lain-lain.
Kita mungkin pembaca berduka cita bila khatam ratusan novel Indonesia. Kita mengingat kemahiran para pengarang bercerita dan jenis kematian terbaca dalam novel. Selama menjadi pembaca novel, kita tak sempat membuat catatan-catatan mati untuk mengerti pamrih pengarang-pengarang. Di tiap novel, kita membaca mati sering dengan maklum atau sejenak bimbang.
Pada saat masih kewalahan membuat daftar kematian dalam novel-novel Indonesia, kita disuguhi novel berjudul Lebih Mati Dari Mati (2021) gubahan Agus Subakir. Judul gamblang mengundang pembaca masuk ke halaman-halaman mengenai mati. Kita boleh menduga kehadiran novel itu memastikan mati menjadi “terpokok”, melampaui mati-mati pernah terceritakan dalam ratusan novel terdahulu.
Di buku berjudul Art of Novel (2002), Milan Kundera berkhotbah: “Garis edar novel muncul sebagai sebuah sejarah paralel dari era modern.” Ia menjelaskan novel di Eropa. Kita membaca setelah kedatangan novel-novel ke Indonesia memberi rangsang kemunculan para pengarang novel. Babak berbeda mengartikan posisi novel pun berbeda pengaruh dalam penentuan sejarah peradaban di Nusantara. Konon, zaman modern itu zaman penuh dengan kematian-kematian. Sekian orang membahasakan terjadi krisis kemanusiaan. Kita mengingat lagi itu terjadi di Eropa, sebelum menular ke pelbagai negara berbarengan dengan pemujaan novel.
Novel itu tanda kemodernan di Indonesia. Dulu, novel-novel masih lugu. Pada masa berbeda, novel-novel Indonesia dalam penciptaan sejarah berbeda. Agus Subakir turut berada dalam pembuktian penulisan novel bukan selalu “pengulangan” atau “mengikuti” corak-corak telah dipersembahkan sejak puluhan tahun lalu. Kini, kita agak mengerti garis cerita mati mengental dalam novel gubahan Agus Subakir.
Di halaman awal, kematian diceritakan enteng. Kematian itu dikuatkan dengan sedih, tangisan, dan kenangan. Kematian tokoh bapak memiliki deretan cerita membuat pembaca berhak sebal, dendam, prihatin, dan marah. Kematian tokoh berkaitan dengan latar sejarah. Tokoh ibu saat muda berpendidikan di SMA Kejuruan Kebidanan. Ia berada dalam situasi pelik dan berdarah. Agus Subakir mengingatkan kematian-kematian pada 1965. Ibu dan para murid menanggung rumit: “Mereka harus dibuat giris dan berkeringat dingin dengan dada berdebar…” Malapetaka 1965 di Solo menghasilkan kematian-kematian tak wajar.
Cerita terus bergerak dengan mati-mati. Pengarang mengajukan latar desa dengan tata cara hidup memerlukan kepahaman bereferensi Jawa. Agus Subakir mengakrabi desa, terceritakan dengan kesungguhan tanpa berlebihan. Di desa, kematian-kematian memiliki kaitan-kaitan keluarga, mistik, pekerjaan, politik, agama, dan lain-lain. Kematian tak sekadar peristiwa. Kita membaca kematian dengan kemungkinan-kemungkinan sebelum memahami takdir. Di novel, Agus Subakir menjadi pengisah kematian sering tak wajar.
Tokoh minta diberi perhatian besar dalam novel: bapak. Kita lancar membaca tapi diajak bermasalah dengan kejawaan dan situasi pergaulan sosial-kultural pada masa Orde Baru. Gagasan keluarga (Jawa) minta terbaca serius sambil kita menandai lakon desa di naungan rezim Orde Baru memiliki “kesopanan” berbahasa politik dan “kekejian” dalam “menertibkan” warga negara di seantero Indonesia.
Pengarang sodorkan pengisahan: “Meskipun bukan sebuah susuk yang ditanam dalam tubuh, mantra yang dirapal berulang-ulang juga akan menyatu dengan darah. Dalam ilmu Jawa itu tak ada bedanya dengan susuk. Harus dibuang sebelum mati, jika tak ingin menjelang kematiannya membuat jengkel dan giris orang di sekitarnya karena tak mati-mati.” Sosok bapak telah rampung dengan pekerjaan “resmi”. Ia berada dalam petualangan lain, menghadirkan konsekuensi-konsekuensi tragis untuk keluarga dan desa. Ia dalam permainan kegilaan dan kematian.
Kita tergoda menikmati halaman-halaman novel diselingi membaca buku berjudul Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa (1981) susunan Clifford Geertz. Kita mencoba mengerti posisi orang-orang hidup di desa dengan perbedaan kategori-kategori. Agus Subakir dalam novel seperti membuat struktur sosial-kultural menjadikan kejawaan tak gampang dimengerti. Para tokoh memiliki peran-peran berkaitan pendidikan, pekerjaan, agama, silsilah, ideologi, dan lain-lain. Geertz memulai penjelasan memukau dengan kalimat bisa tergunakan dalam membaca novel: “… rupanya terdapat tiga inti struktur sosial di Jawa pada masa ini: desa, pasar, dan birokrasi-pemerintah – yang masing-masing diambil dalam artian yang lebih luas daripada biasanya.”
Pasar itu gejolak hidup. Di novel, pasar pun diramaikan orang-orang gila. Pengisahan makin mendebarkan dengan misi bapak mengurusi orang-orang gila. Di desa, usaha itu menimbulkan perhatian memicu pengertian-pengertian mistis. Kebiasaan bapak di pasar dan pinggiran desa berkaitan orang gila seperti mengambil alih peran birokrasi untuk mencipta tatanan hidup tenang, damai, dan makmur. Situasi terus pelik. Pengarang menjebak pembaca dengan urusan-urusan mencekam ketimbang girang. Pengisahan demi capaian sesuai judul: Lebih Mati Dari Mati.
Kita mengikuti kecamuk: “Sikap ibu jauh dari apa yang kubayangkan. Kenapa ia begitu pasrah, sementara aku yang bukan siapa-siapa mereka, malah menyimpan dendam? Bagaimana ini? Pikiranku berkecamuk hebat. Tidak! Semua orang yang membuat ibu tak bahagia harus berurusan denganku. Aku tak ingin pada masa tuanya ini ibu hanya menghabiskan waktu menunggu bapak sadar dan kembali kepadanya. Tidak, tidak! Lebih baik kubunuh saja bapak agar semua drama ini lekas selesai, dan agar ibu berhenti berharap pada lelaki gila itu.”
Agus Subakir pantang “reda” dan “lembut” dalam mengisahkan manusia-manusia dan kematian. Ia menjadi juru bicara kehidupan desa. Makna kematian di desa tak biasa-biasa saja bila menilik pelbagai hal, bukan sekadar gara-gara sakit, pembunuhan, bencana, atau kecelakaan. Kita mengandaikan saat menulis terjadi kerumuman imajinasi kematian untuk tampil. Agus Subakir tak sembarangan memilih kematian agar terbaca (paling) mencekam dalam novel.
Kita berhak jeda untuk mengamati lagi perkara-perkara Jawa melalui buku Koentjaraningrat berjudul Kebudayaan Jawa (1984). Persoalan keluarga dan pergaulan orang-orang desa dalam novel gubahan Agus Subakir mungkin dalam cocok atau “selisih” saat kita ingin mengerti berpatokan kematian-kematian. Pelbagai pola hubungan sosial-keluarga, ritual, kewajiban politik, dan pembahasaan di Jawa mengiringi penerimaan atas makna kematian.
Koentjaraningrat mengingatkan bahwa kelahiran dan kematian di (desa-desa) Jawa itu berkaitan religiomagi. Kita mengerti profesi ibu sebagai bidan. Bapak pernah mengalami hidu-hidup bercorak militeristik. Pensiun justru mengarahkan ke urusan wibawa dan petualangan bikin ruwet dengan orang-orang gila. Kematian-kematian dalam peristiwa-peristiwa rumit tak lekas selesai dengan mengartikan itu takdir. Di Jawa, pengisahan dan penjelasan justru menjadikan kematian menjadi heboh, menakjubkan, fantastis, dan tragis.
Agus Subakir bercerita: “Sekejap saja, orang-orang sudah berdatangan. Bersama-sama mereka membuka rumah itu dan mendapati mayat Pakde Samijan terbujur kaku di atas meja dengan segala pirantinya. Orang-orang hanya butuh keranda dan peti mati untuk membawanya ke kuburan. Orang-orang – para tetangga itu – sebenarnya telah menaruh curiga karena beberapa hari ini Pakde Samijan tak mengerek burung-burung perkututnya di halaman dan samping rumah. Ia juga tak pergi ke langgar untuk mengimami salat berjamaah.”
Lebih Mati Dari Mati bukan novel tebal. Kita cuma memilih untuk betah membaca atau memilih berhenti ketimbang kepikiran mati-mati. Agus Subakir terbukti pengarang “tabah” mengisahkan mati tak cuma mati. Begitu.
Judul : Lebih Mati Dari Mati
Penulis : Agus Subakir
Penerbit : Indonesia Tera
Cetak : 2021
Tebal : 221 halaman
ISBN : 9789797753245