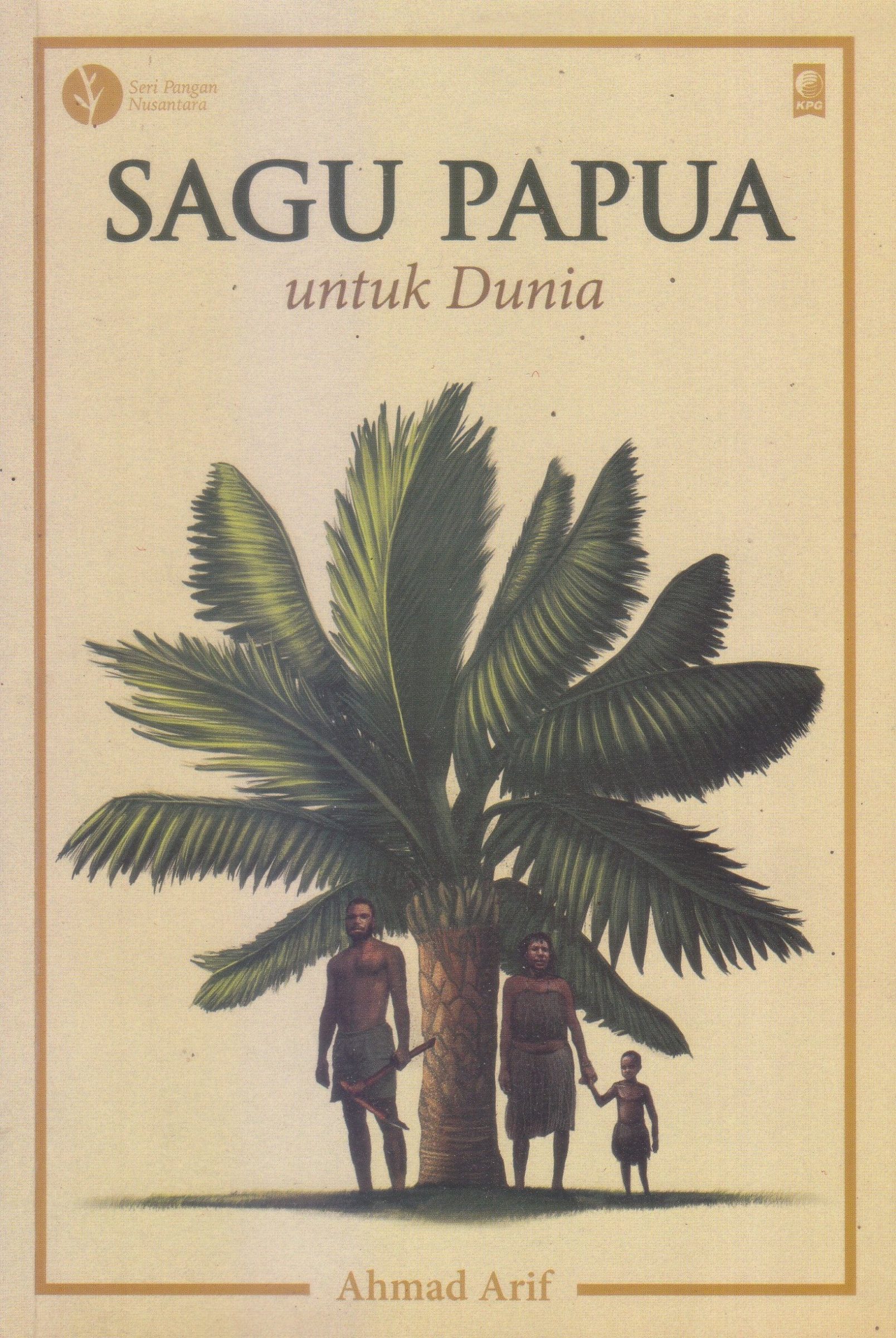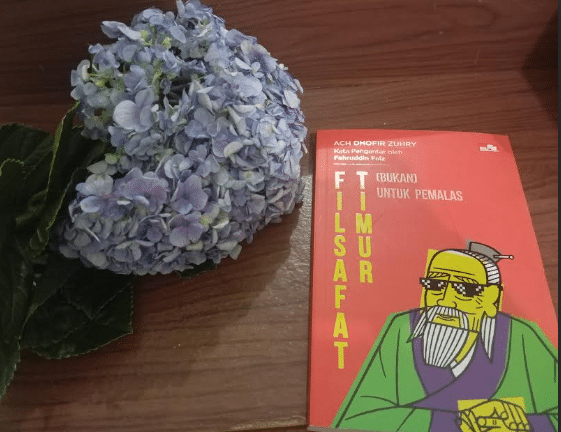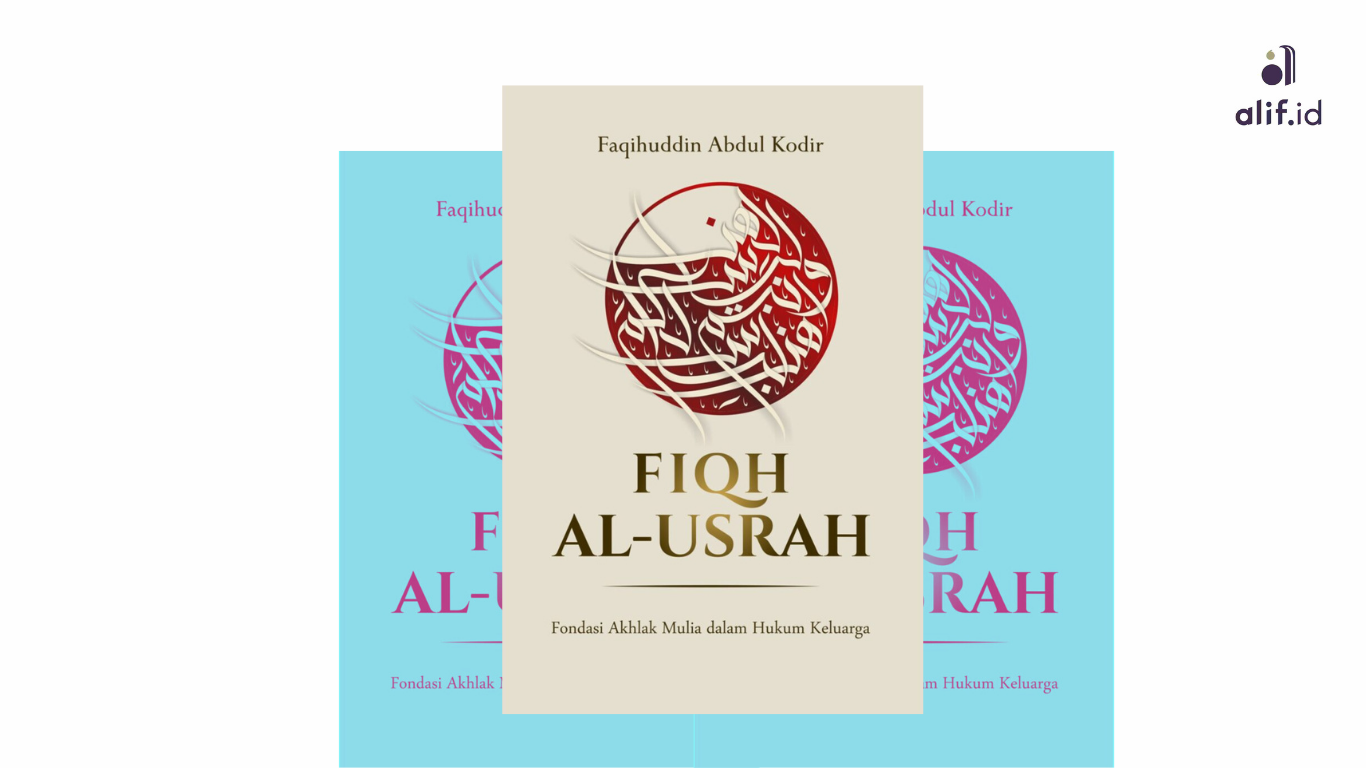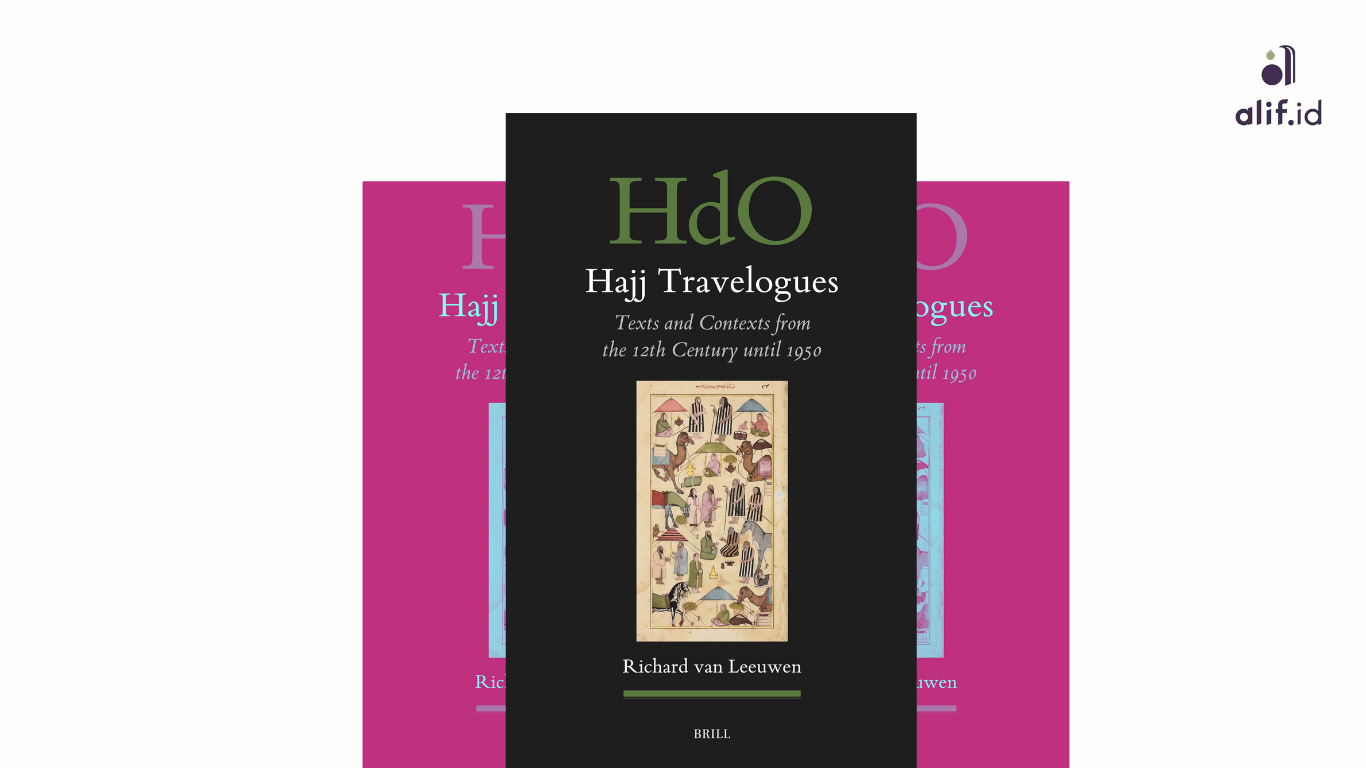Dulu, kaum muda bermimpi bisa kuliah di perguruan tinggi sering berada di kota-kota. Di kampus, mereka bakal berstatus mahasiswa dan bertemu buku-buku. Konon, misi berilmu memang mewajibkan membaca buku. Universitas memiliki misi keilmuan. Perpustakaan pun wajib ada. Perguruan tinggi abai buku bakal menimbulkan malu.
Tuduhan itu berlaku di masa lalu. Pada abad XXI, orang-orang mengaku kuliah di perguruan tinggi mungkin cuma memiliki 10 buku selama setahun. Semua buku tak mampu dikhatamkan. Mereka bisa lulus. Keinginan menekuni ilmu-ilmu sesuai jurusan sudah tak bergantung ke buku-buku.
Di perguruan tinggi Islam, buku-buku masih ada dan perpustakaan masih berdiri. Kita cuma menuduh: buku itu menganggur dan perpustakaan itu termangu.
Di Indonesia, kita mengetahui perguruan tinggi Islam negeri disebut STAIN, IAIN, atau UIN. Jutaan mahasiswa menempuh pendidikan di situ. Mereka belajar ilmu-ilmu agama dan umum. Nah, apakah mereka masih memerlukan tumpukan buku setinggi 10 meter untuk belajar dan lulus?
Jawaban bisa lekas diberikan tanpa malu-malu. Mereka semakin tak bergantung buku. Kita sejenak mengikuti laporan dikutip di Republika, 10 Juli 2019. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama melakukan penelitian dengan hasil: 90,9 persen mahasiswa belajar agama lewar internet. Penelitian bertema literasi keagamaan itu dilakukan di perguruan tinggi Islam negeri di Jakarta, Bandung, Banten, dan Cirebon. Duh, buku-buku menganggur dan memendam rindu tak kesampaian. Buku-buku tanpa pembaca.
Kita menghindari sangkaan buruk dengan membaca buku berjudul Al ‘Alaq, Bacalah! (2019) oleh Eko Prasetyo. Dulu, ia terkenal dengan buku-buku berjudul Orang Miskin Dilarang Sekolah dan Orang Miskin Dilarang Sakit. Kita bisa memberi usul jika buku baru diganti judul: “Orang Islam (Tak) Dilarang Baca Buku.” Oh, usulan tak bermutu. Judul buku sudah megah dan mengingatkan kita kembali ke Al Quran. Sejak kecil, Eko keranjingan buku-buku.
Pada pertengahan masa 1980-an, ia sudah rajin membaca majalah Tempo dan harian Kompas. Dua santapan memberi gairah berpikir dan menentukan sikap untuk pelbagai hal. Kebiasaan itu berlanjut saat menjadi pelajar dan mahasiswa dengan membaca buku-buku bertema agama. Ia mulai mengerti ada ajakan mengubah zaman dengan membaca buku-buku. Pembaca terbiasa bersantap buku-buku menanggungkan dampak ke iman.
Eko mengaku bahwa membaca memastikan ia masih merasa memiliki iman. Pengakuan berlatar kejengkelan atas umat Islam sudah abai perintah “bacalah”.
Kita membandingkan dulu pengalaman baca Eko dengan Taufik Abdullah, sejarawan dan kolomnis ampuh asal Sumatra. Di buku berjudul Bukuku Kakiku (2004), Taufik Abdullah turut menulis biografi membaca:
“Saya telah duduk di kelas tiga SMP ketika saya membaca buku Achdiat Kartamihardja, Atheis. Ini saya lakukan gara-gara saya sempat membaca di sebuah majalah tentang perdebatan mengenai buku ini. Karena Buya Hamka mengatakan bahwa ia senang dengan buku itu, saya pun membacanya juga.”
Si remaja itu tak menjadi atheis. Ia membaca buku untuk iman, menempuhi jalan keilmuan, kesusastraan, dan keagamaan. Pada buku-buku, Taufik Abdulah mulai menapaki jenjang akademik dan memberi penjelasan sejarah ke publik. Kita mengingat ia menulis disertasi tentang “Kaum Muda” di Sumatra berkaitan politik, pendidikan, dan agama.
Kini, zaman digital memiliki “umat” fanatik. Eko berlagak “melupakan” dengan kenekatan menulis surat di kertas. Di surat mengandung imajinasi dialamatkan ke Ibnu Sina, Eko memberi kabar, keluhan, kemarahan, dan kerinduan masa lalu. Ibnu Sina jadi tokoh idaman gara-gara tekun membaca dan mengerti kitab suci. Ibnu Sina pun menulis buku-buku berpengaruh di peradaban dunia: Timur dan Barat. Selama ratusan tahun, Ibnu Sina dihormati kaum intelektual. Eko mengagumi dan menulis kalimat-kalimat di surat tak bakal pernah sampai ke alamat:
“Kini, buku seperti menjauh dari rumah ibadah kami. Masjid kami bangun megah. Lapangan parkir didesain indah. Menara untuk adzan dibangun menawan. Tak jarang lantai masjid itu dibuat mengkilap. Namun, kami tak memiliki perpustakaan megah: jumlahnya bukunya sedikit dengan judul sangat terbatas.”
Kalimat-kalimat sindiran bagi pemerintah-pemerintah di pelbagai kabupaten dan kota sedang mendirikan masjid besar (agung) dengan dana miliaran rupiah. Sekian masjid sudah berdiri dengan arsitektur meniru Timur Tengah tanpa ada pengabaran di situ ada perpustakaan. Masjid memang belum dimengerti penuh sebagai rumah ibadah, rumah buku, rumah percakapan. Surat itu siasat memberi sindiran ke umat Islam agar memikirkan buku ketimbang menara tinggi menghabiskan miliaran rupiah. Buku-buku bakal jadi menara iman dan meninggikan pengetahuan umat.
Kita masih di lembaran-lembaran surat buatan Eko. Sekian protes, sesalan, dan impian dicantumkan. Beralih ke surat diniatkan untuk Ibnu Hazm, pujangga kondang meninggalkan warisan puisi-puisi memikat, bergerak dari asmara ke pengabdian kepada Tuhan. Kekaguman membaca puisi gubahan Ibn Hazm memunculkan usulan. Eko mengutip puisi:
Saat kutenggelam dalam samudera cinta/ Hamparan bumi seolah kering binasa/ manusia laiknya buih-buih di lautan/ Menghuni mayapada laiknya lalat-lalat beterbangan.
Kutipan itu dijadikan dalih mengusulkan agar masuk dalam buku pelajaran agama di SMA. Eko pasti pamer sesalan bahwa dulu saat SMA tak pernah menemukan puisi di buku pelajaran agama dan guru agama tak mengerti sastra. Puisi cuma menghuni buku pelajaran bahasa Indonesia. Usulan Eko bisa dipertimbangkan dan minta restu Kementerian Agama. Buku pelajaran agama diharapkan mengandung gairah-indah, bukan cuma menjelaskan perintah dan larangan.
Usulan itu bisa ditambahi dengan materi biografi para tokoh di Indonesia: Hamka, M Natsir, Agus Salim, Ali Audah, dan lain-lain. Mereka itu ulama, intelektual, pengarang bermisi memajukan Islam di Indonesia dengan rajin menghasilkan buku-buku.
Mereka menegakkan iman dengan siasat keaksaraan. Di buku pelajaran, murid-murid SMA mungkin tergoda turut menjadi “kaum buku”. Guru agama berhak mengajurkan para murid membaca novel, puisi, atau cerita pendek agar mengerti bahwa beriman dengan membaca buku itu bukan larangan. Ingat, orang ingin beriman tak terlarang membaca buku. Kini, beriman dengan sibuk berinternet saja belum mendapat fatwa larangan.
Kita akhiri dengan membaca petikan surat Eko kepada Muhammad Iqbal, filosof dan pujangga agung. Kalimat-kalimat masih keras mengandung marah: “Kini, kita seperti kehabisan ide karena ketentuan agama diciutkan pada organisasi dan aturan hukumnya. Agama dibajak oleh para pemuka yang merasa punya pengetahuan dan pengalaman lebih. Tapi, itu pula yang membuat agama gampang disalah-gunakan.”
Eko belum reda dari marah. Ia masih berseru bacalah! Orang membaca mungkin insaf dan mengerti dalam penguatan iman dan menjadikan peradaban itu mulia bagi semua. Ia bakal terhindar dari ulah-ulah kotor, norak, dan biadab mengatasnamakan agama. Pembaca buku berhak jadi pemberi peringatan, pembantah, dan peralat dari jebakan-jebakan kebodohan, kekerasan, kekolotan, dan keminderan umat Islam di Indonesia abad XXI. (RM)
Judul : Al ‘Alaq, Bacalah!
Penulis : Eko Prasetyo
Penerbit : Intrans Publishing dan Social Movement Institute
Cetak : 2019
Tebal : 194 halaman
ISBN : 978 602 6293 75 6