
Untuk sekian waktu ke depan, politik Indonesia masih akan terus terjebak pada kontroversi soal politik identitas. Bagi sebagian orang, politik identitas sungguh ada dan berbahaya. Bagi sebagian yang lainnya, politik identitas adalah sesuatu yang alamiah dan oleh karenanya mesti ditanggapi sewajarnya. Pertanyaannya, kapan sesungguhnya identitas berubah menjadi politik identitas dan apa maknanya?
Di Indonesia hari ini, secara lebih khusus politik identitas merujuk pada peristiwa-peristiwa di sekitar aksi 212 yang terjadi beberapa tahun silam. Tentu saja sebelumnya istilah itu telah mengemuka, tetapi rangkaian aksi 212 selama 2016-2017 membuat signifikansi yang berdampak panjang. Terutama bagi mereka yang merasa kalah dalam pertarungan politik Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menjadi latar belakang utamanya, aksi 212 menimbulkan trauma yang harus dihindari agar tidak terulang.
Rupanya, bahkan setelah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan melalui mekanisme penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat, trauma terhadap kembalinya aksi 212 terus membayangi. Aktor-aktor dan simbol-simbolnya dipercaya masih berdaya seperti dulu. Seolah-olah sejak itu politik Indonesia berhenti pada ruang dan waktu tertentu.
Dalam kenyataannya, politik Indonesia sejak aksi 212 bergerak sangat dinamis. Sentimen negatif terhadap individu-individu dan kelompok-kelompok yang terlibat dalam aksi tersebut berhasil dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi untuk meningkatkan legitimasi pemerintahannya. Terlebih lagi sejak Prabowo Subianto ikut bergabung ke dalam kabinet Jokowi setelah Pemilu 2019, para tokoh aksi 212 yang dulu terlihat gagah sekarang tampak seperti pasukan ringkih yang terlunta-lunta di kancah perang.
Konsolidasi kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi pasca-212 dapat dikatakan sangat berhasil, bahkan melebihi apa yang mungkin dia bayangkan. Sejak itu arus konservatisme agama yang menguat sejak Reformasi 1998 dipukul mundur. Meski diyakini mempunyai ribuan dan bahkan jutaan anggota, pembubaran HTI dan FPI nyaris mulus tanpa gejolak yang berarti. Sejak itu apa yang oleh Martin van Bruinessen (2014) disebut sebagai “conservative turn” dalam kehidupan keagamaan di Indonesia kehabisan nafas karena pergeseran orientasi patron ekonomi-politik di belakangnya.
Pokok yang ingin dikatakan adalah bahwa politik identitas pada dasarnya bukan hanya soal identitas, tetapi juga kekuatan ekonomi-politik yang mampu memobilisasi itu. Islam saja tidak cukup, tetapi siapa yang bisa menggerakkan orang-orang agar mau berjuang atas nama Islam ke medan laga. Dalam sejarah terbukti siapa yang menggerakkan itu tidak selalu orang yang mempunyai komitmen pribadi terhadap Islam, sebab bisa saja kalangan sekuler sejauh mempunyai uang dan kepentingan. Secara sosiologis sebagian dari mereka yang dituduh konservatif itu bukan berasal dari golongan santri, melainkan kaum abangan yang bertransformasi menjadi lebih religius. Ini artinya, dalam praktik keseharian, baik santri maupun abangan adalah identitas-identitas yang cair dan dalam kondisi tertentu bisa saling dipertukarkan.
Masalahnya, kampanye anti-politik identitas yang digelorakan selalu merujuk pada identitas sebagai biang keladinya. Seolah-olah perkaranya adalah pemahaman terhadap agama yang salah. Tidak heran kegiatan moderasi beragama yang dilancarkan oleh pemerintahan Jokowi lebih menyasar aspek hermeneutis daripada problematik ekonomi-politik.
Selain itu, kampanye anti-politik identitas juga jarang atau bahkan tidak pernah diarahkan kepada identitas sekuler. Seakan-akan nasionalisme bukan sebentuk identitas. Publik Indonesia tidak dikenalkan dengan kenyataan di sejumlah negara Barat di mana nasionalisme bisa berkembang sangat eksesif sedemikian rupa sehingga terjatuh pada sikap rasis dan fasis. Bukankah dua perang dunia di abad lalu terjadi karena politisasi identitas nasionalisme yang super berlebihan?
Salah kaprah mengenai politik identitas bertambah rumit di era digital sekarang ketika para buzzer semakin mendapat tempat dalam konstruksi pengetahuan publik. Secara sengaja mereka mereproduksi pengertian tentang politik identitas yang statis. Di berbagai platform media sosial mereka menyebarkan pandangan bahwa, misalnya, Muslim tradisional dan modernis tidak mungkin bersatu atau NU dan FPI adalah mirip air dan minyak. Di sisi lain, mereka menyodorkan kesan bahwa dalam sejarah politik Indonesia yang boleh cocok berpasangan hanyalah santri tradisional dan abangan atau, dalam konteks politik elektoral sekarang, NU dan PDIP.
Sekali lagi, politik identitas akan terus menjadi kontroversi, tetapi jika itu dianggap ancaman lalu apa alternatifnya? Bukankah kampanye anti-politik identitas sama dengan kampanye anti-SARA (suku, agama, ras, antar-golongan) yang dulu diajarkan oleh pemerintahan Soeharto? Apakah kita mau kembali pada zaman itu?
Tentu tidak. Oleh karena itu, mari kita memahami identitas dalam lintasan ruang dan waktu. Identitas menjadi politik identitas ketika ditetapkan pada satu pengertian yang seolah-olah tidak akan bisa berubah. Fiksasi inilah yang berbahaya karena pasti akan digunakan sebagai senjata untuk menghancurkan mereka yang berbeda.















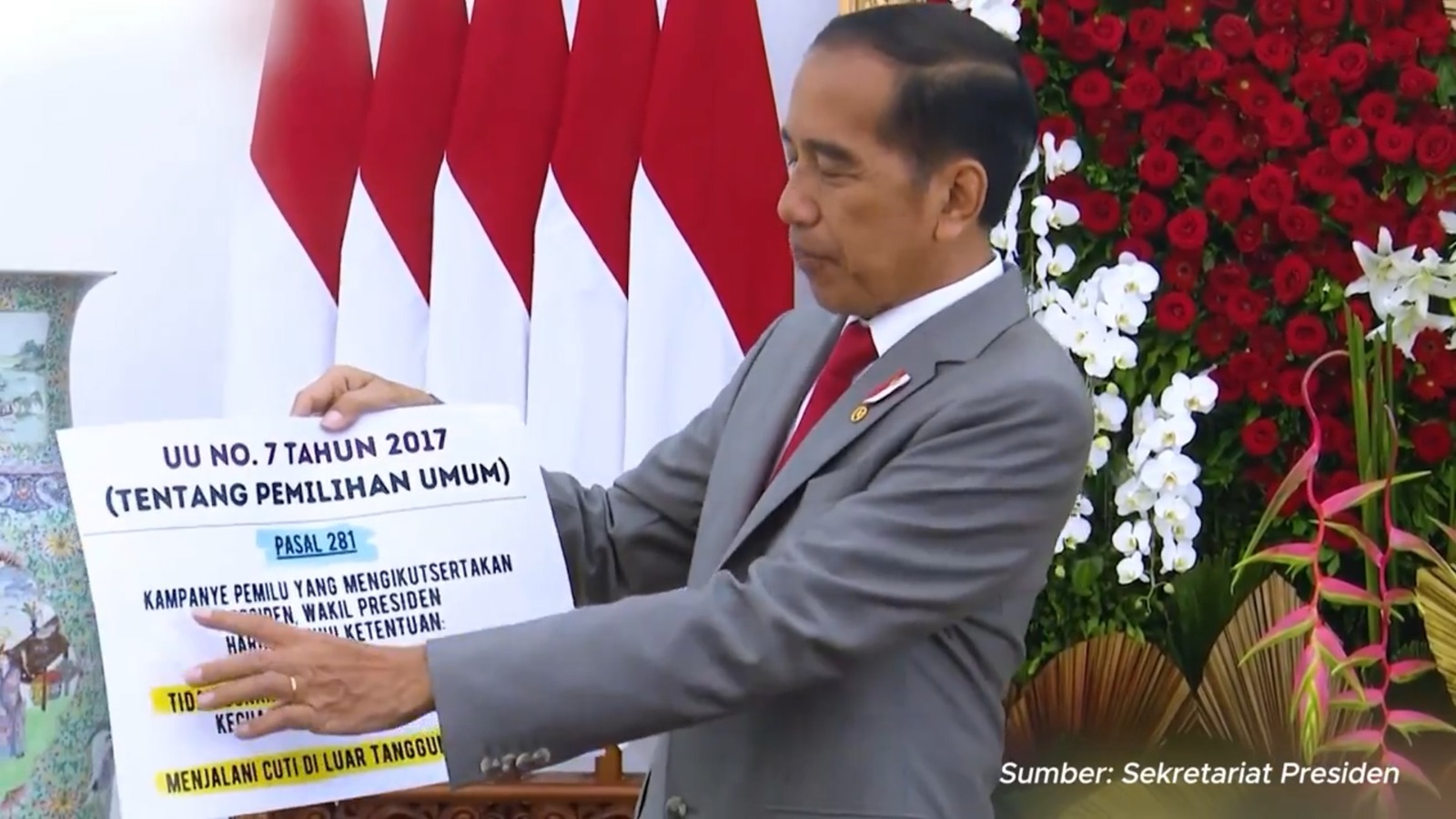




![Sejumlah warga Gaza mengaku kebingungan setelah tempat tinggal mereka hancur akibat bom yang dilancarkan oleh pihak Israel. [foto: AFP]](https://alif.id/wp-content/uploads/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-11-at-05.31.38.jpeg)