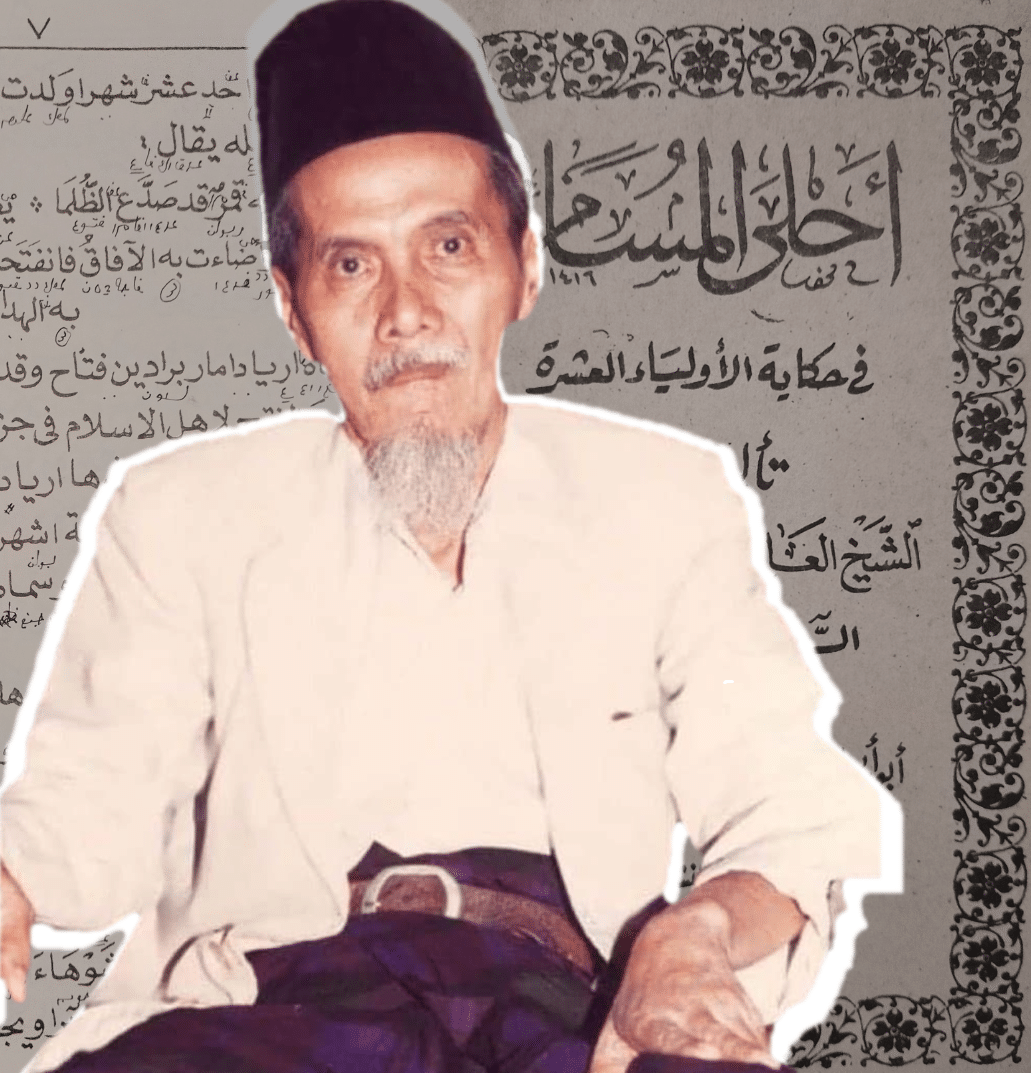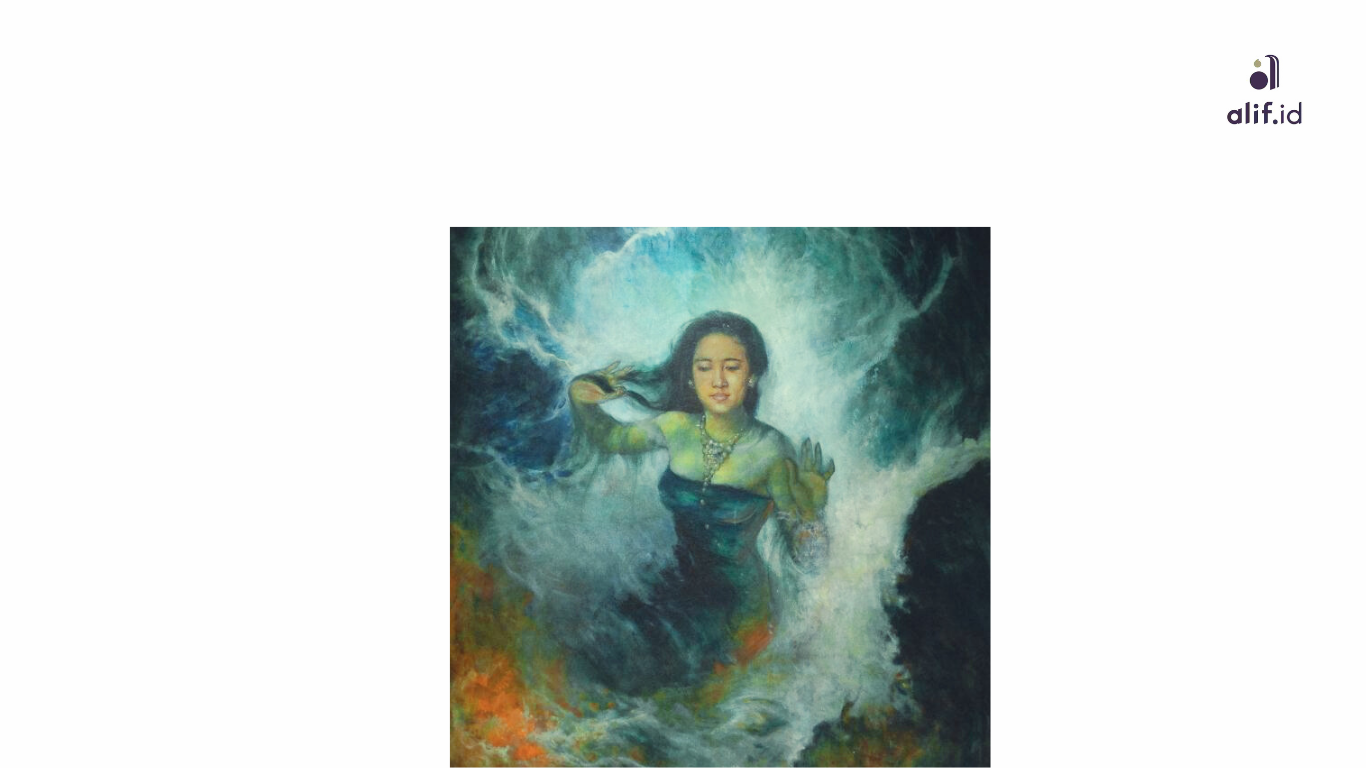Ya, Jesusmu adalah juga Jesusku/Ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan tinggi hati/Ia membuatku cinta pada yang dinista!/Semoga Semua Hidup Berbahagia dalam kasih. (2013)
Empat baris kalimat di atas adalah penutup puisi Paskah, karya Ulil Abshar Abdulla yang belakang banyak menuai soroton. Sebenarnya seorang yang terbiasa membaca puisi, tak ada hal yang patut dicurigai dari puisi Paska itu, apalagi dipersoalkan. Kenapa?
Sebab setiap puisi ia membangun sesuatu, sebuah struktur, dari imaji, pengalaman, bacaan, ritual, pergumulan, juga tentu pengetahuan dan teologi. Dan, manusia memerlukan semuanya itu. Terlebih seorang penyair. Lebih-lebih penyair atau intelektual yang hari-harinya sering berkutat dengan doktrin tasawuf.
Jika kita meminjam cara pandang Badiou, adalah sebuah “kejadian” dan tafsirnya: tiap ikatannya tak pernah terpisahkan dari latar belakang dengan dunia si penerima peristiwa dan segala pengalamannya, baik yang-utuh, maupun yang tidak. Kejadian itu lalu bisa ditafsirkan, dan diperas menjadi sebuah puisi.
Karenanya menurut Paul Ricoeur, tidak bisa kita membaca teks sastra, selalu mengkaitkan dengan makna umum yang biasa berlaku di masyarakat, atau dalam membaca sastra tak bisa kita memahami hanya sebatas bahasa yang normatif. Untuk menikmati keindahannya mau tak mau, rela tak rela, kita harus melepaskan makna yang normatif dan umum itu! Inilah teori sastra itu. Karena itu, kemudian lahirlah pencetus-pencetus teori membaca sastra.
Menurut Paul Ricoeur, ada tiga langkah untuk memahami karya sastra, yaitu:
Pertama, langkah simbolik yang berlangsung dari penghayatan atas simbol-simbol ke gagasan tentang “berpikir dari” simbol-simbol.
Kedua, langkah pemberian makna oleh simbol serta “penggalian” yang cermat atas makna.
Ketiga; langkah yang benar-benar filosofis, yaitu berpikir dengan menggunakan simbol sebagai titik tolaknya.
Ia yang rebah, di pangkuan perawan suci, bangkit setelah tiga hari, melawan mati.
Ia yang lemah, menghidupkan harapan yang nyaris punah.
Ia yang maha lemah, jasadnya menanggungkan derita kita.
Ia yang maha lemah, deritanya menaklukkan raja-raja dunia.
Ia yang jatuh cinta pada pagi, setelah dirajam nyeri.
Ia yang tengadah ke langit suci, terbalut kain merah kirmizi: “Cintailah aku!”
Tak bisa dipungkuri, jika kita membaca bait diatas dengan bacaan standart normatif atau fikih an-sich, secara permukaan tampak ada yang tak beres dengan akidah muslim secara awam. Bagaimana jasad yang lemah bisa menanggungkan derita anak manusia? Bagaimana seorang yang dirajam bisa membangkitkan sebuah harapan? Apakah ini bukan doktrin Kristiani?
Sebenarnya bait puisi seperti itu dalam tradisi tasawuf menjadi hal yang lumrah. Gagasan pluralisme atau kemanunggalan atau Kesatuan Eksistensi, bukan barang baru, dan milik Ulil Abshar Abdulla. Tapi hampir semua sufi besar yang tercerahkan bicara tentang gagasan ini. Suatu ketika Abu Bakar al Syibli pernah berujar: “Aku menemukan diriku di antara Kuil-Kuil dan belahan waktu”, Abu Yazid al Bisthami berucap :”O, Betapa Maha Sucinya Aku.”
Ibnu Arabi mengatakan: “Seorang sufi melihat Allah dalam Kakbah, dalam Masjid, dalam Gereja dalam Kuil.” Hazrat Inayat Khan: “Masjid, Geraja, Wihara, Klenteng, Sitogog hanyalah baju untuk menutup diri agar jiwa tak hilang.”
Begitu juga dengan Al-Hallaj. Ia mengatakan: Sungguh, aku telah merenung panjang agama-agama/Aku temukan satu akar dengan begitu banyak cabang/Jangan kau paksa orang memeluk satu saja/Karena akan memalingkannya dari akar yang menghunjam/Seyogyanya biar dia mencari akar itu sendiri/Akar itu akan menyingkap seluruh keanggunan dan sejuta makna/Lalu dia akan mengerti. (Diwan, 50)
Abdullah bin Thahir al-Uzdi pernah bercerita: “Aku bertengkar habis dengan seorang Yahudi di sebuah pasar di Baghdad. Kepada si Yahudi itu aku katakan: Hai anak anjing! Tak disangka Al-Hallaj kebetulan lewat dan memandangku dengan tidak suka. Lau dia berkata; “hentikan kekonyolanmu”, lalu pergi.
Begitu kami usai bertengkar, esoknya aku menemuinya dan memohon maaf. Hallaj lalu mengatakan: “Saudarku, ingat! Semua agama adalah milik Allah. Setiap golongan memeluknya bukan karena pilihannya, tetapi dipilihkan Tuhan. Orang yang mencaci orang lain dengan menyalahkan agamanya, dia telah memaksakan kehendaknya sendiri. Ingatlah, bahwa Yahudi, Nasrani, Islam dan lain-lain adalah sebutan-sebutan dan nama-nama yang berbeda.
Jalaludin Rumi juga pernah mengatakan: “Kucari Tuhan di Candi, Gereja dan Mesjid. Namun kutemukan Tuhan justru di dalam hatiku.” Bahasa cinta Rumi, dan yang lainnya yang mereka gunakan itu adalah bahasa universal melampaui formalitas agama.
Demikian itu menurut Al-Syarqowi, karena seseorang sudah mencapai maqam Ma’rifah, dan itu bisa diraih saat seorang hamba sudah mampu melewati sekat-sekat formalitas dan matrealisme. Pikiran dan pengalaman Hulul, Ittihad atau Wahdah al Wujud tak pelak melahirkan gagasan Pluralisme agama-agama. Itu keniscayaan. Baginya semua agama adalah sama. Para pemeluk agama tak pernah berhenti mencari Sang Realitas, melalui beragam jalan, berbagai nama. (al-haqq, al-sahq wa al-mahq). (Al-Syarqowi, Al-Fadh Shufiyyah, 194)
Salah satu buku kumpulan puisi Rumi yang sangat terkenal, yakni Masnawi. Buku yang dari enam jilid dan berisi 20.700 bait syair. Dalam karyanya itu menurut Syarqowi sudah melampaui sekat-sekat itu, dan yang terlihat hanya ajaran-ajaran tasawuf yang mendalam, yang disampaikan dalam bentuk apologi, fabel, legenda, anekdot, dan lain-lain. Karenanya dalam muqadimahnya Jalaluddin Rumi mengatakan:
“Aku tidak mendendangkan Masnawi agar orang membaca dan menjadikannya nyanyian atau sekedar menjadikannya lagu dan puisi, akan tetapi aku berharap agar orang meletakkan tiap paragraf buku itu, agar menaruhnya di telapak kaki dan tangan mereka, kata-kata itu bisa terbang bersamanya untuk menggapai tangga pendakian dan membelah sekat-sekat dhahir menuju kebenaran…”
Imam Jalal al-Suyuti, salah satu pembela kaum sufi yang dianggap sesat, terutama Ibnu Arabi, dengan tanpa ragu mengatakan : “Ma Kana Kabirun fi ‘Ashr Illa Kana Lahu ‘Aduwn min al Safalah” (Orang besar dalam sejarah selalu punya musuh orang-orang bodoh).
Jadi seperti itulah, ketika puisi ditulis atau diungkapkan kata Paul Ricoeur, sebenarnya tak bisa disekati oleh batas-batas otoritas manapun, termasuk oleh agama. Karenanya puisi itu bersifat subyektif, sekaligus universal, ditulis secara pribadi tapi boleh dibaca oleh siapapun, dan menjadi pengalaman siapapun. Masing-masing pembaca merdeka dengan pemaknaannya.
Begitu juga puisi Ulil Abshar Abdulla yang beragama Islam bisa dibaca oleh siapapun, termasuk yang berbeda agama. Namun, saya setuju dengan ungkapan arab, likulli maqal maqam, walikulli maqal maqam. Semua ada tempatnya masing-masing. Karenanya, sayangnya puisi sufistik Ulil ini dibaca oleh siswa, yang maqamnya bisa menjadi perdebatan. Wallahu’alam bishawab.
Kasongan, 14 April 2020