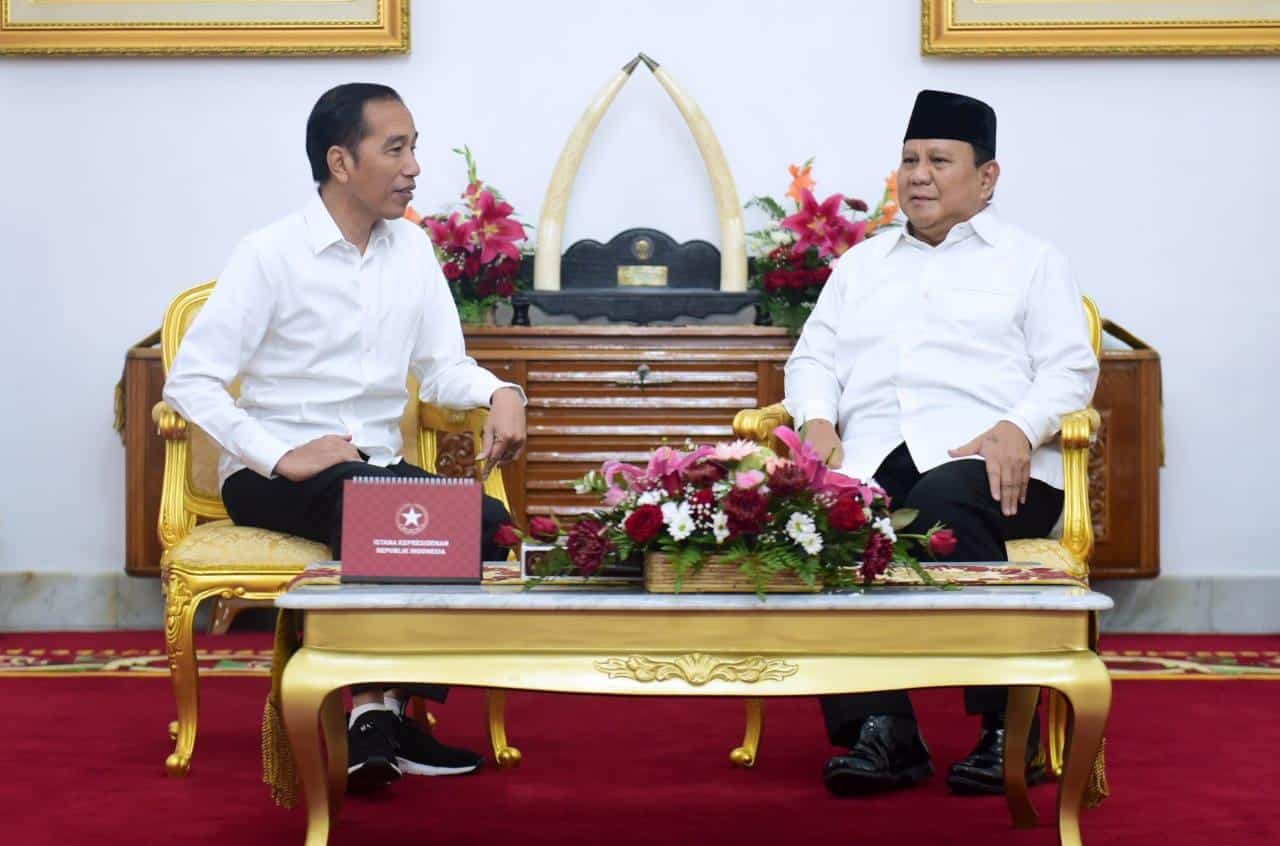Tidak perlu baper, tulisan pendek ini memang diniatkan sebagai kritik diri. Indonesia yang begini besar populasi dan wilayah geografisnya—selain sejarah yang panjang dan sumber daya alam yang melimpah serta kekayaan budaya yang luar biasa—sampai sekarang masih begini-begini saja, antara lain karena mayoritas kita lebih sering berpikir sempit dengan imajinasi kecil.
Untuk banyak urusan, kesadaran kolektif kita adalah kesadaran kolektif kecil parokial. Kita kerap sulit keluar dari ikatan-ikatan kolektif kecil untuk berpikir dan bekerjasama dengan imajinasi besar demi kepentingan kolektif yang lebih besar. Para pendiri bangsa telah berhasil melampaui imajinasi kecil dan ikatan kolektif kecil itu melalui Sumpah Pemuda 1928 dan deklarasi kemerdekaan 1945. Sekarang kita justru sering macet, jika bukan malah mundur dari sana.
Dalam konteks hidup berbangsa yang besar dan plural ini, kita sering terjebak dalam ikatan-ikatan kolektif kecil seperti agama, suku, bahkan organisasi dan masih sulit keluar dari imajinasi kecil itu. Bagi saya, banyaknya partai politik sejak Reformasi 1998 bukan pertama-tama merupakan isyarat sehatnya demokrasi, tapi justru gejala dari imajinasi kecil dan ketakmampuan kita melampaui ikatan-ikatan kolektif kecil tadi. Ketika berpikir tentang Indonesia, banyak diantara kita yang membayangkannya tidak lebih dari kelompok kecil agama, suku, wilayah daerah atau bahkan organisasinya.
Imajinasi kecil dan ikatan kolektif parokial sempit ini bahkan tetap terlihat di kalangan orang Indonesia yang hidup di luar negeri. Sebagai warga bekas jajahan, para keturunan India, Pakistan, dan Bangladesh yang tinggal di Inggris berjumlah besar dan punya daya tawar politik yang besar secara kolektif. Mereka bisa mengorganisasikan diri sehingga punya kemampuan mendesakkan kepentingan kolektif mereka terhadap pemerintah bekas penjajahnya itu. Tapi, meskipun telah menetap sekian lama di Belanda, kenapa warga keturunan Indonesia tak punya daya tawar yang sama di sana?
Kita terbiasa hidup dengan imajinasi kecil dalam ikatan-ikatan kelompok kecil yang berjalan sendiri-sendiri. Alih-alih membangun penghubung, secara administratif mulai dari tingkat RT, dusun, desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi, misalnya, masing-masing unit kelompok merasa perlu membuat batas-batas pemisah seperti gapura atau tugu yang menunjukkan betapa kita berpikir serba terkotak-kotak ke dalam.
Di beberapa kota, dalam situasi darurat, gapura RT bahkan menghambat akses, seperti membuat mobil pemadam kebakaran yang hendak menolong keselamatan warga jadi tak bisa masuk. Ruwetnya penanganan banjir Jakarta antara lain juga akibat imajinasi kecil dan cara berpikir parokial ini. DKI hanya berpikir DKI, Jawa Barat hanya berpikir Jawa Barat, padahal hujan, sungai dan aliran air ya satu.
Batas-batas fisik yang ditonjolkan itu sekaligus juga menjadi penegas bahwa masing-masing kelompok berdiri secara ekslusif, yang membuatnya sulit ditembus oleh mereka yang dianggap berasal dari “luar”. Siapapun yang pernah tinggal di luar wilayah suku, agama, bahkan asal daerahnya tentu pernah mengalami bagaimana diperlakukan sebagai “orang luar” entah dalam kategori asli-pendatang atau pribumi-nonpribumi dengan segala konsekuensi sosialnya yang tak mudah. Kesadaran mengenai keragaman atau multikulturalisme kita masih bercorak ala “Taman Mini Indonesia Indah” atau ramai-ramai mengenakan baju adat pada hari-hari tertentu, perayaan yang masih bersifat permukaan. Keragaman belum menjadi kekayaan bersama yang menyatukan dan saling menguatkan.
Akibat kecenderungan imajinasi kecil dalam ikatan-ikatan parokial kecil itu, meski hidup dalam ikatan kolektif yang besar, setiap unit kelompok lebih sering berdiri dan mengurus atau mencukupi semua kebutuhannya sendiri secara saling terpisah. Sumber daya, waktu dan potensi yang ada kerap terhambur di banyak kelompok dan lokasi sehingga tidak menjadi kekuatan besar yang bisa didayagunakan secara efektif melalui koordinasi yang baik demi kepentingan kolektif yang lebih besar.
Kita lebih banyak hidup dalam komunitas dengan “strong ties” (ikatan-ikatan kuat), dalam istilah sosiolog Mark Granovetter (1973), yakni komunitas kecil-kecil dengan ikatan sangat kuat ke dalam, tapi lemah ke luar, yang kerap menandai watak masyarakat agraris. Dalam komunitas seperti itu, identifikasi kelompok kecil memang sangat kuat, tapi konflik internal juga sangat tinggi karena semua orang berebut di dalam wilayah sempitnya masing-masing yang tertutup dan terbatas. Strong ties (ikatan-ikatan kuat), karena itu, justru menjadi penghambat kemajuan.
Masyarakat maju justru ditandai oleh weak ties (ikatan-ikatan longgar), dimana para warganya punya lebih banyak asosiasi dan ruang lingkup pergaulan yang melampui batas-batas kelompok sempitnya sehingga mereka bisa bergerak leluasa baik untuk mengakses peluang-peluang lain dan terhindar dari keterjebakan konflik internal yang sengit.
Dalam konteks ini, menarik untuk melihat fenomena Perguruan Tinggi kita. Di kampus-kampus besar seperti UGM, UI, ITB, Unair dll, universitas kerap mirip himpunan dari fakultas-fakultas sebagai “kerajaan-kerajaan kecil” dengan strong ties yang diandaikan serba mencukupi dirinya sendiri. Masing-masing fakultas punya perpustakaan, kantin, tempat parkir, bahkan musholla. Universitas adalah kumpulan fakultas-fakultas dalam relasi yang disebut “alone together”, sendiri-sendiri tapi secara berjama’ah.
Akibatnya, banyak civitas akademika yang sebenarnya adalah warga fakultas (bahkan prodi!) dengan pergaulan yang minimal di tingkat universitas. Meski identitas formalnya adalah warga universitas, dalam kenyataan identifikasi diri mereka lebih nyata pada fakultas, atau bahkan prodi. Tidak heran, selain kerap sulit dikoordinasi di tingkat universitas sebagai lembaga yang lebih besar, konflik internal fakultas juga sangat tinggi karena wataknya yang bersifat strong ties tadi.
Tapi, silakan tanya: berapa banyak sumberdaya dan peluang lebih besar yang ‘terbuang’ gara-gara setiap unit-unit kecil dalam suatu entitas besar bernama universitas maunya berjalan sendiri-sendiri, seperti pengelolaan perpustakaan atau penyediaan ruang publik lain, yang mestinya lebih efektif jika dikelola bersama? Berapa banyak ruang, sistem, tenaga, buku-buku dan hal-hal lain, yang harus disediakan untuk kepentingan yang sama bernama perpustkaan yang banyak dan kecil-kecil di setiap fakultas? Jika itu semua disatukan, bukankah perpustakaan akan menjadi lebih besar dan megah, lebih efektif tenaga dan sistemnya dan setiap kekayaannya bisa dimanfaatkan untuk melayani warga kampus dari fakultas mana saja yang mengaksesnya?
Kalau kita sudah sangat paham metafora kelemahan lidi dan kekuatan sapu lidi, kenapa kita masih terus melakukan kesalahan yang sama? Apakah kita memang lebih suka menjadi raja-raja kecil dengan kekuasaan semu, ketimbang membangun kekuatan bersama yang nyata tapi dengan posisi yang tak selalu terlihat serta-merta? Inilah yang saya sebut imajinasi kecil, yang tak sebanding dengan kuantitas dan potensi besar yang tersedia. Kita masih menjadi bangsa besar tapi kecil.
Di luar kampus juga tidak jauh beda. Di kalangan umat Islam, pesantren begitu banyak jumlahnya, tapi masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Umat Islam jumlahnya begitu besar, tapi tidak sebanding dengan kekuatan yang dimilikinya, khususnya ketika menyangkut kontribusi terhadap kehidupan bersama yang melampaui batas-batas kelompok. Banyak orang Islam baru bersatu, itu pun bersifat sementara, ketika marah karena merasa kepentingan sempitnya terancam. Kebersamaan kita masih lebih banyak di permukaan dan diikat oleh semangat perjuangan melawan (fight against) yang parokial, ketimbang semangat perjuangan demi (fight for) kepentingan bersama yang lebih universal.
Kita tahu, ketika dulu orang-orang Belanda datang untuk mendesakkan kepentingan dan akhirnya menjajah, kita gampang diadu domba. Selain mereka punya peta dan statistik, kita memang sudah terjebak dalam imajinasi kecil dalam ikatan-ikatan kelompok kerajaan-kerjaan kecil itu. Devide et impera tak akan bekerja dengan efektif sekian lama, jika kita tak menyediakan peluang yang banyak untuk diadu domba. Jumlah manusia dan wilayah yang besar serta potensi yang melimpah tak akan banyak artinya, jika imajinasi kita kecil dan terikat dalam kesadaran kolektif parokial yang sempit. Negeri Belanda kini berpenduduk sekitar 17 juta saja, tapi kekuatan mereka jauh di atas Indonesia, sesuatu yang berlangsung sejak jaman mereka menjajah kita selama ratusan tahun sampai sekarang.
Imajinasi besar dan kemampuan untuk mengelola diri sebagai bagian dari warga dengan ikatan kolektif yang besar melampaui batas-batas kelompok kecil adalah kuncinya. Tanpa itu kita akan tetap menjadi bangsa yang besar terutama dalam soal angka. Cocok menjadi penonton dan pasar empuk komoditas apa saja, tapi hanya berperan marginal dalam berbagai urusan dunia.
Negara-negara seperti Denmark, Norwegia, Finlandia dan Singapura berpenduduk sekitar 5 juta saja. Luas teritori negara-negara itu juga kecil. Menurut statistik dan peta mereka adalah negara-negara kecil. Tapi capaian ekonomi, peran politik global dan prestasi negara-negara itu dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olah raga dan kebudayaan secara umum sangat menonjol. Mereka termasuk kategori negara-negara yang memainkan peran strategis dan kontribusi penting, mereka adalah negara-negara besar.
Sebaliknya, Brazil, Pakistan, Nigeria, dan Indonesia berpenduduk lebih dari 200 juta. Tapi di panggung internasional, peran strategis dan kontribusi mereka justru kerap jauh di bawah negara-negara berpenduduk 5 juta tersebut. Di Timur Tengah, Syria dan Yaman berpenduduk 20 juta lebih, penduduk Saudi Arabia dan Irak lebih dari 30 juta. Tapi kekuatan mereka dibanding Israel yang hanya berpenduduk sekitar 8 juta seperti bukan apa-apa. Bukan cuma Israel bisa memenangi perang 1967 ketika dikeroyok negara-negara Arab sekitarnya, bahkan ia berhasil mencaplok wilayah negara-negara penyerangnya dan tak bisa diambil kembali sampai hari ini.
Kita hanya bisa menjadi bangsa besar jika punya imajinasi besar dan kesadaran kolektif besar, yang membuat kita mampu membangun relasi positif sebagai warga dari entitas besar dengan koordinasi yang efektif, tidak ambyar!