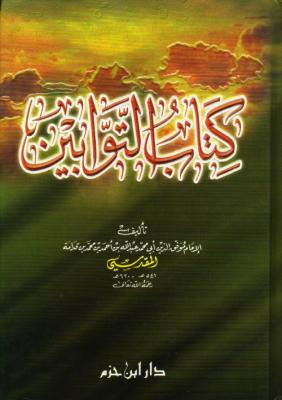Stop. Saudara jangan marah dulu. Jangan terburu-buru. Mari sejenak merenung dan memaknai kembali apa sejatinya yang dimaksud kafir. Di bukunya Hidup Itu Harus Pintar Ngegas dan Ngerem (2016) Cak Nun menuliskan makna kafir. “Asal-usul kafir itu dari petani. Disebut kafir karena pekerjaan petani menutupi tanah dengan tanaman. Lalu kafir diambil untuk istilah teologi. Kafir adalah orang yang menutupi kebenaran Allah.”
Jangan-jangan kita pun tidak sadar kalau selama ini menutupi kebenaran Allah. Sering kita tanpa sadar menghukumi orang yang tidak tahu tentang agama. Orang memeluk agama melalui proses masing-masing. Ada orang usia tiga puluh tahun belum bisa shalat diolok-olok “Kamu ini bagaimana, usia tiga puluh kok belum bisa shalat?” “Kafir kamu, masak orang Islam tidak pernah ke masjid, malah nongkrong terus di mal”.
Kalimat-kalimat seperti itu sejatinya masih sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Kita justru menutupi orang yang sedang berproses menuju Allah. Islam adalah rahmatan lil alamin. “Tugas” agama pada hakekatnya adalah seruan, ajakan. Artinya, tugas kita sebagai makhluk beragama hanya menyeru, mengajak. Kalaupun orang yang kita ajak atau seru belum mendapat hidayah, tugas kita mendoakan, bukan mengkafirkan.
Memang lebih baik mengakui diri kita sebagai seorang yang salah, yang masih menutupi kebenaran Allah, alias kafir. Untuk apa menutupi kebenaran Allah? Yah untuk siapa lagi kalau bukan untuk yang bukan dari Allah. Kesombongan, pamer, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dilihat, ingin orang tahu.
Padahal sejatinya Islam tidak seperti itu. Kita dilihat sebagai orang Islam justru dari perilaku kita sebagai manusia. Saat kita telah berlaku layaknya manusia yang layak sebagai khalifatul fil ardl, saat itu pula sebenarnya kita sudah mengamalkan Islam. Syahadat adalah gerbangnya.
Tapi selama kita belum bisa melakukan amal yang layak sebagai khalifatul fil ardl maka lebih baik kita bercermin terlebih dahulu ketimbang melihat orang lain terus-menerus, apalagi memberikan penilaian terhadap keislaman mereka.
Mestinya sebelum kita menjadi islam, kita belajar menjadi manusia dulu. Kalau sudah lulus menjadi manusia, baru akan indah islammu. Kalau kamu belajar islam tapi belum jadi manusia, repot jadinya. Demi Islam kamu boleh menyakiti orang. Demi Islam kamu boleh mencuri. Demi Islam kamu boleh memecah-belah warungnya orang? Demi Islam?
Padahal, demi kemanusiaan saja seharusnya kamu tidak akan tega melakukan itu. Jadi, kalau belum lulus menjadi manusia, susah untuk menjadi muslim. Itulah yang saya dapat dari Emha Ainun Najib.
Sejatinya memang kita belum sepenuhnya menjadi manusia yang pantas mendaku paling beriman. Mau menjadi manusia bagaimana, kalau adab kita terhadap alam saja masih belum sempurna. Suka buang sampah sembarangan, suka mengotori, bahkan merusak alam. Belum adab kita pada manusia, maupun kepada Tuhan.
Kepada sesama manusia saja kita masih mempertimbangkan banyak hal untuk menolong dan peduli, masih melihat kamu agamanya apa? Masih suka membeda-bedakan dan merasa dirinya paling suci.
Maka dari itulah, mending kita bersama ucapkan bahwa kita sejatinya masih menjadi orang kafir. Kita belum lolos dalam ujian keimanan. Sebab keimanan itu memang hak prerogatif Tuhan. Lebih baik dituduh kafir daripada sering dikatakan paling beriman. Sebab dengan dituduh kafir kita akan dan terus belajar untuk menilai ke dalam diri.
Melihat ke dalam diri kita, bahwa sejatinya kita belum sepenuhnya utuh iman kita. Kita masih menampakkan iman kita dalam terang, sementara dalam gelap dan sepi, kita justru tampak sebagai yang “kafir”. Kita sering nampak berbuat baik dan amal salih saat banyak orang tahu, tapi begitu sepi dan jarang beramal saat tidak ada yang melihat kecuali dzat-Nya.
Sajak yang ditulis oleh Sunan Panggung sekian abad yang lalu, layak untuk kita resapi bersama : Orang yang tak mengetuk pintu rahasia/ Hanyalah terbelenggu oleh tata krama/ Sembahyang sunnah dan fardu tak pernah tertinggal/ untuk menutupi kelalaiannya terhadap tetangganya yang lapar/ …sepedati penuh kertasnya/ Yang dibicarakan hanya masalah halal haram… Sajak Sunan Panggung tadi pernah ditulis di buku Emha berjudul Slilit Sang Kiai (1992).
Islam bukanlah stempel, identitas semata, tetapi meresap dalam tingkah laku. Umat Islam selama ini sering terjebak pada simbol. Orang bisa lebih NU, lebih Muhammadiyah, lebih LDII ketimbang lebih islami. Seringkali kita beribadah dengan mengedepankan eksistensi. Padahal sejatinya ibadah adalah mengabdi, melayani.
Tugas kita sejatinya adalah beribadah, menanam sebaik mungkin. Berusaha, beramal sebaik mungkin, dan percaya kepada Allah bahwa amalan kita diterima. Jangan berhenti untuk melakukan kebaikan, tanpa harus dilihat orang lain. Jangan berhenti mengamalkan kemanusiaan, mengamalkan Islam.
Saya jadi ingat kata-kata Goenawan Mohamad dalam bukunya Tuhan dan Hal-Hal Yang Tak Selesai (2019). Pengalaman religius, seperti nasib dalam gambaran sajak Chairil Anwar, adalah “kesunyian masing-masing”.
Ada baiknya kita merenungkan bagaimana kita beragama seperti puisi indah yang ditulis oleh Triyanto Triwikromo di buku puisinya Kitab Para Pencibir (2017):
“Rahasiakanlah cintamu pada-Ku. Jangan sampai angin mendengar meski sesiut apa pun. Rahasiakanlah cintamu pada-Ku. Jangan sampai senja melihat mesti sezarah apa pun. Rahasiakanlah cintamu pada-Ku. Jangan sampai langit meraba meski selembut apa pun. Jadi mengertilah, cintaku. Sembunyikanlah tangismu meski seluka apa pun. Diamlah. Aku membenci dunia yang gaduh.” (SI)