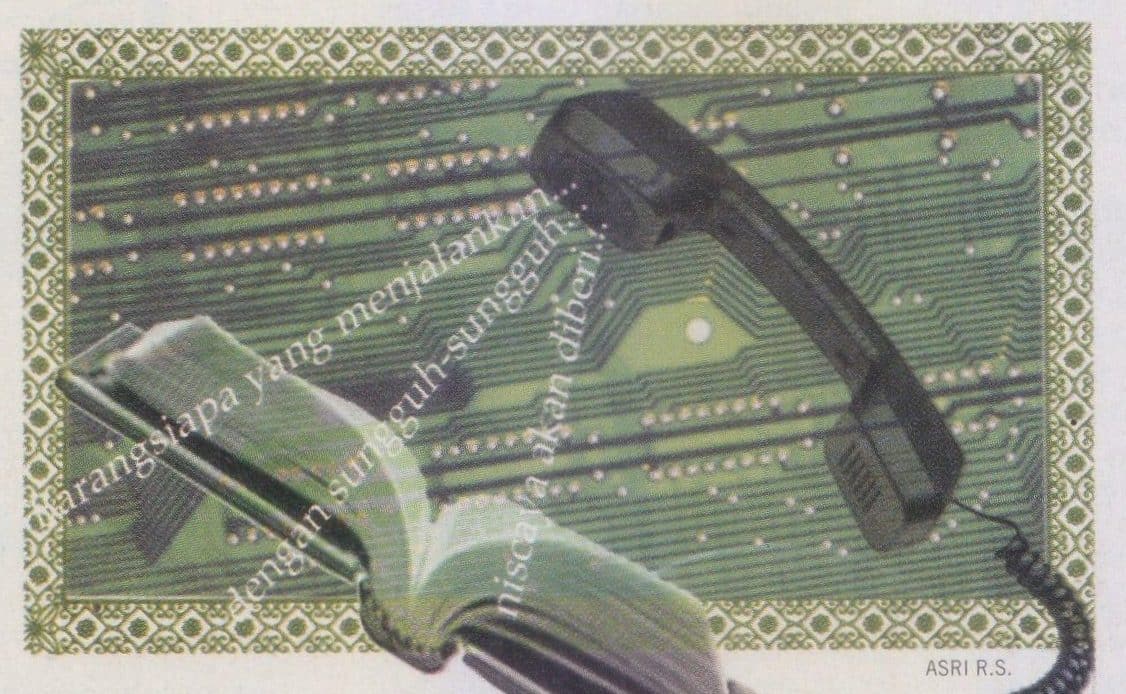
Pada saat berseragam biru-putih, penulis ikut lomba membaca kitab suci di Solo. Ia masuk daftar pemenang. Panitia memberi hadiah Al Quran dan terjemahan terbitan Departemen Agama. Di rumah, kitab suci itu kadang dibaca tapi penulis merasa kurang terpikat dengan terjemahan “resmi” menurut institusi bentukan pemerintah.
Pada tahun berbeda, penulis ingin menikmati terjemahan kitab suci. Sepeda onthel bergerak, dari rumah (Colomadu) menuju Stadion Sriwedari (Solo). Di belakang stadion, jajaran kios-kios menjual buku dan majalah bekas. Di situ, penulis membeli Al Quranul Karim: Bacaan Mulia. Ia sudah mengenal HB Jassin. Edisi puitisasi terjemahan kitab suci oleh kritikus sastra itu melegakan ketimbang edisi pemerintah.
Pengalaman itu memang tak memastikan peningkatan iman dan takwa. Ia membaca tanpa sanggup mengobrolkan panjang dengan ulama atau ahli agama. Keranjingan membaca buku sastra semakin memberi kemauan besar khatam puitisasi terjemahan kitab suci. Ingat, khatam membaca tulisan-tulisan berbahasa Indonesia dan beraksara Latin. Lega. Ia tetap belum “mengerti”.
Penulis tak belajar di pondok pesantren dan malas ikut pengajian-pengajian. Nah, pengetahuan tentang kitab suci tentu rendah. Ia terus saja membaca dan membaca sambil menikmati percakapan-percakapan pendek bila bertemu orang-orang dianggap paham agama. Pada suatu hari, ia semakin lega setelah mendapatkan Qur’an: Terjemahan dan Tafsirnya oleh Abdullah Yusuf Ali. Dua edisi bahasa Inggris sudah dimiliki, mendapat tambahan terjemahan bahasa Indonesia oleh Ali Audah. Oh, ia tetap saja diragukan terbukti meningkatkan iman dan takwa.
Di hadapan Tempo, 4 Agustus 2002, ia tercengang membaca berita kecil. Gambar itu aneh. Telepon dan kitab terbuka. Apa? Oh, tulisan berjudul “Dakwah Seluler”. Gambar telepon itu mengesankan peradaban seluler. “Banyak jalan menuju dakwah, termasuk melalui Al Quran seluler alias dakwah melalui telepon,” tulis di Tempo. Penulis teringat masa-masa orang girang dengan telepon di rumah, telepon di wartel, dan telepon genggam. Benda itu “melipat jarak” dan mengubah persepsi waktu. Pada telepon, orang-orang ingin meningkatkan iman dan dakwah. Telepon itu alat-cara. Keanehan pernah dialami oleh orang-orang Islam di Indonesia, sebelum terlalu cepat dianggap kuno setelah bermunculan perangkat teknologi baru dan tata cara mutakhir.
Simak saja: “Caranya? Cukup membayar bulanan dan pulsa, lalu hubungi nomor 021-788831001. Dari ujung sana akan terdengar pembacaan ayat suci Al-Quran, disusul ceramah singkat dari dai terkenal macam Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) atau Ihsan Tanjung.” Wah, masa lalu itu wagu: dakwah dan telepon. Penulis belum pernah mengalami memegang telepon bermaksud belajar agama. Penulis saat remaja sering takut dengan telepon. Secuil pun tak ada keinginan menggunakan itu bermisi agama. Pada masa berbeda, ia malah membaca buku berjudul Telepon Genggam, berisi puisi-puisi gubahan Joko Pinurbo. Ia tetap saja sulit memahami masalah telepon.
Pada 2020, penulis perlahan paham peradaban telepon setelah membaca dua jilid Lagak Jakarta, 1997-2007 (Benny dan Mice). Penulis tertawa dan malu menikmati gambar dan kata mendokumentasi telepon di Indonesia masa lalu. Telepon digandrungi jutaan orang untuk pelbagai misi: bisnis, politik, hiburan, agama, dan lain-lain. Industri dan teknologi telepon turut membentuk lakon hidup di Indonesia, termasuk orang ingin belajar agama. Pada masa lalu, telepon telah digunakan dalam urusan agama. Kita membaca lagi nostalgia dakwah seluler: “Kini, sambil mengantre di bank atau menunggu busa datang, silakan beribadah melalui telepon.” Masa lalu itu wagu. Begitu.















