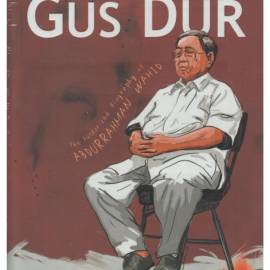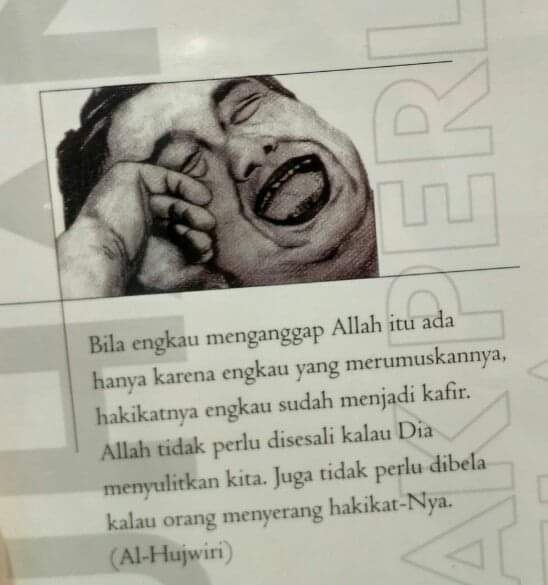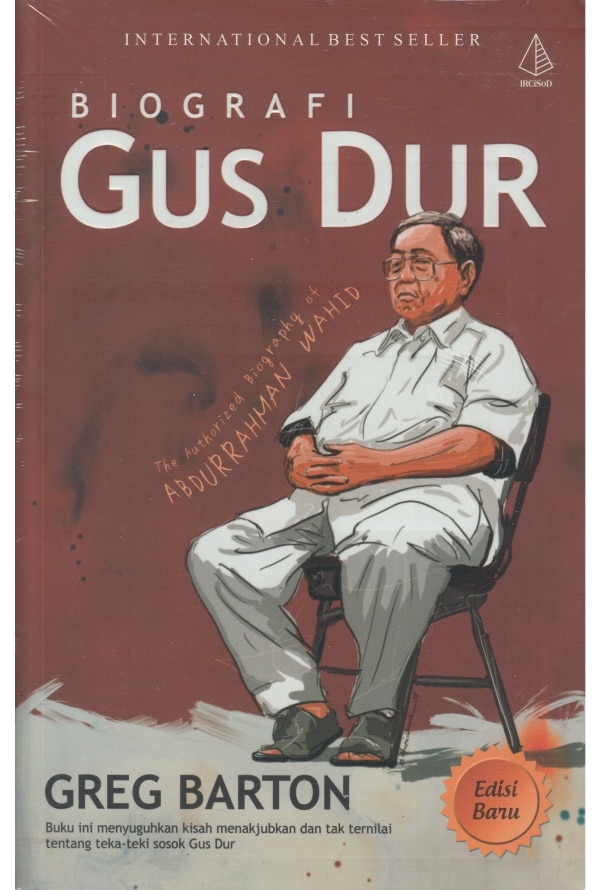
Gus Dur lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil diambil dari pahlawan dari dinasti Umayah yang berarti “Sang Penakluk”. Ayahnya adalah orang besar sekaligus pahlawan yang turut serta melawan penjajah di masanya.
Ayahnya pernah menduduki jabatan sebagai menteri agama di tahun 1949. Kakeknya adalah Kiai Hasyim Asyari adalah seorang pendiri NU pada tahun 1926. Konon kakeknya juga merupakan keturunan dari raja Jawa yakni Raja Brawijaya VI. Ia adalah pendiri pesantren Tebuireng. Dari garis keturunan yang baik ini pulalah, Gus Dur dididik oleh kedua orang tuanya agar kelak menjadi pewaris yang akan meneruskan cita-cita kakek dan ayahnya.
Gus Dur adalah sosok yang kontroversial. Dari Gus Dur itulah, kita tahu dan belajar menjadi manusia yang tidak selalu disukai, tetapi juga tidak terus-menerus dibenci. Greg Barton menuturkan kisah Gus Dur yang komprehensif pada buku Biografi Gus Dur (2020). Greg Barton telah menyajikan kisah Gus Dur sebagai manusia biasa dengan kelebihan dan kekurangannya, sekaligus menghadirkan sosoknya yang kontroversial.
Masa kecil Gus Dur boleh dibilang adalah masa kecil yang cukup pahit. Ia harus menerima satu pukulan telak dalam fase kehidupannya, yang akan menuntunnya menjadi orang besar. Fase itu ia alami ketika ia berusia 12 tahun dan harus kehilangan ayahnya.
Greg Barton menulis : “Di usia dua belas tahun, Gus Dur sudah ditinggal oleh ayahnya. Gus Dur mengamati betapa ayahnya yang meninggal dikelilingi oleh kerumunan orang dari sepanjang perjalanannya dari Jakarta ke Jombang. Gus Dur memahami, ayahnya sangat dicintai oleh banyak orang. Lalu ia berpikir : “ Apa yang mungkin dapat dilakukan oleh seorang manusia sehingga rakyat sangat mencintainya? Apakah ada prestasi yang lebih baik daripada hal ini dalam hidup?” (h. 46).
Peristiwa kematian ayahnya begitu membekas dan secara tidak langsung menempa jiwanya sekaligus membentuk dirinya untuk mengilhami apa yang dilakukan ayahnya yang menuntunnya menjadi orang besar yang memberi dan berbuat terus untuk kepentingan kemanusiaan.
Gus Dur kecil ditinggal ayahnya di usia remaja, tetapi didikan ayahnya di masa kecil cukup membekas dalam jiwanya. Pada saat usianya empat tahun, ia dibawa ke Jakarta oleh ayahnya yang memungkinkannya bertemu dengan tamu-tamu besar ayahnya.
Pada saat itu, ia sering bertemu dengan Mohammad Hatta maupun Tan Malaka. Perjumpaannya dengan Tan Malaka ini tidak saja mengantarkannya menjadi pembaca buku yang rakus di usia belia, namun membawanya menjadi seorang yang cukup mudah memahami teori marxis bahkan semenjak usia remaja.
Kegoncangan jiwanya akibat meninggalnya sang ayah tidak membuat Gus Dur putus membaca, meski nilai kognitifnya dibilang turun. Kegigihan dan kesabaran ibunya Solichah inilah yang kelak membekas mendalam di hati Gus Dur yang turut membentuk jiwanya meski tidak seperti bapaknya.
Perhatian dan kasih sayang Solichah hadir dalam keterbukaannya, keleluasaannya, dan kebebasan yang diberikan kepada Gus Dur mengantarkannya menjadi pribadi yang merdeka dan berkembang pemikirannya. Peranan ibunya yang memberikan kebebasan untuk membaca pustaka peninggalan bapaknya akhirnya membentuk Gus Dur sebagai manusia buku.
Sedari kecil Gus Dur memang dibebaskan untuk menjelajahi pustaka ayahnya. Proses ini membentuk Gus Dur menjadi seorang penggila buku sejak kecil hingga pada saat dewasa kelak. Bahkan sampai saat ia menjadi presiden, ia tidak meninggalkan buku.
Jejak berbuku ia tempuh bahkan sedari usia empat tahun, hingga di usia remaja tepatnya 12 tahun ia telah menjadi seorang yang paham akan marxisme leninisme. Kecintaannya pada buku berlanjut hingga saat ia menempuh studi di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, ia membenamkan diri ke dalam lautan buku di perpustakaan Kairo.
Kecintaannya kepada buku sempat ditulis oleh Gus Mus [K.H.Ahmad Mustofa Bisri] di buku Gus Dur garis miring PKB (2008). “ Salah satu hal yang menarik dari Mas Dur, waktu itu ke mana pun dia pergi, di tangannya selalu ada buku bacaan. Seringnya buku novel bahasa Inggris, atau paling tidak majalah (ia selalu baca Times atau Newsweek, dan The Economics). Dan ia membaca buku tanpa memandang tempat dan waktu. Di ruang tunggu bioskop, di terminal, bahkan ketika berdiri di atas bus, ia bisa asyik membaca tanpa menghiraukan kanan-kiri. Bahkan Saya—yang berjalan bersamanya—sering dianggap tidak ada ketika dia sedang asyik membaca. Seringkali Saya harus menunggu seperti orang bloon sampai ia berhenti membacanya.” Begitu asyik masyuknya Gus Dur tenggelam lautan kata-kata pada buku yang ia bawa dan baca.
Kontroversial Namun Konsisten
Gus Dur adalah orang yang kontroversial, tetapi sekaligus konsisten. Ia tidak hanya membuat orang bisa dengan mudah membencinya, karena kata-katanya yang ceplas-ceplos dan tidak lazim dari yang umum. Namun ia juga bisa dengan mudah mendapatkan simpatik, perhatian, dan cinta dari orang-orang yang mengaguminya.
Greg Barton melukiskan ini dengan kalimat yang sungguh tepat : Walaupun Gus Dur mempunyai kelemahan-kelemahan kecil yang bisa membuat orang jengkel, namun ia bisa menimbulkan kesetiaan dan rasa sayang dalam diri mereka yang berada di sekelilingnya (h.347).
Di balik sikapnya yang kontroversial itu, ia memiliki sikap yang konsisten dalam membela orang yang lemah, minoritas dan terpinggirkan. Kepemimpinannya di Nahdlatul Ulama telah memberikan perubahan yang cukup signifikan. Orang yang dulu menganggap Nahdlatul Ulama sebagai organisasi jago kandang, kini mulai berubah.
Kini, orang NU tidak lagi dipandang sebagai ndeso, sarungan, dan pintar kitab kuning semata. Di buku Djohan Effendi yang berjudul Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi (2010) terekam pada masa kepemimpinan Gus Dur di NU telah membawa kemajuan berpikir di kalangan anak muda NU.
Gus Dur telah mendobrak kemapanan masyarakat secara umum. Guyonannya dalam politik maupun dalam keseharian membuat suasana menjadi cair dan tidak tegang. Ia telah keluar dari mainstream dan memberikan jalan tengah bagi setiap persoalan bangsa. Impresi ini bukan sesuatu yang baru, banyak orang juga menilai demikian, tapi tidak ada salahnya saya tekankan lagi.
Langkahnya yang selalu hadir dan intim terhadap persoalan kebangsaan telah membuka mata kita semua bahwa kepedulian layak dibangun oleh siapa saja. Kepeduliannya kepada yang minoritas dan terpinggirkan menyadarkan kita akan pentingnya pengamalan agama tidak hanya dalam kata, namun juga perbuatan.
Bagi saya, Gus Dur tidak hanya kiai yang “kiri”, tetapi juga kiai yang mengilhami Islam dan mengamalkannya dalam laku keseharian. Kekurangan pada tubuhnya yang diakibatkan karena kecelakaan di mata kirinya membuatnya terus bertahan dan berjuang hingga akhir hayatnya. Gus Dur meski buta, ia adalah seorang yang tidak pernah menutup mata batinnya ketika melihat yang mengusik nuraninya.
Kepemimpinan dan sikapnya yang penuh hati-hati dan anti kekerasan membuat ia harus rela memendam dalam-dalam ego pribadinya demi kepentingan bangsanya. Seperti saat ia memimpin bangsa ini meski dalam waktu singkat, dan penuh jalan terjal, Gus Dur tetap konsisten dalam sikapnya yang membela kemanusiaan. Gus Dur telah membawa perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Gus Dur telah memberikan pelajaran berharga tentang cinta dan kasih sayang. Tentang sikap hidup yang anti kekerasan dan mengusung nilai-nilai perdamaian dan membela kemanusiaan. Greg Barton telah menuliskan kisah Gus Dur yang rasional, sekaligus emosional, yang menyuguhkan mata air keteladanan bagi kita semua. (SI)