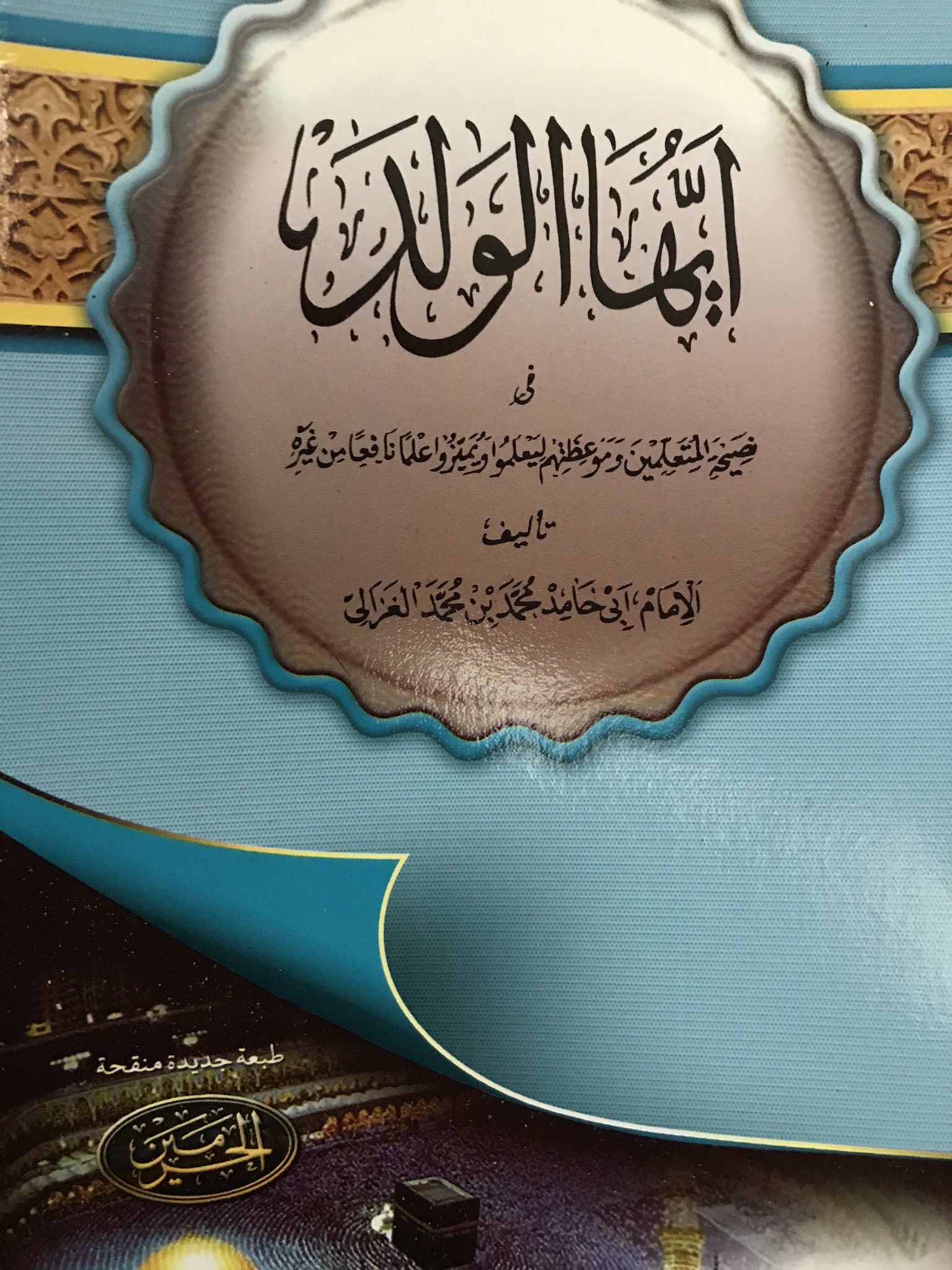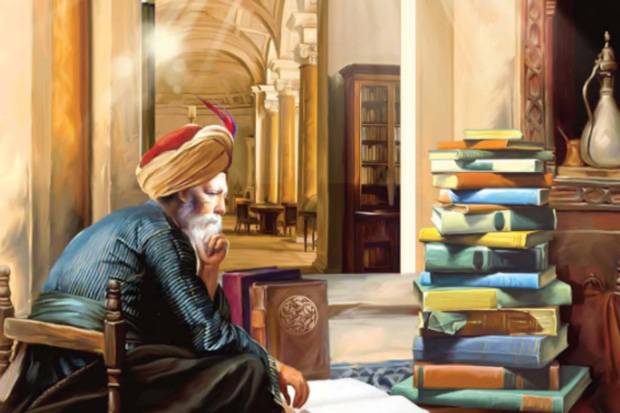Kisah pertobatan bisa sangat mengesankan. Kita diajak melihat bagaimana seorang sufi di masa awal bertobat. Permulaan dari perjalanan panjangnya menuju ilahi dimulai. Keindahan duniawi menjauh perlahan. Kesenangan menjadi pangeran harus ditinggalkan. Inilah kisah Ibrahim bin Adham (w. 160 H/777 M).
“Ayahku berasal dari Balkh,” Ibrahim bin Adham dikabarkan pernah berkata, “dan dia adalah salah seorang penguasa di Khurasan. Dia seorang yang amat kaya dan mengajariku suka berburu.
Suatu hari aku keluar untuk berburu bersama anjingku. Saat itu muncul seekor terwelu atau rubah muncul. Aku memacu kudaku; kemudian aku mendengar suara di belakangku berkata, ‘Bukan untuk hal ini engkau diciptakan; Bukan hal ini engkau wajib lakukan. Aku berhenti, melihat ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada seorang. Dan aku berkata, ‘Tuhan lindungi aku dari setan terkutuk’.
Kemudian aku memacu kudaku lagi, lalu aku mendengar suara yang lebih jelas dari sebelumnya. ‘Wahai Ibrahim bukan untuk hal ini engkau diciptakan; Bukan hal ini engkau wajib lakukan’. Aku berhenti sekali lagi, dan melihat kanan dan kiri, tapi masih saja aku tidak melihat seorang. Aku berkata lagi, ‘Tuhanku lindungilah aku dari setan yang terkutuk’.
Aku memacu kudaku sekali lagi, saat aku mendengar suara dari bagian bawah pelana kuda, ‘Wahai Ibrahim bukan untuk hal ini engkau diciptakan; Bukan hal ini engkau wajib lakukan’. Aku berhenti dan berkata, ‘Aku sadar sekarang! Aku sadar sekarang! Peringatan dari Tuhan telah datang kepadaku. Aku tidak akan ingkar atas perintah-Nya sejak hari ini…” (Arthur J. Arberry, Sufism, 1950)
Kisah memberikan sebuah kesan “kengerian” sekaligus “keindahan”. Suara kesadaran Sang Aku menghentak keluar. Kehidupan penuh kenyamanan harus ditinggalkan. Keterasingan dari masyarakat, yang merupakan tanda bagi kaum elit masa itu, harus dihapus. Ibrahim bin Adham harus merasakan kehidupan rakyat biasa.
Namun, sebuah jalan terjal dan menjulang membawa kita pada sebuah pemandangan gunung nan agung. Ibrahim bin Adham menjadi santri lelana. Perjalanan dari desa ke desa membawakan kearifan. Dunia ini lebih luas dari sekedar istananya. Komunikasi tulus muncul dari seorang hamba dengan hamba, bukan dari para penjilat di istana.
Bahkan, perjalanan panjang mengenalkan Ibrahim memahami satu pesan universal. Manusia adalah makhluk Tuhan yang ditugaskan mengenal-Nya. Dari seorang biarawan Kristen ilmu tentang mengenal Tuhan ia dapatkan. Ibrahim bin Adham bercerita:
“Aku belajar makrifat dari seorang biarawan bernama Romo Simeon. Aku mengunjunginya di pondoknya, lalu berkata padanya, ‘Romo Simeon, berapa lama engkau sudah berada di pondok ini?’ ‘Sudah tujuh puluh tahun’ jawab Romo Simeon.
‘Apa makananmu?’ tanyaku. ‘Wahai Hanafi (seorang yang lurus beragama)’, dia berkata, ‘apa yang menyebabkanmu menanyakan hal ini?’. ‘Aku hanya ingin tahu’ jawabku. Kemudian dia berkata, ‘Setiap malam, sebuah labu siam (chickpea)’.
Aku berkata, ‘apa yang tersirat di hatimu sehingga satu buah ini cukup untukmu’. Dia menjawab, ‘Mereka mengunjungiku pada satu hari tiap tahun, menghiasi pondokku, dan melakukannya untuk menghormatiku.
Kapan saja diriku merasa lelah akan peribadatan, aku mengingatkan diriku akan momen satu jam itu, dan memikul beban selama setahun semata-mata untuk satu jam itu. apakah engkau, wahai Hanafi, akan memikul beban (ibadah) selama satu jam untuk keagungan yang abadi?’ Setelah itu makrifat menurun pada hatiku.”
Kisah mengajarkan sebuah kearifan. Ilmu dan kebijaksanaan berasal dari agama mana pun tetaplah ilmu dan kebijaksanaan. Belajar dari tradisi lain, bukanlah sebuah aib. Tradisi ini berasal dari Rasul saw. atas petunjuk Tuhannya.
Ibadah haji ke Baitullah menjadi teladan. Napak tilas perjalanan Ibrahim adalah awal mulanya. Ibadah dilakukan oleh umat Yahudi, umat Kristiani, kaum pagan Quraish yang mengaku keturunan Ibrahim. Seandainya kaum pagan tidak melingkupi Rumah Tuhan dengan 360 berhala, maka umat Yahudi dan umat Kristiani akan tetap berhaji ke sana.
Puasa Asyura juga menjadi contoh. Sebelum puasa Ramadan ditetapkan, Nabi saw. selalu menjalankannya. Namun kaum Yahudi pun melakukannya. Kata mereka, ‘Ini adalah hari nan mulia. Allah menyelamatkan umat Yahudi dari musuhnya, Fir’aun, pada hari ini. Maka Musa berpuasa pada hari itu.’ Bahkan kaum Quraish di masa Jahiliyyah pun berpuasa pada hari itu, sesuai dengan niat mereka.
Sufisme memang mengajarkan bahwa inti adalah tujuan. Kulit tetaplah kulit. Ia diperlukan untuk membungkus suatu ini. Ketika datang waktu bersantap, maka inti adalah primadona. Kulit selesai dengan tugasnya.
Kisah Ibrahim bin Adham mengajarkan satu hal. Mengenal Tuhan adalah inti kehidupan. Bungkus mengambil rupa praktik seorang Rohaniwan Kristen, atau puasa Quraish pagan, atau haji ke Baitullah kaum Yahudi. Hanya ketika seorang sudah mengupas kulit, ia bisa menikmati keindahan inti. Wallahu a’lam.