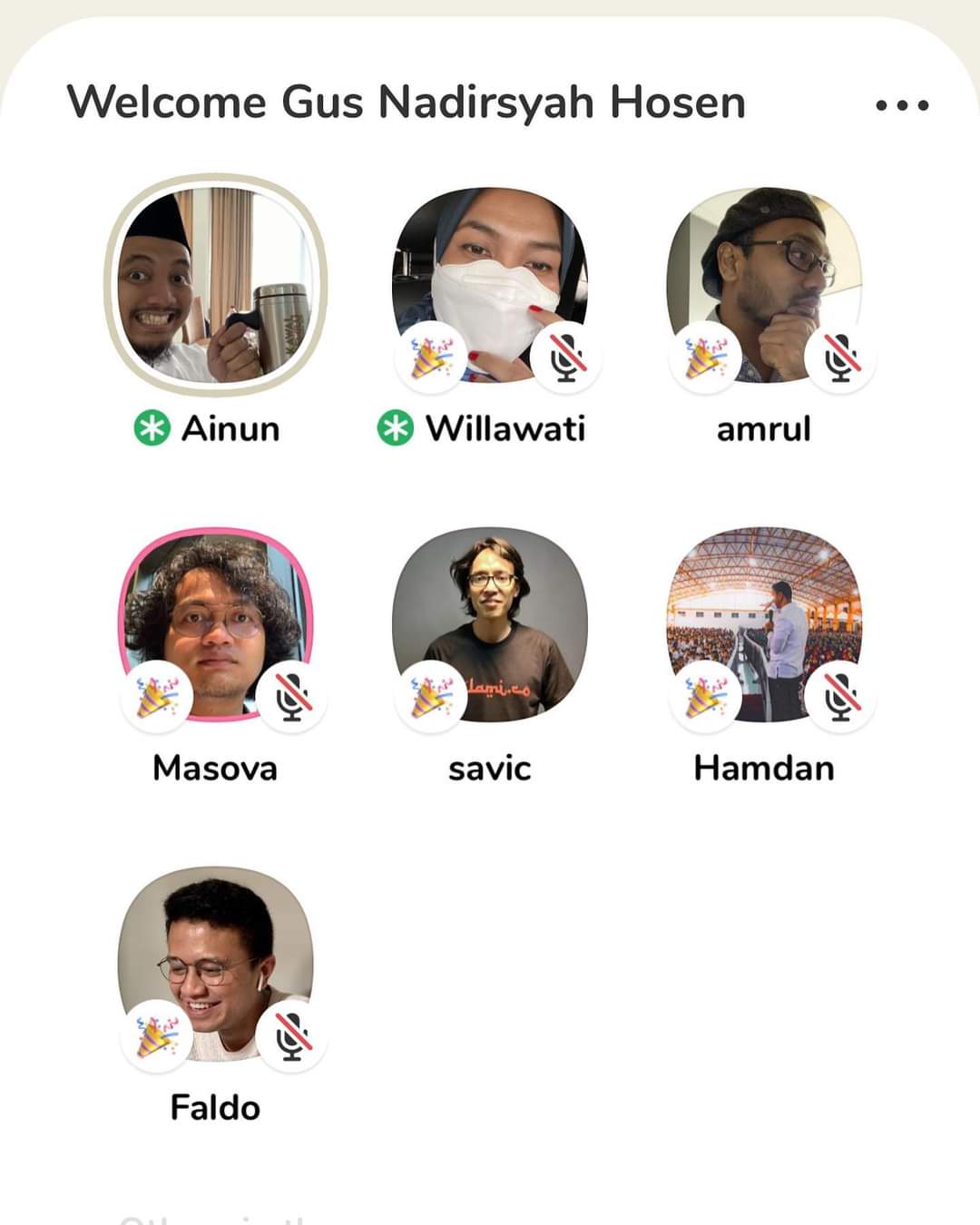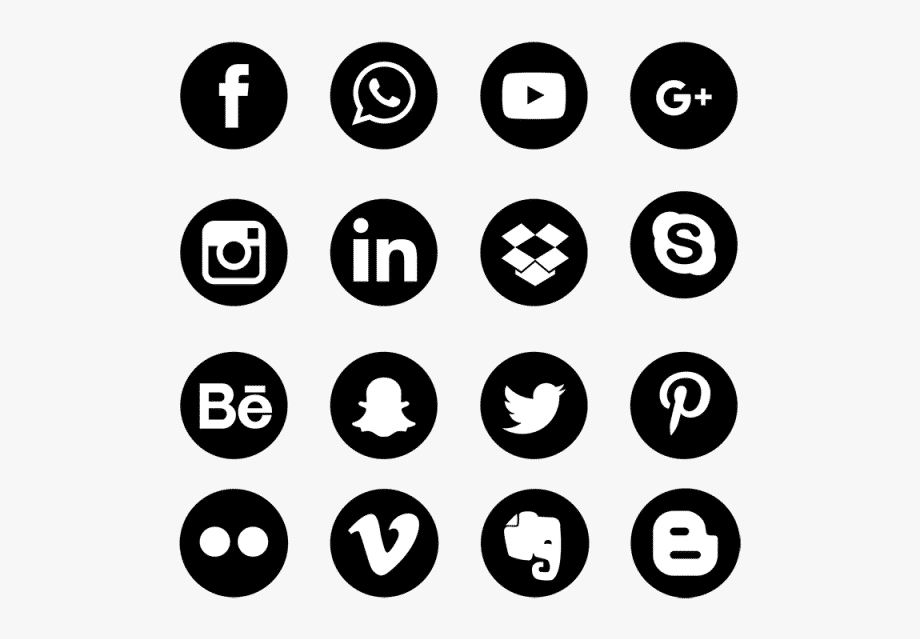“Mau tahu sesuatu yang lucu?” tawar Dufresne di sela-sela lemari buku kepada karibnya. “Apa? Katakan padaku,” sergah tertarik. Dufresne menyungging senyum penuh arti, wajahnya melandai dekat. Sambil memelankan suaranya di sela rak, Dufresne mulai berbisik menyasar daun telinga teman serutannya itu, kata dia: “Di luar aku adalah pria yang jujur. Masuk penjara aku malah mulai (belajar) jadi penjahat.”
Bagi yang sudah pernah nonton film lawas: The Shawshank Redemption (1994) besutan Frank Darabont, pasti sudah tidak asing lagi dengan dialog menarik Tim Robbins dan Morgan Freeman di atas. Stephen King pemilik asli kisahnya, memang jagonya soal ramu-meramu alur cerita yang bikin bulu kuduk merinding. Tapi untuk karyanya yang satu ini, sepertinya bukan itu tujuannya. The Shawshank Redemption malah kentara muatan kritik sosialnya.
Selain tertuju pada kaum elit yang semena-mena, karyanya itu juga boleh jadi adalah sindiran yang coba menggelitik mereka –manusia modern– yang bermuka dua di kesehariannya. Umpamanya dewasa ini dalam kasus bermedia. Hari ini banyak orang-orang seperti Dufresne yang baik-baik saja di dunia, nyata sebelum punya media sosial. Setelah punya, bukan malah memanfaatkannya untuk kebaikan, mereka malah belajar banyak hal untuk melakukan hal-hal tak lazim. Semuanya dilakukan dengan gawai pintarnya, sama seperti kita.
Genealogi Media Sosial
Menurut Nezar Patria, aktivis dan wartawan senior, akar pikiran lahirnya media sosial yang jadi wajah kemajuan teknologi, sebenarnya bisa ditelusuri sejak awal abad Masehi, zaman pencerahan juga revolusi industri. Obsesi yang tengah menjamur di Eropa saat itu adalah semacam kegandrungan “mengukur segala obyek setepat mungkin: semacam obsesi akan presisi”.
Rakyat Eropa saat itu, sedang giat-giatnya menilik segala detil fisik: ukuran, bentuk, isi dari realitas material.
Kegandrungan itu Galileo ekspresikan lewat seuntai adagiumnya yang terkenal: “Ukurlah yang dapat diukur, dan buatlah agar dapat diukur sesuatu yang tidak dapat diukur.” Dari mulai mengukur bumi, sampai menelisik obyek paling rumit di alam semesta, yaitu manusia sendiri, hasrat berpresisi ini terus menggeliat, hingga manusia di awal abad 21 ketiban berkahnya manakala Google, tanpa sadar, telah menjadi referensi utama dilanjut dengan kelahiran pelbagai media sosial.
Jadi, rahim yang melahirkan media sosial, sebenarnya, adalah semangat untuk berpikir rasional. Apalah kata Galileo, jikalau ia berkesempatan membaca kelakuan cicitnya zaman sekarang yang dibutakan oleh bias informasi di media sosial. Mereka dininabobokan oleh algoritma para programmer yang menggiring mereka untuk mengonsumsi informasi yang mereka minati saja. Yang mereka baca dan mereka tonton, yang muncul di beranda, dan kanal kesukaan mereka saja.
Di Amerika, yang konservatif tontonannya: Fox News. Yang liberal: CNN dan MSNBC. Sisanya blokir, atau kalau perlu taruh nomor channel-nya di yang ke- 100 sekian.
Di pusaran post-truth, masyarakat membatasi konsumsi informasinya hanya pada kecendrungan diri, bukan lagi pada kegandrungan mencari kebenaran. Cita- cita masa pencerahan (enlightenment)‒ untuk melahirkan manusia dengan akal yang cerah‒ terkubur bersama kekecewaan Galileo membaca nasib cucu- cucunya.
Selokan Dosa Bernama Sosial Media
Karena terbiasa buram melihat kebenaran, akhirnya manusia modern benar-benar luput makna akan kebenaran. Kebingungan itulah yang membuat mereka percaya diri melakukan hal-hal tidak benar. Dari mulai ngikut-ngikut orang ke mana pun pergi (follow), sampai nerobos rumah orang untuk lihat-lihat foto-foto atau ocehannyanya (stalking). Semua ketidaklaziman di dunia nyata itu, bisa Dufresne lakukan dengan mudahnya di (penjara) media sosial, cukup dengan menggesek layar di gawai pintarnya.
Masih karya pena Stephen King. Jikalau masih ada perumpamaan yang pas bagi para empunya media sosial yang kehilangan kebijaksanaan, Pennywise di ceritanya: IT, boleh jadi adalah salah satu yang paling tepat menyarunya. Di kota Derry, Pennywise menghibur anak-anak dengan kelap-kelip balon dan dan warna-warni pakaiannya. Di dalam selokan, lain lagi cerita. Pennywise menculik Georgie dan anak-anak kota untuk dapat diapungkan jadi hiasan tempat tinggalnya.
Mereka yang nir-kebijaksanaan bermedia sosial, bermain muka di dunia nyata, mengelabui orang, menghibur, membangun citra diri baik-baik, menyirat rapat-rapat aib yang bermuara dalam diri. Namun, diam-diam, tanpa seorang pun (perlu) tahu, di ‘selokan’ media sosial, barulah mereka mengairi hasrat-hasrat kelam yang meluap dalam diri, dalam sebentuk aksi-aksi tidak wajar, yang menerobos norma-norma kehidupan manusia di dunia nyata.
Apalah artinya dusta, bagi mereka yang tidak lagi mengindahkan norma. Di media sosial, alih-alih menampilkan kedirian yang sebenarnya, mereka malah menampilkan kedirian yang seirama dengan selera pasar. Pasar suka pujangga, mereka siap mengukir kata-kata cinta di dinding (penjara) media sosial. Sehari sekali. Atau dua dan tiga juga tak mengapa. Bahkan lima kali sehari pun seperti salat wajib mereka sanggupi; demi mendapat predikat pujangga di mata masyarakat (apalagi calon mertua).
Bukan Penjara Shawshank, bukan pula Selokan Pennywise
Sayang seribu sayang, fungsi media sosial sebagai penyambung lidah ekspresi kedirian dengan jujur, malah latah disalahgunakan. Dufresne dan karib-karibnya mencemari media sosial dengan dustanya. Mereka lebih memilih menjadi hamba pasar yang menjajakkan dirinya sesuai pesanan khalayak awam, menghianati jadi diri sendiri.
Karenanya, media sosial tak ubahnya seperti penjara Shawshank atau selokan Pennywise apabila tuannya tak mampu bijaksana menghuninya. Yang kasat mata memang terlihat berbatas, namun sejatinya yang tidak berbatas amat sangat luas di sana. Dengan segala bentuk kebijakan privasi yang seperti kawat berduri di tembok penjara, sosial media tidak juga menjamin jemari- jemari penggunanya bisa bijaksana dalam memilah informasi, mengindahkan norma, jujur dalam menampilkan kedirian.
Jangan sampai media sosial jadi seperti penjara Shawshank bagi Dufresne yang kebalik-balik. Bukan malah membantunya jadi pribadi yang baik, penjara malah mempertemukannya dengan komplotan kriminal yang mengajarkannya hal-hal yang tidak baik. Media Sosial mengandung embrio cita-cita mereka para pencerah untuk melahirkan manusia yang berjalan dengan akal budi, bukan malah diakal-akali oleh oara pialang saham industri aplikasi untuk dikuras isi dompetnya.
Tom Nichols penulis The Death Of Expertise menganologikan internet dengan Hukum Sturgeon yang mengatakan: “90 persen dari semua hal (di dunia maya), adalah sampah.” Perumpamaannya pas berarti. Media sosial adalah selokan bagi para pemulung mengais sampah informasi. Sekaligus wadah bagi mereka untuk memuntahkah sepah ekspresi diri. Sosial media menjanjikan milyar bunga tumbuh bersamaan dalam satu taman, namun sebagian besarnya berbau busuk.
Meskipun busuk, sampah-sampah itu bisa bernilai kebaikan jika dikelola oleh para arif bijaksana. Sebaliknya di tangan Pennywise sampah yang membusuk mencemari kepribadiannya yang kalem di dunia nyata, menjadi kelam di ‘selokan’ dunia mayanya. “Al- hikmatu dhōlatul mu’min,” sabda Rosūlullāh ﷺ.
Hikmah itu adalah barang hilang milik orang beriman. Mukmin yang berbudi pekerti luhur bisa mememungut hikmah yang dicari-carinya di mana saja, hatta di selokan sekalipun.