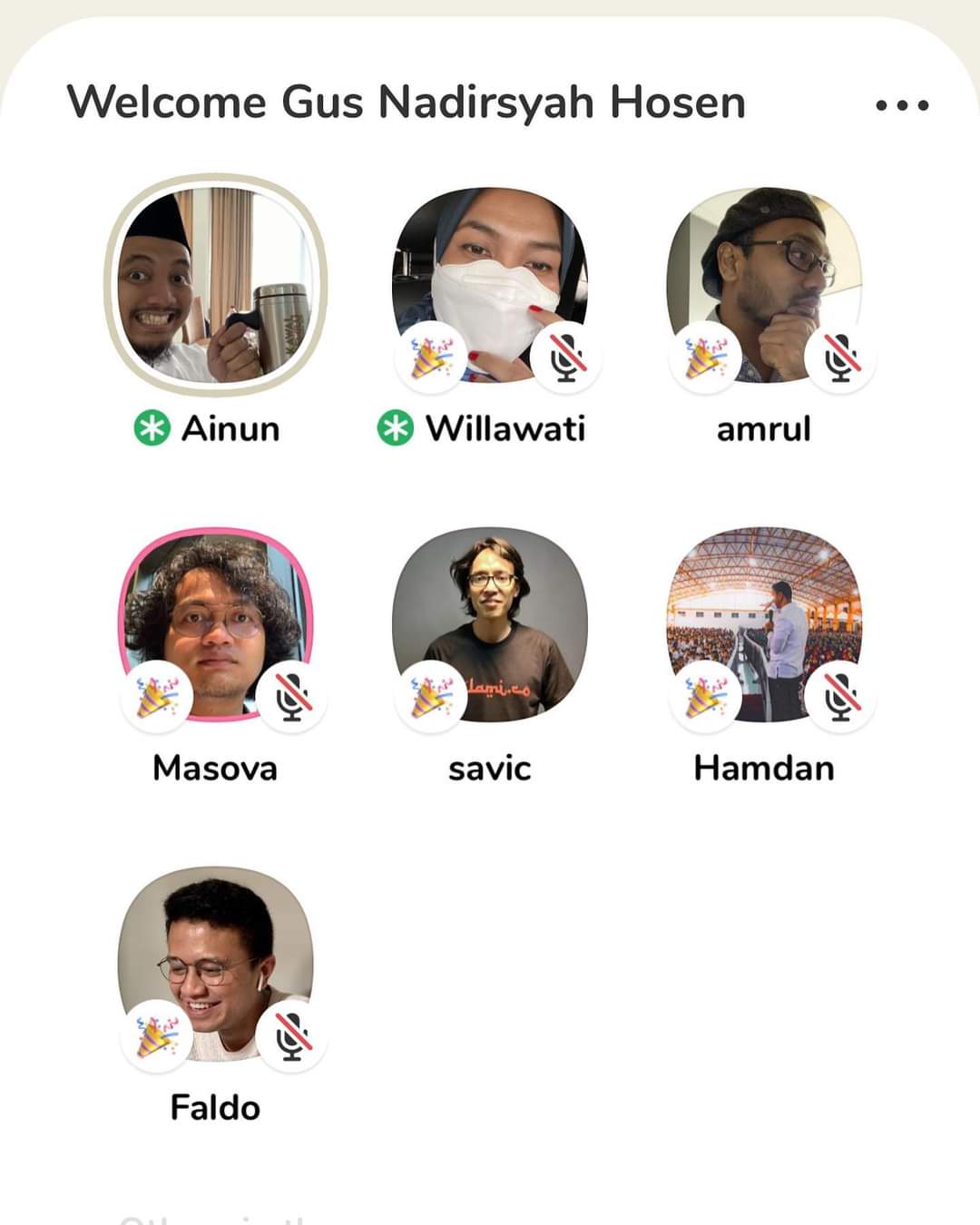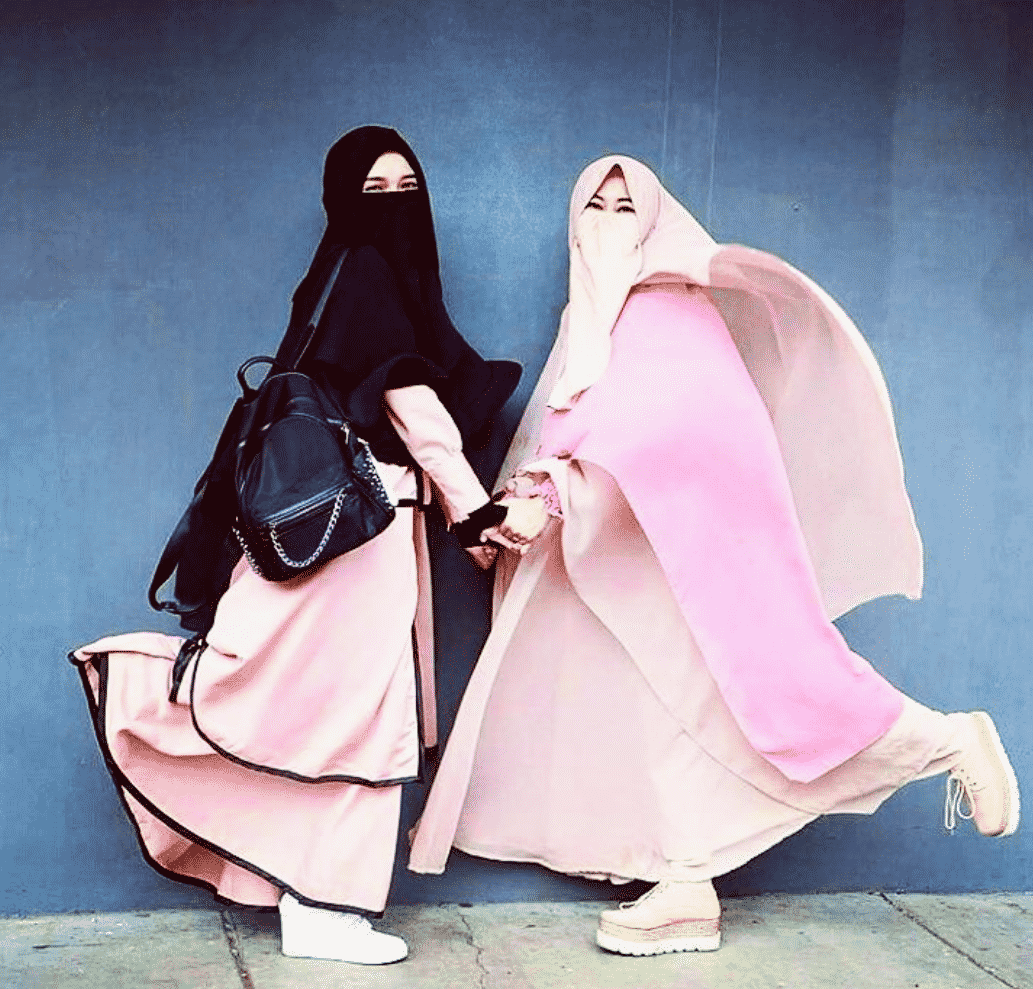
Hari itu, Fernandez kembali menampakkan batang hidungnya setelah menghilang beberapa hari. Rupanya kemarin ia sakit sehingga tidak bisa masuk kuliah. Saya langsung menghampirinya dan berkata “Alhamdulillah, kamu sudah sehat sekarang.” Dia membalas saya dengan berkata “Iya, Puji Tuhan, Yaya. Semoga nggak sakit-sakit lagi.”
Tak perlu kiranya saya jelaskan latar belakang agama Fernandez, karena semua sudah teridentifikasi lewat bahasanya kan? Oleh karena itu, ada rasa damai usai mendengar kata alhamdulillah dan puji Tuhan berpadu di udara. Seindah pemandangan cara berdoa yang berbeda saat kami makan bersama. Saya dan kawan muslim yang lain menadahkan tangan sementara dia mengatupkan kedua tangannya sambil memejamkan mata.
Fernandez menguraikan banyak hal tentang kesehariannya. Dia adalah penyanyi gereja. Sungguh, suaranya merdu sekali. Baginya, hal tersebut menjadi sarana untuk melayani Alah (kira-kira begitulah caranya melafalkan). Dia juga sering bertanya tentang Islam kepada kami. Sehari sebelum bulan Ramadan, dia mengirimi saya pesan yang isinya ucapan selamat berpuasa.
Di hari lebaran, dia juga tak lupa mengucapkan selamat. Saat dia berpuasa 40 hari sebelum paskah, saya berusaha untuk tidak makan di hadapannya. Saya dan kawan yang lain juga pernah menemani dia dan saudaranya berbuka puasa. Sungguh, indah sekali pertemanan antar agama ini.
Selain dengannya, saya juga menjalin pertemanan dengan Rosa. Dia gadis yang baik dan sangat ramah. Dia sangat menghormati kawan-kawan muslim di sekelilingnya. Suatu ketika, saat kami menginap di kota lain untuk seminar, Rosa mampir ke kamar saya. Kebetulan waktu itu saya hendak salat Magrib. Sembari Rosa berbicara dengan kawan saya yang lain, saya melaksanakan salat.
Di tengah salat, teman kamar Rosa memanggil untuk mengajak pergi.
Sebenarya, Rosa bisa saja langsung melewati saya untuk keluar dari kamar. Tetapi, ia malah dengan sabar menunggu saya menyelesaikan salat, berwirid dan berdoa, hingga melipat sajadah dan mukena. Sebelum meninggalkan kamar, dia bertanya apakah materi saya sudah siap untuk dipresentasikan besok, dan saya mengiyakan. Dia menjawab “Alhamdulillah kalau begitu, Yay. Aku keluar dulu ya. Kalau mau nitip sesuatu kabarin aja” Saya tersentak dan membisu beberapa saat.
Dia mengucapkan alhamdulillah? Bagaimana bisa? Dia kan Nasrani?
Menarik tampaknya melihat bagaimana Fernandez dan Rosa mengekspresikan rasa syukur. Fernandez tetap menggunakan leksikon yang ada dalam agamanya, sementara Rosa tidak demikian. Rosa bukanlah satu-satunya kawan nasrani yang mengucapkan alhamdulillah, Ya Allah dan astagfirullah. Ada sejumlah kawan nasrani lain yang melafalkan hal serupa ketika berinteraksi. Jadi, mari berfokus pada fenomena ini.
Dalam Islam, tiga kata di atas disebut sebagai kalimat thayyibah. Karena dianggap kalimat thayyibah, maka ada nilai ‘sakral’ di dalamnya. Kesakralan ini secara tidak langsung membatasi penggunaannya. Artinya, hanya orang-orang yang berada di lingkaran sakral tersebut yang boleh memakainya. Tiga kata ini seakan menjadi identitas seorang muslim untuk menunjukkan sisi religiusitasnya. Ya, setidaknya kita tahu bahwa semakin religius seseorang, bahasa yang digunakannya pun semakin dekat dengan bahasa-bahasa dalam kitab (dalam hal ini adalah bahasa Arab).
Dalam penggunaan sehari-hari, tiga kalimat thayyibah ini digunakan sebagai interjection atau kata seru dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah diucapkan ketika mendapatkan kebahagiaan. Astagfirullah digunakan ketika mendapat berita buruk atau musibah. Sementara Ya Allah digunakan dalam banyak kondisi, misalnya saat terkejut, merasa kasihan, kesal, menyesal, dan beragam kondisi lainnya. Tiga kata ini memiliki padanan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti Ya ampun, Syukurlah, Oh My God/ OMG, What the…, Yeay, Hore, Astaga, Asyik, dan Akhirnya.
Untuk menjelaskan kesalehannya, sebagian orang Islam cenderung menghindari kata seru dalam bahasa Indonesia dan menggantinya dengan bahasa Arab. Saya juga pernah dikritik seorang kawan muslim ketika menggunakan kata astaga dan ya ampun. Dia bilang “Kamu kan orang Islam, harusnya pakai kata astagfirullah dan Ya Allah dong, Yay. Kalau tidak, apa bedanya kamu dengan ‘mereka’?”
Saya hanya membisu sambil mencerna kalimat bernada nasihat itu.
Beberapa waktu yang lalu, saya membaca tulisan di kompasiana.com yang menyatakan bahwa di Malaysia, penggunaan kata Allah hanya diperbolehkan untuk orang Islam saja. Kebijakan tersebut mengundang banyak perdebatan. Saya jadi takjub. Bagaimana mungkin relasi antara bahasa dan identitas keagaamaan dapat sedemikian kompleks? Bagaimana mungkin penggunaan kata seru dapat mempengaruhi keimanan seseorang? Lihatlah, betapa dahsyatnya power yang dimiliki bahasa dalam mengidentifikasi dan mendeskripsikan seseorang, bro/bung/akhi/sis/kak/ukhti sekalian!
Upaya untuk menunjukkan kesalehan ini nampaknya berhasil sebab digunakan secara masif. Saking masifnya, orang yang berada di luar ‘lingkaran kesalehan’ ini juga mulai terbiasa menggunakannya, seperti cerita Rosa tadi. Saat saya bertanya mengapa mereka menggunakannya, Rosa dan beberapa kawan Nasrani di sekeliling saya mengaku bahwa mereka terlalu sering mendengar dan melihatnya baik dalam komunikasi nyata maupun maya. Kata-kata tersebut akhirnya masuk ke dalam keseharian mereka. Keakraban dengan kata-kata ini membuat mereka tidak segan menggunakannya dalam interaksi.
Menariknya, orang Islam malah nyiyir dan julid ketika berhadapan dengan situasi seperti ini. Ada perasaan tidak rela ketika bahasa ‘sakral’ mereka diucapkan oleh agama lain.
Fenomena Konvergensi
Dalam Sosiolinguistik dikenal istilah teori akomodasi. Teori ini menjelaskan tentang dua pola komunikasi antar penutur dengan latar belakang yang berbeda. Pola tersebut, yaitu konvergensi dan divergensi.
Menurut Holmes (2012:245), Konvergensi terjadi ketika salah satu di antara dua orang dari latar belakang berbeda merasuk ke dalam bahasa yang digunakan yang lain. Hal ini ditujukan untuk membuat lawan tutur merasa nyaman karena berada dalam frekuensi yang sama. Holmes juga menyatakan bahwa Konvergensi ini merupakan polite strategy dalam berkomunikasi.
Sementara, divergensi justeru sebaliknya. Penutur dan lawan tutur berusaha menunjukkan perbedaan kode-kode dalam bahasa mereka untuk menunjukkan ciri khas.
Konvergensi, menurut Holmes mengindikasikan bahwa kode-kode bahasa yang digunakan lawan tutur acceptable dan worth imitating. Akomodasi dalam komunikasi inilah yang tampaknya terjadi antara Nasrani dan muslim, utamanya dalam menggunakan kata seru yang diposisikan sebagai kalimat thayyibah yang sakral oleh pihak muslim itu sendiri. Sebagian kawan Nasrani yang saya kenal juga menyatakan bahwa mereka ikut menggunakannya agar dapat menyatu dalam komunikasi dengan kawan-kawan muslim sehingga komunikasi berjalan lebih lancar. Alasan lainnya adalah untuk menghormati kawan muslim yang menggunakan kata tersebut.
Lebih jauh, fenomena konvergensi ini dapat diteroka dari dua sudut pandang, yakni makna dan juga bentuk (baik fonologi maupun ortografi). Perlu dicatat bahwa sekalipun tiga kata/kalimat thayyibah tadi sudah dikonvergensi dalam proses komunikasi, tetapi pemaknaan terhadapnya tentu berbeda. Orang Islam memaknai kata tersebut sebagai ungkapan untuk memuji Tuhan. Nilai sakral yang terkandung di dalamnya masih tetap terjaga.
Sebaliknya, non-muslim memaknai kata tersebut hanya sebagai kata seru biasa. Tidak ada muatan kesakralan yang sama, seperti yang dirasakan oleh orang Islam.
Selain itu, fenomena konvergensi ini rupanya melahirkan bentuk baru. Setidaknya, dua dari tiga kata di atas kini memiliki varian bentuk fonologi yang juga berpengaruh terhadap bentuk ortografinya. Di media sosial khususnya, ditemui sejumlah bentuk ortografi Ya Allah yang menjadi ‘Yawla’ atau ‘Yaaloh’ . Ada pula Astagfirullah menjadi ‘Astakfirlah’ atau ‘Astakpirloh’. Menurut Sebba (2007) dalam Spelling and Society: The Culture and Politics of Orthography Around The World, salah satu strategi modifikasi ortografi adalah dengan menggunakan ejaan yang mrepresentasikan pengucapan non-standar.
Bentuk-bentuk tersebut merupakan pengucapan non-standar karena tidak sesuai dengan pelafalan bahasa Arab yang merupakan bahasa sumbernya. Bentuk yang berbeda ini tentu telah menanggalkan nilai kesakralan yang dimiliki bentuk sebelumnya, sekalipun sumbernya sama. Bentuk ini menjadi lebih universal untuk digunakan oleh semua kalangan. Uniknya, bentuk baru ini juga acap kali digunakan oleh orang Islam dalam komunikasi di media sosial.
Dengan demikian, jelaslah bahwa pencerminan identitas melalui bahasa sifatnya sangatlah fleksibel. Sejumlah kata yang menjadi penanda identitas kaum tertentu, bisa melebur saat digunakan secara masif hingga membuat orang di luar kaum tersebut menggunakannya juga. Tidak berhenti sampai di situ, masifnya penggunaan kata ini juga menggerakkan kreativitas pengguna bahasanya untuk memodifikasi bentuk dan bunyi hingga terlahir varian-variannya. Begitulah kiranya metamorfosis sebuah kata dan petualangan sebuah bahasa.
Lantas, apakah kesakralan tiga kata ini telah hilang? Tentu saja tidak. Tiga kata tersebut tetaplah sakral bagi orang Islam. Sebab, pemaknaan terhadap sebuah kata sudah menjadi urusan pribadi penuturnya. Lalu, bagaimana dengan bentuk baru dari kata-kata ini? Apakah etis jika dipandang dari sisi agama?
Entahlah, saya tak mampu menilai. Karena kata dosen saya, Linguis bukan seorang polisi bahasa, tetapi hanya orang yang menjelaskan fenomena kebahasaan saja. Wallahu a’lam (aa)