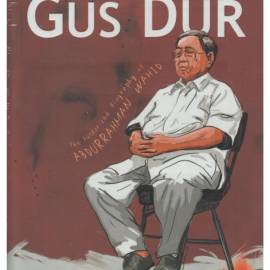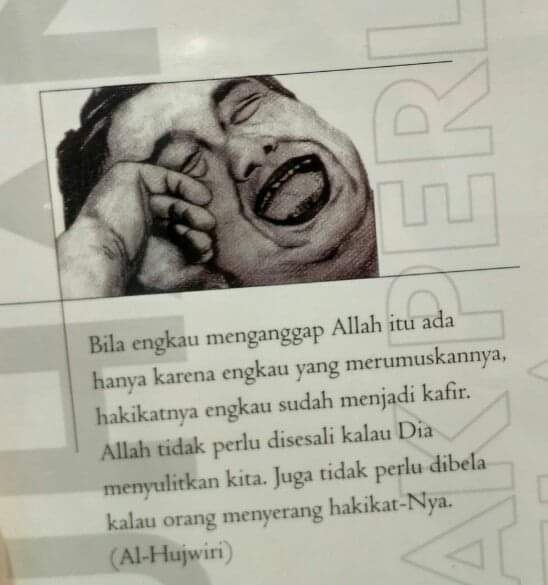Semula saya tak paham betul omongan seorang rekan Indonesia yang saya jumpai di trotoar dekat Dasut Thani, hotel tempat saya menginap. “Mau ke Patpong?” katanya sambil cengengesan.
Bersama sejumlah orang, rekan ini baru saja makan malam entah di daerah mana. Saya dan seorang teman memang baru keluar dan akan cari makan malam di luar hotel. Kebetulan ini kali kedua ia mengunjungi Bangkok. Saya pemula. Masih unyu-unyu, culun.
Saya datang ke kota ini pada 25-28 September untuk dua tujuan kegiatan yang mengangkat tema sama: ekstremisme kekerasan. Satu kegiatan digelar The Asia Foundation Bangkok dan UN Women. Dua kegiatan ini menghadirkan peserta dari sejumlah negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, dan Amarika.
Tiba di lokasi, baru saya mengerti inilah maksudnya. Patpong lokasi klub malam. Klub-klub itu berjajar dari ujung ke ujung dan berhadap-hadapan. Tentu saja dengan nama yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya menyebut nama “massage”, pijat, di belakangnya.
Di lokasi ini banyak perempuan berbikini berdiri atau duduk di bangku-bangku klub sambil menjajakan harga. Sejumlah laki-laki ikut menawarkan sembari menenteng daftar harga.
Saat melintasi lorong ini, secara tak sengaja saya lihat dari balik pintu sebuah klub yang terbuka. Lokasinya persis di tengah antara mulut gang satu dengan mulut gang berikutnya di ujung sana. Puluhan perempuan berbaju minim berjalan di atas panggung. Berlenggak-lenggok genit dan manja. Sebagian deri mereka membelit besi putih yang ditancapkan di tengah panggung. Puluhan laki-laki dan perempuan pengunjung cekikian. Juga perempuan-perempuan itu.
Saya sendiri heran mengapa praktik ini seperti bebas-bebas saja. Di Jakarta, praktik yang terbuka begini 99,9 % bakal digeruduk ormas agama. Apakah di sini tak ada ormas Buddha radikal? Atau ada tapi diuntungkan dari praktik semacam ini? Entahlah.
Di depan klub-klub ini berjajar pedagang souvenir mirip di Tenabang. Orang asing lalu lalang: Arab, Afrika, Eropa, dan Asia. Mereka juga cuek-cuek saja. Klub satu soal, toko souvenir soal lain.
Kami melewati lorong ini menuju mulut gang di seberang sana. Kami mencari makan malam. Pilihan jatuh pada tom yam pinggir jalan. “No pork?” Tanya teman saya. “Ya. Kita sudah pisahkan dengan daging babi,” kata penjual dengan bahasa Inggris seadanya.
Pergi ke tempat-tempat di mana Islam tak mayoritas, di Indonesia atau luar negeri, sering menyediakan dilema semacam ini. Dalam masyarakat santri, umumnya muslim, babi daging pertama yang mesti dihindari. Segala hal terkait babi terlarang. Begitupun dengan makanan yang tercampur dengan babi.
Dalam al-Quran, misalnya Surat Al-Maidah (makanan) ayat 3, daging babi ada di urutan nomor tiga. Pertama, bangkai, kedua, darah, dan keempat hewan yang disembelih atas nama selain Allah.
Saya jadi ingat lelucon Gus Dur tentang babi yang saya baca di buku yang saya lupa judulnya. “Gus, makanan apa yang paling haram,” tanya seseorang pada Gus Dur. “Babi,” jawab Gus Dur. “Lalu?” tanya orang itu lagi. “Babi mengandung babi,” jawabnya
Kami makan. Saya masih mikir apakah wajannya betul-betul tak tersentuh babi. Yakin sajalah. Al-yaqinu la yuzalu bisy-syak, keyakinan tak terhapus dengan keraguan. Wallahua’lam.