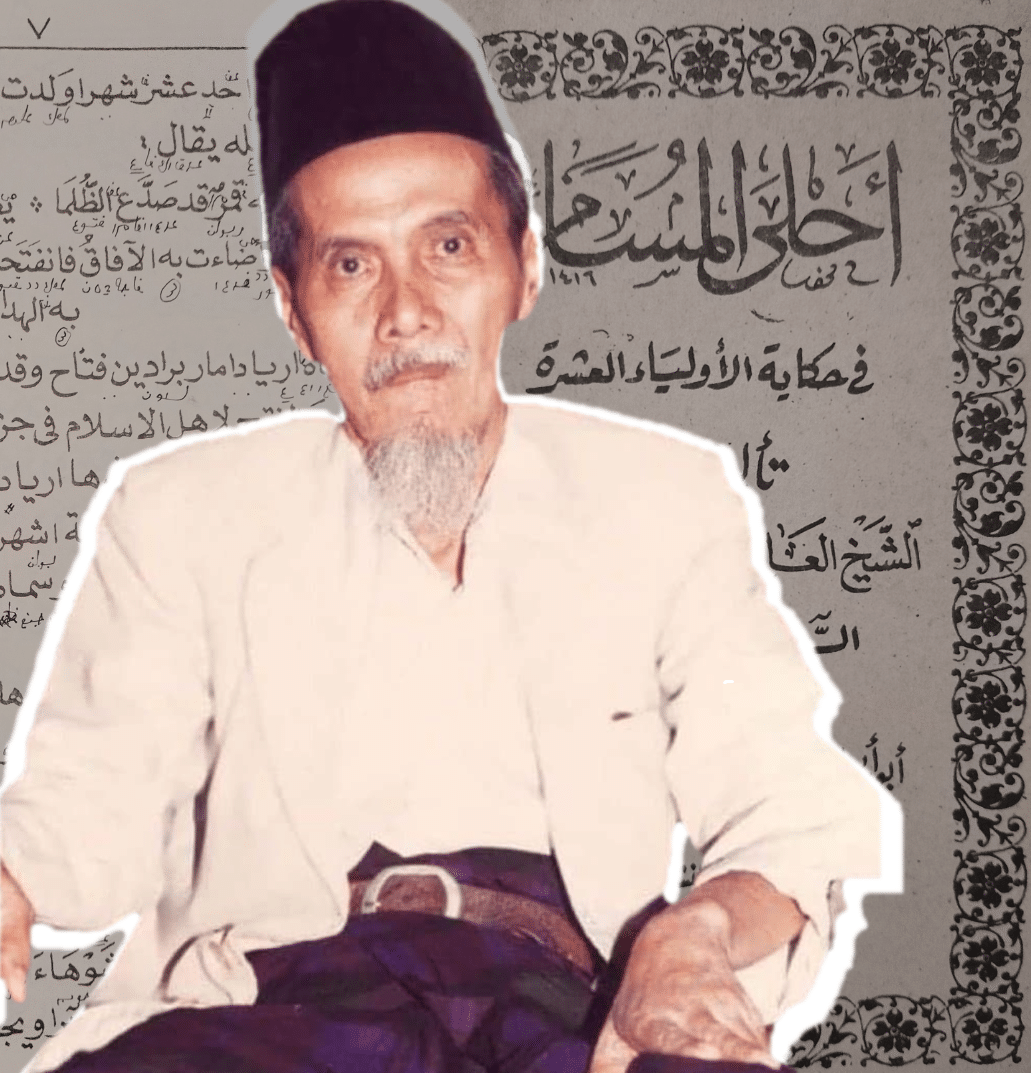Dalam estetika nusantara, khususnya Jawa, terdapat “gradasi estetis”, saya sebut demikian. Misalnya dalam bidang musik tradisional (karawitan). Makin bertempo lambat satu komposisi gending, makin halus garap iringannya, dan tak rumit secara teknis tapi penuh penghayatan, makin bernilai tinggi komposisi itu. Syaratnya ada pada gelimang “rasa”, sebagai piranti dominan dalam bermusik.
Misalnya, terdapat perebab (pemain intrumen rebab) dengan kemampuan melampaui urusan teknis, ditandai dengan tak adanya pembatas nada pada dua dawai, yang menandakan dominannya piranti rasa. Perebab seperti itu dinilai ahli, begitu pula pemain instrumen lain dalam olah gamelan.
Tingkatan pembelajaran gamelan Jawa beranjak dari gending-gending dengan garap yang keras (sora), seperti bentuk lancaran dan ladrang, hingga naik ke bentuk gending ketawang dengan garapan yang lebih halus. Gending ketawang ini kadang membawa hawa kantuk, yang menandakan bekerjanya alunan musik ke otak.
Anda boleh bertanya, lantas andaikata ada “gradasi estetis” di bidang musik tradisional, lantas bentuk atau karakteristik musik yang tertinggi akan seperti apa?
Untuk menjawab pertanyaan itu, saya teringat arsitektur candi Borobudur yang tersusun secara berjenjang, dari kamadhatu, rupadhatu, dan arupadhatu sebagai puncak tertinggi yang justru secara paradoksal tak berupa. Setali tiga uang dalam jagat pewayangan, penggambaran wayang pada karakter wayang yang memilikin tingkat tinggi hanya sampai pada Sang Hyang Wenang. Di atas itu tak ada lagi perwujudannya meski ada nama dan sifatnya, atau dikisahkan mereka menitis (nuksma) ke wayang yang berada pada tingkat di bawahnya.
Berkaca pada arsitektur candi Borobudur dan pewayangan Jawa, maka seni rupa di Jawa pun memiliki prinsip estetika yang sama dengan seni musik tradisionalnya, beranjak dari yang kasar, halus, dan bahkan—sebagai bentuk tertinggi rupa—sampai tak berupa.
Demikian pula pada seni tari, seperti solah baik wayang wong maupun wayang kulit, semakin gerakannya bersifat minimalis, tak akrobatik, penuh rasa dan kehalusan, maka sebuah karakter wayang akan dianggap elok, dalam arti, kadar spiritualitasnya melebihi karakter yang memiliki solah lebih tegas atau bahkan ugal-ugalan.
Karena itulah kenapa dalam adegan gara-gara selalu saja wayang berkarakter halus yang diembani oleh panakawan—Semar, Gareng, Petruk, Bagong—dan dekat dengan para Rsi atau Brahmana. Kontras antara karakter halus dan karakter pethakilan atau banyak tingkah terang tersaji dalam adegan perang kembang ataupun perang begal di mana Cakil selalu saja menguntit dan mengganggu setiap langkah para ksatria dalam menggapai tujuannya (Kadhung Kedhuwung, Gua dan Beberapa Catatan Tentangnya, https://alif.id/read/hs/kadhung-kedhuwung-gua-dan-beberapa-catatan-tentangnya-b227234p/)
Dengan demikian, dalam estetika Jawa tradisional, semakin halus dan minimalis sebuah gerakan akan dianggap lebih tinggi daripada yang cepat, akrobatik, dan kompleks. Karena itu pula Ki Hajar Dewantara membuat sesanti sebagai filosofi pendidikannya, “neng-ning-nung-nang,” yang merupakan singkatan dari meneng (diam), ening (hening), anung (fokus), dan menang (menang).
Dalam versi lain sesanti neng-ning-nung-nang tersebut diartikan pula sebagai “enenging solah bawa, eninging amangku puja, nunggaling cipta-rasa-karsa, wenang jumeneng (diamnya segala gerak, keheningan orang berdoa, kesatuan cipta-rasa-karsa, berhak tegak).” Secara pragmatis kerapkali prinsip ini dijadikan kiat bagi sebuah keberhasilan dalam hidup. Pada konteks pendidikan, seringkali pula prinsip ini disandarkan pada keberhasilan seorang anak didik karena fokus pada apa yang ingin diraih.
Dari ketiga bidang seni Jawa tradisional—seni musik, seni rupa, dan seni tari—dapat diketahui bahwa gradasi estetis berujung pada sesuatu yang melebihi fisik belaka. Metafora yang tepat dalam hal ini adalah bayi.
Sama sekali tak ada yang marah pada tangis, tawa, atau desahan seorang bayi (musik). Tak ada pula yang sampai menempeleng gerakan minimalis seperti kerangkangan yang dilakukan oleh seorang bayi (tari). Demikian pula tak tersua orang yang muak pada perwujudan bayi mungil dan tanpa rasa bersalah (seni rupa).
Pada seorang bayi yang lazim dilakukan orang untuk pertama kalinya adalah justru merengkuh untuk menggendong dan menyayanginya. Tak mungkin orang akan menyabetkan sebilah celurit padanya, apapun yang telah dilakukannya.
Tentu, dari gradasi estetis ini, saya kira orang mesti melacak pada terminal selanjutnya untuk mengerti estetika Jawa tradisional dalam rangka merengkuh sesuatu yang melibihi fisik belaka: kondisi di rahim sang ibu atau bahkan kondisi di rahim sang alam.
Seandainya sesanti Sosrokartono “anteng mantheng sugeng jeneng” dan “trimah pasrah mawi pejah” hanya dapat menggambarkan kondisi di rahim sang ibu, bagaimana dengan kondisi di rahim sang alam, atau bahkan yang memiliki alam?
Puncak estetika Jawa tradisional adalah ketika rasa, baik rasa dari para pelaku maupun para penikmat dapat bertemu yang akhirnya membentuk sebuah kesepemahaman yang mengatasi hal-hal yang sifatnya indrawi. Di sinilah kemudian istilah Jawa tanggap ing sasmita menemukan konteksnya. Wilayah rasa semacam ini memang sulit diteorisasikan, tapi setidaknya dapat dipetakan.
Kembara Sang Pujangga: Wajah Lain Sang Ronggawarsita
Bagus Burham adalah nama aslinya. Sejak usia 12 tahun ia telah terpisah dari keluarganya. Konon, ia dibesarkan oleh eyangnya, pujangga kenamaan di masanya. Ayahnya sendiri, Mas Pajangswara, tewas karena keterlibatannya dalam perang Jawa, yang dikobarkan oleh sang pangeran tersisih, Dipanegara. Atas informasi seseorang, Belanda kemudian menciduknya. Dan tiba-tiba jasadnya ditemukan di daerah Luar Batang. Karya-karyanya pun, konon, ikut dibakar.

Praktis Burham hanya mewarisi nama ayahnya yang bagi khalayak awam bukanlah siapa-siapa. Paling banter mereka hanya tahu tentang eyang dan eyang buyutnya: Yasadipura II dan Yasadipura I. Pendidikan kesusasteraan diberikan oleh eyangnya, Yasadipura II. Untuk memperdalam ilmu-ilmu agama, Burham kecil dikirim ke sebuah pesantren di Timur Gunung Lawu dengan di dampingi oleh emban setianya, Ki Tanujaya.
Burham (masa) bodoh dalam belajar ilmu-ilmu agama. Wejangan-wejangan sang guru hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kesukaannya hanya memancing ikan, menyusuri kali. Selain itu, judi dan sabung ayam menjadi kebiasaannya sehari-hari.
Mlilir, konon, merupakan daerah perjudian terbesar di wilayah Timur Lawu. Setelah diusir sang kyai yang tak menyukai tingkahnya, ia bersikeras mengajak Ki Tanujaya ke pasar Mlilir. “Sudahlah, Paman, ikuti saja aku. Aku sudah muak dicacimaki orang-orang pesantren. “Terus mau ke mana, Gus?” tanya Ki Tanujaya pada si bocah kepala batu itu.
“Ke Mlilir, mencegat jodohku!” Ki Tanujaya tak kaget dengan keanehan bendaranya itu. Sebelum menginjakkan kakinya di pesantren yang kemudian membuangnya, Burham pernah dikasih cincin oleh eyangnya, warisan Nyai Padmanagara. Tapi yang membuatnya bingung kenapa mesti di pasar Mlilir, tempat perjudian yang terkenal?
Dasar kepala batu, akhirnya Ki Tanujaya menemani junjungannya ke pasar Mlilir. Mereka berjudi selama berhari-hari. Sampai suatu ketika, serombongan orang terpandang singgah di Mlilir. Apa yang dilakukan si Burham tengik?
Dengan pakaian lusuh dan wajah kusam khas pejudi, ia menyibak kerumunan orang terpandang itu. “Tak usah banyak cakap!” (Serat Babad Cariyos Lelampahanipun Suwargi Raden Ngabehi Ronggawarsita, 1931).

Bagus Burham, yang kelak tenar dengan gelar R.Ng. Ronggawarsita, merupakan sosok yang terkenal sebagai pujangga. Bahkan, ia disebut-sebut sebagai sang pujangga panutup. Banyak orang mengenalnya sebagai seorang yang secara spiritual bercorak sinkretis yang sangat kental dengan paham manunggaling kawula-Gusti.
Tapi saya memiliki bukti lain bahwa Burham adalah juga seorang yang karib dengan tasawuf akhlaqi yang cenderung pada wilayah praksis daripada teoritis atau filsafati. Selain eyangnya sendiri, Yasadipura II, Pangeran Wijil, Kanjeng Kyai Kasan Besari, dan seorang Ajar (spiritualis Hindu di Banyuwangi), rupanya Burham pernah tercatat pula berguru pada seorang “kyai desa” di Kediri.
Setidaknya, dalam kesusasteraan Jawa klasik dikenal adanya empat macam bentuk karya sastra: serat, babad, suluk, dan wirid. Serat umumnya merupakan prosa yang memiliki plot, karakter, konflik dst. Babad lazimnya mengisahkan cerita sejarah dalam bentuk tembang macapat.
Suluk merupakan karya sastra yang berisi ajaran-ajaran tasawuf atau ketuhanan yang disampaikan dalam bentuk tembang pula. Adapun wirid merupakan karya yang berisi ajaran-ajaran tasawuf atau ketuhanan yang disampaikan dengan bahasa argumentatif.
Ronggawarsita, sebagai seorang pujangga terbesar Jawa, jamak memakai ketiga bentuk karya sastra tersebut, misalnya, Serat Cemporet (prosa), Suluk Salaka Jiwa (suluk), dan Wirid Hidayat Jati (wirid).
Dalam hampir semua karyanya yang dapat diidentifikasi, tampak bahwa Ronggawarsita secara sufistik berpaham wujudiyah, yang paling kentara tampak pada Wirid Hidayat Jati, karya yang menjadi rujukan bagi kalangan tertentu. Tapi anak Mas Pajangswara ini tak serta merta berpaham wujudiyah. Seperti pamannya, Ronggasasmita, pengarang Suluk Acih (baca: Aceh), anak keturunan Yasadipura ini mengambil Syathariyah sebagai salah satu tarekatnya.
Ajaran martabat 7—yang diperas dari Ibn ‘Arabi-Abdul Karim al-Jilli, Syaikh Burhanpuri, dst, memang cukup mendominasi dalam ajaran tarekat Syathariyah. Dan jelas, andaikata berbicara masalah status mu’tabarah di lingkungan nahdliyin, Syathariyah masuk dalam salah satu kriterianya.
Di samping terpengaruh oleh ajaran martabat 7 yang bercorak filsafati, Ronggawarsita juga memiliki guru yang cenderung berpaham tasawuf akhlaqi. Di kisahkan dalam Kawruh Rasuk, guru Ronggawarsita yang bernama lengkap Kiai Wusman dari Desa Gumuk, Ngadiluwih, Kediri, adalah seorang “kyai desa” yang jauh dari keraton.
Naskah Kawruh Rasuk yang saya pegang masih berupa tulisan beraksara Jawa. Saya menduga bahwa Burham berguru pada Kyai Wusman setelah ia menikah dengan R.Ay. Gombak, putri dari Adipati Kediri, sembari mengulik serta menggubah naskah-naskah Jayabaya di Kediri.
Wejangan-wejangan Kiai Wusman yang tercatat dalam Kawruh Rasuk, terdiri dari empat bab atau empat macam kawruh kasampurnan. Dalam karya pamungkas Ronggawarsita, Serat Sabdajati, di mana sang pujangga pamit mati, sangat tampak bahwa wejangan-wejangan Kiai Wusman menjiwai Ronggawarsita sepuh yang sudah mupus.
Dengan demikian, di antara guru-guru Ronggawarsita dan aliran-aliran spiritual yang pernah ia sesap, di akhir hidupnya yang sendu, wejangan-wejangan Kiai Wusman adalah wejangan yang paling memengaruhi kesiapan sang pujangga untuk mati.
Nuansa yang dihadirkan oleh kawruh kasampurnan Kiai Wusman memang berkaitan dengan bagaimana cara yang efektif untuk menjemput kematian. Karena itu saya kira, orang pertama-tama harus meletakkan kawruh kasampurnan Kiai Wusman yang diajarkan pada Ronggawarsita sebagai wejangan yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang secara harfiah sudah sepuh, tak punya lagi keinginan yang bermacam-macam kecuali manising pati patitis dan nasib anak keturunannya di kemudian hari.
Rasa dalam Kawruh Kasampurnaan
Untuk keperluan konsep gradasi estetis di atas, saya ingin membahas satu bagian kawruh kasampurnan Kiai Wusman yang berkaitan dengan rasa yang sedikit banyak mendasari estetika sekaligus spiritualitas Jawa. Pada bagian ngelmu rasa, seorang kiai yang berasal dari Desa Gumuk ini membaginya menjadi empat sub-bab: wujuding rasa, kahananing rasa, pratingkahing rasa, dan wataking rasa.
Terkadang orang tak dapat menjelaskan apa itu rasa meskipun setiap detik ia merasakan sesuatu dan setiap saat mengucapkan istilah yang ada kaitannya dengan rasa: “perasaan,” “dirasakan,” “merasakan,” “serasa,” dan “rasakan.” Benarlah pendapat para filosof analitis bahwa kerancuan segala sesuatu adalah karena orang tak pernah memikirkan atau bahkan tak pernah tahu tentang apa yang ia ucapkan sendiri.
Atas petuah seorang “kyai Desa,” Kiai Wusman, yang disebut sebagai rasa itu pada dasarnya tak berwujud. Perwujudannya adalah dari rasa-nya sendiri (katone mung saka rasane dhewe). Ia hanya dapat dijelaskan lewat sanepa (via analogia dalam teologi).
Kiai Wusman memperumpamakan rasa sebagai hawa kang luwih dening alus (daya yang lembut) yang berada pada segala sesuatu: tumbuhan, satwa, manusia, dan juga barang. Rasa inilah yang menyebabkan segala sesuatu dapat berkembang-biak (mranak).
Dan segala sesuatu yang sudah kehilangan rasa sudah pasti tak akan berkembang-biak atau mati—meskipun dalam alam halus ia masih dapat berfungsi, seumpamanya pada kasus mimpi dan out of body experience, juga kepercayaan pada arwah yang gentayangan (mrayang).
Adapun keadaan rasa (kahananing rasa) bersifat macam-macam dan banyak. Yang jelas, ia tak dapat sama sekali lepas dari panca indera manusia. Yang berkaitan dengan indera peraba adalah semisal keset, licin, dst. Yang berkaitan dengan indera pembau berupa wangi, bacin, dst.
Yang berkaitan dengan indera pengecap seumpamanya gurih, kecut, manis, dst. Sedangkan yang berkaitan dengan indera pendengar tak jauh dengan lirih, keras, dst. Yang terakhir yang berkaitan dengan indera penglihatan adalah sebagaimana terang, gelap, dst.
Tingkahnya rasa (pratingkahing rasa) bersifat dinamis dan menyebar sekaligus tenang (lerem) dan mengumpul (meneb) di pusat yang berada di kepala—tak jauh beda dengan peredaran darah. Rasa akan bertingkah selagi ada hal yang hinggap di panca indera dan akan senantiasa bergolak tanpa henti. Sampai suatu ketika ia akan lerem ketika akal-budi—untuk tak menyebutnya sebagai otak—tak menindaklanjutinya. Maka ia pun akan kembali meneb dan hening di pusat.
Karakter rasa (wataking rasa) karena itu seturut dengan keadaan yang dirambah. Rasa yang memencar pada bayi jelas berbeda dengan orang dewasa atau orang tua. Rasa pada manusia juga jelas berbeda dengan tumbuhan, panda, atau batu.
Ketika terjadi peristiwa kukuting rasa, ketika rasa menjadi lerem dan mengumpul pada pusat (meneb), di situlah letak tujuan tertinggi segala bentuk estetika Jawa tradisional yang melingkupi musik (yang justru tanpa suara dan nada), seni rupa (yang justru tanpa rupa), dan seni tari (yang justru tanpa gejolak dan pergolakan).
Bukankah ketika orang mendengarkan Gendhing Laler Mengeng ataupun salawatan gaya pedesaan, melihat hamparan nan hijau dari sebuah gunung, atau bergerak secara rileks dan minimalis tanpa rancangan pikiran, akan terhantar pada sebentuk kantuk yang tak berujung lelap (liyep-layaping-aluyup)? (SI)