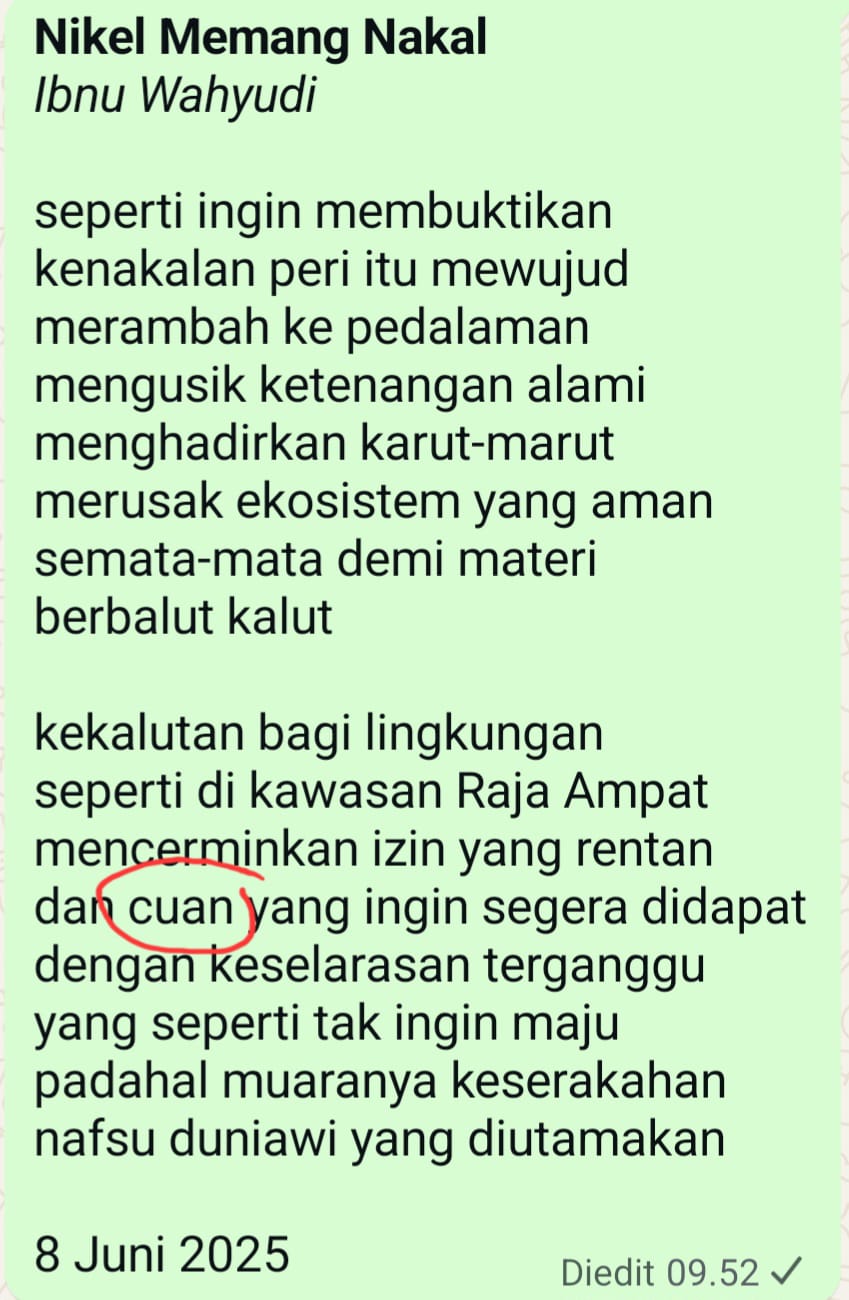NU lahir dari sebuah pergulatan batin yang sangat panjang serta merupakan respons dari proses-proses kesejarahan terkait dengan permasalahan sosial keumatan, upaya memperkuat madzhab, serta berjalan seiring dengan cita-cita nasionalisme Indonesia yang tumbuh pada awal abad ke-20. Indikator dialektis dari kelahiran NU, adalah tantangan yang datang dari Dinasti Saud di Arab Saudi yang berniat untuk membongkar makam Nabi Saw disebabkan menjadi poros spiritual untuk diziarahi serta dianggap sebagai perbuatan bid’ah. Raja Saud juga berniat mendelate praktek bermadzhab, serta dengan sebuah pandangan monolitik, akan menjadikan Wahabi sebagai satu-satunya madzhab resmi negara.
Apa yang dilakukan Raja Saud adalah upaya terstruktur lewat institusi formal negara untuk melakukan penyangkalan terhadap basis-basis epistemologi pengetahuan serta struktur kesadaran mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Dilihat dari sudut pandang ini, bentuk-bentuk negasi oleh Kaum Wahabi, malah memberikan tantangan terhadap kelompok Ahlus Sunnah wal Jam’ah (Aswaja) untuk membuktikan kebenaran dari proposisi-proposisi ajarannya.
Tantangan Dialektis
Pandangan Aswaja telah mengalami pematangan secara konseptual, baik dari sisi aqidah, fiqih, maupun tasawuf. Secara aqidah berhaluan pada pandangan Imam Al-Asy’ari serta Imam Al-Maturidi. Secara fiqih pada empat Imam Madzhab: Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, serta Imam Syafi’i. Dari sisi tasawuf bermadzhab pada Syeikh Junaid Al-Baghdadi, serta Imam Al-Ghazali. Sebagai konsekuensi dari pilihan bermadzhab ini, maka telah memunculkan kekhasan-kekahasan seperti keyakinan adanya sifat 20 bagi Allah, qunut bagi para penganut fiqh Imam Syafi’i, ziarah qubur, sejumlah ritual tarekat seperti dzikir, tawajuh serta manaqiban, marhabanan, tahlil, dll.
Keunikan-keunikan seperti disebut yang dinegasi oleh kaum Wahabi dengan diktum “ar-ruju ilal Qur’an wa sunnah” ala Ibnu Taymiyah serta menolak adanya keragaman cara pandang dalam kehidupan beragama. Dengan pemahaman yang sangat dangkal, menurut mereka, semua merupakan amalan bid’ah serta tidak merujuk pada sumber otentik Alquran serta Sunnah Rasul.
Apa yang dilakukan oleh Wahabi itu, tampaknya, merupakan sebuah upaya terstruktur, sistematis, massif, serta didukung dengan pendanaan sangat besar sehingga bisa meluaskan pengaruhnya ke seluruh dunia. Niat dari Dinasti Saud untuk menghancurkan makam Nabi Saw, tampaknya didasarkan pada pemahaman agama yang salah serta untuk memutus ‘kesinambungan’ mata rantai sejarah berikut ikatan batin antara kehidupan Rasulullah dengan umatnya. Namun, tantangan dialektis itulah, yang telah menyadarkan para ulama di Jawa dalam memberikan jawaban sekaligus melakukan penyelamatan atas rencana penghancuran makam Rasulullah Saw, serta telah melahirkan Komite Hijaz.
Komite Hijaz berupa panitia kecil yang diketuai oleh KH. Wahab Chasbullah, membicarakannya akan selalu relevan pada saat menjelang peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama (1926-2026). Melalui komite tersebut, sebuah langkah mendasar telah diambil. Sendainya tidak ada Komite Hijaz, umat Islam mungkin telah kehilangan poros spritualitas yang menjadi pengikat eksistensi masa lalu, masa kini, sekaligus untuk melakukan lompatan-lompatan yang jauh bagi masa depan kehidupannya. Terkait dengan penguatan madzhab serta kesadaran historis keumatan, 2 poin penting dari Komite Hijaz ini, pertama, terkait tuntutan pluralitas bermadzhab di negeri Hijaz, baik secara aqidah, fiqh, maupun tasawuf, serta, kedua, ajuan untuk tetap diramaikannya tempat-tempat bersejarah seperti yang telah diwakafkan untuk masjid. Umat bisa mengambil ibrah dari tempat-tempat bersejarah tersebut.
Tampaknya, kesadaran sebagai umat yang memiliki sejarah itu yang akan dieliminir oleh orang-orang Wahabi. Padahal, gambaran sebagai umat yang memiliki sejarah, ajaran, serta sistem nilai, yang membuat satu pribadi besar di masa lalu seperti Rasulullah Saw, akan tetap memiliki posisi strategis, baik pada level epistemik pengetahuan, maupun pada amaliah-amaliah dalam bentuk pelaksanaan ritual-ritual keagamaan. Uswah Hasanah yang diberikan Rasululah Saw pada masa lalu berada dalam sebuah hubungan dinamis, yang terikat dengan perjalanan ruang dan waktu, dan berada dalam poros kesadaran sejarah umatnya, bahkan hingga akhir dari usia dunia ini.
Embrio kelahiran Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 yang bertitik tolak dari Komite Hijaz ini, adalah sebagai sebuah respons atas situasi internasional yang berkembang di Tanah Hijaz. Faktanya, walaupun aspirasi umat Islam Indonesia yang berhaluan Aswaja diterima oleh Raja Ibnu Saud, tapi progresivitas gerakan Wahabi, bagai sebuah badai gurun yang tidak pernah mengambil jeda untuk berhenti, dari dahulu sampai kini. Dalam catatan Sekjen PBNU, Helmi Faisal Zaini, penghancuran-penghancuran tempat bersejarah itu tetap terjadi. Di antara penghancuran itu sebut saja, misalnya, penghancuran makam Sayyid Imam Uradhi ibn Ja’far as-Shiddiq pada 2002 yang diledakkan dengan menggunakan dinamit. Rumah Sayyidah Khadijah dijadikan toilet umum dan juga masjid kompleks Hamzah Abdul Muthalib yang dibuldoser pada 1998. Bahkan, menurut Irfan al-Alawi, Executive Director the Islamic Heritage Research Foundation Arab Saudi dalam kutipan Helmi, sampai 2011 tercatat kurang lebih 400-an lebih situs bersejarah umat Islam yang dihancurkan (REPUBLIKA.co.id, 22 April 2016).
Di Indonesia, disamping membid’ahkan amaliah yang sudah lazim dilakukan kalangan Aswaja, dalam beberapa tahun belakangan ini kita begitu sering mendengar para propagandais Wahabi, menihilkan keberadaan dari sejarah dakwah Walisongo dalam bentuk asumsi-asumsi a-historis. Ini juga tidak lain dari upaya untuk mengeliminasi kesadaran sejarah umat, tanpa didukung dengan fakta historis serta kajian empiris berdasarkan pada kecanggihan metodologi yang ada.
Bagi kalangan NU, karakteristik dialektis dari gerakan Wahabi ini, tampaknya malah menimbulkan respons balik menguatnya paham ke-Aswaja-an. Walaupun dibid’ahkan, berziarah pada Rasulullah di Madinah merupakan bagian tidak terpisah dari ibadah haji, qunut tetap dijalankan pada sholat subuh, demikian juga dengan ziarah Wali Songo, manaqiban yang selalu dibanjiri umat, tahlilan sebagai pengkat kohesivitas masyarakat tetap berjalan, serta amaliah-amaliah khas NU yang lain tetap dilakukan, walaupun dalam gempuran paham Wahabi.
Tantangan dialektis di atas penting untuk lebih menguatkan energi sejarah. Jika eksistensi dari fakta sejarah Aswaja itu menjadi lebih kuat, segala bentuk negasi itu, malah akan melahirkan energi kreatif bagi tumbuhnya cakrawala pandangan keagamaan yang lebih bergerak dinamis serta mampu menghadapi dimensi kritik secara lebih positif. Dan, penulis pikir, NU, sejak kelahirannya 31 Januari 1926, telah menunjukkan karakter dinamis untuk memberi respons terhadap tantangan-tantangan yang datang padanya. Semakin besar tantangan dari gerakan Wahabi, maka semakin besar pula jawaban-jawaban yang diberikan NU untuk menunjukkan etos juang serta jati dirinya.
Adanya gagasan yang berkembang di kalangan NU untuk menggulirkan Komite Hijaz Jilid 2, adalah juga dalam kerangka penguatan basis epistemik serta amaliah-amaliah Aswaja, sesuai dengan situasi, konteks, kebutuhan, serta semangat zaman. Gagasan Komite Hijaz Jilid 2 ini akan menjadi batu ujian bagi kekuatan sejarah NU, saat menyongsong satu abad dari rentang masa kelahirannya.[]